Text
Aum! : Perlawanan, Sinema dan Orde Baru

Satriya (Jefri Nichol) muncul dari balik pakaian yang dijemur, berlari di lorong sebuah rumah susun. Ia berlari dan tetap mewaspadai sekitar, sesekali melihat ke belakang. Ia sembunyi, dan berlari lagi dari kejaran orang-orang yang mengenakan pakaian laiknya ‘preman’—umumnya ini bagian dari militer, kaki-tangan di era Orde Baru. Sampai pada Satriya menemui jalan buntu dan berbalik arah, lalu dari balik tembok muncul kepalan tangan tepat ke wajahnya.
Adegan berdurasi 1:30 menit itu menjadi pembuka dalam Aum! (2021). Setidaknya dari awal cerita, narasi aktivisme di akhir era Orde Baru sudah cukup kental. Satriya tampak sebagai representasi para mahasiswa yang berjibaku dengan aktivisme untuk memperjuangkan reformasi.
Di Pertunjukan (Bagian I) dalam Aum! ini, diceritakan bahwa ternyata Satriya memiliki saudara yang berprofesi sebagai militer, yakni Adam (Aksara Dena). Di tengah ketegangan akhir kejayaan Orde Baru, di mana militer tengah gencar-gencarnya memburu siapa saja yang dianggap sebagai pemberontak, Satriya sebagai mahasiswa ialah salah satu target militer.
Linda Salim (Agnes Natasya Tjie) sebagai produser dan tim produksi Pertunjukan lainnya, berupaya membuat film dengan sekepal narasi menyoal wacana reformasi di era Orde Baru. Bagi Linda dan teman-temannya, penuturan lewat sinema berisi wacana reformasi sama pentingnya dengan ribuan kepalan tangan mahasiswa di jalanan yang memperjuangkan tumbangnya sang diktator.
Praksis Gerilya Produksi Film di Akhir Orde Baru
Hakikatnya Aum! merupakan film dalam film. Pada Perjalanan (Bagian II) kita disuguhkan bagaimana proses produksi film independen di era Orde Baru. Khusus konteks film ini, Perjalanan sebagai proses produksi Pertunjukan. Hal inilah yang membedakan Aum! dengan film-film bertemakan reformasi lainnya. Di mana itu menggambarkan titik-titik penting dalam peristiwa ’98; demonstrasi mahasiswa, kerusuhan yang mengakibatkan etnis Tionghoa sebagai korban, dan kebejatan rezim Orde Baru. Namun setelah melewati 25 menit pertama dalam Aum! hadirlah Perjalanan dan menegaskan tema seperti ini ternyata sama pentingnya.
Bambang Kuntara Mukti sebagai sutradara Aum! termasuk jeli dalam memilih narasi produksi film independen di era Orde Baru untuk mendapatkan sisi human interest lainnya. Selain itu, produksi film independen juga menjadi tepat ketika hal ini ditekankan dalam menyuarakan kebebasan berekspresi.
Membuat film independen bukanlah hal yang mudah di Orde Baru. Membuat film independen sama saja seperti melawan negara. Pada era Orde Baru, mengutip Eric Sasono , terdapat satu-satunya organisasi perfilman bernama KFT (Karyawan Film dan Televisi). Ini berkaitan dengan pelarangan negara terkait adanya lebih dari satu organisasi profesi agar mudah dikendalikan. Otomatis, melanggar ketentuan KFT berarti sama sekali tak mungkin bisa masuk ke industri film dan televisi.
Dalam Perjalanan, hadir sosok Paul Whiteberg (Richard) sebagai wartawan dari Amerika Serikat yang meliput seputar reformasi ‘98 di Indonesia. Dari lensa kamera Paul inilah Perjalanan disajikan serupa film dokumenter. Awal kehadirannya tentu menjadi momok bagi para kru film, karena rezim Orde Baru sangat berhubungan dengan Amerika Serikat. Namun, Linda meyakinkan rekan-rekannya termasuk Panca Kusuma Negara (Chicco Jerikho) sebagai sutradara, bahwasanya Paul berada di pihak mereka.
Senada dengan Pertunjukan, dalam Perjalanan juga menarasikan ketegangan dan kewaspadaan mahasiswa terhadapa rezim Orde Baru. Pertama-tama, yang paling menonjol adalah saat produksi film, Linda kerap kali mengingatkan kru lainnya untuk tidak berisik dan sebisa mungkin bekerja dengan keadaan senyap. Hal itu tentu saja mengantisipasi suara dan wacana yang mereka tuang dalam film agar tidak terdengar oleh orang lain. Apalagi, di era Orde Baru, dwifungsi ABRI benar-benar berjalan dalam tatanan idealnya. Sehingga bisa jadi tukang sapu, pedagang bakso, dan profesi sipil lainnya diperankan oleh militer. Sebab itu, Linda tak henti-hentinya bersikap sangat hati-hati.
Penyajian narasi proses produksi film independen dalam Aum! bukan tanpa alasan, atau sekadar agar terlihat berbeda dari film bertemakan reformasi lainnya. Produksi film independen di era Orde Baru, sejatinya memang benar-benar dilakukan. Meski pergerakan dibatasi dan adanya penyensoran film, produksi film independen tetap bergerilya, baik kelompok maupun individu.
Lihat Quirine Van Heeren dalam Jiwa Reformasi dan Hantu Masa Lalu: Sinema Indonesia Pasca Orde Baru (2019) memberi contoh film independen yang diproduksi di era Orde Baru yakni Kuldesak (1999) yang diproduksi secara bawah tanah oleh empat sutradara Mira Lesmana, Riri Riza, Rizal Mantovani, dan Nan Achnas. Mereka, sebut Heeren, melanggar semua peraturan produksi film yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Sekilas, Orde Baru melakukan praktik sebagaimana disebutkan Heeren, cursive practices (praktik miring) dalam mediasi film di tahapan produksi, distribusi, dan penayangan film guna mempropagandakan dan merepresentasikan nilai dan politik negara dalam film.
Masih mengutip Heeren, Kuldesak diproduksi secara sembunyi-sembunyi selama dua tahun (1996-1998) dan keempat sutradara itu mengabaikan peraturan legal-formal rezim Orde Baru soal produksi film untuk menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Uniknya, para sutradara Kuldesak sengaja tidak mendaftarkan rencana produksi Kuldesak kepada Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video Departemen Penerangan.
Paling tidak, narasi Aum! mendekati itu. Produksi film independen oleh mahasiswa dengan peralatan seadanya dan melanggar asas-asas peraturan membuat film di Orde Baru, menyatakan bahwa film ini mengingatkan tentang bagaimana represifnya Orde Baru dari perspektif pembuatan film.
Warisan Orde Baru Hari Ini
Hari ini, 23 tahun sudah reformasi berlangsung di Indonesia. Harapan para reformis yang memperjuangkan reformasi pada 1998 silam, menjadi aspek penting yang bisa ditarik pada Aum! Dengan pola naratif yang kompleks, Aum! mencoba memberikan penggambaran hidup di era Orde Baru, khususnya kepada saya yang tidak merasakan hidup di era tersebut.
Dengan adegan-adegan dalam Aum! bisa dikatakan sebenarnya tak jauh beda dengan keadaan saat ini. Lihat saja, ketika Linda tak bosan-bosan mengingatkan kru film lainnya agar sesenyap mungkin dalam bekerja. Walaupun berbeda konteks, hari ini kita juga tak bosan-bosan mengingatkan diri sendiri untuk bersuara, berpendapat, dan berekspresi dengan hati-hati terutama di media sosial agar tidak terjerat UU ITE.
Selain itu, Aum! secara halus menarasikan sifat militer Panca saat berlangsungnya produksi film. Orde Baru diketahui tak suka dengan pers, bahkan beberapa perusahaan pers seperti Tempo, DeTik, dan Editor dibredel. Panca sebagai sutradara yang idealis justru tidak suka jika kamera Paul menyorotinya. Padahal seperti yang dikatakan Linda, posisi Paul di situ untuk liputan. Selain itu Panca juga bertingkah semaunya sendiri, sampai-sampai Linda mengatakan, “Tidak ada tempat untuk orang yang keras kepala, apalagi semaunya sendiri”.
Dalam Pertunjukan, adegan para tentara menggelar konferensi pers, mereka mengingatkan aktivis dan mahasiswa agar berdemonstrasi secara tertib dan tidak melanggar hukum. Hari ini, narasi-narasi aparat seperti ini kerap kali ditemukan. Bagaimana mungkin berdemonstrasi secara tertib dan tanpa kekerasan di mana kekerasan sendiri ialah aparat. Menghadapi kekerasan dengan cara tanpa kekerasan sama dengan bunuh diri.
Hari ini juga, para orang tua dan sahabat korban peristiwa ’98 juga masih menuntut keadilan, mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan oleh rezim Orde Baru. Dalam Pertunjukan, masih dalam gelaran konferensi pers, seorang wartawan menanyakan nasib aktivis dan mahasiswa yang hilang. Sontak gelagat para militer itu langsung berubah, mendiskusikan apa yang harus disampaikan ke pers dan apa yang tidak, seakan-akan menyembunyikan sesuatu. “Kami telah membentuk sebuah tim pencari fakta. Kami pastikan kurang dari 14 hari, kami sudah menemukan fakta-fakta baik secara empiris maupun lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” terangnya kepada wartawan. Namun, sampai hari ini juga belum selesai dan masih ada aktivis dan mahasiswa yang dinyatakan hilang dalam peristiwa itu, dan artinya penyelesaiannya tidak menyeluruh.
Terlalu banyak korban dalam peristiwa ’98 yang belum diselesaikan negara hingga hari ini. Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) , empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat militer dan 681 orang dari berbagai kampus mengalami luka-luka. Pada rentang 13-15 Mei 1998 juga korban berjatuhan di Jakarta, Bandung, Solo, dan beberapa kota, sebanyak 1.300 lebih orang tewas dan ratusan perempuan diperkosa tanpa mendapatkan keadilan hingga sekarang. Itu data kasar yang sampai ke Kontras, saya yakin bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari itu.
Singkatnya, hari ini “Orde Baru” masih bekerja dan difasilitasi negara. Pemerintah melanggengkan perlakuan Orde Baru kepada rakyat, dengan cara yang berbeda namun sama menyakitkannya. Reformasi mungkin saja terjadi, tapi sifat-sifat kediktatoran dan kekerasan negara itu mendarah daging.
Dalam konteks ini, saya mengaminkan pernyataan Errico Malatesta dalam Malatesta: Life and Ideas (2005) di mana ia mengatakan, pemerintah dan kelas istimewa alamiahnya selalu mempertahankan diri, mengembangkan kekuasaan; jika ketika mereka menyetujui reformasi itu karena mereka menganggap bahwa hal itu menguntungkan mereka atau karena mereka kehilangan kekuatan dan menyerah, karena takut akan alternatif yang lebih buruk bagi mereka.
Aum! dengan penuturannya sepanjang film menegaskan produksi film independen bagian dari perlawanan terhadap negara, baik di era Orde Baru maupun hari ini. Isyarat dalam Aum! bisa ditarik sebagai bahwasanya pembuat film independen sebenarnya dekat sekali dengan militer. Institusi penyiaran hari ini juga melanggengkan sikap militeristik era Orde Baru. Di negara yang militeristik, bisa jadi orang-orang terdekat kita—saudara, orang tua, sahabat, dll—bagian dari militer. Dan tentu saja, dari dekat sekali, memeriksa isi kepala kita sendiri perihal kelanggengan militeristik.
Penulis : Bagus Pribadi
Aum! | 2021 | Sutradara: Bambang "Ipoenk" Kuntara Mukti | Pemeran: Jefri Nichol, Chicco Jerikho, Aksara Dena, Agnes Natasya Tjie | Negara Asal: Indonesia | Durasi: 83 menit | Produksi: Lajar Tantjap Film
Bagus Pribadi

Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang skripsian. Agar tidak mengutuk waktu, ia nyambi jadi jurnalis di salah satu media lokal di Pekanbaru.


1 note
·
View note
Text
Sorry We Missed You : Kapitalisme dan Keluarga.

Pertengahan tahun ini, media sosial diramaikan dengan viralnya rumor eksploitasi perusahaan pengiriman barang pada kurir mitra. Rupa-rupa kenelangsaan dipublikasikan mulai dari pelanggan menyebalkan dalam pengiriman cash on delivery, penurunan insentif yang diterapkan perusahaan, hingga aksi mogok kerja dan implikasinya pada ketepatan waktu barang untuk sampai.
Narasi negatif pada konsep “mitra” perusahaan ini selalu membawa saya pada film Sorry We Missed You, yang disutradarai Ken Loach. Bercerita tentang Ricky Turner, seorang kelas pekerja di Newcastle Inggris yang mencoba peruntungannya dalam bekerja dengan zero-hour contract, di mana pekerja mitra, yang dapat menentukan jam kerjanya sendiri dan berpenghasilan sesuai pekerjaan yang diselesaikan. Kemiskinan dan tekanan lingkungan kerja membuat kehidupan keluarganya renggang. Istrinya Abby, dan kedua anaknya Seb dan Liza terpengaruh langsung secara finansial dan psikologis.
Loach yang dikenal dengan penggambaran realis kelas pekerja dalam filmografinya, berusaha mengeksplorasi kecacatan sistem ekonomi ini. Ia membawakan kemiskinan dalam suasana depresif tanpa sekalipun memaksakan kesedihan kepada penonton, menangkap realita keseharian manusia yang memang nyatanya menyedihkan. Konstruksi penggambaran realis ini membuat karyanya menjadi autentik.
Ilusi Kewirausahaan
Film dibuka dengan eksposisi pekerjaan Ricky oleh Maloney, mandor pengirim barang. “Pengirim barang tidak dipekerjakan, mereka ikut serta. Pengirim barang tidak bekerja untuk perusahaan, mereka bekerja bersama perusahaan. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada target performa. Tidak ada gaji, tapi pembayaran.” Eksposisi ini diatas kertas terasa seperti sebuah preposisi ide bisnis. Ricky tidak bekerja dengan jam yang ditentukan. Ricky adalah seorang pengusaha waralaba. Membeli mobil pengantar barang merupakan sebuah modal yang harus ia gelontorkan untuk memulai bisnisnya. Narasi ini meyakinkan Ricky bahwa ia bekerja untuk dirinya sendiri. Ilusi Kewirausahaan ini pada akhirnya dihadapkan oleh banyak beban berat yang harus ditanggung oleh kurir pengirim barang.
Pemindai yang berfungsi sebagai peranti dalam cerita, merupakan barang yang dipinjamkan perusahaan kepada Ricky. Benda ini mengatur alamat, daftar pekerjaan yang harus dilakukan, juga menjadi alat pelacak keberadaan paket. Pemindai ini menyimpan ketepatan waktu kurir dan data pelanggan. Pemindai mengatur pekerjaannya, jam kerjanya, juga target kerjanya. Alat ini pada akhirnya mengaburkan definisi kewirausahaan dalam pekerjaannya. Ricky yang semula yakin ia bekerja untuk dirinya sendiri, sekarang menyadari bahwa dirinya bekerja untuk pemindai tersebut.
Pemindai menjadi alegori pemegang modal atau si kapitalis. Ia tidak berwajah, berlindung dibalik nama perusahaan. Ia tidak peduli apa yang pekerja lalui, ia hanya ingin tugas yang tertera selesai. Dalam sebuah adegan, Ricky terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami pembegalan paket dijalan. Ia harus membayar biaya perawatannya sendiri, juga harus mengganti rugi barang hilang yang tidak punya asuransi. Pemindai yang dipinjamkan kepada Ricky hancur, sehingga ia juga harus membayar biaya ganti rugi.
Cerita pembodohan pekerja ini dikemas dengan subtil, seakan-akan apa yang disajikan dalam layar menjadi realita mutlak. Kamera ditempatkan jauh dari karakter, menggunakan lensa panjang. Pergerakan kamera juga dibatasi kepada panning simpel. Loach mendorong perasaan “objektif” kepada penonton. Karakter terlihat jauh, dan kecil. Penonton ditempatkan sebagai peneropong dari jauh, menyaksikan kelicikan nyata si kaya dan kepelikan hidup si miskin. Kamera tidak dibiarkan masuk kedalam dialog diantara karakter. Mencegah penonton menghidupi kenelangsaan Ricky, dibatasi cukup menyaksikan tanpa bisa melakukan apapun untuknya. Meskipun penonton dihadirkan sebagai pengamat, keberpihakan Loach tetap jelas. Loach seakan memberikan kita teropong dan memaksa kita menyaksikan titik yang ia inginkan, mengisolasi titik lain yang tidak mendukung penceritaannya.

Kerja, Kerja, Kerja, Keluarga?
Sadar tidak sadar, ilusi ini telah masuk dalam sela-sela hubungan keluarganya, menggerogitinya sampai habis. Secara literal dan figuratif Ricky bersekutu dengan setan, menjual keharmonisan keluarga demi status tidak resmi sebagai wirausahawan. Dijanjikan glamornya kemadirian, juga kebebasan untuk menentukan kapan dan kemana ia bekerja. Semua kemungkinan buruk terbang menggocek kepalanya. Pada akhirnya realita lapangan yang membuatnya babak belur.
Ricky pernah jadi seseorang yang nyaman secara ekonomi. Ia berkeluarga dan memiliki rumah cicilan yang ia yakini akan lunas seiring waktu. Hingga keuangannya hancur bersama dengan resesi ekonomi tahun 2008. Sejak saat itu, Ricky hidup mengontrak bersama keluarganya, bekerja untuk bertahan hidup. Sampai pada akhirnya Ricky menemukan konsep kerja mitra ini. Dengan pekerjaan barunya, Ricky menjajikan kehidupan yang lebih layak kepada keluarnganya. Sepanjang film, Abby, Seb, dan Liza tidak diperlihatkan memiliki kekhawatiran pada kondisi ekonomi keluarganya. Ironisnya, mereka bahagia dalam kesederhanaan. Namun, semua berubah, ketika Ricky memutuskan untuk mengambil bagian dalam bisnis zero-hour contract.
Abby terpaksa menjual mobil yang ia gunakan untuk bekerja demi memberikan Ricky modal mobil van pengantar barang. Imbasnya, untuk berangkat kerja Abby terpaksa naik transportasi umum dan menghabiskan sepanjang hari di jalan. Abby menjadi orang tua yang semu, yang tidak dapat hadir dalam apapun. Abby tidak punya waktu untuk merawat keluarga, dalam banyak scene ditunjukkan bahwa Abby hanya dapat berkomunikasi pada Liza dan Seb lewat voice mail yang ditinggalkan. Abby yang ironinya adalah seorang perawat orang tua, perlahan-lahan mulai gagal dalam merawat relasi keluarganya. Dalam banyak scene ditunjukkan keretakkan emosi Abby.
Liza dipresentasikan sebagai anak bungsu yang polos. Ia menderita Insomnia, dan ketidakhadiran orang tuanya tidak membuat jam tidurnya lebih baik. Liza mengemban tugas sebagai seorang ibu akibat absennya Abby. Liza menjadi lem terakhir yang terlalu dini dipaksa untuk merekatkan keluarga. Dalam satu adegan, Liza bahkan menyembunyikan kunci mobil Ricky. Motivasinya adalah agar Ricky bisa berhenti bekerja dan keluarga Turner menjadi keluarga yang utuh sekali lagi.
Seb tergambar sebagai anak sulung yang tidak mengerti keadaan keluarganya. Film seakan-akan membuatnya sebagai lawan tanding bagi Ricky. Perilaku destruktif Seb seringkali berkontribusi pada kerenggangan keluarga Turner. Seb seorang seniman graffiti memilih untuk berada dijalan daripada menghabiskan waktu di sekolah. Jika digali lebih dalam, karakter Seb dapat dibaca sebagai anti-tesis karakter Ricky. Ricky dan Seb sama-sama mengerti dampak sistem kapitalisme pada kemiskinan mereka. Yang berbeda adalah cara 2 karakter ini menghadapinya. Ricky digambarkan sebagai seorang pekerja yang jatuh dalam dunia kerja yang eksploitatif. Ia tahu kehidupan tidak adil dan satu-satunya jalan adalah bekerja. Ricky sangat terstruktur dan displin. Ia bekerja 14 jam sehari tanpa mengeluh.
Di sisi lain, Seb adalah seorang seniman dengan jiwa bebas. Ia mengerti bahwa pekerjaan ayahnya hanyalah hidup dalam sistem yang mengeksploitasi. Seb menjadi seorang pribadi pemberontak. Menolak sekolah, juga menolak menjadi seorang Ricky. Dinamika karakter yang bersebrangan ini disatukan diakhir film. Dalam scene pasca Ricky babak belur di rumah sakit, Ricky memaksakan diri untuk bekerja. Seb berusaha semaksimal mungkin mencegahnya, berkata bahwa Seb hanya ingin Ricky berhenti bekerja menjadi kurir lepas, Seb ingin semuanya kembali seperti semula.
Ricky meyakinkan dirinya bahwa ia bekerja keras demi keluarganya. Kemandirian ekonomi dirasa menjadi kunci membahagiakan keluarga. Nyatanya, diakhir film, ketiga karakter berada pada titik terendah, semua akibat Ricky dan ambisinya. Ia bukan bekerja demi keluarganya, ia bekerja demi egonya.

Loach dan Kelas Pekerja
Sorry We Missed you membahas secara ekstensif bagaimana perusahaan menggunakan ilusi entrepreneurship untuk memploroti kurir demi keuntungan sebesar-besarnya. Pekerja tidak diberikan biaya libur, tidak diberikan asuransi kesehatan, tidak diberikan asuransi kecelakaan kerja, dan tidak difasilitasi membentuk serikat pekerja. Ricky memikul beban yang seharusnya dipikul oleh perusahaan dan mengorbankan keluarganya dalam proses ‘rags to riches’ yang ia konstruksi di kepalanya.
Sejalan dengan arah politiknya, Loach kerap menggambarkan bagaimana kapitalisme bekerja dalam rupa-rupa bentuk. Kemiskinan struktural lewat Kes (1969), ironi buruh yang tidak bisa menikmati hasil kerjanya lewat Riff-Raff (1991), perlawanan terhadap janji palsu sistem tunjangan kesehatan lewat My Name Is Joe (1998) dan I, Daniel Blake (2016), Ken Loach tidak berhenti menyajikan keberpihakan kepada pekerja yang tertindas dan menyajikan seluruhnya secara jujur.
Cerita soal kelas pekerja tidak hanya digambarkan dalam realitas sosial di Inggris. Indonesia juga mengalami cerita kelas pekerja serupa. Salah satunya, Viriya Singgih, seorang wartawan Project Multatuli melakukan eksperimen sosial dimana ia menjajal pekerjaan sebagai kurir mitra Shopee Express. Ia mempublikasikan essay tentang pengalaman pahit manis menjadi seorang pekerja mitra, khususnya kurir barang. Terdapat banyak pararel dari esai Singgih dengan cerita Ricky. Aplikasi Shopee yang menilai kinerja kurir menjadi subtitusi tracker. Interview kerja terasa seperti briefing dengan ketidakadaan persetujuan jalan tengah. Tidak sebandignya usaha dengan hasil kerja. Ketidakhadiran jaminan kerja.
Keharusan mengganti produk yang hilang dan rusak. Kesialan-kesialan yang dialami Ricky dan Singgih menjadi refleksi bahwa Kapitalisme ada dimanapun, dengan bentuk yang sama. Seluruhnya memiliki dampak yang cukup menjengkelkan bagi teman-teman pekerja yang menjadi penopang bentuk ekonomi. Lewat Sorry We Missed You, Loach memotret eksploitasi kapitalisme dalam ekonomi digital. Sorry We Missed You menjadi rekaman adaptasi kapitalisme yang semakin pandai mengibuli kelas pekerja. Entah dalam selimut Zero-hour contract, atau dengan nama yang lebih bersahabat seperti pekerja mitra, sistem ekonomi yang masih dikuasai sekelompok individu akan selalu merundung pekerja kecil.
Sorry We Missed You | 2019 | Sutradara: Ken Loach | Pemeran: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Ketie Proctor, Rhys Stone | Negara Asal: Inggris| Durasi: 101 menit
Penulis : Indigo Gabriel Zulkarnaen
Indigo Gabriel Zulkarnaen

Mas-mas biasa yang suka sinema


0 notes
Text
Love: Bukan Sekedar Film Porno Estetik

Beberapa waktu lalu aku sempet ngeliat tanggapan teman-teman sinefil tentang video di YouTube, konten dongeng alur film yang nyeritain tentang alur satu film dan dikasih judul yang ‘mengundang.’ Dengan diksi-diksi yang eeeggghhh 18+ menjijikkan, tapi sebenarnya familiar buatku. Kayak genjot misalnya. Kecuali serabi lempit. Anjir lah aku baru denger diksi gituan.
Parahnya, film-film yang dijadikan konten itu bukan bergenre drama erotis atau film syur yang seolah-olah jualannya cuma adegan seksnya. Clickbait banget. Seolah ingin mengalahkan video-video Atta Halilintar di channel YouTube yang bergelimang clickbait dari zaman dia masih bujang sampai sekarang udah nikah.
Nah karena konten dongengin alur film itu cukup meresahkanku juga, aku jadi mikir kenapa channel-channel YouTube itu nggak nyeritain film drama erotis aja sekalian? Bukan, bukan Fifty Shades of Grey (2015), itu nanggung. Bukan juga 365 Days (2020), yang adegan enak-enaknya bentrok sama lagu-lagu pengiring adegannya yang anjeeeer itu lagu siape faaak ngerusak momen vulgar aja. Tapi film... Love (2015), yang lahir dari seorang Gaspar Noé, om-om mesum dari Prancis yang biasa menggeluti film-film erotis fantastis adegan seksnya bikin mendesissssss.
Love (2015) adalah film erotis kontroversial dari sang sutradara, yang tanpa malu-malu menampilkan adegan seks sebagai bumbu cerita. Atau dalam kasus film ini, adegan seks adalah bahan utamanya. Jor-joran. Pas nonton bikin ngerasa berlumur dosa berlipat ganda karena adegannya kelewat terbuka. Seolah mengolok-ngolok film erotis serupa yang para pemainnya masih pakai daleman atau adegan enak-enaknya di-shoot cuma dari atas atau bahkan dari belakang. Film ini saking jor-jorannya, sempat kuanggap sebagai film porno estetik, yang memperluas cakrawala akan seks layaknya buku [GP1] Homo Deus yang memperluas cakrawala akan ilmu pengetahuan (dan pedekate). Sekaligus berdampak negatif buat anak polos kayak aku. Bikin aku jadi phobia threesome.
Aku mikir kenapa para kreator konten dongeng alur film itu nggak nyeritain film ini aja?
Mungkin ada kali ya. Cuman nggak keangkat. Atau mungkin memang nggak ada? Secara nyeritainnya rada susah akibat alur filmnya ini nggak runut. Maju mundur saaay kayak dua karakter utama filmnya. Maju mundur melancarkan hentakan keras antara dua alat vital. Yang biasanya ngehasilin bunyi pok-pok-po---
OKE CHA STOP CHAAA NGGAK USAH DIKASIH TAU JUGA BUNYINYA KAYAK GIMANAAA.
So, di hari yang Fitri ini, aku tergerak buat nge-review film kotor yaitu Love (2015). Full spoiler. Aku gagal menjaga izzah dan ma’ruahku. Dosaku dimulai dari 0 lagi dengan nge- review film ini. Kayaknya. Sialan. Semua gara-gara konten dongeng alur film!!!!!!!!
Sebelumnya aku udah pernah nonton film ini sih, dan aku pernah review juga di blogku tapi dalam bentuk tulisan wawancara dengan orang yang udah nonton. Waktu itu aku nggak ngerasain emosi kedua tokoh utamanya selain pas mereka lagi melakukan pergulatan kelamin. Ketika mereka lagi ngobrol seperti manusia pada umumnya, aku nggak ngerasain emosi apa-apa. Vibe mereka sebagai pasangan bahagia, pasangan yang lagi berantem, pasangan yang lagi bersedih, itu nggak nyampe ke aku. Aku mikir film ini nggak ada rasanya. Cuma sekedar film porno yang estetik dan artsy, dengan sinematografi yang indah dan tegas.[GP2] Warna filmnya yang didominasi dengan warna merah membuat film ini terkesan seksi bukan hanya karena adegan buka-bukaannya. Pun dengan adegan selain adegan seks, yang indah padahal sederhana. Contohnya adegan berantem di mana dua tokoh utama debat kusir di mobil tapi terlihat indah padahal cuma siluet mereka berdua. Gils nyeni banget!!!! Belum lagi dengan para pemainnya yang good looking. Memanjakan mata sampai bikin celana mendadak ketat karena si ‘adik’ terbangun dan ingin berdiri. Bahkan menakutkan buatku karena banyak penampakan tititnya si karakter utama. I know, penismu tinggi besar gemuk, Mas Karl Guzman. Tapi ya nggak EJAKULASI DEPAN KAMERA JUGAAAAAA.
Terus tentu aja adegan threesome-nya yang menyeramkan itu. Aku mikir apa enaknya threesome sih? Udah harus berbagi pasangan, capek, bagi-bagi tugas...
Maka dari itu aku nggak terhubung sama film ini. Hingga aku bilang film ini nggak ada rasanya. Aku suka Gaspar Noé. Aku suka Irreversible (2002), yang sekaligus aku benci. Itu adalah bukti aku ngerasa terhubung sama Irreversible. Sedangkan sama film ini?
Tapi... itu pemikiranku beberapa waktu lalu. Karena pas aku nyoba nonton lagi, aku ngerasain hal berbeda. Yang aku sendiri heran kenapa aku baru sadar sekarang. Aku auto keluar dari barisan orang-orang yang 'sinis' sama film ini.
Love bercerita tentang Murphy (Karl Guzman, mantan suami Joe Kravitz, salah satu perempuan terseksi di dunia), yang udah berkeluarga dengan istri dan anak yang masih kecil. Di pagi awal tahun baru, Murphy dikejutkan dengan telpon dari ibunya si mantan. Tahun baru tapi dijejelin kenangan lama.
Murphy pun jadi terkenang akan Electra (Aomi Muyock), sang mantan. Yang putus sama dia akibat dia ngehamilin Omi (Karla Kristin). Perempuan yang jadi rekan threesome dalam semalam sewaktu mereka masih pacaran. Perempuan yang sekarang jadi istrinya dan ibu dari anaknya. Kentara banget Murphy nikah sama Omi karena terpaksa. Dia cintanya sama Electra. Dia nggak bisa moveon.
Murphy mengajak para penonton untuk ambyar bersamanya dalam kenangan-kenangan semasa pacaran sama Electra. Ya film ini 80%-nya adalah momen-momen kebersamaan mereka berdua, yang sebagian besar diisi dengan adegan bercocok tanam alias ngewe dalam berbagai gaya. Sedangkan 20%-nya adalah resiko yang harus ditanggung dari perbuatan menghamili Omi. Bahaya threesome. Kamu bisa selingkuh dan diputusin pacarmu.
Yaaa tapi itu pemikiranku dulu. Setelah nonton ulang, ternyata lebih dari itu.
Ternyata nggak perlu kehamilan Omi untuk bikin Murphy dan Electra putus. Murphy memang bangsat dari sananya jauh sebelum ketemu Omi. Hubungan mereka udah lama nggak sehat. Sebelum ada Omi, mereka udah berantem. Sebelum ada Omi, Murphy memang suka celap-celup ke cewek lain, tapi selalu balik ke Electra. Mereka punya banyak alasan untuk putus selain karena Omi. Aku jadi kasihan sama Omi karena dia masih belasan tahun plus dinikahin karena terpaksa pula. Aku juga kasihan sama Electra yang dikhianatin dan sekarang nggak tau nasibnya gimana. Entah bunuh diri atau tenggelam dalam obat-obatan terlarang. Okelah ide buat threesome itu dicetuskan sama Electra, tapi itupun karena ditanya Murphy. Kalau Murphy nggak nanya, nggak bakal kejadian. Kalau Murphy-nyaprofessional cukup threesome aja nggak usah ngewe lagi sama Omi, nggak bakal kejadian Omi hamil. Hhhhhhh keseeeeel.
Gils. Aku mulai ngerasain ada emosi di film ini. Aku udah kayak ibu-ibu yang suka reflek ngatur plot sinetron pas lagi nonton. Harusnya begini, harusnya begitu.
Aku juga mulai ngerasain kalau film ini bukan sekedar film dengan referensi enak-enak yang berlimpah. Di mana ada handjob, blowjob, missionary, doggy style many style (dari nungging, baring sampai berdiri), threesome, cowgirl alias woman on top, restroom attendant, sampai enak-enak dengan transgender. Benih-benih aku memandang film ini bukan hanya sekedar itu pun tumbuh.
Aku jadi ingat kalau aku pernah baca entah di mana aku lupa, yang jelas itu tentang selingkuh bagi cewek dan cowok itu beda. Selingkuhnya cowok bisa ke mana-mana tapi hatinya tetap milik pacarnya dan ujung-ujungnya balik lagi ke pacar. Sedangkan kalau selingkuhnya cewek itu pakai hati, jarang ada yang bisa balik lagi ke pacar. Itu omong kosong buatku, sampai akhirnya aku nonton film ini dan jadi kepikiran. Jangan-jangan memang kayak gitu? Jangan-jangan itu yang terjadi sama Murphy?
Dengan berlandaskan udah ada rasa sama film ini, aku menyimpulkan kalau... ya. Murphy kayak gitu. Pun dengan Electra yang pengen threesome. Mungkin itu bentuk cinta yang tulus melihat pasangan dibahagiakan orang lain versi Electra. Omi yang legowo ngeliat suaminya masih galauin mantan di saat anak mereka lagi sakit, mungkin juga bentuk cinta. Omi cinta keluarga kecil mereka, karena kontra sama aborsi. Omi sendiri lahir dari kehamilan yang nggak diinginkan, btw. Dia bersyukur dia nggak jadi diaborsi dan tentu aja, dia nggak mau anak hasil kondom sobeknya Murphy diaborsi.
Bentuk cinta lain yang aku dapatkan adalah kecintaan Murphy pada impiannya sebagai sutradara. Murphy sendiri adalah sinefil dilihat dari poster-poster film di kamarnya. Salò, orthe 120 Days of Sodom (1975), M (1931), The Birth of a Nation (1915), Taxi Driver (1976), dan Freaks (1932). Murphy juga menyebutkan 2001: A Space Odyssey (1968) sebagai film favoritnya di obrolan pedekate wasweswos fafifunya dengan Electra. Dia bilang pengen bikin film dengan sudut pandang seksual, yang menyeret aku ke pemikiran kalau Murphy ini kok kayak Gaspar Noé...
Ditambah nama mantannya Electra itu Noé. Nama anaknya Murphy itu Gaspar. Pas aku obok-oboktrivia film ini, namanya Lucile mantannya Murphy itu nama istrinya GasparNoé yaitu Lucile Hadzihalilovic. Nama Murphy diambil dari nama belakang ibunya, yaitu Nora Murphy. Terus 2001: A Space Odyssey (1968), ternyata adalah film favoritnya Gaspar Noé. Alasan Karl Guzman direkrut jadi Murphy, awalnya karena ditanya film favoritnya apa terus dijawab Enter the Void, filmnya Gaspar Noé tahun 2009.
Sampai sini aku mikir kalau GASPAR NOÉ NARSIS BANGET ANJEEEEEEEEEER. Semuanya yang ada di film ini berkaitan sama diaaaaaa. Gilssssssssss. Film ini bentuk kenarsisan yang sungguh absolut.
Lama-lama aku jadi mikir kalau... oke. Itu bukan narsis. Itu mungkin bentuk cinta. Gaspar Noé sebegitu cintanya sama film ini, sampai sebenarnya terbuatnya Irreversible (2002) karena pengen brojolin film ini. GasparNoé passionate memuncratkan pemikiran-pemikiran soal kalau cinta dan seks sungguh berkaitan itu lewat film ini. Gaspar Noé menikmati julidan-julidan pedas soal film ini dengan bilang,
"Saya menikmati ulasan-ulasan itu. Kau akan merasa lebih senang dengan ulasan yang lebih menghina dibanding yang bagus. Ulasan yang bagus membantu filmnya tetap ada, namun yang memberikan ulasan jelek membantu mendapat semacam rencana balas dendam, dan bersemangat untuk film selanjutnya."
Begitu sabda Gaspar Noé, seperti yang kukutip dari artikel CNN.
Gaspar Noé mengekspresikan dirinya lewat film ini. Melakukan hal yang disuka. Yang bikin aku mikir kalau film ini Gaspar Noé mencintai dirinya sendiri dengan berkarya lewat film ini.
Love (2015) bukan soal Murphy, bukan soal Electra, bukan soal Omi, bukan soal titit ejakulasi depan kamera. Film ini soal Gaspar Noé. Film ini adalah bentuk percaya pada apa yang diyakini, nggak peduli kata orang karena yang dia pedulikan adalah rasa senangnya. Gaspar Noé bersenang-senang dengan ide film ini dan eksekusinya. Film ini bentuk menolak insecure. Film ini ternyata soal... self love.
Ternyata di balik banyak hal-hal negatifnya, film ini sepositif itu. Ketika Murphy membuat Omi positif hamil, Gaspar Noé membuat pikiranku akan film ini dari negatif jadi positif. Film ini bukan ngajarin soal seks. Tapi soal self-love. Aku jadi tersadar kalau aku harus bisa seyakin dan se-passionate Gaspar Noé kalau mau ngelakuin sesuatu.
Oke. Ini film bersih untuk Idul Fitri. Nggak jadi film kotor. Karena self-love itu termasuk bentuk rasa syukur. Allah mencintai hamba-Nya yang pandai bersyukur kan?
Desain : Nona Damanik
Love | 2015 | Sutradara: Gaspar Noe| Pemeran: Aomi Muyock, Karl Glusman, Klara Kristin | Negara Asal: Perancis, Belgia | Durasi: 135 Menit | Produksi: Les Cinémas De La Zone
Icha Hairunnisa

Perempuan melankolis yang nulis review film karena buat kedok aja supaya bisa curhat di tulisan. Mengharapkan dia bisa menulis intelek sama dengan mengharap Gaspar Noe menggarap film religi. Budaknya film-film romance, komedi, dan... erotis.


1 note
·
View note
Text
Turah : Memantik Kepekaan Meski Berujung Kalah.

Sebuah kampung yang asing—atau lebih tepatnya diasingkan—menjadi penopang hajat hidup segelintir orang yang kurang ‘beruntung’. Kampung Tirang, di mana Turah (Ubaidillah) dan warga lainnya tinggal dan menggantungkan hidupnya kepada juragan kaya, Darso (Yono Daryono). Warga Kampung Tirang saban hari bekerja untuk si juragan dan menerima upah yang membuat mereka tidak bisa berharap lebih—hanya mampu menutupi kebutuhan sehari-hari.
Kita bisa merasakan bagaimana Kampung Tirang sangat dikucilkan melalui visual yang disuguhkan di film ini. Wicaksono Wisnu Legowo, sebagai sutradara Turah (2016) berhasil menyajikan itu kepada penonton. Hal ini bisa dilihat dari misalnya, akses menuju Kampung Tirang menggunakan getek, lalu di balik pagar beton di seberang Kampung Tirang yang dibatasi sungai, dapat dilihat lahan industrialisasi dengan bangunan megah. Jaraknya hanya dibatasi sungai kecil, tapi ketimpangan ini jauh ke dasar relung kehidupan yang ada.
Darso sebagai juragan memiliki sumber pundi-pundi keuangannya. Kolam ikan menjadi sentral bisnisnya, disusul dengan ternak kambing. Rumah-rumah yang ada di Kampung Tirang relatif sama dari segi arsitekturnya. Listrik di kampung ini menggunakan mesin manual yang dinyalakan saat malam hari. Konon, Kampung Tirang ini milik Darso dan sebab itulah sudah semestinya mereka bekerja untuknya. Di Indonesia, dalam skala besar kehidupan seperti ini kita bisa melihat pada kebun-kebun kelapa sawit di pedalaman daerah dengan rumah mungil yang dijatah dan penyalaan listrik dibatasi waktu sesuai kemauan perusahaan.
Upaya Memantik Api Perlawanan
Konflik dalam film ini bermula ketika Jadag (Slamet Ambari) merasa diperlakukan tidak adil oleh Darso dan seorang mandor, Pakel (Rudi Iteng) seorang sarjana yang sangat licik. Di bagian ini kita akan bertanya-tanya siapa sebenarnya pemeran utamanya. Sementara Turah, yang namanya menjadi judul film, direbut setir kemudinya oleh Jadag.
Pakel memonopoli segalanya demi kepentingan personal dengan sangat kasar, sehingga Jadag bersikeras melawan Pakel. Tapi bukan berarti si juragan Darso tidak memonopoli keadaan itu, paling tidak ia memetik buah hasil kerja liciknya Pakel. Darso yang bersikap baik dan sangat ramah kepada pekerjanya juga membuat keberadaannya untuk disegani dan ditakuti warga Kampung Tirang.
Dalam beberapa adegan, tampak Darso bersikap sangat baik kepada pekerjanya. Misalnya saat Turah meminta kenaikan gaji dan langsung diaminkan Darso, saat Kandar (Bontot Sukandar) yang bekerja menjaga kambing ditanyai perihal kebutuhan guna menunjang pekerjaannya dan memintanya agar berterus terang mengatakan apa saja yang dibutuhkannya. Bahkan ketika adegan Darso menjenguk seorang anak dan neneknya yang sakit-sakitan di gubuk reot, di mana Darso memberikan uang kepada mereka. Tapi sikap manipulatif seperti itu sama sekali tak melunturkan kepekaan Jadag. Dimulai dari Turah sampai ke Kandar, Jadag menjalankan propaganda yang menjadikannya sebagai pemantik kepekaan. Misalnya saat Jadag bercerita ke Turah bahwasanya dia stres karena kerja bertahun-tahun tapi upahnya segitu-gitu saja, sedangkan Pakel baru kerja tiga tahun sudah diangkat jadi mandor hanya karena bergelar sarjana. Jadag juga mengatakan mereka tak seharusnya menuruti semua aturan yang dibuat Darso dan Pakel, karena seharusnya Darso yang membutuhkan mereka karena kalau mereka semua tak mau bekerja untuk Darso, juragan itu akan kelabakan. “Tuyul disuruh kerja?” kata Jadag.
Propaganda itu tidak berjalan mulus, bahkan Turah sendiri memilih jalur kompromi. Ditambah lagi kehidupan Jadag yang problematis, baik dalam rumah tangga maupun dengan orang-orang di lingkungannya. Hal itu kerap kali menjadi pemicu orang-orang di sekitarnya menyepelekannya meski upaya-upaya yang dilakukan Jadag itu penting.
Wicaksono menyiratkan bahwa sebagai individu, kita tidak bisa memaksakan untuk mengubah sifat individu lainnya. Manusia hanya dapat memberitahu apa yang dianggapnya benar, dan berharap orang lain sepakat dan mengaminkan pernyataannya. Namun film ini juga menjelaskan ketika orang lain tidak setuju dengan kita—terutama orang yang sama-sama kalah—bukan berarti menjadikannya sebagai bulan-bulanan selama tujuh turunan. Hal itu ditekankan pada hubungan Turah dan Jadag yang tetap menjadi rekan di Kampung Tirang.
Rudolf Rocker (1938) berpendapat bahwa pekerja tidak boleh bersikap masa bodoh dengan kondisi ekonomi kehidupannya dalam masyarakat, ia juga tidak boleh bersikap masa bodoh dengan struktur politik negaranya. Baik dalam perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun melakukan beragam propaganda yang mengarah pada kebebasan sosialnya, ia membutuhkan hak-hak dan kebebasan politik, dan ia harus berjuang untuk dirinya sendiri setiap kali hak dan kebebasan mereka disangkal.
Agaknya apa yang dilakukan Jadag sesuai dengan pendapat Rocker dalam lingkup yang lebih kecil namun sama pentingnya dalam kehidupan manusia. Pada Jadag bisa dilihat bahwa titik serangan dalam perjuangan bukan terletak pada mereka yang mempekerjakannya dengan berharap kebaikan mereka, melainkan pada masyarakat itu sendiri—pada pekerja itu sendiri. Kepatuhan terhadap sistem yang diterapkan Darso pada pekerjanya, sama sekali tidak menjamin kebutuhan sehari-hari dan hak lainnya.
Majikan dalam hal ini Darso, akan segera menyiksa pekerjanya jikalau menuntut hak yang seharusnya dimiliki mereka, dan ini menggambarkan watak asli majikan tersebut. Jika pun majikan bersikap baik pada pekerjanya, yang seharusnya dilihat bukan bentuk kebaikan apa saja yang dilakukan majikan, tetapi alasan mengapa majikan itu berbuat baik kepada pekerjanya.
Menuju Ranting Gantung
Karakteristik Turah, Jadag, dan warga Kampung Tirang lainnya sangat mewakili sikap pesimistis. Turah dengan pembawaan yang kalem sepanjang film ini menunjukkan betapa begitulah hidup adanya. Keterasingan Turah dan warga lainnya yang hidupnya dipandang sebagai angka catatan penduduk sehingga dibutuhkan saat menjelang Pemilu saja bukanlah persoalan tunggal melainkan struktural. Begitu juga kematiannya kelak hanya sebagai data statistik negara menjelaskan ketidakberharganya mereka sebagai manusia.
Mereka benar-benar harus melakukan segalanya dengan mandiri, karena majikannya—dalam lingkup lebih luas, negara—sebenarnya tidak peduli dengan keberlangsungan mereka yang hidup di atas ‘seonggok’ tanah bernama Kampung Tirang. Turah menyadari ini sepenuhnya, bahwa keadaan hidupnya sudah mentok, tidak dapat lebih baik lagi meski sejengkal. Hal itu juga disadari istrinya, Kanti (Narti Diono) yang dijadikannya pledoi untuk memutuskan tidak memiliki anak. Kanti benar-benar tak bisa membayangkan betapa mengerikannya hidup anaknya jika persis dengan apa yang dialaminya saat ini.
Berbeda dengan Turah, pesimistis yang tampak pada Jadag lebih mengarah kepada fatalisme. Jadag menuntun kita untuk melihat bagaimana praktik nihilistik di Polandia yang dilakukan para tahanan di dalam Kamp Konsentrasi buatan Nazi dengan Adolf Hitler sebagai penggawanya. Karena tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab munculnya praktik nihilistik adalah karena pesimis dan keputusasaan terhadap suatu hal.
Serafinski dalam bukunya Blessed is the Flame (2016) menuliskan, tetapi ketimbang menjalani hidup untuk menunggu kebangkitan massa yang sepertinya tidak akan pernah terjadi, maka lebih baik untuk menyerang sekarang dan lihat ke mana tindakan tersebut membawa kita.
Begitulah yang terjadi pada Jadag. Ia menyerang mereka yang memang pantas untuk diserang dengan tanpa bekal apa pun, karena ia memang tak memiliki akses untuk mempelajarinya. Ia dihantam berkali-kali menyisakan lebam di wajahnya, bangkit lagi dan dihantam lagi bahkan dipenjara barang semalam saja. Sampai pada ia duduk menikmati selebaran kertas judi kesayangannya, turut jua kerangka tulang rusuknya yang tampak, dan malam yang dingin ‘memaksa’ dirinya agar mati dalam keadaan gantung diri di pohon ringkih di halaman rumahnya.
Turah | 2016 | Sutradara: Wicaksono Wisnu Legowo | Produser: Ifa Isfansyah | Pemeran: Ubaidillah, Slamet Ambari, Yono Daryono, Rudi Iteng, Narti Diono, Bontot Sukandar | Negara Asal: Indonesia | Durasi: 83 menit | Produksi: Fourcolours Films
Penulis : Bagus Pribadi
Desain : Nona Damanik
Bagus Pribadi

Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang skripsian. Agar tidak mengutuk waktu, ia nyambi jadi jurnalis di salah satu media lokal di Pekanbaru.


0 notes
Text
Antara Sekop, Telepon dan Kasir Kelontong :10 Pilihan Film Tentang Pekerja

Bicara soal buruh, saya menolak mentah-mentah definisi buruh yang semata-mata berkonotasi sebagai pekerja kasar yang lebih menggunakan tenaga (otot) ketimbang kemampuan intelektual (otak). Zaman telah berubah, kawand. Tatanan sosial telah berakselerasi, sistem feodalisme sudah berganti menjadi kapitalisme, revolusi fisik bertransisi menjadi perang tagar dalam kicauan Twitter, sementara filsuf seperti Karl Marx dan Friedrich Engels yang telah tiada mendapatkan pewaris layaknya dengan kemunculan tokoh-tokoh cendekiawan baru seperti Fiersa Besari dan Raden Rauf. Maka pendefinisian buruh juga mengalami pergeseran, tak lagi sesempit sebelumnya yang hanya diidentikkan dengan "pekerja kasar".
Garis demarkasi antara pekerja kerah biru dan pekerja kerah putih semakin kabur. Semua orang yang bekerja di sektor swasta dan mendapatkan upah, baik pada perorangan maupun lembaga tertentu, secara de facto, adalah seorang buruh. Seorang staff yang berbusana rapih dan bekerja di ruangan ber-AC dalam sebuah gedung perkantoran di wilayah Metropolitan hanyalah versi lain dari seorang kuli bangunan yang bekerja sembari menahan teriknya matahari di kawasan kota kabupaten. Kendatipun kontras, hubungan mereka sama-sama dapat dimaknai secara horisontal. Sekalipun kegiatan kerja dan nominal upahnya tak sama, secara status, baik pekerja kasar ataupun pekerja profesional, mereka adalah buruh. Undang-undang (yang sejujurnya saya lupa UU mana) sudah membunyikan landasan definitif: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun”. Hanya saja, karena kata "buruh" mengalami makna peyoratif dan cenderung merujuk pada golongan yang selalu ditekan di bawah pihak lain (majikan), maka istilah ini kemudian diupayakan untuk diganti dengan sebutan "pekerja", hingga kemudian kian diameliorasi dengan sebutan karyawan, profesional, freelancer, mitra, dan sejenisnya yang, sebetulnya mah, hanyalah alternatif nama lain dari “buruh” saja.
Mereka sama-sama diperah, dieksploitasi, sama-sama mesti tunduk pada pemegang otoritas tertinggi demi kesepakatan kompensasi (upah), yang kerap kali mencederai banyak hal dalam kehidupannya. Belum lagi jika berurusan dengan iklim kerja yang toksik, desakan kebutuhan materi di zaman neolib yang tidak sebanding dengan kondisi finansial, terjebak dalam kemiskinan struktural, dan tetek-bengek lainnya yang bisa-bisa membentuk sebuah mozaik dalam mengartikan beraneka macam kepiluan yang menyertai para pekerja di tengah cengkeraman borjuasi. Urgensi tersebut, tak jarang dimanifestasikan lewat medium film yang dari hari ke hari semakin membuang sikap malu-malu kucing untuk merespons persoalan aktual yang kian kompleks ini — baik secara tersirat ataupun tersurat. Bagaimana tuntutan dunia kerja mengorbankan banyak hal; termasuk cinta, hingga sikap penguasa yang terlalu blagak budeg untuk mendengarkan aspirasi pekerjanya, berikut kami merangkum film-film yang dapat kalian tonton di hari buruh yang fitri ini. Tidak semuanya spesifik mempersoalkan kehidupan buruh, namun setidaknya dapat membuat kita menyelami dunia kerja yang tak kenal kompromi, syukur-syukur cukup mampu mengobarkan semangat kita untuk berteriak "persenjatai buruh dan tani".
Turah (2017) – Wicaksono Wisnu Legowo

Andai berbentuk syair, Turah adalah elegi yang meratapi keputusasaan akan kemiskinan absolut. Jika dimaknai secara historis, Turah bisa jadi cerminan ketegangan akar rumput masyarakat Jawa pada era 1960-an (yang kemudian diakhiri dengan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern pada tahun 1965-1966: G30S PKI). Lebih dari segalanya, Turah adalah potret nyata ketimpangan kelas dan kemiskinan struktural yang tak berkesudahan. Bagaimana kerja-kerja eksploitatif bukan dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan napas pada suatu ekosistem, namun kerap menjadi modus penundukan sekaligus penindasan terhadap orang-orang yang lemah, dan hal demikian telah diyakini sebagai keniscayaan. Letaknya di Kampung Tirang, lingkungan yang berdiri di atas tanah timbul di pesisir pantai utara Tegal, diisi oleh wajah-wajah masyarakat pinggiran yang diselimuti asap kemiskinan selama bertahun-tahun lamanya mengabdi kepada juragan Darso — sosok yang mengklaim Kampung Tirang miliknya dan mempekerjakan warga sekitarnya sebagai buruh/budak. Ritus ekonomi yang kelewat batas dan nasib yang tak kunjung mengalami perubahan kemudian membiakkan gejolak amarah dan upaya penentangan kepada sang tuan tanah; meskipun belum tentu menang, yang penting sudi melawan.
Modern Times (1936) – Charlie Chaplin

Tiada henti-hentinya saya menyanjung sosok Charlie Chaplin. Karyanya senantiasa humanis sekaligus politis: bukan hanya menyentuh realitas sosial yang problematis lewat kemiskinan sebagai sorotannya, namun juga seakanakan meninju penguasa bajingan secara bertubi-tubi. Background-nya yang berasal dari kalangan bawah seolah memberikannya legitimasi untuk berpihak pada perjuangan rakyat kecil yang identik dengan kelas pekerja dan buruh. Modern Times adalah salah satu dari sekian pretelan Chaplin mengenai isu kelas. Sekuens pembukanya saja sungguhlah superior, memperlihatkan ritme kerja yang beringas di sebuah pabrik manufaktur ketika manusia (buruh) diharuskan untuk sinkron mengimbangi kecepatan mesin pabrik yang berkali-kali dipercepat demi melaju produktivitas. Tekanan kerja tersebut, kemudian diolah menjadi punchline menyegarkan dalam adegan berikutnya manakala Tramp (karakter yang diperankan Chaplin) mendadak hiperaktif selayaknya orang kesurupan dan menciptakan kekacauan pada seisi pabrik. Menyaksikannya, saya merasa berdosa telah melampiaskan gelak tawa yang sangat kencang.
In the Mood for Love (2000) – Wong Kar-wai

Berlatarkan Hong Kong pada dekade 1960-an, masa ketika industrialisasi berjalan sedemikian masif, Wong Kar-wai menggagas kisah romansa yang terjalin di antara dua tetangga lewat kesadaran modernitas yang kuat. Memang, In the Mood for Love berpusat pada keanggunan asmara platonik di antara Mr. Chow (Tony Leung) dan Mrs. Chan (Maggie Cheung). Namun, hulu dan hilirnya berada tepat menyasar pada basis kerja masyarakat modern dalam lanskap urban industrial, yang semakin menggerus kebutuhan akan ruang nan intim. Mr. Chow sebagai representasi kelas pekerja, buruh berdasi yang berdandan necis, memijakkan plot cerita dengan tandas manakala tuntutan dunia kerja jurnalistik mengintervensi waktu dan ruang privatnya sehingga memicu ketidakhadiran istrinya (dan juga suami Mrs. Chan yang juga diperbudak kesibukan). Tersirat sistem dunia kerja yang bahkan tak mengenal ketetapan waktu (tidak otoritatif), dampak dari neoliberalisme yang senantiasa membisikkan budaya konsumtif sehingga kian meringkus lebih banyak lagi nilai (ruang dan waktu) dari sang pekerja demi kebutuhan ekonominya, dan pada akhirnya, sosok seperti Mr. Chow diposisikan sebagai precariat, yang tak ubahnya menjadi simbol dari proletariat (kelas pekerja) yang berada pada kondisi rentan.
Indonesia Calling (1946) – Joris Ivens

Pertama kali tergugah akan dokumenter berikut karena insight dari Profesor Ariel Heryanto yang sempat menukil bahwasanya Indonesia tidak merdeka sendiri, kemerdekaan Indonesia tak lepas dari kontribusi bangsa tetangga. Sampailah saya menyaksikan film yang disebut-sebut sebagai film awal yang merekam gagasan kemerdekaan ini, yang mana partisipasi serta signifikansi dukungan serikat pekerja di Australia dalam jalan menuju kemerdekaan Indonesia ditampilkan secara patriotik; pengetahuan yang bahkan belum pernah saya dapatkan sebelumnya dalam kurikulum sejarah maupun dongeng turun temurun dari kakek buyut saya yang paling lantang membicarakan sejarah. Ikatan solidaritas yang singset di antara buruh lintas-negara di Australia termaktub lewat aksi pemboikotan dan mogok kerja demi menentang agresi militer Belanda yang ingin berlayar ke Indonesia. Pemboikotan ini menyebar ke seluruh pekerja pelabuhan dan membuat lebih dari 550 kapal besar Belanda yang memuat amunisi persenjataan terbengkalai. Momen ini menjadi perhatian luas hingga mendapat dukungan dari para elit Australia, pemimpin partai, sampai serikat-serikat buruh, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Black Armada. Buruh-buruh dari Cina, India, dan Australia dipotretkan sebagai pahlawan, namun bangsa kita rasanya terlampau malu untuk mengakui ironi kepahlawanan lintas-negara berikut secara eksplisit dalam teks sejarah karena ditakutkan mencemari rasa chauvinisme yang tinggi, mungkin?
Sorry to Bother You (2018) – Boots Riley

Enaknya sinema tuh seperti ini, deh. Kita bisa concern mengenai segala wacana yang penting untuk diperbincangkan secara khusus dengan cara apapun: serius maupun bercanda, silahkan saja selama tidak tuna acuan. Di sini, Boots Riley mengiris-iris lapisan cerita yang mempunyai beragam wajah: kapitalisme, perbudakan, dan rasisme — serta memadukannya sebagai konsep hibridasi yang sempurna dalam memelesatkan kritik mahadahsyat kepada tatanan sosial (societiehhh). Premisnya sederhana saja, Sorry to Bother You membuka rajutan kisah lewat pekerja kulit hitam bernama Cassius (Lakeith Stanfield) yang menjadi telemarketing sukses karena kelihaiannya mengadopsi suara kulit putih untuk menarik perhatian pelanggannya (yak, ironi memang). Karirnya meroket sementara kawan-kawan seperjuangannya membentuk perserikatan untuk menuntut upah dan jam kerja yang layak. Namun, semakin Cassius dekat dengan hierarki status paling atas, ia mendapati konspirasi janggal dalam dunia kerjanya ketika atasannya, Steve Lift (Armie Hammer) mendiskusikan keinginan untuk membentuk dunia kerja yang baru. Tepatnya, dunia kerja yang lebih absurd untuk dapat mengubah tenaga manusia setara dengan tenaga kuda; tidak manusiawi, namun sempurna bagi sistem industri yang eksploitatif. Semakin durasi berjalan, gema schadenfreude semakin nyaring, apa yang layak dan tidak layak ditertawakan menjadi kabur, closure yang kian mempertegas balutan satir nan absurd semakin membuat mulut kita secara mau tak mau meresponsnya dengan "bajingan ngopo iki".
Marsinah: Cry Justice (2001) – Slamet Rahardjo

Perjuangan buruh saat ini hanyalah catatan kaki dari apa yang harus ditanggung Marsinah kala menjelma sebagai (saya sebetulnya geli memakai istilah ini) poster girl dalam memperjuangkan nasib buruh pada saat aspirasi buruh hanya dianggap pemanis mulut semata dan rakyat kita sedang diselimuti ketakutan akan rezim otoriter ala Soeharto; bapak presiden yang senantiasa menghiasi semesta per-meme-an di media sosial. Masyarakat online masa kini boleh saja leluasa melakukan ejekan-ejekan jahat untuk mengkritisi bobroknya Orba dahulu kala. Namun perlu digarisbawahi, bahwa hal demikian tak lebihnya seperti menggarami lautan: tegas, definit, tidak berisiko. Sebaliknya, pada masa Orba, jangankan mengejek, menyuarakan perbedaan pendapat, mengkritisi penguasa, menagih sustainabilitas publik, atau bahkan menjadi aktivis yang vokal sekalipun akan mengancam keselamatan nyawamu. Marsinah, mempunyai nyali yang cukup untuk melakukan hal tersebut, dan kisah tentangnya diabadikan ke dalam film semi-dokumenter berikut. Agak tak dinyana, ini bukanlah film biopik yang menarasikan kehidupan Marsinah lewat sudut pandangnya, melainkan semacam "mentahan" fragmen dalam mengobservasi sesosok Marsinah (dan kekejian Orba) melalui sudut pandang Mutiari. Ketokohan Marsinah seolah dimisteriuskan, memberi jarak kepada penonton untuk senantiasa mengaguminya, sehingga kian menjauhkan diri dari kubangan klise yang acapkali menjebak formula film sejenis: romantisasi.
Stachka (1925) – Sergei Eisestein

Sebelum Battleship Potemkin yang ikonis itu, Sergei Eisenstein, sineas pelopor montase asal Soviet, telah lebih dahulu meniupkan napas sosialisme yang mengharumkan lewat debutnya yang berdaya ledak ini. Diuraikan lewat enam chapter, Stachka tampil dengan tegas dalam menampilkan versi retelling dari Revolusi Rusia pada tahun 1905, yang mana demonstrasi buruh berakhir menjadi pemandangan kematian dan penyiksaan tiada tara yang dilakukan oleh pihak militer. Mulai dari pencambukan dan pembantaian para pekerja, brutalisme yang mempertontonkan seorang anak kecil naif yang dilempar dari lantai atas, tuduhan fitnah yang dialamatkan kepada seorang buruh hingga membuatnya gantung diri, sampai satir mahadahsyat yang memperlihatkan bahwa aspirasi buruh dari secarik kertas tak ubahnya seperti sebuah lap bagi para borjuis yang apatis itu. Sama seperti halnya Vladimir Lenin yang percaya bahwa sinema adalah medium multidimensional yang paling penting (...sebagai alat propaganda) karena dapat menjangkau massa yang lebih masif. Sergei Eisenstein sebagai salah satu seniman kiri juga meyakini kredo tersebut dengan sikap politisnya dalam merefleksikan kolektivisme para buruh yang memiliki perasaan senasib sepenanggungan yang kuat.
Clerks (1994, Kevin Smith)

Film ini memang bukan hal yang pertama muncul ataupun dipikirkan dalam benak orang saat membicarakan film tentang pekerja. Bagi saya, Clerks bukan hanya film tentang tongkrongan gejolak kawula pemuda amerika serikat yang diselingi dengan lelucon seputar kultur pop yang mungkin hanya dimengerti oleh orang yang tinggal di ibukota provinsi. Clerks adalah sebuah potret 24 jam bersama pekerja kelontong yang penuh dengan ketidakpastian dan terkadang, keabsurdan. Kevin Smith tidak ingin mengasihini penonton dengan kisah pekerja dengan cara banal atau bahkan terlihat seperti romantisme kemiskinan. Sebaliknya, ia menceritakan kisahnya dengan komedi menggelitik dengan sedikit bumbu sarkas. Clerks sejatinya merupakan potret pekerja kelontong umur dua-puluhan di amerika serikat yang sebenarnya tidak ingin memiliki pekerjaan itu, melainkan hanya untuk menyambung hidup.
Errorist of Season (2017, Rein Maychaelson)

Dampak perubahan musim di Indonesia tak hanya berdampak pada perbuahan iklim, suhu dan morfologi dari suatu daerah. Namun, ia juga berdampak tentang bagaimana relasi antara mata pencaharian ekonomi dan perubahan musim. Karena sepertinya tidak ada yang mau makan es krim di hari saat hujan mengguyur selama berhari-hari. Perubahan musim ini memunculkan kemungkinan praktik ekonomi yang baru seperti ojek payung, atau dalam film ini, ojek perahu karet.
Pulung, seorang pekerja pabrik baru dipecat akibat bahan baku yang naik dikarenakan banjir yang melanda di cina. Errorist of Season menampilkan realita terhadap pekerja yang dipecat dengan mengganti pekerjaan sebagai pengendara ojek perahu karet. Sama seperti Clerks yang tidak menampilkan potret buruh yang banal, Errorist of Season ditampilkan dengan jenaka dengan komedi satir yang cukup menggelitik. Errorist of Season menyampaikan bagaimana sistem praktik kapitalisme bekerja dengan sistematis; perubahan atau kejadian musim di Cina dapat memengaruhi praktik ekonomi di Jawa.
One Cut Of The Dead (2017, Shinichiro Ueda)

Jangan terkecoh dengan paruh awal di film ini yang menyajikan film horror murahan ala film kelas b. Ada baiknya rasa sabar anda dipertebal untuk duduk selama kurang lebih empat puluh menit dalam sajian film horror kelas b itu. Karena setelahnya Shinichiro Ueda memotret tentang bagaimana memilukannya nasib pekerja film di dalam Industri Film. Seorang pimpinan perusahaan televisi meminta seorang sutradara untuk membuat film zombie siaran langsung dalam satu kali take. Hal ini terdengar konyol untuk sang sutradara, namun demi sesuap nasi ia pun mau tak mau mengiyakan permintaan dari pimpinan tersebut demi rating yang tinggi. Film ini menggambarkan bagaimana relasi timpang antara pimpinan perusahaan terhadap para pekerja film. Realita bagaimana keinginan konyol dari pimpinan perusahaan memeras peluh pekerja film hanya demi jumlah rating dan keuntungan saja tanpa memikirkan keselamatan dan keamanan yang terjadi di dalam set film.
Penulis : Alana Putra & Galih Pramudito
Desain : Nona Damanik
Alana Putra

Senantiasa berdoa untuk dijauhi dari golongan o̶r̶a̶n̶g̶-̶o̶r̶a̶n̶g̶ ̶k̶a̶f̶i̶r̶ tujuh setan desa perfilman


0 notes
Text
La La Land: Mimpi Juga Bentuk Dari Jatuh Cinta.

Impian ternyata bukan cuma menjadi muara harapan tetapi juga bisa menjadi salah satu sumber rasa sakit. Demi impiannya, Sebastian rela untuk berpisah dengan Mia. Sebs memilih untuk tetap bertahan di Los Angles dan berjuang mendirikan sebuah Kelab Jazz klasik di tengah pasar musik yang semakin modern. Mia pun demikian, ia pergi ke Paris untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang aktris. Hal ini membuat mereka harus berpisah. La La Land membawa konsep dinamika romansa yang unik antara manusia dengan impiannya. Upaya menggapai cita-cita ini membawanya kedalam kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan bahagia, atau sebaliknya.
Sebs dan Mia sudah bersiap akan kemungkinan kandasnya percintaan mereka. Cinta seharusnya tak menghanguskan cita-cita seseorang. Kurang lebih itulah yang dipahami mereka. Sebs dan Mia sepenuhnya sadar kalau mereka menyerah dengan mengatasnamakan objek cinta mereka pada bentuk yang salah, maka semua impian mereka pun akan menjadi sesuatu yang dimaknai secara dangkal. Bukan lagi tentang apa itu memiliki sebuah klub jazz klasik atau menjadi aktris profesional.
Mimpi tak ubahnya menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi keduanya, namun Sebs dan Mia melebur perasaan sakit atas realitas impian mereka yang begitu terjal untuk dicapai pada bentuk cinta yang baru. Bagai seseorang yang melarikan diri dari sebuah realitas, keduanya tersadar bahwa apa yang sebenarnya mereka cintai hanyalah impian-impian mereka.
Mungkin mereka jatuh cinta kepada impiannya
Fromm (1956) memiliki pandangan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sebuah berkah yang dinamakan kesadaran atau awareness. Baginya, kesadaran ini meliputi bagaimana manusia sadar akan dirinya sendiri, sadar akan kemungkinan masa depannya, hingga sadar akan jangka hidupnya yang pendek. Diantara semua jenis kesadaran tersebut, ada satu yang mendasari manusia untuk terus menjalin ikatan dengan lingkungan sekitarnya yaitu kesadaran akan perpisahan atau yang juga disebut awareness of separation.
Manusia sedari lahir sudah sadar bahwa mereka adalah entitas yang terpisah antara satu dengan lainnya, mulai mereka dilahirkan (terpisah dari rahim ibu) hingga mereka meninggal (terpisah secara eksistensi dengan yang hidup). Hal tersebut pun menjadi akar dari segala bentuk kecemasan yang menghinggapi manusia sepanjang hidupnya, ketika keterpisahan dimaknai menjadi sebuah putusnya akses ataupun ketidakmampuan untuk bisa menjalin ikatan dengan dunia dan manusia secara normal.
Manusia pun selalu memiliki dasar dorongan untuk bisa mengatasi perasaan keterpisahan tersebut dengan berbagai cara salah satunya yaitu membentuk sebuah keterikatan yang bukan lagi bersifat orgiastik atau sementara tetapi keterikatan yang didasarkan pada sebuah keyakinan yang nyata. Fromm lebih lanjut berpendapat bahwa cinta tidak melulu tentang sebuah hubungan dengan orang-orang tertentu melainkan lebih dipahami sebagai sebuah sikap yang dicerminkan melalui bagaimana seseorang tersebut menjalin keterikatan dengan dunia di sekelilingnya secara utuh, bukan hanya pada satu objek tertentu saja.
Sebs dan Mia sadar bahwa eksistensi mereka memiliki konsep yang sama dengan manusia lainnya bahwa mereka adalah entitas yang terpisah satu dari lainnya, kesadaran yang merupakan akar dari segala jenis kecemasan ketika keterpisahan itu dimaknai sebagai terputusnya akses karena adanya jarak antara satu orang dengan orang lainnya yang hanya bisa dijembatani oleh sebuah objek yang disebut cinta.
Untuk mengatasi hal tersebut, Sebs dan Mia berulang kali berusaha untuk membentuk sebuah keterikatan antara satu sama lain. Musim demi musim mereka lewati bersama, dari jazz-date dan segala perdebatan mereka tentang musik jazz hingga momen di planetarium menjadi puncak perasaan antara keduanya. Namun nyatanya semua hal tersebut hanya bersifat orgiastik karena hal tersebut hanya merupakan jalan keluar sementara yang diciptakan dari sebuah kecemasan kesepian.
Pada akhirnya kecintaan mereka pada impian ini terlalu besar, Mia mulai mempertanyakan keseriusan Sebs akan impiannya tentang kelab jazz ketika Sebs sudah terlalu nyaman dengan kegiatan band yang dilakukannya. Sebs pun rela menjemput kembali Mia dari rumahnya ketika Mia mulai menyerah dan kecewa pada impiannya menjadi seorang aktris. Mereka memahami satu sama lain dan sadar bahwa yang mereka berdua butuhkan bukan kebersamaan satu sama lain tetapi bagaimana mereka bisa tetap menghidupi impiannya.
Mereka sadar bahwa bentuk cinta yang hadir diantara mereka bukanlah objek cinta yang sesungguhnya mereka yakini, Sebs dan Mia tahu bahwa kesadaran akan keterpisahan yang tidak dibarengi dengan pemenuhan objek berupa cinta yang tepat hanya akan memunculkan kecemasan-kecemasan baru. Sempat salah dalam mengatasi hal tersebut hingga tenggelam pada romansa semu, keduanya menyadari bahwa terdapat objek yang mampu membuat mereka bisa mengatasi perasaan keterpisahan tersebut yakni kecintaan mereka pada impiannya.
Keyakinan yang kuat terhadap mimpi mereka masing-masing membuat keterikatan yang terjalin pun tidak hanya bertahan sementara atau periodik. Tanpa keyakinannya, Sebs mungkin akan tetap jadi pemain band populer biasa dan membuang harga diri jazz klasiknya. Sama juga dengan Mia, mungkin akan tetap lanjut untuk studi-nya kalau aja dia gak punya keyakinan yang kuat untuk jadi aktris. Pada perkembangan yang semakin modern dimana musik jazz klasik mungkin sudah tidak memiliki tempat lagi di tengah kemajuan serta evolusi teknologi pada dunia musik, Sebs masih memegang teguh keyakinannya akan mimpinya untuk menghidupkan kembali klub jazz klasik. Mia pun sama, meskipun harus ditolak dan gagal berulang kali pada proses casting ataupun sepinya peminat pada dunia seni teater monolog tetapi ia tetap begitu mencintai impiannya.
Nyatanya bagaimanapun gilanya mimpi-mimpi Sebs dan Mia, dan betapa berliku-nya proses untuk pada akhirnya bisa mencapai semua yang mereka impikan, keduanya mengawalinya dengan bagaimana kuatnya keyakinan yang mereka miliki pada impiannya masing-masing. Meskipun terkadang impian yang mereka miliki terasa begitu jauh dan mustahil tetapi kecintaan mereka terhadap mimpi-mimpi itu sendiri sudah cukup sebagai pengingat untuk tidak pernah berhenti meyakini hal tersebut.
Epilog tragis, namun begitulah mimpi.
Fromm menjelaskan bahwa pada perkembangan masyarakat yang semakin modern, individu semakin jarang untuk memahami akar dari perasaan cinta mereka. Orang-orang terlalu berfokus pada hal-hal eksternal yang memiliki pengaruh dengan perasaan cinta itu sendiri seperti; kesuksesan, prestige, uang dan unsur kapitalisme lainnya. Pemaknaan pada konsep cinta ini pun tereduksi menjadi bentuk-bentuk yang dapat diterima secara kolektif. Ketika semakin banyak individu yang menganggap cinta hanyalah ilusi dan sementara, maka selanjutnya cinta berakhir menjadi sebuah komoditas yang melahirkan sesuatu yang cukup dangkal.
Premis tersebut menurut Fromm menghadirkan sebuah asumsi bahwa permasalahan terkait cinta selalu ada terletak pada objeknya, bukan pada kemampuan atau kapasitas untuk mencinta. Pada akhirnya, seseorang selalu berpikir bahwa konsep cinta merupakan sebuah konsep yang simple, tetapi bagaimana untuk menemukan objek yang tepat-lah yang membuatnya menjadi rumit. Maka dari itu, Fromm menjelaskan bahwa konsep cinta bukan lagi tentang kedekatan kepada objek tertentu melainkan bagaimana seseorang mampu menjalin keterikatan dengan dunia sekitarnya secara utuh.
Sebuah epilog indah tentang akhir kisah cinta Sebs dan Mia yang mungkin lebih diterima audiens ditampilkan. Kali ini, keduanya menjadi sebuah keluarga kecil, memiliki seorang anak serta hidup di dalam rumah yang bahagia layaknya keluarga normal. Ternyata kebahagiaan keduanya bisa dicapai dengan cara yang lain, jauh dari impian memiliki sebuah kelab jazz ataupun menjadi seorang aktris. Sepanjang sekuens, semuanya diperlihatkan begitu indah, beginilah perasaan cinta mereka berakhir jika menyerah pada impian-impiannya dan membiarkan cinta mereka menjadi dangkal.
Ternyata semua hal tersebut tetap hanyalah angan semata, sebuah akhir alternatif ketika Sebs dan Mia menyerah untuk terus mengejar impian mereka. Nyatanya, Sebs meyakini bahwa untuk memiliki kelab Jazz klasik tetap menjadi objek dari perasaan cintanya. Pun dengan Mia yang akhirnya berhasil menjadi seorang aktris yang terkenal sesuai apa yang selama ini ia perjuangkan. Mungkin akhirnya keduanya kehilangan apa yang mengikat mereka karena telah memilih untuk mengejar impian masing-masing daripada harus hidup bersama. Sebs dan Mia pun masih tersenyum kepada satu sama lain di akhir cerita, mengisyaratkan tidak ada sedikitpun penyesalan karena telah “berkorban” untuk impian masing-masing dan benar-benar berhasil mewujudkannya.
Here’s to the fool who dreams, Crazy as they may seem.
Penulis : Dicky Prastya
Desain : Nona Damanik
La La Land | 2016 | Sutradara :Damien Chazelle | Pemeran : Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt , John Legend, J.K Simmons | Negara Asal : Amerika Serikat| Durasi : 128 Menit | Produksi : Summit Entertaiment
Dicky Prastya

Penonton film biasa yang gampang ketiduran waktu nonton. Menulis ulasan di Dickbot Mufi, tapi lebih suka bikin puisi buat crush daripada nulis resensi film.

0 notes
Text
Klub Sinema Sisifus : Perfilman, Salatiga, dan Batu Berguling.

"Pada medio 2018, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam komunitas film kampus di Salatiga menggelar pemutaran film-film produksi mereka. Namun setelahnya, mereka harus dihadapkan persyaratan birokratis jika tetap ingin menjalankan kegiatan. Karena jengah, mereka kemudian memisahkan diri dari kampus dan berganti nama. Mereka menyebut kelompoknya itu Klub Sinema Sisifus”
Pasca Orde Baru tumbang, Salatiga diterpa gelombang teknologi kamera digital yang dapat digunakan untuk merekam video. Hal tersebut menjadi titik awal lahirnya komunitas film. Perfilman yang mulanya bermuara di bioskop seperti Reksa, Salatiga Theatre, dan Atrium menjadi menyebar ke beberapa penjuru kota. Ekosistem berusaha dibentuk mulai dari produksi, ekshibisi, pendidikan, dan apresiasi. Pada dekade pertama, corak produksi film didominasi oleh komunitas kampus dan ekstrakulikuler pelajar seperti XFILIS, STILL, Qariyah Thayyibah, Finger Kine Klub, PopCorn, COFILA, Commedia, dan lainnya. Hal ini karena pengaruh dari bagian pendidikan dan apresiasi film disokong oleh kampus seperti UKSW dan IAIN Salatiga yang memiliki beberapa program studi media dan film. Setelah tahun 2010an, bermunculan komunitas di luar kampus yang aktif dalam produksi film seperti Blackmonk Film, Next Project, Edelweis Film, Rajut Sinema, Laboratorium Eksperimen Film Sinemulakra, dan Militia Picture.
Ekshibisi film di Salatiga memiliki sejarah pemutaran film bioskop sejak 1930 hingga 2007an. Sejauh ini tercatat ada tiga bioskop yang pernah berdiri pada masa kolonial Hindia Belanda; Rex Bioscoop, Omnia Bioscoop, dan Tijgre Bioscoop. Gitanyali dalam bukunya Blues Marbabu (2011) menuliskan bahwa di masa transisi antara Orde Lama dengan Orde Barubioskop Rex merupakan jantungnya Salatiga. Bioskop Rex terletak persis dipertigaan yang ramai dan satu jalan dengan gedung-gedung pemerintahan. Tidak jauh dari situ, terdapat bioskop Ria yang bergaya art deco.
Hal itu menunjukan bahwa Bioskop Rex adalah satu-satunya bioskop yang dapat bertahan dari masa kolonial, baru kemudian berganti nama menjadi Bioskop Reksa ketika pertengahan masa Orde Baru. Disusul berdirinya bioskop-bioskop lainnya seperti Salatiga Theatre, Madya, dan Atrium. Beberapa film barat ditayangkan di bioskop Reksa, seperti Flash Gordon (1980), Superman III (1983), American Ninja (1985), sementara untuk film-film Indonesia seperti Gepeng Bayar Kontan (1983), Bangunnya Nyi Roro Kidul (1985), Ari Hanggara (1985). Bioskop Reksa pernah menjadi tempat pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) bagi pelajar SD hingga SMA di Salatiga. Memasuki era Reformasi, bioskop ini justru mengalami krisis. Masalahnya muncul VCD/DVD serta siaran TV swasta yang menggantikan fungsi bioskop sebagai tempat hiburan. Selain itu, untuk mendapatkan film Indonesia yang baru, bioskop Reksa harus menunggu 2-6 bulan setelah bioskop jaringan di kota-kota besar selesai memutarnya. Berdasarkan kurun waktu tersebut, VCD/DVD bajakan sudah beredar. Hal tersebut membawa dampak tersendiri pada jumlah penonton di bioskop. Setelah 2007, bioskop Reksa sudah tidak lagi beroperasi.
Bersamaan dengan munculnya teknologi digital, ekshibisi film di Salatiga diramaikan dengan kemunculan layar tancap di kampung-kampung. Namun, kehadiran VCD/DVD film bajakan berikut dengan alat pemutarnya yang murah menjadi tren sekaligus akhir bagi era bioskop dan layar tancap. Menonton film yang awalnya adalah kegiatan di ruang publik bergeser menjadi aktivitas privat di rumah. Bioskop berhenti beroperasi dan kegiatan layar tancap sudah tidak dapat dijumpai lagi. Namun kesunyian tersebut tidak berlangsung lama. Komunitas mengambil alih ekshibisi perfilman. Tahun 2011 muncul KOFIS (Komunitas Film Salatiga) yang memiliki semangat untuk menayangkan film-film independen, terutama film-film lokal. Program mereka seperti “Masih Ada Layar Tancap” yang digelar tahunan dalam rangka Bulan Layar Tancap Nasional berupaya untuk memperkenalkan film pendek pada masyarakat. NoDisk (Nobar Diskusi) adalah agenda tiap dua minggu sekali untuk mendiskusikan karya komunitas di publik. Pelajar Bicara Film adalah inisiasi untuk memperkenalkan film pendek ke siswa-siswi SMP dan SMA dengan harapan menarik minat mereka. Sedangkan Bioskop Darurat adalah suara keresahan mereka atas minimnya etalase film pendek di kota tersebut.
Pada tahun 2012, Finger Kine Klub dari FEB UKSW pernah menggelar Salatiga Film Festival atau SAFFEST pertama yang menghadirkan beragam film panjang dan pendek, fiksi dan dokumenter untuk ditayangkan serta dikompetisikan. Festival ini dirayakan setiap satu tahun sekali sebagai program wajib mereka dengan variasi program seperti lokakarya produksi film dan temu komunitas. Agenda ini dimanfaatkan bagi pembuat film untuk mendapatkan referensi film yang memengaruhi teknik dan gaya bercerita. Sementara KOFIS dengan segala program pemutarannya harus berhenti pada tahun 2013, gelaran SAFFEST hanya dapat berlangsung hingga tahun 2019. Finger Kine Klub kemudian mengadakan kompetisi film fiksi pendek dan fokus pada produksi karya video. Sedangkan KOFIS sudah tidak mengadakan pemutaran sama sekali. Komunitas film di Salatiga memang memiliki kendala paling berat dengan daya tahan (durability) dan keberlanjutan (sustainbility). Disana jarang ada komunitas film yang dapat bertahan hingga lebih dari lima tahun, pun jika ada terdapat masalah soal regenerasi atau transfer pengetahuan. Pondasi dari ekosistem film di Salatiga waktu itu adalah kampus dan sekolah yang menjadikan komunitas film sebagai tempat singgah atau taman bermain sebelum kemudian mempunyai pekerjaan yang serius. Sangat sulit kala itu untuk membayangkan dapat hidup dari film.
Tongkat estafet ekshibisi kemudian diteruskan oleh Klub Sinema Sisifus yang melakukan program pemutaran pertama mereka pada November 2018. Kenapa kami mengambil nama Sisifus? Melihat dari pola yang ada, komunitas film di Salatiga seperti mendorong batu besar hingga ke puncak. Namun batu tersebut berguling kembali hingga dasar. Albert Camus dalam Mite Sisifus Pergulatan dengan Absurditas (1999: 154) menuliskan "Para dewa telah menghukum Sisifus untuk terus-menerus mendorong sebuah batu besar sampai ke puncak sebuah gunung; dari puncak gunung, batu besar itu akan jatuh ke bawah oleh beratnya sendiri. Mereka beranggapan, dan anggapan itu benar adanya, bahwa tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada pekerjaan yang tak berguna dan tanpa harapan itu." Camus menambahkan bahwa yang menjadikan mitos tersebut tragis adalah, Sisifus sadar apa yang dia lakukan. Pada awal pembentukan klub sinema ini, kami menyadari bahwa membuat komunitas film memiliki peluang tinggi dalam mengulangi masalah yang sudah-sudah. Hanya saja, seperti kata Camus, kebahagiaan dan absurditas adalah dua anak kembar yang tidak terpisahkan.
Klub Sinema Sisifus awalnya berdiri sebagai komunitas yang fokus pada ekhsibisi film. Tujuan utamanya adalah mempertemukan film dengan penonton, khususnya film-film lokal Salatiga. Ini juga merupakan dukungan terhadap sineas yang sering bingung ketika filmnya hendak ditayangkan ke publik. Kemudian seiring berjalannya waktu, acara yang diadakan Klub Sinema Sisifus menjadi ajang untuk saling temu dan berbagi antar pembuat film dan penikmat film. Melalui acara semacam itulah akhirnya komunitas perfilman yang sempat tercerai berai kembali memiliki wadah. Setiap sebulan sekali terdapat sebuah program bernama "Bertancap Layar" yang menayangkan film-film Salatiga kemudian mendiskusikannya bersama. Selain itu, beberapa program lainnya menyajikan film-film pendek dari luar Salatiga dan mengangkat isu tertentu. Misalnya program “Pentas Orang-orang Kalah” menampilkan film yang menceritakan tentang kekalahan tokoh utama dalam menghadapi konfliknya. Setelah itu terdapat program “Bioskop Rumahan” yang berusaha membawa suasana nobar di rumah seorang warga. Ada juga program “Manuver Sinema” sebagai respon atas terbatasnya kegiatan yang melibatkan keramaian karena pandemi Covid-19.
Setelah Klub Sinema Sisifus melakukan kegiatan selama dua tahun, lahir banyak kemungkinan baru dalam membentuk ekosistem perfilman di Salatiga. Komunitas film menjadi lebih giat dalam produksi karena sudah tersedia layar untuk menayangkan karya mereka. Apresiasi muncul pada karya komunitas yang mulai dibicarakan oleh media-media lokal. Program-program tersebut akhirnya juga membuka akses film yang selama ini sukar untuk didapatkan oleh penonton di Salatiga, terutama film-film alternatif. Terjalinnya kerja sama antara penyelenggara acara dengan pemilik kafe atau bar yang mutual. Dukungan dari kelompok seni lainnya seperti teater, seni rupa, musik, dan lainnya memungkinkan memperluas jaringan kesenian di kota ini. Meskipun efek dari adanya bioskop alternatif tersebut terasa begitu cepat, ada beberapa hal yang masih dibutuhkan untuk melengkapi ekosistem yang kami harapkan. Ekosistem ini berjalan tanpa dukungan pemerintah kota dan mengandalkan solidaritas antar komunitas. Selain itu problem terkait kuantitas dan kualitas pada produksi film juga masih menjadi hambatan, sehingga program semacam Bertancap Layar terkadang tidak dapat terselenggara karena belum adanya film baru yang ditayangkan.
Tahun ini, Klub Sinema Sisifus mulai menginisiasi beberapa siasat untuk lebih membangkitkan ekosistem perfilman seperti penelitian, pengkajian dan pengarsipan yang fokus pada sinema Salatiga. Penelitian terhadap sejarah sinema, kegiatan menonton film, dan catatan mengenai geliat komunitas film di Salatiga mulai dikumpulkan agar dapat dipelajari. Apresiasi seperti kajian dan kritik film Salatiga mulai dilakukan. Kami juga mengumpulkan film-film yang diproduksi oleh komunitas. Barangkali film yang sekarang dianggap biasa saja akan lebih menarik dan dapat dibicarakan sepuluh tahun kedepan. Arsip-arsip film Salatiga yang masih banyak yang berserakan dan sudah banyak yang hilang karena sudah tidak tahu mau diapakan lagi. Beberapa masih dapat ditemui di Youtube atau Facebook. Rencana peningkatan ekosistem ini perlu tenaga dan waktu yang besar, terutama jika hanya mengandalkan kami. Partisipasi dari komunitas, penonton, dan elemen lainnya sangat dibutuhkan di sini. Harapan Klub Sinema Sisifus adalah suatu ekosistem yang dapat berjalan dengan sehat di Salatiga. Impian dalam mendesentralisasi sinema nasional pelan-pelan mulai dibangun.
Sesekali kami memandang puncak gunung itu, tentang bagaimana jadinya nanti jika kami mencapai sana. Ada kalanya kami diam termenung. Memandang bongkah batu di depan mata. Lalu mendorongnya kembali dengan susah payah. Kami percaya, masalah komunitas film soal daya tahan (durability) dan keberlanjutan (sustainbility) selalu hadir. Itulah batu kami. Kami juga yakin bahwa selalu ada kemungkinan terburuk. Tentu saja, sejak awal berdiri kami membayangkan bahwa kami akan bubar. Namun sekali lagi, seperti kata Camus: bayangkan Sisifus yang bahagia!
Penulis : Gerry Junus
Desain : Hotman Nasution
Gerry Junus

Kurator dan programmer Klub Sinema Sisifus. Sedang berupaya untuk melakukan pengembangan sinema di Salatiga sembari menghabiskan waktu luang dengan menonton filem, membaca, menulis, dan mendengarkan lagu
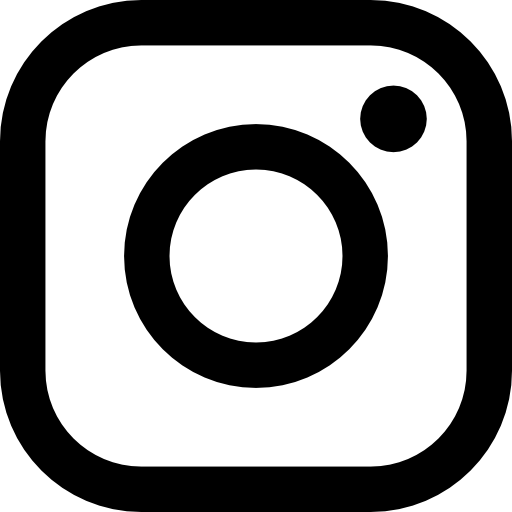
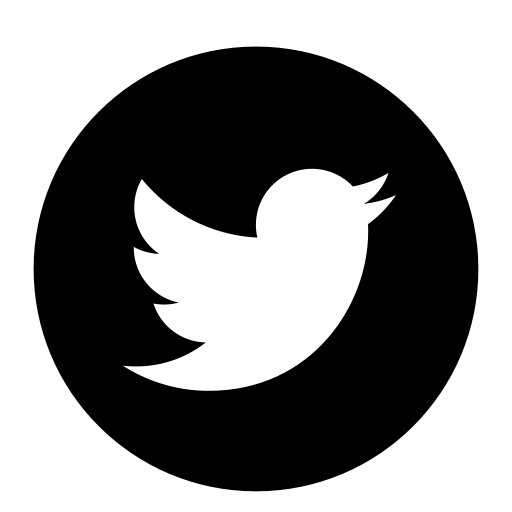
0 notes
Text
Nomadland : Melihat Sudut-Sudut Amerika Serikat.

Adegan pembuka dimulai setelah kita dituntun untuk melihat sejarah singkat Empire, Nevada, yang ditinggalkan Fern setelah Tambang Sheetrock tutup pada 2011. Empire adalah kota di mana Fern dan mendiang suaminya menjalani kehidupan.
Sejarah yang ditampilkan di awal menegaskan bahwa film ini berangkat dari kisah nyata, diadaptasi dari buku Jessica Bruder yang berjudul Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century (2017). Buku non-fiksi ini digarap Jessica Bruder yang juga seorang jurnalis Amerika, menarasikan perjalanannya dan mewawancarai sekitar 50 pengembara selama tiga tahun. Di tangan sutradara Chloe Zhao, Nomadland digambarkan dengan karakter-karakter fiksi yang semuanya tetap memiliki latar belakang yang sama, yakni manusia yang sedang menjalani masa tua dan korban terdampak The Great Recession. Di Amerika Serikat, The Great Recession terjadi di Abad 21 dimulai pada Desember 2007 hingga Juni 2009.
Nomadland (2020) bercerita tentang orang-orang yang hidup Nomaden, kebanyakan adalah penghuni van tua di Amerika Serikat. Meski tiap tokoh memiliki ceritanya masing-masing mengenai alasan mereka memutuskan untuk hidup nomaden, keadaan dan nasib mereka tak jauh beda dengan Fern. Mereka memiliki posisi tawar yang serupa dengan Fern.
Bergumul dengan Kepahitan
Chloe Zhao sangat memanjakan penonton melalui gaya visual. Permukaan dataran yang terhampar luas mengingatkan pada savana di Nusa Tenggara dalam Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017).
Lewat visualisasinya, Nomadland dijelaskan bahwasanya seberapa luas tanah indah yang jadi kepemilikan negara tidak menjamin manusia memiliki rumah. Hal ini bisa dilihat dari puluhan van tua dan pemiliknya melintasi alam indah Amerika Serikat yang tampak dalam film ini membuktikan mereka tak memiliki bangunan berbentuk rumah pada umumnya. Adegan saat Fern bertemu temannya beserta dua anak perempuan di supermarket, mengukuhkan status hunian bagi Fern. Saat seorang anak perempuan itu bertanya benarkah Fern sekarang menjadi gelandangan, Fern menjawab dengan tegar, “I’m not homeless, I’m just houseless. Not the same thing, right?”
Nomadland menjelaskan bahwa hidup nomaden bukan hanya tentang jalan-jalan, bersenang-senang, atau bentuk dari eskapisme atas rasa penat kehidupan kota dengan rutinitas yang itu-itu saja. Hidup nomaden di usia 60-an terasa seperti memikul beban ganda. Sepanjang film, Fern terus bergonta-ganti pekerjaan untuk sekedar menyambung hidup.
Ia bekerja di Amazon dan bergabung dengan pekerja usia lanjut lainnya yang di bayar murah. Untungnya, mereka masih sempat bercerita tentang hal-hal yang disukai di hidup ini sambil menyantap makanan. Seperti salah seorang teman baru Fern, yang menceritakan tattoo-nya bergambar penyanyi bergenre Britpop, Morissey dengan lirik-lirik indahnya.
Ada banyak film yang bercerita tentang kehidupan nomaden, seperti The Human Shelter (2018), film dokumenter Boris Benjamin. The Human Shelter menarasikan dengan frontal melawan ‘gaya hidup mapan’, seperti orang-orang yang memilih tinggal di habitat NASA yang mereplikasi isolasi kehidupan planet Mars di tanah vulkanik Hawaii, juga ada warga yang tinggal di kota gubuk terapung di Nigeria. The Human Shelter juga menjelaskan alasan pengungsi di Irak karena adanya perang, juga dengan suku-suku yang hidup nomaden guna mempertahankan tradisinya dengan cara primitivisme demi keseimbangan alam. Tapi, Nomadland memilih perspektif yang lebih dekat dengan tidak bercerita seperti lazimnya film nomaden, melainkan menarasikan wujud kolektifitas antar orang-orang yang bernasib sama di salah satu negara paling luhung di dunia.
Melihat Lebih Jauh
Tokoh-tokoh dalam film ini memaparkan berbagai sudut pandang. Mulai dari Fern yang hidup sendiri sebab ditinggal mati suaminya. Swankie (Swankie) yang menyadari waktu hidupnya tak lama lagi dan memilih untuk hidup nomaden di sisa kehidupannya. Fern bergabung dengan kelompok nomad setelah mengetahui dari temannya bernama Linda (Linda May). Dalam satu adegan di dalam van tua, Linda bercerita kepada Fern bahwa ia telah membesarkan dua anak perempuan dan merasa terjebak di sofa yang ada di rumah kontrakan putrinya, hal tersebut membuatnya memutuskan untuk hidup nomaden. Karakter Linda menjelaskan bahwasanya sebelumnya ia pekerja keras dan ketika tua tak memiliki pekerjaan, ia merasa resah.
Ia juga bertemu dengan seorang mantan dokter di masa Perang Vietnam yang mengidap gangguang PTSD sehingga tak bisa hidup di keramaian dan memilih hidup nomaden. Kemudian ada Bob (Bob Wells) yang menjadi mentor sekaligus rekannya dalam menjalani hidup nomaden. Dan Dave (David Strathairn) lelaki tua yang berinteraksi cukup intens dengan Fern perihal kiat hidup nomaden dan tetap merasa aman di jalanan.
Dalam wawancara Barry Pateman dengan Noam Chomsky pada 2004 dalam Chomsky On Anarchism, Chomsky mengatakan “Emosi normal manusia adalah simpati dan solidaritas, bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk lumba-lumba yang terdampar. Itu adalah reaksi normal manusia.” Selagi mengadakan perkumpulan, orang-orang ini melakukan kerja-kerja kolektif dari hal yang paling sederhana.
Mereka mengadakan lapak gratis dengan menaruh barang-barang yang tak dibutuhkan lagi dan menukarnya dengan barang-barang yang dibutuhkan. Sehingga tidak terjadi aktivitas filantropi. Hal ini bisa terbentuk karena mereka juga menyadari hidup nomaden adalah hidup dengan serba keterbatasan. Artinya, mereka tak mungkin mengambil barang yang tidak terlalu dibutuhkan dan hanya mengambil yang paling dibutuhkan saja guna menunjang kehidupan nomadennya.
Selain itu, Nomadland memberikan gambaran tentang menjadi tua dan kesepian adalah dua hal yang datang beriringan. Sepanjang film, banyak ditemukan adegan yang senyap tanpa dialog, merasakan kesepian yang begitu hebat. Salah satu adegan yang menyayat hati, saat malam tahun baru Fern sendirian di dalam van kesayangannya. Ia memakai bando berwarna perak dan meniupkan terompet kecil tahun baru, sedangkan di luar mobil miliknya, samar-samar terdengar suara petasan perayaan pergantian tahun. Berbagai latar belakang tokoh mengantarkan kita pada satu kepastian, bahwa mereka hidup sendiri mengendarai vannya di usia tua. Bahwa mereka jauh dari keluarga yang masih hidup atau sudah meninggalkan kehidupan ini.
Chloe Zhao berusaha menyajikan sudut pandang berbeda tentang Amerika Serikat sebagai negara idaman banyak orang. Chloe Zhao menyajikan potret kegetiran hidup orang-orang menengah ke bawah yang hidup nomaden dan harus tetap bekerja. Pekerjaan orang-orang nomaden seperti main lotre, pekerjaan apa yang dapat harus diterima demi kebutuhan hidup. Kegetiran hidup perempuan dan lelaki dengan usia lanjut, beban ganda seorang janda tua, dan beban menjadi tua diiringi dengan berbagai penyakit yang diperoleh dari masa lalu.
Nomadland, layaknya berita hasil jurnalis yang menerapkan elemen kedua jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel—keberpihakan terhadap masyarakat—dan Nomadland berpihak pada orang-orang yang terpinggirkan, yang hanya punya pilihan sangat terbatas dalam menjalani kehidupan. Sebab, hidup berpindah-pindah di masa tua dengan van tua dan harus mencari pekerjaan musiman merupakan bentuk keterpinggiran dari hidup layak.
Penulis : Bagus Pribadi
Desain oleh : Hotman Nasution
Nomadland | 2020 | Sutradara : Chloe Zhao | Pemeran : Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells | Negara Asal : Amerika Serikat| Durasi : 108 Menit | Produksi : Highwayman Films Hear/Say Productions
Bagus Pribadi
Bagus Pribadi

Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang skripsian. Agar tidak mengutuk waktu, ia nyambi jadi jurnalis di salah satu media lokal di Pekanbaru.


0 notes
Text
Cinemuach: Menonton Film Sebagai Kegemaran dan Kesenangan

Catatan Redaksi : ‘Memori Sinema’ adalah rubrik terbaru dari kami yang akan mewawancarai orang dari latar belakang yang berbeda untuk membahas bagaimana penglaman mereka menonton film di tahap personal. Kami percaya bahwa kaitkan film dengan pengalaman personal tidak akan pernah terpisah. Selamat membaca!
Hampir semua orang tentu pernah merasakan pengalaman menonton film. Tentunya motivasi setiap manusia ketika hendak menonton pasti beragam, seperti misalnya menonton karena ingin mencari hiburan semata, menonton untuk memenuhi tugas dari dosen atau guru, menonton untuk mengilangkan penat, menonton untuk belajar dan memaknai setiap adegan demi adegan, dan lain-lain.
Pada kesempatan kali ini kami mewancarai salah satu penonton film yang mungkin cukup dikenal di media sosial twitter. Ia dikenal dengan banyak ciri khas; nama pengguna yang unik, foto profil yang ikonik dan tentunya bagaimana dia memberi rekomendasi tontonan film yang cukup beragam. Kak Firda atau biasa dikenal dengan nama pengguna twitternya, Cinemuach berkenan untuk menceritakan pengalamannya dengan film dari sudut penonton. Ia bercerita bagaimana pengalaman pertamanya bertemu dengan film, bagaimana film membuka peluang dan pengalaman lain di dalam hidupnya dan banyak lagi.
Simak wawancara kami berikut ini!
Gimana nih kak awal mula kak Firda bisa suka sama film?
Pertama kali aku tahu tentang film ketika aku diperkenalkan sama papaku—pada saat itu aku masih SD dan merasa biasa aja sama film. Suka sama film, tapi tidak seantusias seperti sekarang. Ketika aku masih SD dulu aku nonton filmnya di TV, papaku gemar menyewa kepingan disc dengan berbagai judul film di persewaan film. Hingga akhirnya aku SMP dan aku mulai mengikuti munculnya film baru yang ada di bioskop bersama teman-teman. Akhirnya teman-teman jika ingin menonton film, mereka bakal nanya rekomendasi film yang menurut versiku seru dan menyenangkan untuk ditonton. Hingga aku duduk di bangku SMA pun teman-teman seringnya meminta rekomendasi film ke aku.
Sampai akhirnya aku kuliah, aku juga masih mengikuti munculnya film baru yang ada di bioskop dan aku selalu mengusahakan untuk menonton pada hari pertama penayangan, tetapi masih dalam ranah pemutaran bioskop atau mainstream—belum sampai pada ranah sidestream. Menginjak tahun 2017—tahun ketika aku lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan aku meluangkan waktuku untuk mencari film dan mencoba eksplor berbagai genre. Mencoba menggali berbagai film yang belum pernah aku tahu sebelumnya. Hingga akhirnya aku berkenalan dengan orang-orang film Twitter seperti mas Andi Akbar, mas Yohan, dan lain-lain. Mereka memberikan aku rekomendasi film yang menantang aku untuk menjelajah lebih dalam lagi. Sampai akhirnya aku bisa menemukan sendiri film yang aku mau dan aku butuhkan—yang awalnya aku dituntun, akhirnya aku bisa jalan sendiri untuk menemukan film yang aku mau.
Aku suka film karena aku seringnya penasaran. Ketika aku memutuskan untuk menonton film tersebut, aku nggak pernah baca review ataupun sinopsis, dan nonton trailer-nya, atau apapun. Ya aku langsung nonton aja dan menelaah sendiri bagaimana filmnya. Ketika aku masih kuliah—aku menonton film sebagai salah satu sarana hiburan. Di usia sekarang, aku menonton film sebagai salah satu bahan pembelajaran untuk diri aku sendiri juga aku menemukan perspektif baru melalui film yang aku tonton. Film selain sebagai sarana hiburan, juga bisa dilihat sebagai seni dalam menyampaikan informasi.
Tadi kak Fir bilang kalau kakak nonton film karena rasa penasaran—rasa penasaran seperti apa kah?
Awal-awal tuh lebih penasaran dengan ceritanya. Itu sebabnya kenapa aku suka dengan film yang dekat dengan realita sehari-hari. Aku suka menggali film-film indie low budget, dan temanya membumi.
Kak, coba dong sebutin dua atau tiga film yang bikin kakak suka sama film !
Film-filmnya Jim Jarmusch kali yaa karena memang Jim Jarmusch adalah salah satu sutradara favorit aku—aku suka banget dengan cara dia menangkap peristiwa sehari-hari dalam filmnya dan itu terlihat menjadi menarik. Film pertama beliau yang aku tonton adalah Mystery Train semenjak nonton itu aku langsung eksplor film-filmnya Jarmsuch apalagi nih yang menarik untuk ditonton. Itu aku nontonnya tahun 2017, kemudian aku lanjut jajal Night on Earth dan aku ngerasa relate sama beberapa scene-nya.
Film apa nih kak yang kakak rekomendasikan untuk orang-orang yang baru mengenal film?
Kalo aku ya itu tadi sih cobain Mystery Train sama Night on Earth-nya Jarmusch karena dua film itu ringan banget. Pasti bakal suka, deh! Menurut aku film itu bisa mewaikili kehidupan kita, nggak perlu mikir yang gimana-gimana ya nikmati aja. Nonton mah nonton aja!
Kak, bisa ceritain gak kenapa nama akun sosmed-nya jadi Cinemuach?
Sebenernya akun ini berangkat dari akun pribadi yang emang dari dulu suka bikin tweet tentang film sejak tahun 2017, tapi lebih ke rekomendasi sama review mengenai film. Aku nggak pernah nulis review karena aku nggak merasa diri aku sebagai reviewer. Aku ngerekomendasiin film yang menurut aku penting untuk ditonton untuk khalayak luas. Pada satu malam aku ngerasa akunku harus mengerucut menjadi sebuah akun yang mmebicarakan tentang kesukaanku—yaudah ngomongin film sama musik. Kemudian aku mencari nama yang mudah dihafal dan diingat atau istilahnya eyecatching—yaudah akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan nama cinemuach—cine diambil dari cinema dan muach—adalah ungkapan cinta. Jadilah akun cinemuach yang karena memang aku cinta dengan sinema.
Di sinilah akhirnya ku memutuskan untuk membicarakan segala hal yang berhubungan dengan film tanpa melepas identitasku. Selain film, aku juga suka melakukan kurasi musik. Jadi, yang orang-orang tahu akun cinemuach adalah akunnya Firda yang suka ngetweet tentang film dan musik.
Kenapa harus ganti nama, kak?
Aku dulu nggak pernah kepikiran untuk jadi akun film karena sudah banyak akun film di linimasa. Hanya saja aku mikirnya kalo cinemuach itu akun yang berbeda dari akun film yang lain. Aku suka mengajak orang-orang untuk menonton film yang sekiranya buatku menarik dan orang-orang mungkin ada yang belum menonton. Cinemuach lebih mengajak orang-orang untuk menonton, sih! Hehehehe.
Apakah nilai sebuah film menjadi bertambah bagi kakak pribadi?
Bertambah sih, ya! Aku dapet tawaran pertama dari visinema. Meskiun aku dapet job buat nonton, tetep nggak ngurangin kesenanganku untuk menonton film. Aku sendiri nggak pernah menjadikan sebuah beban ketika menonton film, apapun filmnya. Karena memang kegemaranku nonton ya aku seneng-seneng aja dan nggak ngerasa punya beban. Perkara filmnya bagus atau jelek ya itu urusan belakangan.
Tempo menonton kakak dalam sebulan itu berapa kali?
Kalo dulu belum kerja sih sehari bisa menonton 4-5 film. Untuk di usia sekarang karena sudah renta dan sudah uzur :D mentok dua film dalam sehari—itu ketika harian, kalau akhir pekan bisa menonton 3-4 film.
Gimana cara kakak buat menikmati film?
Ketika aku menemukan sebuah film dan aku memutuskan untuk menonton dan film itu ternyata bagus itu rasanya kayak menemukan kebahagiaan sih. Sekalipun film yang aku tonton itu nggak bagus, aku masih ngerasa aku mendapatkan sesuatu dari film yang aku tonton. Yaudah aku nikmatin aja sih sama apa yang aku tonton. Aku nonton film apa yang aku mau dan apa yang aku pengen tonton, sih.
Gimana cara kakak membagi waktu menonton dengan kehidupan pribadi juga pekerjaan kakak?
Jujur untuk saat ini aku memang agak keteteran, terutama aku juga ada kerjaan utama. Biasanya aku bakal menyempatkan menonton di pagi hari sebelum berangkat kerja. Jam 07.00 aku biasanya bakal menyempatkan diri untuk menonton dan sebelum tidur juga aku bakal menonton.
Apanih kak film yang sangat berpengaruh pada kehidupan kakak?
The Green Ray (Le Rayon Vert) filmnya Eric Rohmer karena karakter utamanya si cewek itu relate banget sama aku. Suka sama karakter perempuannya karena ketika si karakter menghadapi kesulitan dan kesedihan itu aku ngerasanya kayak “WAH INI GUE BANGET, NIH!” tapi sejujurnya banyak banget film bagus yang udah aku tonton, tapi tidak cukup berpengaruh bagi aku. Aku belum bisa menyebut yang lain selian Night on Earth sama Le Rayon Vert tadi. Karena seringnya aku memandang film secara umum aja sih kebanyakan.
Ada saran ga kak buat penonton film, petuah atau apa gitu?! Hehehe
Jangan jadi SNOB!!! WKWKWKWKWKW well, sesama penikmat film yaa nikmati aja lah sama apa yang kamu tonton. Jangan ngrasa jago karena udah menonton film obscure. Nggak usah balapan karena nggak lagi lomba. Jangan ngerasa sok pintar hanya karena lebih bisa menelaah sebuah film. Santai aja 😊 intinya nggak usah pamer mengenai refrensi. Boleh berbagi, tapi jangan sombong!
Diwawancarai oleh : Galih Pramudito
Ditulis dan disusun oleh : Mega Fadila
Desain oleh : Nona Damanik
Galih Pramudito Mega Fadilla


Salah satu pendiri Mania Cinema. Pernah aktif di komunitas Sinelayu dan menjadi juru program Palagan Films di Pekanbaru. Kebanyakan waktunya ia habiskan untuk menonton, membaca, makan, selebihnya melamun. Saat ini tengah menyelesaikan studi Ekonomi Islam di UII Yogyakarta. Seorang penonton film juga pecinta Chungking Express paling taat. Menjadi seorang podcaster FilmExpress di Spotify apabila tidak mager. Sisa waktunya biasanya dihabiskan untuk menulis dan tidur.




1 note
·
View note
Text
Malcolm & Marie : Jangan Cuma Bisa Bilang I Love You.

Catatan Redaksi : Sebelum membaca ulasan ini kami ingin memperkenalkan rubrik baru terbaru yaitu “Dunia Icha”. Kami berkolaborasi dengan Icha Hairunnisa yang merupakan teman kami dan salah satu sejawat pengulas film aktif di blog pribadinya , ichahairunnisa.com . Di rubrik ini pembaca akan dibawa dalam semesta ulasan film Icha yang lucu, absurd, seru dan terkadang.. penuh birahi. Teknik gaya ulasan Icha cukup berbeda -- ia kerap blak-blakan dan ada adanya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan pembaca kami dan menyatakan bahwa ulasan film tidak hanya bisa disusun dengan serius dan penuh dengan teori. Ia juga bisa disusun secara menyenangkan dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selamat membaca!
.
Okeeee Valentine bukan budaya kita. Budaya kita adalah bikin twit template bla bla bla bukan budaya kita. Tapi izinkan aku buat merekomendasikan Malcolm and Marie sebagai tontonan pas di Hari Valentine (selain Fake Taxi atau Public Agent, kalau pasanganmu ‘open minded’ eheee). Atau seenggaknya, izinkan aku buat ngebahas film ini dari sudut pandangku sebagai tukang baperin film. Ngebahasnya full spoiler, btw.
Malcolm and Marie bercerita tentang dua sejoli yaitu Malcolm (John David Washington) dan Marie (Zendaya) yang baru pulang dari premier film. Malcolm ini sutradara dan penulis, tentu saja itu acara premier filmnya. Alih-alih mereka merayakan malam besar itu dengan mabok sampai pagi, ngudut rokok satu slop, atau silaturahmi kelamin sampai hari terang kayak lagu 34+35-nya Ariana Grande, mereka malah debat kusir semalaman suntuk tanpa memedulikan kenyamanan tetangga.
Berawal dari keluhan kurang lebih, “Pidatomu! Kamu lupa bilang terima kasih sama aku, Malcolm! Di saat kamu bilang terima kasih untuk 112 orang termasuk guru kelas tigamu, kamu lupa bilang terima kasih sama pacarmu?” Marie dan Malcolm adu argumen dan saling menyalahkan. Menunjukkan kalau selama ini ada yang salah dengan hubungan mereka. Malcolm dan Marie debat, baikan, hampir ngewe, nggak jadi ngewe, sebat, debat lagi, baikan lagi, hampir ngewe, nggak jadi ngewe, debat lagi, baikan lag--- OKE AKU UDAH MULAI CAPEK NULISNYA.
Tapi percayalah, menonton ini nggak bikin capek dalam artian bosan dan malas ngelanjutin sampai habis. Seenggaknya buatku. Aku dengan senang hati rela digenjot dinamika mereka yang naik turun. Kadang Malcolm memimpin, kadang Marie. Kadang Marie terdiam kena skakmat, kadang Malcolm yang terdiam. Aku dibuat penasaran sama akhir film ini. Apakah mereka bakal putus? Apakah mereka baikan dan memulai dari nol lagi? Apakah mereka bakal dilaporin ke Pak RT karena udah mengganggu ketentraman warga sekitar tengah malam?
AKU PENASARAAAAAAN.
Marie udah kayak kesurupan Najwa Shihab saat mendebat Pak Arteria Dahlan anggota DPR yang sempat viral beberapa waktu lalu. Aku pikir Marie ini cuma lagi drama aja. Entah karena dia lagi laper tapi dicecar rentetan kenarsisan pacarnya yang overproud, terlihat dari dia bilang, "Aku belum makan semalaman." Atau mungkin karena dia kesel plus capek mendapati kenyataan bukannya mereka mampir makan di restoran buat makan, malah langsung pulang ke rumah dan disuruh buatin Mac n Cheese.
Atau karena dia udah ngantuk jadinya rewel. Anak kecil aja kalau kurang tidur atau udah ngantuk bawaannya rewel. Apalagi orang dewasa kan? Who knows? Tapi nggak gitu. Film ini adalah definisi dari ucapan, "Masalah dan amarah jangan dibawa tidur." Apa yang dipermasalahkan Marie itu nyata dan besar adanya. Malcolm memilih buat ngebahas kenapa Marie bersikap dingin walaupun tetap ngadonin Mac n Cheese yang hangat. Pilihan Malcolm yang bikin aku ngeliat dia adalah pacar bijak. Tapi ternyata dia nggak bijak. Dia bijik.
John David Washington sukses memerankan karakter bijik Malcolm. Ngegas banget jadi orang. Kasar sama pacar yaitu Marie dan terang-terangan menunjukkan dirinya adalah hater-nya para kritikus film. Apalagi pas adegan dia marah-marah soal review yang dia dapatkan, kemudian merembet ke soal dunia perfilman Hollywood. Marah-marah yang... untuk apa? Toh review yang dia dapatkan itu positif. Walaupun nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Masih lebih masuk akal kalau Joko Anwar yang sambat marah-marah in real life soal pembajakan film di Telegram, film Perempuan Tanah Jahanam-nya nggak masuk Oscar tahun ini, dia yang nasibnya disama-samain dengan Livi Zheng...
Film ini mendulang banyak review positif dan negatif. Ada yang suka ada yang nggak. Ada yang suka banget dan ada yang benci banget. Ada yang bilang film ini cuma mengandalkan hitam putihnya yang artsy tapi filmnya nggak berisi, ada yang bilang kalau film ini bikin bosan dan capek nontonnya, ada yang mungkin bilang kalau film ini cuma jadi ajang curcol Sam Levinson selaku sang sutradara. Tapi.... gimana, ya. Aku suka. Karena menurutku film ini bisa menjadi milik banyak kalangan. Kalangan yang suka film dengan format hitam putih... iya. Kalangan yang ngefans sama Zendaya... iya. Kalangan yang suka film drama cinta-cintaan... iya. Kalangan yang merasa keluh kesahnya soal industri perfilman juga iya. Kalangan yang pernah mengalami hubungan nggak sehat atau kata anak sekarang, toxic relationship, iya juga. Jujur, aku sempat ke-trigger nonton ini.
Aku pernah punya momen di mana punya pasangan yang narsis dan sombongnya naudzubillah kayak Malcolm. Kurang lebih aku pernah ada di posisi Marie, bedanya aku tidak secantik dia dan tidak sevokal dia dalam mengkomunikasikan perasaanku. Aku cuma bisa cerita di akun Tumblr-ku yang ku-private, atau cerita ke temanku kalau aku udah lega dan siap dikatain "Kok kamu masih mau sih sama diaaaa?" hingga aku jadi malas buat cerita lagi. Mau langsung ngomong kayak Marie ke Malcolm, ujung-ujungnya aku bakal ngerasa kalau aku salah sudah ngomong. Adegan di bak mandi sewaktu Malcolm menyanggah kalau inspirasi tokoh Imani, tokoh utamanya di filmnya itu bukan cuma dari Marie melainkan dari banyak mantannya juga, bikin aku benar-benar tersulut kenangan buruk.
Si mantan mirip Malcolm yang doyan pamer mantan seolah nunjukkin kalau dia adalah superhero bagi cewek-cewek rusak. Menyuratkan kalau aku harus berterima kasih padanya karena udah diselamatkan. Karena cuma dia yang mau begitu. Cowok lain nggak bakal mau. Itu yang dia tekankan ke aku selama kami berhubungan. Itu juga yang dirasakan Marie selama berhubungan sama Malcolm. Marie didatangi Malcolm pas lagi rapuh-rapuhnya. Marie didampingi selalu tapi juga dibikin rendah diri. Marie bilang kurang lebih, "Aku tau persis tipemu, tapi kamu lebih memilih bersama si badan ceking ini," itu ASTAGAAAAA RELATE BANGEEEEEEET. Aku juga pernah memandang diriku rendah kayak gitu.
Bisa dibilang aku suka film ini karena punya kedekatan emosional sama Marie, tapi nggak cuma itu. Film ini bergerak runut maju dan nggak ada adegan flashback ke masa lampau untuk ngasih tau konflik mereka ke penonton, layaknya yang dilakukan film debat kusir dalam semalam lainnya, yaitu Story of Kale: When Someone's In Love (2020). Film ini nggak butuh itu, karena dialog dan tindak-tanduk mereka udah cukup menunjukkan konflik hubungan mereka. Udah cukup menunjukkan kalau Malcolm orangnya bagaimana dan Marie orangnya bagaimana. Malcolm yang ucapan "I love you-" gampangan, tapi buat bilang “Maaf,” dan “Terima kasih,” aja kayaknya susah banget.
Malcolm yang sombong akan hasil karyanya dan punya kehidupan lebih layak daripada Marie. Malcolm yang kesal dipandang medioker terlihat saat dia disamakan dengan Spike Lee dan Barry Jenkins maupun saat Marie frontal bilang dia medioker. Malcolm yang panikan terbukti dari adegan nyari dompet dan handphone. Malcolm yang haus pujian akan dirinya, yang nggak bakal lelah dengar Marie semalaman mengarang cerita halu tentang dia di masa depan.
Marie yang cool dari luar tapi rapuh di dalam. Marie yang sebenarnya malas berdebat terbukti dari dia yang awalnya bilang, "Bicara besok saja," sewaktu ditanya ada apa sama Malcolm. Marie yang suportif, bukan cuma dari rentetan cerita dia menemani Malcolm dari nol. Tapi juga dari bahasa tubuhnya. Dari senyum dan tawanya saat Malcolm sambat ria teriak sana sini habis baca review dari LA Times yang.... positif. Dari dia yang mengiyakan waktu nama Spike Lee dan Barry Jenkins disebut sebagai setaranya Malcolm. Dari dia yang turut antusias sama review filmnya Malcolm. Marie yang sebenarnya rendah diri dan lagi mati-matian mencintai dirinya sendiri. Berharap Malcolm yang egosentris itu mengehargai dia sebagai pasangan, minimal nggak melupakan namanya di pidato. Membuatnya merasa jadi orang yang berarti di hidup Malcolm.
Aku berterima kasih banget sama akting Zendaya yang prima. Marie mungkin cuma bakal jadi sosok drama queen yang suka membesar-besarkan masalah kecil, kalau bukan karena Zendaya. Aku suka wajah malas menghindari konfliknya dari awal. Aku suka wajah cemberutnya. Aku suka gaya bicaranya yang lantang penuh emosi menyerang Malcolm yang asik makan Mac n Cheese sambil julid. Aku suka senyum berlagak jual mahalnya sewaktu Malcolm merayu. Aku suka ketawa psikopatnya pas adegan audisi dadakan menjadi Imani. Aku suka isak tangisnya yang bikin aku sesak dengarnya. Aku suka, dan paling suka, walaupun ini sederhana banget. Aku paling suka waktu dia foreplay dengan mau nge-blowjob John David Washington sebagai Malcolm, sambil mau adu argumen lagi. Malcolm bilang, "Bisa kita bicarakan nanti?" tapi Marie tetap maju terooos. Akhirnya nggak jadi blowjob.
GOOD JOB, GIRL! MAMPUUUUS NGEGANTUNG DEH NGEGANTUNG HASRAT PEJUMU, MALCOLM! RASAKNOOOO!
Seperti hanya ada dua pemeran, di film ini hanya ada dua warna. Yaitu hitam dan putih. Tapi ada banyak yang bisa dikomunikasikan ke pasangan selain "I love you." Karena ucapan "I love you," itu kadang bisa bermaksud lain. Bisa ya bullshit doang, lip service doang, atau buat menutupi kesalahan. Bisa nggak tulus. Menurutku itu yang dirasain Marie. Menurutku ucapan terima kasih dan maaf dari pasangan itu sangat berarti. Minta maaf saat salah. Terima kasih saat merasa terbantu. Karena kalau udah berdua, rasanya nggak mungkin nggak pernah buat salah atau mampu ngelakuin segala sesuatu dengan sukses sendirian.
Film ini bikin aku yang baperan ini mikir... jangan cuma 'bisa' bilang “I love you,” kayak Malcolm. Cinta tanpa rasa menghargai itu... bentuk keegoisan. Nggak ada yang mau punya pasangan yang egois.
Desain : Nona Damanik
Malcolm & Marie | 2021 | Sutradara : Sam Levinson | Pemeran : John David Washington & Zendaya | Negara Asal : Amerika Serikat| Durasi : 104 Menit | Produksi : Netflix.
Icha Hairunnisa

Perempuan melankolis yang nulis review film karena buat kedok aja supaya bisa curhat di tulisan. Mengharapkan dia bisa menulis intelek sama dengan mengharap Gaspar Noe menggarap film religi. Budaknya film-film romance, komedi, dan... erotis.


1 note
·
View note
Text
Love Streams : Kegamangan Dalam Memaknai Cinta.

Cinta merupakan sebuah topik universal yang tidak akan pernah basi untuk dikupas—terutama melalui medium film. Jika kita bertanya pada setiap manusia ‘apa itu cinta?’ maka kita akan memperoleh jawaban yang beragam. Karena definisi mengenai cinta bagi setiap orang tentulah berbeda. Namun, apakah selama ini kita telah mengerti dan memahami konsep tentang cinta?
Love Streams mempertanyakan hal serupa. Berawal dari Robert Harmon (John Cassavetes) seorang penulis ternama yang alkoholik, juga seorang pemain wanita ulung yang tiba-tiba dimintai bantuan oleh mantan istrinya untuk merawat anak lelakinya yang tak pernah ia temui sejak lahir. Ia pun terpaksa merawat anak tersebut selama beberapa hari. Tak disangka, keeseokan harinya—Robert Harmon kedatangan seorang tamu istimewa—saudari kandungnya yang sudah lama tak bersua dengan Robert—Sarah Lawson (Gena Rowlands) yang dilanda depresi pasca berpisah dengan suaminya.
Love Streams memotret ketidaktahuan dua orang manusia ketika mereka dihadapkan dengan hal magis yang bernama cinta. Film ini membuat saya cukup yakin bahwa kita tidak pernah benar-benar mengerti akan cinta. C.S Lewis dalam bukunya yang berjudul The Four Loves—di mana beliau menjelaskan bahwa cinta dibedakan menjadi empat jenis, yakni; agape, eros, storge dan philia.
Ragam Jenis Cinta
Empat jenis cinta tersebut berhubungan erat dengan mitologi Yunani kuno—seperti halnya agape, dalam bahasa Yunani agape bermakna cinta yang altruistik—jenis cinta dengan level tertinggi karena cinta ini tidak membutuhkan balasan. Cinta dengan jenis agape sering dihubungkan dengan hal kerohanian—seperti hubungan Tuhan dengan manusia. Cinta dengan jenis eros dalam mitologi Yunani kuno diambil dari nama dewa yang bernama Eros—dia adalah dewa cinta yang mengarah pada gairah. Kemudian storge dalam mitologi Yunani merupakan cinta yang antar keluarga—cinta antar orang tua dan anak..
Storge sendiri dalam bahasa Yunani merujuk pada cinta keluarga. Philia dalam mitologi Yunani kuno merupakan cinta antar teman. Orang Yunani kuno percaya bahwa cinta jenis philia merupakan jenis cinta yang suci—karena melambangkan pengorbanan, ketulusan, dan kesetiaan antar sesama—di mana hal-hal tersebut merupakan basis fundamental dari asas persahabatan. Orang Yunani kuno percaya bahwa cinta jenis philia lebih agung daripada cinta jenis eros.
Penggambaran cinta antara Sarah dan Robert adalah storge—ikatan cinta antar adik dan kakak. Sarah dan Robert sudah sudah saling memahami sifat masing-masing. Sarah yang terluka hatinya akibat dari bahtera rumah tangganya yang hancur, ia mencoba menyembuhkan rasa sakitnya dengan mengunjungi Robert—berharap Robert mampu menenangkan Sarah yang kacau.
Kompleksitas Cinta
G.G Libowitz (dalam Wortman, 1992) pernah mengatakan bahwa cinta merupakan sebuah emosi positif—sebuah perasaan yang kita rasakan terhadap seseorang yang kita anggap istimewa. Dalam ragam jenis cinta, komponen perhatian terhadap orang yang kita anggap spesial merupakan salah satu komponen yang begitu berarti. Jika tidak ada elemen perhatian di dalamnya maka akan terasa datar dan tak memiliki makna. Juga hal demikian tergambar pada tokoh Robert Harmon—awalnya ia merasa senang dan tidak terganggu dengan kedatangan Sarah. Namun, lambat laun ulah Sarah yang di luar dugaan membuat Robert bingung dan frustrasi. Sarah memberikan perhatian paling tulus yang belum pernah diterima Robert dari siapapun. Hal ini menunjukkan kasih sayang antar saudara kandung (storge) yang dimiliki Sarah kepada Robert begitu kuat meski awalnya Robert tidak menyadarinya.
Secara tidak langsung Sarah telah membuat hidup Robert berantakan, tetapi karena kedatangan Sarah di rumah Robert membuat atmosfir kediaman Robert menjadi berbeda dan jauh menjadi lebih hangat—Sarah berinisiatif membelikan Robert berbagai macam hewan piaraan, agar Robert bisa merasakan cinta terhadap makhluk hidup—juga Sarah berharap hewan piaraan yang dibeli oleh Sarah mampu menginspirasi Robert untuk menulis tentang cinta. Karena Sarah berpikir bahwa Robert adalah manusia yang tak bisa merasakan cinta dan Robert hanya mengetahui soal sex dalam novel yang ia tulis ketimbang makna cinta.
Robert mulai merasakan sesuatu yang asing dalam dirinya—sesuatu yang menurutnya sangat klise, yakni cinta. Robert mendapati dirinya mulai merasakan cinta ketika ia melihat Sarah tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri. Jiwa kesepian Robert mulai terusik—ia mulai merasa kehilangan Sarah tatkala Sarah terbaring sakit di atas ranjang—ia merawat adiknya dengan penuh perhatian. Robert pun yang awalnya tak peduli dengan hewan piaraan pembelian Sarah—ia mulai merawatnya dengan kasih sayang.
Manusia dan Cinta
Robert akhirnya bisa merasakan cinta berkat Sarah—karena dirinyalah Robert percaya bahwa cinta memang nyata meski kita tidak dapat melihat wujudnya. Robert ingin menjadi sosok yang bisa memberikan kebutuhan cinta terhadap Sarah yang sulit ditebak dan bisa meledak sewaktu-waktu. Karena Robert merasa telah mengenal Sarah dengan baik. Robert merasa ia bisa menggatikan posisi mantan suami Sarah dan akan memberikan banyak cinta kepada Sarah. Robert hanya ingin merawat dan saudari kandungnya tersebut dan tak ingin Sarah terluka karena cinta lagi.
Sarah memutuskan kembali kepada mantan suaminya meski Robert memintanya untuk tetap tinggal. Sarah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali bersama suami dan anaknya—karena Sarah menganggap bahwa sumber cinta dan kebahagiaan Sarah ada pada mereka. Cinta yang dimiliki Sarah kepada mantan suaminya tersebut merujuk pada eros—karena Sarah menganggap mantan suami dan putrinya merupakan pusat kebahagiaan bagi dirinya.
C.S Lewis juga menyatakan kebutuhan manusia akan cinta tidak akan pernah cukup—yang berarti bahwa manusia memiliki kebutuhan cinta tidak hanya pada pasangan. Tentunya mereka membutuhkan afeksi dari hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Selain rapuh—John Cassavetes menampilkan tokoh Sarah dan Robert merupakan dua manusia kesepian yang sedang mencari arti cinta itu sendiri. Cassavetes menampilkan Robert sebagai playboy kesepian yang cenderung apatis bahkan sinis ketika membicarakan cinta.
Namun, semuanya berubah ketika Sarah yang kacau mendarat di pintu rumahnya. Bisa dikatakan bahwa pertemuan Robert dengan Sarah adalah sebuah anugerah—karena Sarah secara tidak langsung menunjukkan Robert arti cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sarah mungkin depresi dan kacau pasca perceraiannya, tetapi dari kekacauan Sarah—Robert akhirnya mengetahui mengapa saudarinya begitu menginginkan hidup dengan cinta—karena dengan adanya sentuhan cinta, kehidupan manusia menjadi lebih berwarna dan manusia menjadi lebih peka terhadap sekitar meski kita semua terkadang masih awam dalam memahami cinta.
Sarah sangat mendambakan cinta. Ia berpikir bahwa ia tidak akan benar-benar merasakan bahagia seutuhnya jika ia tidak hidup dengan seseorang yang ia cintai. Namun, Sarah juga gagap dalam memahami cinta. Karena bagi Sarah cinta merupakan aliran yang tidak akan terputus. Benarkah demikian? John Cassavetes dalam Love Streams dengan lantang mempertanyakan kembali makna cinta—penonton seakan diajak untuk merenung sejenak mengenai pemahaman tentang cinta.
Melalui Love Streams—Cassavetes menegaskan bahwa cinta mungkin adalah hal yang sepele bagi beberapa individu, bahkan mungkin sebagian dari kita akan skeptis jika berbicara tentang cinta. Namun, hidup tanpa cinta jauh lebih buruk—karena hal tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak akan benar-benar merasakan kehidupan yang subtil, juga manusia akan mati rasa bila dunia dan seisinya tercipta tanpa cinta. Karena terkadang ego manusia begitu tinggi dalam menerjemahkan falsafah cinta yang begitu kompleks.
Kita mungkin berpikir bahwa kita sudah pandai memaknai cinta, tetapi bisa jadi kita yang gagap dan nihil dalam memahami cinta. Kita mungkin pernah tersesat dalam menemukan arti cinta layaknya Robert dan Sarah, tetapi cinta bisa tumbuh pada diri kita jika kita meyakini bahwa cinta memang nyata kehadirannya tanpa harus mengetahui rupa cinta itu sendiri.
Love Streams|1984 |Sutradara: John Cassavetes |Durasi: 144 Menit |Negara Asal: Amerika Serikat |Pemeran: Gena Rowlands, John Cassavetes
Mega Fadilla

Seorang penonton film juga pecinta Chungking Express paling taat. Menjadi seorang podcaster FilmExpress di Spotify apabila tidak mager. Sisa waktunya biasanya dihabiskan untuk menulis dan tidur.


1 note
·
View note
Text
The Lunchbox : Memberi Makan Rasa Cinta

Film ini berkisah tentang Ila (Nimrat Kaur), seorang ibu rumah tangga biasa yang sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan suaminya. Pada mulanya Ila bermaksud mengubah hubungannya yang monoton lewat pembaharuan menu makan siang. Bukan suasana hubungan yang berubah, yang terjadi malah salah pengiriman kotak makan menu siang tersebut. Saajan Fernandes (Irrfan Khan) yang menerima kotak tersebut rupanya menikmati pembaharuan menu dari Ila. Pertemuan indra pengecap ini kemudian menjadi sebuah tanda perubahan bagi masing-masing.
Secara umum banyak hal mewarnai film ini. The Lunchbox menggambarkan suatu perspektif budaya, gastronomi, kehidupan masyarakat kelas mengengah ke bawah di India, sampai hubungan pasutri. Sebagai sutradara, Ritesh Batra berhasil mengemas warna film ini dengan komposisi yang pas. Tidak suram tak pula terang, tidak selalu menyedihkan tapi juga tidak berarti membahagiakan. Meski bergenre drama-romansa, The Lunchbox tak berfokus pada persoalan jatuhcinta. Menurutku, Ila dan Sajaan malah tampak belum saling jatuh cinta.
Mengingat teori triangular cinta menurut Sternberg (1986), cinta setidaknya memiliki 3 komponen; kedekatan atau keintiman, gairah, dan komitmen. Ila dan Sajaan digambarkan hanya memiliki komponen kedekatan atau keintiman. Hal ini dibangung lewat hubungan keduanya yang berbagi kisah lewat surat, mereka saling terbuka dan menunjukkan afeksi satu sama lain.
Kedekatan emosional diantara keduanya juga tidak hanya berupa kisah-kisah pengalaman sehari-hari tetapi juga obrolan seperti saat Ila bicara tentang suaminya, atau ketika Ila berbagi pandangan dari tetangganya yang bangun dari koma bertahun-tahun hanya untuk membetulkan kipas angin. Kedekatan atau keintiman mereka hanya sampai di tahap nyaman atau suka (liking). Bagaimanapun cinta adalah perasaan abstrak yang interpretasi setiap orang tidak harus sama. Kotak makan disini juga menjadi saksi bisu sekaligus medium yang menggambarkan perasaan Ila. Manakala hati Ila masih terpaut pada suaminya, kotak makan itu berisi menu-menu kesukaan suaminya yang ia bagikan kepada Sajaan. Seiring Ila gagal mencoba memperbaiki komunikasi dengan suaminya, ia mulai menyuguhkan menu-menu kesukaan Sajaan yang diinformasikan lewat surat. Setiap tatapan dan ekspresi Ila menunjukkan layaknya ia tak benar-benar butuh cinta. Ia hanya ingin merasa dihargai dan didengar.
Begitulah bagaimana ia menikmati komunikasi lewat teriakan dengan bibi yang tinggal diatas apartemennya ataupun dengan Sajaan yang tak pernah ditemuinya. Sementara senyum tak pernah ia tampilkan saat berada di kamar atau meja makan bersama sang suami. Sebaliknya, Sajaan menikmati perihnya kesendirian sejak ditinggalkan istrinya. Hingga datang peran orang lain di hidupnya, ia mulai belajar dan menikmati rasa menghargai dan mendengarkan.Perasaan-perasaan karakter utama digambarkan dengan baik secara verbal dan non-verbal.
Sementara karakter-karakter pendukung berperan sesuai porsi yang ‘mendukung’ bagaimana Ila dan Sajaan tergerak untuk melihat perspektif baru tentang kehidupan. Begitupun penonton bisa menerima informasi dengan baik melalui penggambaran lanskap kehidupan yang dilihat dan diimajinasikan oleh para tokoh. “Kereta yang salah bisa membawamu pada stasiun yang benar”, Begitulah mereka memercayai kisah yang membawa pada lompatan baru. . Kelemahan film ini tampak pada jalan cerita yang sulit untuk diterima penonton. Lebih-lebih penonton yang tidak percaya adanya keajaiban cinta dan takdir. Bisa dibilang dari seribu pengiriman kotak makan di India, mungkin hanya satu kejadian dimana pengirim dan penerima bisa menjalin hubungan pertemanan meski salah satunya sudah memiliki pasangan. Satu kotak itu mungkin hanya milik Ila yang tak nyata. Rasanya hampir mustahil. Di sisi lain, film ini memberi gambaran bagaimana takdir bekerja. Kejadian seperti ini mungkin saja ada. Pada saat seseorang melihat tanda bahwa ia harus beranjak dari posisinya sekarang ini, tanda tersebut bisa muncul lewat apa saja.
Penulis : Agnina Rahmadania
Desain oleh : Hotman Nasution
The Lunchbox | 2013| Sutradara : Ritesh Batra | Negara Asal : India | Durasi : 104 Menit | Pemeran : Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui | Produksi : Sikhya Entertainment, DAR Motion Pictures
Agnina Rahmadinia

Alumni jurusan Ilmu Komunikasi yang di tengah kegiatannya sedikit-sedikit nonton, tapi nontonnya sedikit-sedikit.

0 notes
Text
Adrian Jonathan : Melihat Lanskap Luas dari Perspektif Kritik Film.

Saya sedikit kesal ketika teman-teman saya melontarkan ledekan “Emangnya kritik film itu gunanya apa sih?”. Ingin saya cabik-cabik mukanya, namun tentu saya urungkan niat itu. Sepertinya sudah menjadi hal umum bahwa kritik film kurang diminati di Indonesia. Hal ini bisa dilihat ketika ada lokakarya membuat film dan mengkritik film, tentu lokakarya mengkritik film akan jauh lebih sedikit ketimbang membuat film. Atau sederhananya, ketika saya minta untuk anda menyebutkan pembuat film Indonesia, tentu anda akan lancar menyebutkan nama besar seperti : Joko Anwar, Mouly Surya, Hanung Bramantyo atau yang lebih senior, Garin Nugroho.
Namun, Ketika saya meminta anda untuk menyebutkan nama-nama kritikus film Indonesia, tentu nama besar seperti : Permata Adinda, Afrian Purnama, Eric Sasono, Intan Paramaditha atau yang lebih senior seperti JB Kristanto tidak ada di pikiran anda. Hal ini membuat saya bingung dan mempertanyakan mengapa kritik film di Indonesia kurang diminati? Padahal jika ditilik lagi, kritik film berperan penting dalam ekosistem perfilman. Karena saya ingin menggugurkan rasa penasaran saya, saya mengajak Adrian Jonathan untuk membahas kritik film dalam spektrum yang lebih luas mencakupi ekosistem, literasi dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Adrian Jonathan sendiri adalah salah satu pendiri Cinema Poetica—kolektif kritikus, jurnalis, peneliti, dan pegiat film yang berfokus pada produksi dan distribusi pengetahuan tentang sinema untuk publik. Dari 2007 sampai 2010, mondar-mandir sebagai pengurus program di Kinoki, bioskop alternatif di Yogyakarta. Sempat terlibat di filmindonesia.or.id sebagai anggota redaksi, Festival Film Solo sebagai kurator, dan Berlinale Talent Campus 2013 sebagai kritikus film. Saat ini aktif menulis dan meneliti tentang perfilman Indonesia, serta mengadakan lokakarya kritik film di berbagai kota.
Simak wawancara Mania Cinema bersama Adrian Jonathan berikut !
Mulai dari pertanyaan paling fundamental, Apa itu kritik film? Soalnya masih banyak yang salah paham mengenai kritik film.
Aku pribadi sebenarnya tak yakin apakah jawaban aku benar atau tidak. Aku juga masih belajar, sih. Tapi dari yang aku baca dan hasil diskusi teman-teman forum lenteng, cinema poetica, rumah film dan yang lain, akhirnya semuanya punya tafsirnya sendiri mengenai apa itu kritik film. Jadi, pada akhirnya aku selalu mencoba mengulik pada posisi pengkritiknya sendiri dalam melihat pijakan atau perspektifnya dalam mengkritik.
Jika kita lihat secara umum, kritik film adalah tanggapan terhadap suatu film melalui tahap intepretasi dan evaluasi. Itu masih umum banget ya, kalau misal kita lihat di beberapa buku kajian film, salah satu contohnya dari filsuf Stanley Cavell yang bilang bahwa kritik itu adalah upaya manusia untuk membagi pleasure. Ketika membagikan pleasure, setidaknya ada 3 aspek yang terjadi : aspek testimonial, aspek retorikal dan aspek evidensial/pembuktian. Pendapat Stanley Cavell mengenai ini aku banyak yang setuju. Tapi, kalau aku baca dan teliti lagi, manusia pada umumnya memiliki hal yang berbeda dalam menganggap pleasure/ kesenangan tersebut.
Tiap manusia memiliki perbedaan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kelas, geografis dan lain-lain. Apa yang dianggap pleasure oleh masyarakat kelas menengah kebawah tentu berbeda dengan pleasure oleh masyarakat kelas menengah keatas. Itu baru kalau kita bicara soal menonton film sebagai pleasure, belum soal kebutuhan menonton film yang lain seperti untuk terapi, fandom, dan lain-lain. Ketika mengetahui bahwa kebutuhan orang terhadap film itu beragam, aku menyimpulkan bahwa kritik film itu adalah uji kelayakan. Dan nilai “kelayakan” ini berhubungan erat dengan kebutuhan kita sebagai manusia, karena kebutuhan bisa menentukan nilai layak kita terhadap suatu film.
Nilai kebutuhan ini cukup kuat kaitannya dengan perspektif kita dalam mengkritik sebuah film. Mengkritik film sebagai kebutuhan pengisi waktu tentu akan berbeda dengan mengkritik film sebagai produk pengetahuan. Aku bisa mengambil kesimpulan bahwa kritik film adalah uji kelayakan yang memiliki metode dan standarnya sendiri, di mana standarnya di sini setidaknya berhubungan erat dengan kebutuhan kita terhadap film.
Jadi, apakah kritik film itu penting? Jika penting, seberapa penting kah?
Tergantung penting untuk apa dulu nih, haha. Karena kepentingan itu sendiri ada ranah tertentu. Secara personal, kritik film penting untuk menajamkan tanggapan kita terhadap suatu film. Kritik sebenarnya cara yang bagus untuk memetakan respon kita terhadap suatu film. Misalnya ketika aku menonton The Act Of Killing (2012) aku merasa terganggu, dan perasaan yang membuat aku terganggu ini kemudian bisa dielaborasi lagi dengan pertanyaan “mengapa sih aku merasa terganggu oleh film ini?”, “di adegan mana yang buat terganggu?”. Dengan begitu aku dapat menajamkan respon terganggu-ku terhadap film tersebut, dari cara-cara sederhana ini dapat diketahui kenapa aku merasa terganggu oleh film tersebut.
Di sisi lain, seringkali aku menjumpai orang yang menyukai sebuah film, mengatakan bahwa film yang ia tonton bagus, tapi pas ditanya kenapa dia suka dan dimana letak bagusnya film itu, dia kesulitan untuk menjawab. Nah, fungsi kritik film di ranah personal adalah bagaimana gagasan dan respon kita terhadap film bisa ditajamkan lagi dan memiliki landasan jelas. Kalau dalam ranah komunal atau masyarakat banyak, kritik film bisa mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat.
Hal ini bisa dilihat saat film Tilik (2018) digemari banyak orang. Satu hal yang aku baca terhadap kejadian tersebut adalah kerinduan masyarakat akan kedekatan cerita yang jarang terjadi dalam khazanah sinema Indonesia. Orang-orang menganggap bahwa realita ibu-ibu naik truk adalah hal yang dekat dengan mereka, tampaknya hal itu yang menghubungkan mereka dengan film tersebut. Dapat dilihat juga dari tanggapan penonton bahwa mereka gagap menghadapi ketimpangan kota dan desa. Jadi ya kritik film penting untuk melihat cerminan sesungguhnya dari suatu masyarakat dalam menanggapi suatu peristiwa yang ada.
Selain menjadi cerminan suatu masyrakat, kritik film juga berfungsi menjadi suatu catatan sejarah. Jika membahas sejarah, ia tak hanya berkutat pada preservasi film secara fisik. Tetapi sejarah juga membahas bagaimana respon atau gagasan masyarakat mengenai sesuatu hal pada zaman tertentu. Di era pandemi ini aku cukup sering mengulik dan membeli Koran-koran lama yang berasal dari zaman kolonial dan membaca ulasan filmnya. Aku menemukan bahwa di era itu, film yang dianggap ‘layak’ adalah film yang membahasakan ‘Indonesia’, sangat nasionalistik ketika secara konsep tidak ada negara ‘Indonesia’, yang ada Hindia Belanda.
Bisa dilihat bahwa era tersebut memiliki pijakan kritik film politis yang pada tahun 40-50an sudah berbeda pijakannya, begitu juga dengan tahun selanjutnya. Apalagi di era internet sekarang, pijakan terhadap kelayakannya udah beda dan beragam banget. Itu semua kan disimpan dalam Koran, kliping, video, tulisan dan lain-lain. Ini jadi salah satu akses untuk mengetahui sejarah berpikir masyarakat.
Jika membahas soal kritik film dalam perspektif yang luas, maka kita akan membahas soal “Ekosistem”. Menurut Adrian sendiri, apa itu Ekosistem film?
Kita bisa mulai membedahnya dari kata “Ekosistem”. Kalau dari istilah ilmu biologi, Ekosistem adalah bagaimana suatu lingkungan dianggap sebagai suatu entitas yang terdiri dari banyak komponen, yang interaksinya membentuk sebuah kelanggengan atau keberlangsungan di dalam lingkungan itu sendiri. Jika kita mengadopsi cara berpikir ini ke kebudayaan, maka kurang lebih cara kerjanya akan sama. Salah satu produk kebudayaan yaitu film, bisa dilihat dari cara pikir yang sama. Film terdiri dari beberapa komponen dan pelaku yang interaksinya memiliki dampak terhadap kelangsungan film itu sendiri. Dampak yang paling mudah dilihat adalah dampak materil. Hasil dari dampak ini berupa produksi, distribusi, dan eksebisi. Dampak materil itu sendiri adalah hal utama di suatu ekosistem film. Pada umumnya, dampak ini bersifat terukur dan bisa dihitung dengan angka atau statistik. Contohnya seperti jumlah film yang beredar di bioskop, jumlah film yang diproduksi, jumlah tiket bioskop yang terjual pada tahun tertentu dan lain-lain.
Namun, film tidak hanya dinilai dalam sifat materil nan terukur, ia juga bersifat abstrak nan immateril yang nilainya tidak bisa diukur. Contoh sederhananya ketika kamu menonton film dan merasa sedih, apakah kesedihanmu bisa diukur dalam rupiah atau jumlah lainnya? Atau ketika kamu menonton film Mother Dao, the Turtlelike (1995) yang sarat akan pengetahuan mengenai Indonesia di zaman kolonial, apakah nilai pengetahuan itu bisa diukur dalam jumlah rupiah atau jumlah lainnya? Tentu jawabannya adalah tidak, karena pengetahuan dan emosi adalah dua hal kompleks yang tidak bisa dinilai dalam angka dan statistik. Jika kita mempertimbangkan hal bersifat immaterial seperti arsip, apresiasi dan pendidikan dalam suatu ekosistem film, maka perspektifnya akan luas dan menyeluruh. Jika ke-enam aspek ini, yaitu : produksi, distribusi, eksebisi, apresiasi, pendidikan dan pengarsipan berjalan dengan baik, maka ekosistem film pun akan berlangsung dengan baik pula.
Ini baru mengenai ekosistem perfilman, yang mana ekosistem perfilman sendiri tidak berdiri tunggal, ia merupakan bagian dari ekosistem yang lain. Contohnya, ekosistem film adalah bagian dari ekosistem transportasi publik. Karena tanpa ada sistem transportasi yang baik, orang-orang tidak mudah mengakses ke bioskop. Aku pernah buat riset soal ini di tahun 2015-2016an yang membahas bagaimana ketimpangan penonton di daerah Jabodetabek. Kendatipun, hal ini terjadi sebelum maraknya OTT seperti Netflix dan lainnya menjamur di layar gawai kita, ini merupakan sebuah fakta yang pernah terjadi. Di saat itu, 80 % orang menggunakan kendaraan pribadi untuk mengakses bioskop. Tidak heran akhirnya terjadi ketimpangan penonton, karena kebanyakan bioskop di negara ini dirancang dengan logika untuk orang yang memiliki kendaraan pribadi. Saat itu, sedikit sekali bioskop yang langsung terhubung dengan stasiun kereta atau bis. Jadi, tidak heran kenapa saat itu penonton film Indonesia terbilang sedikit karena akses transportasi ke bioskop yang tidak merata. Ini baru bicara mengenai pengaruh ekosistem perfilman ke ekosistem transportasi publik, belum lagi yang lain. Ekosistem film memiliki lapisan sistem yang cukup kompleks dan berkelindan ke ekosistem lainnya.
Apa peran kritik film dalam ekosistem film?
Dari perspektif umum, aku bisa baca dua hal tentang peran kritik film terhadap ekosistem film. Pertama, ia bisa menjadi tanggapan atau reaksi publik terhadap film. Hal ini tentu erat kaitannya dengan bagiamana publik menerima suatu film. Reaksi penonton bisa berfungsi sebagai dua hal : pertama, ia bisa menjadi evaluasi terhadap pembuat film. Bahan evaluasi ini bisa menjadi gambaran bagi pembuat film tentang bagaimana anggapan publik terhadap filmnya. Entah akhirnya pembuat film itu menerima atau menolak tanggapan tersebut, ia tetap menjadi bahan evaluasi atas reaksi publik terhadap filmnya.
Kedua, seperti yang sudah ku sebut tadi, ia bisa menjadi cerminan bagaimana masyrakat merespon terhadap suatu peristiwa. Meminjam istilah dari J.B Kristanto yang berkata bahwa kritik film adalah sebuah “pertukaran pengalaman”. Setiap penonton atau kritikus pasti memiliki tafsirnya sendiri terhadap suatu film. Karena kritik film adalah menukarkan pengalaman menonton kita terhadap orang lain, dengan cara yang tidak langsung kita sudah berinteraksi melalui kritik tersbeut. Aku jadi ingat perkataan Guy Debord, ia berkata bahwa “Tontonan adalah relasi sosial antar berbagai orang, yang dimediasi oleh gambar/image”.
Nah, aku rasa kritik film cara kerjanya seperti itu juga, ia merupakan interaksi dari satu individu ke individu lainnya dalam bentuk tulisan atau pertukaran gagasan. Mengenai pertukaran gagasan, kita akan bicara bagaimana masyarakat menerima atau terbuka terhadap gagasan baru akan standar kelayakan yang berbeda. Jika misalnya, masyarakat kita terbuka akan standar-standar kelayakan baru dan berbeda, aku rasa akan menjadikan kita masyarakat yang lebih demokratis.
Aku cukup khawatir ketika melihat bagaimana respon masyarakat terhadap standar kelayakan yang berbeda pada kasus film Tilik (2018) kemarin yang terlihat sangat fasis.Dalam menghadapi perbedaan standar kelayakan atau gagasan, harus dihadapi dengan santai,sih, tak perlu bertindak fasis seperti itu. Perbedaan standar kelayakan atau gagasan itu normal dan tidak apa-apa untuk diperdebatkan, tapi tentu dengan cara yang santai dan tidak fasis. Di sini, kritik film juga penting untuk “labaratorium” kebersamaan kita dalam menghadapi reaksi penonton yang berbeda-beda.
Kedua, kritik film penting di ekosistem film sebagai perspektif penonton. Dalam ekosistem film, Kritik berada di irisan antara pendidikan dan apresiasi. Kritik film memang merupakan tanggapan subjektif namun ia juga memiliki metodologi yang sudah terverifikasi oleh ilmu pengetahuan. Dua elemen ini yang membuat kritik film berfungsi untuk menantang atau menguji kembali pendapat atau subjektivitas penonton terhadap segala estetika, pengelolaan gambar dan tutur yang ada pada film. Sehingga, tercipta sebuah perspektif penonton dari hasil pengujian terhadap subjektivitas tadi.
Sayangnya, hal ini belum terlalu banyak dibahas di Indonesia mengingat kurikulum pendidikan Indonesia yang masih berada dalam ranah sempit. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengukur literasi hanya sampai tahap baca-tulis, jika kamu sudah bisa membaca dan tulis, kamu disebut sudah berliterasi. Namun, aku rasa itu belum cukup mengingat medium audio visual yang kian mudah diakses. Aku rasa literasi akan audio visual harus ada. Karena audio visual memiliki cara kerja sendiri dalam memahami makna dari suatu gambar dan suara. Ini kalau kita bicara pada urusan politik yang lebih luas. Namun, perspektif penonton berhubungan dengan bagaimana cara mereka memahami suatu olahan gambar.
Ekosistem perfilman kian berkembang dan beberapa daerah di luar Jakarta sudah mengembangkan ekosistem film di daerahnya sendiri. Apakah kritik film penting dalam spektrum suatu daerah?
Aku rasa tetap penting, karena melihat produksi audio-visual oleh masyarakat di luar Jakarta semakin pesat. Produk audio visual dari luar Jakarta seperti serial web, film atau film pendek cukup banyak diproduksi beberapa tahun belakangan ini. Contohnya, perfilman Makassar yang beberapa tahun belakang cukup pesat produksinya. Belakangan ini mereka merilis film “Jalangkote Rasa Keju” yang sangat kental dengan budaya Makasar. Karena maraknya produksi audio-visual tersebut, seharusnya ada mediator atau penengah antara masyarakat dan pembuat film. Kritik film penting untuk menjadi mediator dalam merespon cerminan realitas yang hadir dalam produk audio-visual tersebut.
Contoh kasusnya di ekosistem film Yogyakarta yang cukup pesat. Kritik film penting untuk mempertanyakan dan menguji lebih dalam mengenai cerminan akan realitas dari masyarakat Yogyakarta. Apakah masih relevan memandang Yogyakarta dalam perspektif angkringan, rindu, dan kenangan? Padahal realitanya, misalnya, ada ketimpangan yang terjadi di Yogyakarta. Nah, di sini peran kritikus film jadi penting untuk menguji kembali akan cerminan realitas yang ada di Yogyakarta tersebut. Hal serupa juga berlaku untuk daerah lain, kendati metodologinya berbeda.
Bagaimana kondisi kritik film di perfilman Indonesia saat ini?
Mulai merangkak dan nampak geliatnya sih, kalau menurutku. Apabila dibandingkan dengan dulu, saat aku baru mengembangkan Cinema Poetica dengan beberapa temanku, itu masih sedikit sekali. Mungkin sejumlah media internet yang bisa disebut seperti Jurnal Footage dan Layar Perak. Itupun tidak berapa lama kemudian, situs Layar Perak sudah tidak aktif. Kalau di sisi akademisi ada Jurnal Imaji dari Institut Kesenian Jakarta atau Cleo dari Yogyakarta. Lebih dari itu, dari sisi media cetak dipegang oleh Kompas dan Tempo. Bisa dibayangkan betapa sepi skena kritik film pada saat itu. Kalau sekarang sih udah lumayan beragam, dari lintas medium dan lintas latar belakang. Publik pun mudah untuk menulis ulasan film di akun blog pribadi dan media sosial lainnya. Dari media seperti Tirto dan Kumparan cukup aktif dalam menulis ulasan film. Dan aku senang ketika ada kritik film yang menggunakan perspektif atau kebutuhan dari kelompok tertentu.
Contohnya ada Arisan Newsletter yang menggunakan perspektif gender perempuan dalam kritik filmnya. Atau, ada teman-teman dari Aceh dan Padang yang menggunakan perspektif kotanya terhadap kritik filmnya. Meski begitu, fakta bahwa substansi dari kritik tersebut harus dievaluasi dan diperbaiki tidak bisa kita tampik. Masih banyak sekali ulasan film di blog pribadi yang belum terstruktur dengan benar. Cinema Poetica pun juga perlu mengevaluasi substansi dari apa yang dikritisi di situs tersebut. Namun ini jadi tanggung jawab bersama untuk terus menguji dan mengevaluasi ketajaman analisa kritik film setiap individu dan kelompok.
Jika membahas kritik film, maka kita juga akan memabahs soal literasi film. Apa itu literasi film?
Simpelnya, Literasi film adalah kemampuan dalam memproses informasi lewat medium audio- visual. Nah, kalau aku elaborasi lagi, apa sih yang dianggap sebagai Informasi? Apakah hanya yang diungkapkan secara tulisan atau oral saja yang bisa disebut informasi? Di Indonesia, cukup rumit membicarakan soal literasi film. Karena, apa yang dianggap informasi oleh masyarakat umum masih sebatas apa yang bisa dilihat, padahal informasi tidak hanya terbatas pada penglihatan inderawi.
Contohnya, ketika suatu film dirubah gambar dan suaranya, maka akan menciptakan informasi yang baru. Informasi baru ini akan mengubah makna dari film aslinya. Penjabaran ini menjelaskan bahwa film atau medium audio visual dapat dimanipulasi dan menghasilkan informasi baru. Masyarakat Indonesia masih gagap memproses informasi seperti ini. Masyarakat masih menganggap bahwa apa yang terlihat secara empiris adalah informasi yang benar. Sehingga masyarakat belum bisa melihat lebih luas dari segi konteks dan hal yang mendukung informasi tersebut.
Bagaimana peran Kritik Film terhadap literasi film?
Tentunya sangat berperan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu fungsi kritik film adalah mencoba untuk membagi interpretasi atau tanggapan penulis akan suatu film. Dalam penulisan kritik film yang baik, penulis diminta untuk tidak hanya menjabarkan apa yang tampil di dalam layar, tetapi juga diminta untuk menjabarkan apa yang tidak tampil di layar yang berupa konteks film.
Contohnya bisa dihilat di tulisan Raksa Santana soal serial The Queen’s Gambit (2020). Di tulisan tersebut, Raksa tidak hanya menjabarkan apa yang terjadi di layar ;orang-orang bermain catur. Namun, ia juga menjabarkan apa yang tidak ada di layar berupa konteks film. Konteks film tentang bagaimana upaya Beth Harmon untuk membela keberpihakan hak kelompok terpinggirkan, relasi sejarah perang dingin dan lain-lain. Literasi film hadir saat bagaimana menjaga koherensi antara apa yang ada di layar dan tidak ada di layar bisa menjadi suatu kritik argumen yang utuh. Jadi ya saling berkelindan satu sama lain.
Apa relasi dari kritikus film dan pembuat film?
Aku rasa kritikus dan pembuat film itu bagaikan saudara kandung. Mereka lahir dari rahim yang sama, yaitu film. Sebagai anak, tentunya kritikus dan pembuat film harus memahami Ibu mereka. Pemahaman akan film ini, tertuang dalam bentuk literasi film. Tentunya, kritikus dan pembuat film harus mempelajari cara kerja dari literasi film. Hal yang menjadi perbedaan antara kritikus dan pembuat film hanya pada metodologi dan hasil akhirnya.
Jika pembuat film memiliki metode membuat film, kritikus film memiliki metode untuk merespon film tersebut. Dan jika hasil akhir pembuat film berupa tayangan atau film, kritikus film berupa ulasan, esai yang mediumnya bisa lewat siniar atau tulisan. Hal yang agak konyol adalah ketika ada orang yang menganggap bahwa salah satu dari pekerjaan tersebut lebih superior dari satu sama yang lain. Padahal, baik kritikus film maupun pembuat film lahir dari titik pijak yang sama, jalan hidupnya saja yang berbeda.
Mengapa jumlah peminat kritik film lebih sedikit?
Masalah utamanya mungkin di unsur materialitasnya. Jika dibandingkan dengan membuat film, apa yang kamu investasikan dengan apa yang kamu hasilkan, hasilnya nampak dan jelas. Kamu belajar tata kamera, tata suara, naskah dan lain-lain menghasilkan sebuah produk film berbentuk film seluloid atau hardisk. Kalau kritik film, proses investasinya sedikit abstrak. Kamu menonton ratusan film dan membaca beberapa buku hanya untuk satu tulisan, logika matematika dan hasil materialnya tidak jelas.
Belum lagi, melihat bagaimana negara ini tidak terlalu menghargai produk-produk intelektual seperti kritik film. Dan masyarakat Indonesia yang tidak gemar membaca dan menganggap bahwa kegiatan menulis tidak membutuhkan usaha yang lebih. Padahal, investasi dalam menulis kritik film itu cukup banyak dan kompleks. Hal ini membuat lingkaran pengetahuan lainnya seperti jurnalistik dan akademik juga sedikit sulit untuk berkembang. Padahal, di Indonesia, kritik film berada pada dua ranah itu, media dan publikasi ilmiah.
Selain itu, perfilman Indonesia pernah mengalami krisis produksi pada tahun 1960-an dan 1990-an. Hal ini membuat kegiatan kritik film sangat sepi karena film yang ingin dikritisi pun jumlahnya hanya segelintir. Wajar kemudian jumlah atau minat terhadap kritik film sedikit, karena diskusi akan film Indonesia itu hanya sedikit. Perfilman Indonesia baru mulai stabil di tahun 2005. Baru mulai beberapa tahun belakangan aku rasa kegiatan kritik film mulai diminati oleh publik, itupun setelah beberapa tahun kondisi perfilman stabil.
Kritik film di Indonesia berupa 50 persen aktivisme dan 50 persen hobi. Hanya sangat segelintir dari ranah professional atau bahkan menganggap kritik film sebagai mata pencaharian. Beberapa nama dari ranah professional mungkin mba Leila Chudori dari Tempo dan Aulia Adam dari Tirto. Mereka pun terdaftar sebagai jurnalis, bukan kritikus film. Kritik film di Indonesia hampir tidak memiliki nilai komersil. Aku sendiri kaget saat aku menulis untuk Criterion dibayar sepuluh kali lipat ketimbang media besar di Indonesia. Padahal tulisan yang aku buat untuk Criterion, usaha dan investasinya sama ketika aku menulis untuk Cinema poetica atau media lainnya. Dari sini bisa terlihat bagaimana kejomplangan valuasi akan kritik film di dua negara ini.
Aku tidak ingin membandingkan, hanya saja aku ingin memberi contoh bahwa bagaimana negara lain menghargai pekerjaan menulis kritik film. Hal ini membuat kritik film tidak dianggap berkelanjutan secara finansial oleh kebanyakan orang. Intinya, matrealistik yang abstrak, kurang dihargai kritik sebagai produk intelektual, latar belakang historis akan krisis film dan ketidakjelasan akan keberlanjutan finansial adalah beberapa alasan mengapa kritik film kurang diminati.
Bagaimana menciptakan ekosistem film dan literasi film yang sehat?
Kalau membicarakan ekosistem yang sehat, sebenarnya kita harus merujuk ke ranah pendidikan, khususnya pendidikan audio-visual. Kalau misalnya masyarakat sudah terdidik dengan baik dengan pengetahuan akan literasi audio-visual yang mumpuni sejak dini, Maka akan menghasilkan penonton film yang kritis dengan argumennya. Dengan begitu, tanggapan penonton akan jauh lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pembuat film pun akan diuntungkan dengan tanggapan atau respon yang kredibel terhadap filmnya. Memang, kedengaran utopis. Namun, jika kita ingin mengambil langkah yang lebih realistis, bisa mulai dari membangkitkan solidaritas kita sesama dari ranah komunitas, industri atau apapun itu.
Solidaritas yang dimaksud adalah bagaimana di dalam suatu komunitas, industri atau yang lain bisa saling berbagi pengetahuan akan film. Hal yang bisa dicontoh, dari teman-teman komunitas Forum Lenteng yang membuat program “DVD Untuk Semua”. Di program ini, Forum Lenteng mengalihbasahakan film-film penting dari penjuru dunia ke subteks Bahasa Indonesia. Hal ini penting untuk distribusi pengetahuan yang lebih luas lagi agar tidak menimbulkan ketidakmerataan pengetahuan film. Atau yang lain, upaya aku dan teman-teman Cinema Poetica dalam menerjemahkan artikel film di dalam rubrik terjemahan. Distribusi pengetahuan film itu cukup penting, sayangnya negara tidak terlalu acuh akan hal tersebut.
Berharap sama negara tidak ada habisnya. Hal paling maksimal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan privilege yang kita punya. Dengan privilege inilah kita manfaatkan menjadi sebuah karya, dan karya tersebut bisa diakses oleh banyak orang. Itu dulu sih yang bisa kita lakukan selain solidaritas komunal yang tadi sudah disebut. Ya, intinya, berusaha dengan apa yang bisa diusahakan.
Diwawancarai dan ditulis oleh : Galih Pramudito
Desain oleh : Hotman Nasution
Galih Pramudito

Salah satu pendiri Mania Cinema. Pernah aktif di komunitas Sinelayu dan menjadi juru program Palagan Films di Pekanbaru. Kebanyakan waktunya ia habiskan untuk menonton, membaca, makan, selebihnya melamun. Saat ini tengah menyelesaikan studi Ekonomi Islam di UII Yogyakarta.
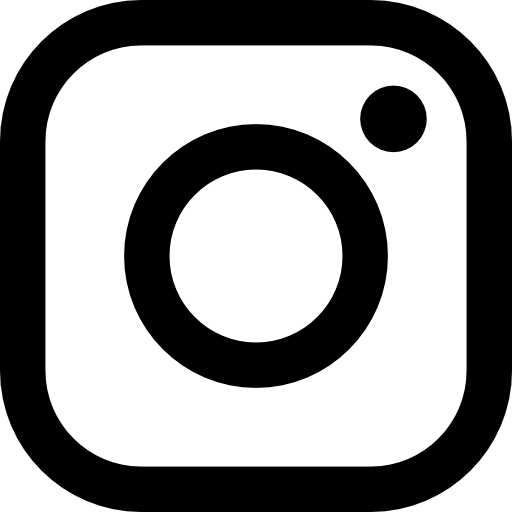
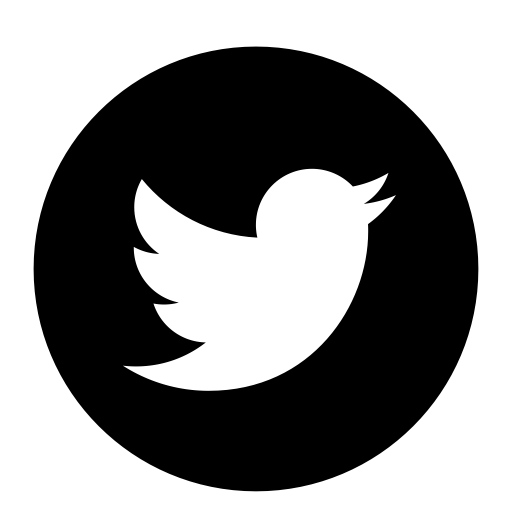
0 notes
Text
Intan Paramaditha : Perempuan dalam Imaji dan Realita Sinema.

Gender merupakan topik yang masih hangat untuk dibicarakan dalam berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali. Dalam ekosistem film sendiri bahkan terdapat teori film feminis yang muncul sejak perkembangan feminisme gelombang kedua yakni sekitar awal tahun 1970an. Teori ini digunakan untuk menganalisis film terutama dalam melihat bagaimana representasi perempuan di dalam film serta stereotip perempuan yang muncul setelah masyarakat menonton film tersebut. Seiring dengan munculnya teori ini, muncul pula berbagai organisasi perempuan dalam film.
Sebenarnya, hal ini tidak lepas dari fakta bahwa perempuan yang terlibat dalam industri film melalui berbagai peran seperti sutradara, produser, penulis, kritikus, programer festival, dan banyak posisi lainnya di industri film masih belum cukup terwakilkan. Dalam industri film hollywood sendiri ada istilah langit-langit seluloid (celluloid ceilling) yang mengacu pada kurangnya perwakilan perempuan dalam perekrutan dan pekerjaan di Hollywood.
Bagaimana pandangan dan kultur atas perempuan di industri film pada akhirnya akan mempengaruhi bagaiamana perempuan berperan dalam ekosistem perfilman, diantaranya dari segi karir, komunitas, serta sekolah film. Paritas perempuaan di ekosistem film terutama dalam hal kesempatan, pembayaran, serta representasi inilah yang masih diperjuangkan hingga hari ini. Setidaknya demikian yang dikutip dari salah satu organisasi yang mengupayakan kesetaraan dan transformasi kultur perempuan dalam film, yakni Woman In Film. Lebih lanjut, kami melakukan wawancara bersama Intan Paramaditha dalam menggali peran dan permasalahan perempuan dalam film serta bagaimana kondisi film dan perempuan di Indonesia. Intan Paramaditha sendiri adalah seorang alumnus PhD dari kajian sinema di Universitas New York. Fokus studinya mengacu pada gender, seksualitas, politik dan budaya. Sekarang ia mengajar sebagai dosen di bidang kajian film dan media Universitas Macquarie, Sydney.
Simak wawancara kami berikut ini!
·Pertama mungkin tentang hal yang paling mendasar dari ‘film dan perempuan’. Sejak kapan, sih, mbak, perempuan dinilai punya peran dalam film?
Kesadaran tentang pentingnya perspektif perempuan sebagai pembuat film menguat seiring dengan berkembangnya teori film feminis di tahun 1970an. Kritikus feminis seperti Laura Mulvey menunjuk bahwa film-film arus utama, dalam hal ini sinema Hollywood klasik, dibuat oleh laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai obyek hasrat penonton laki-laki. Karena itu teori film feminis mempersoalkan masalah representasi dan mengadvokasi film-film yang dibuat oleh sutradara perempuan. Di Indonesia sendiri, sebelum reformasi, peran penting buat perempuan sangat terbatas, misalnya sebagai aktor. Munculnya sutradara dan produser perempuan bertepatan dengan keterbukaan wacana gender dan seksualitas di akhir 90-an, serta hadirnya generasi pembuat film baru yang lepas dari tradisi ‘nyantrik’ dengan sutradara senior laki-laki.
Frase ‘dinilai punya peran’ ini menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Sejak abad 20 sebenarnya perempuan selalu punya peran. Editor The Man with the Movie Camera karya Dziga Vertov adalah perempuan. Tapi pertanyaannya: siapa yang menentukan nilai? Banyak sekali nama perempuan yang disingkirkan dan dianggap tidak penting dalam historiografi. Dalam beberapa dekade terakhir, peneliti sejarah dan pelaku arsip film berupaya untuk menelaah ulang perempuan-perempuan yang terhapus dari sejarah. Di negara-negara Selata, yang praktik penelitian dan pengarsipannya tidak banyak didukung pemerintah, ini masih menjadi tantangan besar.
· Dilihat sudut pandang lain selain teknis, seberapa besar atau pentingnya perempuan berperan dalam membangun ekosistem perfilman?
Harus lebih banyak perempuan berada di posisi pengambil keputusan terkait arah estetika maupun politik film, baik itu sebagai sutradara, penulis, atau produser. Secara estetika, banyak sutradara perempuan yang menyodorkan estetika feminis baru, merespon hubungan antara gambar dan kamera dari sudut pandang feminis. Sebagai contoh, lihat esai saya tentang Pasir Berbisik di Jump Cut.
Produser perempuan cenderung lebih awas dalam hal representasi gender dan seksualitas. Bagaimana perempuan ditampilkan dalam film? Sebagai tokoh yang punya agensi atau pelengkap? Mereka juga lebih peka terhadap persoalan relasi kuasa. Apakah perempuan menempati posisi-posisi strategis, atau hanya di-admin-kan saja dalam proses pembuatan film? Beberapa produser, seperti Mira Lesmana, juga sangat berhati-hati soal potensi pelecehan seksual dan memastikan ada code of conduct yang melindungi perempuan. Memang tidak semua pekerja film perempuan mengidentifikasikan diri sebagai feminis. Tapi sulit sekali membayangkan keputusan diambil tanpa dipengaruhi oleh pengalaman, misalnya pengalaman dilecehkan, dianggap remeh, dianggap tidak kompeten, dijadikan obyek seksual. Perempuan yang tidak pernah mengalami semua ini mungkin sangat privileged.
Bagaimana gambaran-gambaran perempuan dalam film selama ini?
Di awal tahun 2000an banyak sekali hal baru dari segi bagaimana perempuan digambarkan. Pembuat film seperti Mira Lesmana, Nia Dinata, dan Nan Achnas menggugat obyektifikasi perempuan dengan menghadirkan tokoh-tokoh perempuan yang kuat dan kompleks. Sayangnya saya lihat akhir-akhir ini justru obyektifikasi perempuan dinormalisasi. Ini bisa kita lihat di film Dilan, yang buat saya sangat bermasalah karena glorifikasi maskulinitas militer di dalamnya. Di film itu, tokoh Milea seperti tak punya fungsi apa-apa selain menjadi obyek hasrat laki-laki, dari yang sebaya sampai guru sekolah. Dia dipandang, ditimbang, dan diukur oleh orang di sekitarnya berdasarkan satu kriteria saja: cantik.
Di satu sisi, kita senang ada pembuat film feminis seperti Mouly Surya yang menghasilkan film seperti Marlina. Film menyodorkan kritik tajam terhadap sistem patriarki dengan cara yang sangat segar, yaitu merespon estetika genre Western. Tapi di sisi lain, penggambaran perempuan seperti dalam film Dilan juga makin banyak dan dianggap wajar. Belum lagi kerangka patriarki yang membingkai film-film Islami. Mungkin bisa dibilang kita melihat kemunduran dari segi wacana gender dalam film.
Bicara soal komoditas, apakah kebanyakan film hari ini masih sulit untuk lepas dari konsep “male gaze” sebagai upaya menarik penonton, mbak?
Ya, tentu saja. Contohnya ya tokoh Milea dalam film Dilan tadi. Nilai perempuan – baik itu pacar cantik seperti Milea, maupun tokoh ibu yang mengayomi – selalu diukur dari sudut pandang laki-laki, ‘kan?
·Ada tidak, mbak, pengaruh dari perspektif sutradara atau penulis (skrip) perempuan terhadap karya-karya film yang dihasilkan?
Ya, tentu ada. Kita nggak akan punya film yang menyodorkan kritik terhadap poligami dari sudut pandang perempuan kalau tidak ada Berbagi Suami karya Nia Dinata. Kita nggak akan punya film yang bicara tentang kekerasan terhadap perempuan secara demikian subtil kalau tidak ada Pasir Berbisik karya Nan Achnas.
Kenapa, ya, mbak, bicara tentang film dan perempuan rasanya masih tabu untuk dibahas terutama di Indonesia? Mungkin belakangan ini mulai ramai dibahas. Tapi selama ini, kenapa masih kurang? Apa karena sumber daya manusianya?
Tabu menurut siapa? Kalau ada yang menganggap ini isu yang tabu, maka kita harus bertanya: mengapa penyingkiran isu perempuan berlangsung? Kepentingan siapa yang sedang diperjuangkan? Sejak tahun 2000-an sebetulnya selalu ada ruang membicarakan isu gender dalam film. Dulu bahkan ada Festival Film Perempuan. Tapi buat sebagian kalangan, isu ini masih dianggap tidak penting. Ini cara pandang yang mesti dibongkar.
·Menurut Mbak Intan, bagaimana keberadaan perempuan dalam film di Indonesia (yang mencakup semua lini)?
Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, setelah era reformasi, kita punya lebih banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis dalam film. Sebelum itu, sejak tahun 1920-an, perempuan yang menjadi sutradara maupun produser bisa dihitung dengan jadi. Sekarang kita punya Mouly Surya, Kamila Andini, dan produser hebat seperti Meiske Taurisia, misalnya. Pengaruh perempuan di dunia film relatif lebih besar dibanding ranah seni lainnya, seperti teater misalnya. Meskipun ini cukup menjanjikan, tentu saja bias patriarkis masih ada.
· Apa yang membuat Indonesia masih kekurangan sosok perempuan terutama dalam lingkungan filmnya?
Sebetulnya yang menjadi masalah bukan soal kurangnya sosok perempuan, tapi apakah komunitas film dapat menciptakan lingkungan yang menumbuhkan dan juga aman buat perempuan. Dari Lisabona Rahman dan kawan-kawan, kita tahu pelecehan dan kekerasan seksual masih terjadi di komunitas film. Ini sebabnya mereka bikin kampanye #sinematikgakharustoxic. Selain itu, bias respon atas karya sutradara perempuan kadang sangat berbeda dengan karya sutradara laki-laki. Film Marlina misalnya, meskipun dikagumi banyak orang, menuai kritikan pedas karena banyak orang yang merasa terganggu dengan representasi perlawanan perempuan lewat imaji pemenggalan kepala.
·Menurut Mbak Intan, apa tantangan atau kendala utama perempuan untuk survive dalam ekosistem film ini? Baik nilai-nilai penggambaran yang dimuat dalam karya film maupun dari segi peran perempuan secara teknis?
Keberlangsungan adalah salah satu tantangan. Biasanya, dampak interupsi karier karena punya anak cenderung lebih besar dialami perempuan. Setelah punya anak, sulit sekali buat perempuan untuk kembali ke jalannya dengan mulus, business as usual. Ada sih beberapa perempuan yang tidak mengalami ini, tapi biasanya mereka punya privilege tertentu, misalnya punya keluarga yang bersikap terbuka dan memiliki segala macam infrastruktur ekonomi dan sosial. Kita butuh grant untuk pembuat film perempuan untuk survive secara ekonomi, juga untuk mendorong dia belajar lebih banyak lagi agar karyanya lebih tajam.
Terakhir, kalau boleh kasih saran atau pesan, dong, mbak untuk jadi penyemangat perempuan dalam berkarir di industri film.
Buat saya, di bidang film atau seni lainnya, yang terpenting adalah semangat mempertanyakan tatanan. Kalau lingkungan kreatif bikin gak semangat atau malah toxic dan mengancam, pertanyakan kenapa kita harus kompromi, lalu cari sekutu dan coba ubah kondisi itu.
(Wawancara ini pernah diunggah di akun Instagram Maniacinema, Mei 2020)
Diwawancarai dan ditulis oleh : Agnina Rahmadinia
Desain oleh : Hotman Nasution
Agnina Rahmadinia

Alumni jurusan Ilmu Komunikasi yang di tengah kegiatannya sedikit-sedikit nonton, tapi nontonnya sedikit-sedikit.

1 note
·
View note
Text
Eric Sasono : Membuka Perspektif dari Kajian Sinema.

Sinema bukan hanya melulu soal produksi teknis dan bagaimana sinema didistribusikan. Sinema jauh lebih luas daripada itu. Ia juga membahas bagaimana masyarakat merespon pada sinema. Kaitan antara sinema dan masyarakat sungguh sangat erat. Fungsi sinema berubah seiring berubahnya masyarakat. Awalnya sinema berfungsi sebagai bukti untuk para peniliti yang dibuat oleh Lumiere bersaudara. Kemudian George Mieles mengalihkan fungsi sinema sebagai wadah artistik untuk mengungkapkan perasaan. Belum lagi munculnya para sineas rusia yang mengalihkan fungsi sinema sebagai alat propaganda yang dibawakan oleh Kuleshov, Einsenstein dan kawan kawan. Ia terus berkembang.
Sinema adalah respon dari sebuah jaman. Representasi dari sebuah masyarakat atau zaman bisa dilihat pada sinema nya. Tak hanya sebuah respon zaman, sinema juga banyak mempengaruhi masyarakat. Sudah tak diragukan lagi bahwa relasi kita dengan sinema sungguh sangat dekat. Dari menengah kebawah, atas, tukang parkir, konglomerat ataupun mahasiswa menikmati sinema. Pengaruh sinema terhadap masyarakat sungguh sangat kuat. Lihat saja bagaimana film "Dilan 1990" mengubah anak anak SMA memakai jaket jins dan memainkan gombalan yang ada, sungguh sangat masif. Belum lagi pengaruh trauma horor menonton film "Pengkhianatan G30S PKI" yang dirasakan oleh orang tua kita di masa orde baru. Sinema sungguh sangat dengan kita. . Maka dari itu, diperlukan sebuah disiplin ilmu tertentu dalam mempelajari lebih dalam akan sinema. Dari kajian sinema, kita akan belajar sinema dari sudut pandang akademis untuk membedah bagaimana sinema itu bekerja. Saya berbicara dengan Eric Sasono; salah satu pendiri rumahfilm.org, kritikus film Indonesia dan peraih bidang doktor di bidang kajian film King’s College London berbicara mengenai kajian sinema dan dampaknya lebih ke ekosistem perfilman.
Simak wawancara dengan Eric Sasono di bawah ini.
Okay, mas. Mungkin, orang-orang ga banyak yang tau soal apa itu kajian film. Jadi, sebenarnya kajian film itu apa ya, mas?
Kajian film ini bidang akademis yang mengkaji film dengan berbagai pendekatan teoritis, historis dan kritis. Kajian film tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan pembuatan film, melainkan lebih ingin mengeksplorasi narasi film, ekonomi politik film, sejarah film, aspek budaya film, dampak politik film dan kemungkinan filosofis yang dibawa oleh film.
Kenapa kegiatan kajian film ini harus ada?
Sebagai bidang akademis, kajian film diperlukan sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan dan budaya sinema di Indonesia. Film mempengaruhi kehidupan banyak orang secara politik, ekonomi, maupun secara budaya. Pengaruh-pengaruh ini penting untuk dikaji dengan pendekatan yang menempatkan film sebagai medium yang memiliki ke-khasan.
Bentuk dari kegiatan kajian film ini apa aja ya, mas?
Sebagai bidang akademis, kegiatannya tentu berupa kegiatan akademis seperti konferensi, perkuliahan, penerbitan, seminar hingga konsultasi untuk pengambil kebijakan—apabila diperlukan.
Bagaimana cara mengkaji film? Adakah metode pakemnya, mas?
Berbagai metode dalam mengkaji film itulah yang menghasilkan kajian film sebagai bidang akademis, karena banyaknya. Kajian film sendiri tentu terpengaruh dan mempengaruhi berbagai disiplin lain. Saat ini, kajian film banyak masuk ke dalam kajian lain seperti kajian media (media studies), sastra, atau seni. Jelas bidang-bidang ini mempengaruhi kajian film dan metode-metodenya. Bidang filsafat dan keilmuan lain juga mempengaruhi kajian film. Kajian film tidak bisa tertutup.
Siapa saja yang seharusnya melakukan kajian film, mas? Masyarakat, Pelaku Industri, Kritikus film? Dan kenapa?
Sebagai bidang akademis keilmuan, tentu ia dipelajari di bangku kuliah berdasarkan disiplin ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dalam komunitasnya. Pelakunya bisa siapa saja selama memenuhi standar yang diterapkan oleh komunitas ilmiah tersebut. Sekali lagi, kajian film atau film studies adalah satu disiplin akademis.
Di komunitas-ku (mungkin juga terjadi di komunitas yang lain), kajian film seringkali dikerdilkan. Sebenarnya manfaat dari kajian film itu apa, sih? Apakah lebih penting daripada ilmu praktik film itu sendiri?
Manfaat kajian film tentu saja penting, sebagaimana kajian dalam bidang seni dan media lain. Film sudah menjadi bagian keseharian, di mana ia membuka kemungkinan perkembangan ekonomi, kebudayaan, filsafat, politik, kesejarahan dan sebagainya. Saya kasih contoh: kajian terhadap film Indonesia Calling misalnya, akan membuka kemungkinan perubahan dalam cara pandang tentang sejarah Indonesia mengingat film itu dibuat oleh seorang sutradara Belanda (yang dituduh menganut paham komunisme) bercerita tentang solidaritas terhadap kemerdekaan Indonesia oleh serikat buruh Australia. Artinya, kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang bersifat transnasional dan punya nuansa dukungan ideologi kiri. Ini sesuatu yang penting dalam kerangka penulisan sejarah Indonesia. Ini satu contoh saja, dan masih banyak contoh lain terkait kemungkinan2 yg bisa dihasilkan oleh kajian film.
Soal penting mana dengan praktik ilmu film, ya sulit juga membuat hirarki antara dua macam ilmu yg berbeda. Masing-masing pasti penting dan punya nilai yang berbeda kemanfaatannya.
Seberapa penting kajian film dipelajari? Apakah Masyarakat awam harus mengerti rumpun ilmu ini?
Kajian film penting karena dalam kehidupan kontemporer saat ini, film sudah jadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat kita. Ia bisa membuka kemungkinan, termasuk menuju kajian-kajian lain seperti "new media" (youtube, webseries, dsb. yang menggunakan cinematic storytelling dengan medium berbeda), game studies dan sebagainya. Membuka ruang buat kajian film adalah membuka kemungkinan pemahaman lebih baik terhadap masyarakat kontemporer.
Apakah kajian film harus dipelajari oleh para praktisi film di industri film indonesia?
Praktisi dan akademisi kajian film harus saling berdialog dan membuka diri satu sama lain. Para praktisi memiliki sumbangan utama, bahkan primer dalam kajian film karena tanpa adanya praktisi tak ada film dan tak ada yang dikaji. Maka pengkaji film harus menempatkan praktisi dalam posisi yang penting. Sebaliknya, para praktisi selalu diasumsikan sudah mengerti soal bahasa dan keterampilan pembuatan film yang menjadi bagian juga dari kajian film. Tapi, praktisi tidak harus mengkaji film, sekalipun pada umumnya praktisi seperti sutradara, penulis atau produser punya kemampuan untuk itu, setidaknya kemampuan melakukan penafsiran terhadap elemen naratif film.
Bagaimana dengan kondisi kajian film saat ini di rumpun sinema Indonesia?
Kondisinya masih tidak berkembang karena dari sekolah film yang ada, mayoritas orientasinya praktik. Kajian film malah dilakukan di bawah media studies, communication studies atau sastra. Saat ini, doktor di bidang kajian film masih tidak sampai 5 orang, sekalipun banyak dari bidang lain—seperti yang saya sebut di atas—menekuni film sebagai obyek riset utama mereka.
Apa harapan buat kajian film di Indonesia?
Harapan? Saya ganti aja pertanyaannya dengan apa yang bisa dikerjakan, ya, karena harapan itu sesuatu yang abstrak dan sulit dijawab.
Soal yang bisa dilakukan, menurut saya banyak sekali. Bisa dengan membuka kesempatan seperti pendanaan jurnal-jurnal kajian film, public outreach hasil-hasil kajian film dan sebagainya untuk memperlihatkan signifikansi film dalam perkembangan identitas dan kebudayaan Indonesia. Ini perlu dilakukan daripada sekadar bicara sumbangan film terhadap GDP yg menurut saya sulit diukur dan jatuhnya akan kecil terus.
Bahkan di Inggris saja, Kementerian Keuangan menyatakan, salah satu sumbangan terbesar film adalah pada keragaman dan identitas budaya Inggris.
“Cinematic film provides a universal and readily accessible medium for the expression and representation of British culture and national identity. Films can help reflect, explore and challenge our diverse history, cultural beliefs and shared values. In doing so, the best British films not only help us to reach a better shared understanding of Britain and its place in the world, but are also instrumental in spreading awareness and appreciation of British culture around the world. As such, British films are an important part of our cultural heritage and a significant channel for the continuing expression and dissemination of British culture.” (HM Treasury in Oxford Economics, 2012, p.75)
Nah, sumbangan film seperti yang digambarkan itu bisa dieksplorasi lebih luas lewat kajian film yang melihat perkembangan film seiring perkembangan masyarakat yang menghasilkannya dan interaksi secara luas (katakanlah global). Ini dibutuhkan untuk Indonesia.
(Wawancara ini pernah diunggah di akun Instagram Maniacinema, Februari 2020)
Diwawancarai dan ditulis oleh : Galih Pramudito
Desain oleh : Hotman Nasution
Galih Pramudito

Salah satu pendiri Mania Cinema. Pernah aktif di komunitas Sinelayu dan menjadi juru program Palagan Films di Pekanbaru. Kebanyakan waktunya ia habiskan untuk menonton, membaca, makan, selebihnya melamun. Saat ini tengah menyelesaikan studi Ekonomi Islam di UII Yogyakarta.


0 notes
Text
The Color Wheel : Tak Sama Tapi Serupa.

Seseorang biasanya memiliki cara tertentu dalam menjalin suatu hubungan. Entah itu suatu hubungan pacaran, adik-kakak, orang tua-anak, selingkuhan-peselingkuh, mantan istri-suami. Tak ada aturan baku ketika berhubungan dengan orang lain, selama dapat dipertanggungjawabkan serta ada komitmen, entah seabsurd apapun model hubungan tersebut. J.R (Carlen Altman) dan Collin (Alex Ross Perry) sepasang kakak beradik nampaknya menyiasati sendiri hubungan mereka. Kisah itu dimulai saat J.R mengajak Collin untuk mengadakan perjalanan ke apartement dosen J.R . Dosen ini pernah tidur dengan J.R dan memberinya iming-iming pekerjaan baru. Jarak tempat tinggal Collin ke apartemen dosen J.R yang cukup panjang mengharuskan mereka untuk mengambil jeda perjalanan. Dari sinilah adegan-adegan menggelitik hadir dalam hubungan kakak-adik ini.
J.R, Collin dan Delusi.
Pada awal paruh film, Alex Ross Perry sebagai sutradara menggambarkan mereka bagaikan ambivalen yang saling beradu satu sama lain. Tokoh J.R mengalami delusi. Saat ada orang bertanya apa pekerjaannya sekarang. Kendati menjawab, “Ya, aku lulusan sarjana yang masih menganggur”, Ia malah berkata bahwa dirinya adalah seorang pembawa acara berita di stasiun televisi dan memiliki rekan-rekan penting di dalam jaring spektrum sosialnya. Ia digambarkan ceria, meletup-letup dan penuh racau saat menjelaskan tentang pekerjaan yang ia geluti. Jawaban yang diberikannya selalu gonta-ganti. Antara orang satu dengan yang lain pasti tidak sama. Kadang ia mengaku bahwa ia bekerja di stasiun A, kadang juga ia mengaku bahwa ia masih dalam tahap percobaan. Dari penjelasan sebelumnya, Nampak bahwa J.R adalah seorang yang hidup dalam gelembungnya sendiri demi atensi dari orang yang bertanya. Kadang, sedikit kebohongan jauh lebih enak terdengar ketimbang pernyataan klasik dan membosankan seperti : “Ya, aku pengangguran”, bukan?
Lain lagi dengan Collin. Ia digambarkan sebagai lelaki dengan idiom “apa adanya dan adanya apa”. Collin kelewat jujur, ia tidak terlalu memusingkan apa kata orang tentang dirinya. Hidupnya seperti arus kali yang mengalir begitu saja. Collin pernah bercerita bahwa ia ingin menjadi penulis, tapi sepertinya ia tidak ingin melanjutkan cita-cita itu. Ia juga pernah bercerita bahwa ia ingin menjadi guru, namun ya menurutnya itu hanya angan-angan saja. Ia tak memiliki tekad dan gagasan yang kuat dalam hidup.
Kedekatan hubungan mereka mulai nampak pada di kamar motel. Ketika mereka sedang duduk berdua di ranjang motel. Collin bercerita bahwa ia pergi liburan bersama kedua orang tuanya, lalu J.R bertanya mengapa dirinya tidak diajak, Collin memang tak mengajaknya karena khawatir jika J.R bawel dan membuat onar, J.R menyangkal bahwa ia tidak bawel dan merupakan kesayangan kedua orang tua, namun Collin tetap bersikukuh bahwa J.R bawel dan pembuat onar. Sikap Collin yang menyangkal semua pernyataan delusif milik J.R merupakan cara mereka terhubung di sepanjang film.
Kendati fokus film berada di hubungan J.R dan Collin yang rumit, film ini juga menyorot bagaimana kehidupan pasca lulus J.R yang delusif serta haus atensi. Bisa dilihat ketika J.R tak sengaja bertemu teman sekolahnya yang kebetulan sedang mengadakan pesta. J.R memanfaatkan kesempatan dengan dalih mencari relasi di pesta tersebut. Awalnya J.R mengaku bahwa ia adalah pembawa berita di suatu stasiun TV, kemudian berubah menjadi perawat ketika teman-temannya membeberkan pekerjaan mereka yang rata-rata adalah pekerja kelas menengah. J.R seakan kehabisan kata, ia dipermalukan secara tidak langsung. Lidahnya tercekat. Di pesta itu ia juga turut serta membawa Collin yang juga bernasib serupa dengan kakaknya, ia disebut sebagai pecundang dengan orang yang sengaja menumpahkan minuman ke dirinya. Pada adegan ini, mereka tampak benar-benar lelah dan mengalah pada para kaum kelas pekerja menengah tersebut.
J.R, Collin dan Realita
Di rumah singgah inilah dramaturgi hubungan J.R dan Collin semakin intens. Adegan ketika mereka berbaring berdua di sofa panjang saat J.R bercerita mengenai pekerja kelas menengah. J.R mengatakan yang kurang lebih “Persetan dengan mereka, kita bintang, kita bebas melakukan apa saja”, pernyataan J.R mungkin terdengar naïf tetapi itu menegaskan suatu hal : mereka senasib. Di akhir paruh film , Alex Ross Perry menggambarkan bahwa kendati sifat mereka ambivalen, mereka tetap orang yang sama : memiliki masa depan yang tak tentu. J.R dan Collin yang sama-sama gamang dengan kehidupannya mendatang menyikapi hal tersebut dengan cara yang berbeda. J.R menghadapinya dengan sikap delusif nan narsis, sedangkan Collin mengalir di arus hidup yang deras. Alex Ross Perry kemudian menambahkan bumbu gairah di film setelah beberapa adegan kemudian; Collin mencium J.R dengan khidmat. Alex Ross Perry tidak meng-glorifikasi hubungan “yang beda” (atau yang mungkin disebut Inses), ia membiarkan itu dengan natural dalam sorotan kamera film 16mm, menyorot apa adanya yang ada di depan layar dengan teknik kamera handheld yang membuat film ini terasa natural dan tidak dibuat-buat atau bahkan dieksploitasi.
Apa yang dirasakan oleh J.R dan Collin mungkin dirasakan oleh sebagian dari anda. Fase ketika di mana bingung mengerjakan apa untuk menyambung hidup ke depan. Hal ini dirasakan ketika pasca lulus sekolah atau kuliah dengan jebakan tanda tanya besar, “Habis ini mau kemana?”. Tanda tanya besar ini biasa disebut dengan krisis seperempat abad atau dikenal dengan quarter life crisis. Dalam buku “Ramen Noodles, Rent and Resumes: An After‑College Guide”, Kristen Fischer menyatakan bahwa quarter-life crisis adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang seputar relasi, karier, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an.
Hubungan J.R dan Collin yang awalnya digambarkan merupakan ambivalen yang saling beradu satu sama lain menjadi satu padu ketika mereka sadar bahwa mereka senasib. Rasa senasib ini diperoleh oleh rasa-rasa krisis separuh abad yang mereka rasakan. Dua hal inilah yang menjadi pembahasan di film ini. Sayangnya, dua bahasan ini tidak teracik dengan apik menjadi satu kesatuan utuh oleh Alex Ross Perry, ada beberapa bagian yang merasa sedikit jomplang dan tak terceritakan dengan baik. Dituturkan dalam kamera film 16mm dengan warna hitam-putih, dialog yang mengalir dan fluid serta peforma yang meyakinkan hubungan kakak-adik yang unik serta pencarian jati diri dan ketidakmenentuan di kala krisis separuh abad dari Alex Ross Perry dan Carlen Altman.
The Color Wheel adalah salah satu film favorit saya. Salah satu kenalan saya di Twitter, Ghina membuat daftar rekomendasi film favoritnya di blog filmnya, Journal Of Review. Film yang direkomendasi cocok untuk kalian yang menyukai film-film romansa atau fiksi ilmiah dengan sentuhan yang berbeda. Ayo, simak tulisannya di sini ! Favorite Movies: Before Sunrise, Snowpiercer & A Ghost Story Review
Penulis : Galih Pramudito
Desain : Hotman Nasution
The Color Wheel | 2011 | Durasi : 83 Menit | Sutradara : Alex Ross Perry | Negara Asal : Amerika Serikat | Pemeran : Carlen Altman, Alex Ross Perry, Bob Byington.
Galih Pramudito

Salah satu pendiri Mania Cinema. Pernah aktif di komunitas Sinelayu dan menjadi juru program Palagan Films di Pekanbaru. Kebanyakan waktunya ia habiskan untuk menonton, membaca, makan, selebihnya melamun. Saat ini tengah menyelesaikan studi Ekonomi Islam di UII Yogyakarta.


0 notes
Text
Daysleepers : Keintiman dalam Keheningan

Pada umumnya orang-orang bekerja di pagi hari hingga petang menjulang. Selain itu adalah mereka yang bekerja pada malam hari hingga bertemu dengan pagi lagi—seperti yang tercermin pada tokoh Andrea (Dinda Kanya Dewi) dan Leon (Khiva Iskak) di film ini. Paul Agusta selaku sutradara mencoba menangkap momen intim ketika dua karakter tersebut tenggelam pada keheningan yang sudah menyatu pada kehidupan mereka.
Andrea adalah salah seorang karyawan di salah satu perusahaan keuangan di Jakarta. Ia mendapat shift kerja malam hari hingga subuh. Sedang Leon adalah seorang penulis novel yang sedang kembali merintis karirnya pasca kematian istrinya. Ia kerap kali mengerjakan tulisannya di kedai kopi milik mas Tito (Joko Anwar) pada larut malam hingga berjumpa dengan pagi. Di waktu kerja yang bersamaan itu, diam-diam mereka saling memerhatikan dari kejauhan. Ketika merasa bosan dengan pekerjaannya, Andrea sesekali berdiri di depan jendela sambil melihat pemandangan malam—kemudian matanya menangkap sosok seorang lelaki yang sedang berada di kedai kopi, lelaki itu adalah Leon. Begitu pula sebaliknya, mata Leon mengarah pada jendela yang masih menyala di salah satu gedung yang terletak di seberang kedai mas Tito.
Daysleepers hadir dengan segala kesederhanaannya yang memikat. Mengambil latar di salah satu tempat di Jakarta—membuat saya yakin bahwa tak peduli sepadat atau sesunyi apapun tempatnya, setiap insan pasti pernah merasakan kesepian. Andrea yang pada awalnya sangat menikmati jadwal jam kerjanya, akhirnya ia mulai merasakan sesuatu yang hilang pada dirinya selama ini. Sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Saking lamanya ia akrab dan bercumbu dengan kekosongan, ia lupa bagaimana caranya mengisi yang kosong. Ia terbiasa duduk di kursi kantor berjam-jam sembari memakan pop corn dan minum kopi, serta memerhatikan angka-angka yang ada di layar komputernya. Tatkala ia melihat satu jendela yang menyala di salah satu kedai dan matanya membingkai figur yang tak biasa—ia mulai mempertanyakan kembali dirinya sendiri dan mulai menyadari satu hal—ia benar-benar merasakan kesepian.
Leon—semangat menulisnya pernah redup setelah kematian istrinya—ia pun terpuruk dalam luka, kesedihan dan kesendirian, sejak saat itu Leon merasa hidupnya takkan pernah sama. Leon tak pernah merasa utuh tanpa kehadiran sang istri. Lambat laun ia mencoba memulai kembali demi menafkahi putra semata wayangnya. Namun, ia dilanda kebuntuan ketika sedang menggali ide untuk buku selanjutnya. Hingga suatu hari Leon menyadari kehadiran siluet perempuan di jam malam pada gedung seberang kedai kopi mas Tito dan dia dibuat bertanya-tanya dengan hadirnya salah satu jendela yang lampunya masih menyala terang. Leon berharap suatu hari ia bisa bertemu dengan sosok yang mebuatnya penasaran setiap malam. Sosok misterius yang menggantung pada pikirannya. Sosok misterius yang memantik semangatnya dalam menulis novel.
Rasanya tidak berlebihan bila saya mengatakan bahwa hubungan Andrea dan Leon cukup manis dan intim meskipun mereka tidak pernah saling bertemu. Ungkapan ‘jatuh cinta pada seseorang yang belum kita temui’ jadi terasa masuk akal. Daysleepers begitu dekat dengan kita, Paul Agusta mengusung konsep minimalis pada filmnya—latar berkutat pada rumah Andrea, kedai kopi mas Tito, rumah Leon, dan gedung kantor Andrea. Kita akan diperlihatkan bagaimana kegiatan sehari-hari Andrea dan Leon secara berulang ketika sebelum bekerja dan selesai bekerja. Daysleepers dengan bersahaja memotret dua individu yang sama-sama dihinggapi rasa sepi. Keduanya baru menyadari hal tersebut ketika mereka sama-sama menyapa dalam diam dari jendela masing-masing. Tak terasa Leon dan Andrea sudah saling menyapa melalui keheningan yang intim, sekalipun sonder suara dan tatap muka.
Daysleepers adalah surat cinta Paul Agusta bagi mereka yang seringnya bercinta dengan kesepian, kepada mereka yang merasa penat dan membutuhkan jalan menuju distraksi untuk menghilangkan rasa hampa. Juga, ditujukan bagi kita yang berharap akan adanya kejutan kecil yang merubah tatanan hidup yang dirasa teralu statis, hitam-putih, serta membosankan.
(Diunggah pertama kali di Instagram Maniacinema, Oktober 2020)
Penulis : Mega Fadilla
Desain : Hotman Nasution
Daysleepers / Kisah Dua Jendela | 2018 | Durasi : 92 Menit | Sutradara : Paul Agusta | Negara Asal : Indonesia | Pemeran : Khiva Iskak, Dinda Kanyadewi, Agnes Naomi , Djenar Maesa Ayu, Joko Anwar | Produksi : Kinekuma Pictures
Mega Fadilla

Seorang penonton film juga pecinta Chungking Express paling taat. Menjadi seorang podcaster FilmExpress di Spotify apabila tidak mager. Sisa waktunya biasanya dihabiskan untuk menulis dan tidur.


0 notes