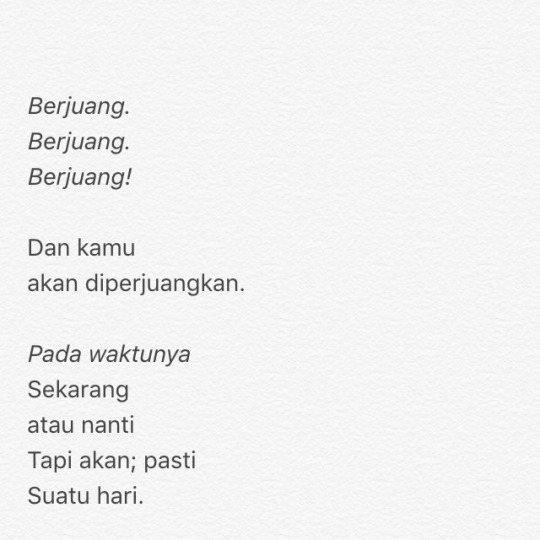Text
27
Twenty-six was something borrowed.

She went by in a flash, yet she was also in slow motion. It didn’t feel like she was mine, as much as she was, and although everything about it was indeed mine, in a lot of ways it also wasn’t. 26 was her own analogy with her own language, who kept correcting—iterating—herself vigorously, so she wouldn’t be recorded entirely as a flaw, a bug, a glitch, or a hideous mess.
Just recently I saw this Instagram Reel of a potter smashing and breaking her flawed products to turn them back into clay and recycle them into new pieces. While I do not dare to say that 26—I—was a flawed product myself, 26 was the year when a lot of things got really, really messy.
A couple of (messy) examples: First of all, I thought I could write. Four semesters, ten unfinished drafts, maybe thirty-thousand words later, I realized writing is about both starting and finishing and all this time I’ve been only floating in the middle. Second, I thought I was smart and brave, especially being one of the few international ESL students, and also one of the only two Indonesians in the program, until I started taking classes with students who have spoken—and written—English their whole lives, who bring novel manuscripts and 30-page brilliant short stories to workshops, some of which have already been published here there everywhere, who win competitions and receive fellowships, who have taught in at least three different continents, who by default I deemed superior. With that, Smart and Brave silently exited the room. Dumb and Scared took their place instead. Lastly, I thought I knew what I wanted, had life half-figured and sort of planned out. Turns out I have only been half-living this whole time, with absolutely no idea what I’m doing and where I’m going, and meeting different people with different backgrounds and their different languages with their different, super supreme YouTube-podcast-book-meme references and their elaborate, sorted-out 10-year life plans, Notion-powered, Forbes30Under30-driven; made me grimace at my own life (obviously unsorted, unNotioned, unForbes), made me unwant what I had and want some things even harder. My dreams shape-shift. Some self-destruct, some become even more stubborn and pronounced. Either way, it ended up being too much. Too loud and too lonely. I ended up becoming one of those clay pots the potter smashed in her video. I broke. Too many times, at that.
-
Amidst all that fire in the house, as I am heavily self-trained to always find light in the darkness no matter how irrelevant and cringe such light can be, at 2:00 am as I cried myself to sleep I thought, what better place to be broken than New York, right? Wrong. Well at least I am in New York, right? Right, but also wrong. Despite only living here for two years-ish, I felt New York was too grand a stage for broken things. For battles I was bound to lose. For wars I wasn't prepared for. It’s too grand a stage for adult growing pains, which are basically aches everywhere in our body due to intense adulting activities (mostly the mental ones), where joy is something we pay in installments, yet horror and sadness are practically freebies. The real secret in @secretnyc Instagram page isn’t in what they tell us (10 tHiNGs yOu DoN’T wAnNa MiSs tHiS wEeKeNd), it’s in what they don’t: People bend in this city, but most of the times they break too.
That being said, for the past seven, eight months, it has really taken a village for a day to start and to not suck, for the hours to go by without too much crying in between. In the first few months there wasn’t even a “village” to begin with, for I was alone, lonely, busy succumbing. My world was shaken up and for a lot of different reasons. New York, once a jewelry box, became a death trap. I was floating but more like a sad balloon—airless and crinkled, certainly not the majestic, colorful, and dreamy-looking hot-air kind—sadly sticking to her day-to-day routine: write in the mornings, class til noon, study until dinner, naps in between.
But as much as I tried, my normal routine alone didn’t even cut it—it felt unsafe and temporary. Some days I was lucky to make it to places, some others I would be walking out of my apartment just to straight up u-turn and run back home. My naps became longer (when my normal ones already last for two hours, minimum) and turned to something I dreaded, but at the same time everything else was a lot worse. Whatever good, normal day I pulled a muscle to have, it wore off as soon as I showered and crawled back to bed. At nights, rest was impossible, but when I finally did fall asleep, I slept with a large hole in my chest, which became a perfect site for a festival of bad dreams.
-
So I resorted to sticking my routine to other people’s. That is how my life became something desperately borrowed: the long library hours, the brisk walks to the boba place, study sessions, the Friday getaways to Yale, last minute lunch and dinner dates, weekend hangouts, half-priced ballet and Broadway shows, ice skating. Surprise pastries that saved my lifeless, bedridden, five-kg-less ass because I couldn’t, wouldn’t, stomach anything else; shoulders on which I helplessly smeared snot all over; ears worn off from having to hear me scream and cry during phone calls or during long conversations over my dining table; iftars and suhoors turned into sleepovers. I borrowed distractions from these people, who willingly shared pieces of their lives with me, which I used to fill the large hole in my chest, hoping they could help rid it of the nightmares, however momentary. I owe so much to so many.
And what did this tiny, little piece of self do? Other than succumbing? Skipping classes, missing her meals? Seeing the days go by from her bedroom window? Hating people on Instagram who seemed contained and composed, happy and unbothered? And back to hating herself even more? Well, it woke up, and at some point, it got up from bed. Two times, it showed up to her pilates sessions. It also sought therapy. If anything, it lived and held me. And it wrote to you, eventually.
And so, writing this, putting it here, containing this internal fiasco in a language and a shape is my attempt at making a peace offering to all sorts of life’s shenanigans that I have yet to face—an effort to upcycle life just like she does, Lady Pottery. That’s 26 to me. Still a quarter life crisis, just a remix. I remember the times where I prayed so hard—Ramadan 2019, for example, which perhaps was my peak shalihah moment, excuse this shameless self-claim, because I wanted grad school so bad—for the things I do have now. These days I’d call Ibu and we’d both cry on the phone (unsure who’s soothing who?), “Bapak and I prayed for all these things for you—your scholarship and your school—and these granted prayers come with tests for our patience and perseverance…” So there you go.
I once asked my older sister how many more times she cried like a monster after 26, because I was exhausted. She said only a couple more times, because afterwards, the cry is silent. I guess if I asked Lady Pottery how many more times she still has to do recycling, the smashing and the breaking, the answer would be about the same.

So. Twenty-seven. Let’s go for a spin.
187 notes
·
View notes
Text
Downpour
It happened like a downpour // at midnight, in secrecy // with all yearnings, with no warning // We carefully watch our steps as we think we know what is right, and what really isn’t But it happened like a downpour; it was one throw of a dice
it was a
free fall
//
And all your words suddenly turn into love songs.
89 notes
·
View notes
Text
Hers and Mine
Through the dreams that are somebody else’s, I see you Through the lighthouse of her North ocean, I hear you Through the withered roses, and her goodbye kisses I feel you // It is through every sense that I have, every sharp, stinging pang Every single bit of it knows that your heart, though not as whole, it belongs to me too.
55 notes
·
View notes
Text
Di Antara
Bisakah kita sejenak beri jeda: sederhanakan kunci dan tangga nada redakan ekspektasi, dan biarkan Sunyi bernyanyi
//
Mari akui: ada hal-hal tertentu yang ingin bisa dinikmati lebih dari barang satu dua hari yang tidak perlu dicarikan justifikasi.
//
Kamu dan aku, bisa bersatu di titik temu adalah perihal waktu Perihal kesepakatan: siapa yang harus (dan mau) menunggu?
//
Kamu, dan aku, kita, tak kenalkah akan jera? Tidak cukupkah Rindu mendera memenjarakan si empunya dalam bunga tidur yang membisikkan namamu, namaku, nama kita: bertubi-tubi bagaikan coda lagu yang dimainkan berulang kali; repetisi tanpa ada tanda henti.
//
Di Antara yang bisa kuberi jeda, apakah Waktu bersahabat dengan kita?
-
Bandung, 11 September, pukul 7 pagi.
/
/
/
(Ah, dan lagi, urusan hati: siapa yang benar-benar mengetahui.)
141 notes
·
View notes
Text
Tentang Suara Dawai,

Bermusik terus di setiap saat aku bisa; mau di mana saja dan dengan siapa saja, yang penting main. Apa yang pernah dipelajari, minimal jangan sampai lupa, bahkan jadi lebih baik lagi kalau bisa!
Aku belajar biola secara formal alias les alias berguru dengan musisi-slash-guru super keren-ku, Kak Ammy Kurniawan, sejak kelas 6 SD. Aku merasa sangat bersyukur sampai sekarang masih bisa terus main musik, terutama biola, di sela-sela aktivitas akademikku yang boleh dibilang cukup padat... meski les-ku sempat terpaksa berhenti begitu mulai kuliah karena aku harus pindah ke Depok. Belajar musik dan salah satunya belajar dengan Kak Ammy ini adalah salah satu bukti konkrit dalam hidupku bahwa bahagia itu sederhana: bisa melakukan apa yang betul-betul kamu suka. Les biola yang sempet cuti di tahun 2011 ketika aku pertukaran pelajar di Amerika (tapi di sana tetep main juga), yang aku kira bakal tetep cuti begitu pulang karena harus fokus belajar buat UN dan SBMPTN dll dll dll, eh nyatanya tanpa pikir panjang langsung dilanjutkan lagi; karena justru dengan main biola sama Kak Ammy penatnya belajar itu jadi mereda :’) Malah aku pikir, kayaknya kalau waktu itu nggak lanjut les bakal stres banget. Sungguh kerasa deh yang namanya “music is my sweet escape” tuh, pas kelas 12.
Begitu mulai kuliah, aku yang awalnya belum sempet kepikiran mau nerusin main musik gimana (tapi tetep bawa biola ke kosan), tau-tau udah ketemu Fathur aja, teman seangkatan yang eh ternyata jago banget gitarnya. Awal kami ketemu, aku belum tau nih kalau dia jago gitar, sampai ketika kami para mahasiswa baru harus nyiapin penampilan buat acara wisudaan fakultas. Aku diseret untuk ikutan nyanyi, sama Fathur yang kebetulan ditunjuk (atau inisiatif ya, lupa deh) buat mengiringi pakai gitar. Singkat cerita, aku yang ngeliat Fathur main gitar pun langsung mikir: “Eh ini anak bisa gitar nih! Tampak fasih juga mainnya; wah wah wah coba ajak main bareng ah”. Fathur pun antusias mengiyakan! Nah, kebetulan waktu itu lagi mau ada acara fakultas berikutnya, yang kali ini khusus digelar oleh para mahasiswa baru untuk dipersembahkan pada kakak-kakak seniornya (kasarnya gitu deh). Aku sama Fathur langsung mendaftarkan diri buat main. Waktu itu kami formasi permainan kami masih campur sari; masih bersama beberapa teman lain yang juga kami ajak main, salah satunya adalah Dhika yang bisa main cajon (perkusi).
One thing leads to another. Setelah main bareng di acara itu, aku pun makin antusias buat nyobain main lagi… dan karena aku kangen banget mainin lagu-lagu yang diajarin Kak Ammy (eeee dan kebetulan bisanya baru itu-itu juga hahaha), aku mulai “ngeracunin” Fathur dengan lagu-lagu beliau… dan memang jodoh nggak ke mana sih ya (loh), Fathur (dan juga Dhika) menerima “racun" itu (muahahaha) dan mempelajari tidak hanya satu… tapi dua, bahkan tiga, eh empat, hampir SEMUA lagu-lagu yang diajarkan Kak Ammy dan aku mainkan selama les! Kami pun mulai nyoba daftar untuk manggung di acara-acara internal fakultas (termasuk lomba akustik Psiko gitu, dan menang juara satuuu, Alhamdulillaaah!), hingga nggak lama setelah itu, (aku lupa persisnya kapan) Suara Dawai pun resmi dibentuk: beranggotakan Fathur di gitar, Dhika di perkusi, Nanta (teman Fathur) di bass, daaan aku di biola! Hure!
Alhamdulillah (seisi tulisan ini akan dipenuhi dengan ‘Alhamdulillah’), Suara Dawai sampai hari ini terbilang cukup produktif manggung. Alhamdulillah juga, manggungnya kami nggak hanya di acara-acara Psiko aja, tapi juga di beberapa acara luar Psiko, bahkan acara yang bukan acara kampus sama sekali (terima kasih banyaaaak!). Salah satunya kami sempat road trip ke Cileungsi, tepatnya ke Islamic Girls Boarding School Darul Murhamah, di mana kami manggung di acara sekolah mereka, GEFORAS. Dan itu adalah... catatan manggung terlama pertama kami! Sampai kami bengong sendiri karena sadar bahwa lah kok ini nampil berasa konser; soalnya selain penontonnya buanyak dan sangat seruu, kami dikasih durasi yang cukup lama; seluruh isi repertoire kami habis dimainin, hahaha! Bahkan sampai kami “terpaksa” nanya penonton; “Eh mainin lagu apa lagi dong?”. :)))) Maklum, biasanya ngisi acara yang durasinya cuma muat dua—maksimal banget tiga—lagu (itu juga udah disumpah-sumpahin eh dipelototin panitia, hehehe), eh ini bahkan sampai delapan lagu (yang rata-rata durasinya ummmm empat menit lah masing2, belum ditambah aku cuap-cuap ngenalin diri plus stand up comedy ngegaring), kami masih punya waktu :’) Seru banget sih itu tapi, betul-betul salah satu pengalaman manggung yang tidak akan kami—setidaknya aku—lupakan. Terima kasih ya teman-teman panitia acara GEFORAS! (kalau ada yang baca, hehe) *peluk jauh*

13 September 2015; foto Suara Dawai terkece pertama yang diabadikan setelah “konser” di Cileungsi.
(Bersambung)
.
.
.
PS: Kami akan sangaaaat senang kalau bisa menghibur teman-teman juga lho! Untuk teman-teman yang kiranya mau seru-seruan bareng Suara Dawai di acara sekolah/kampus/unit/klub/keluarga/dsb mereka, boleh banget menghubungi aku (via Direct Message Instagram, @srizzati) atau Fathur di +62 812 9681 7838! #hehe #pro #mo #si
40 notes
·
View notes
Text
...dan Panggung di Bulan Juli.

Juli kemarin, bukan main senangnya Suara Dawai: kami dapat kesempatan untuk manggung di… GBB! Panggung Graha Bakti Budhaya, Taman Ismail Marzuki! Wah! Kami diminta oleh panitia Arkamaya; tim klub peminatan tari Psiko yang akan pergi melaksanakan misi budaya ke Bulgaria dan Hungaria (begitu tulisan ini teman-teman baca, mereka sudah mulai menari di sana), untuk menjadi salah satu penampil di rangkaian acara gelar pamit mereka (semacam pentas pre-event). Amboooi, panggung beshaaar! Februari lalu aku pertama kali mencicip GBB di bagian pit-nya (tempat di bawah depan panggung, biasanya digunakan untuk para pemusik gitu), eh sekarang bisa mencicip tampil di atas panggung sungguhannya. Alhamdulillah, lagi-lagi Alhamdulillah :’)
Eh, tunggu dulu... ternyata untuk bisa merasakan “senang”nya itu, ternyata kami harus diuji terlebih dahulu. Ah, menarik sekali bagaimana Allah punya cara untuk membuat hamba-hambaNya berkembang. Suara Dawai yang udah semangat banget kedapetan main di panggung besar, eeeh tiba-tiba harus menghadapi tantangan: Fathur nggak bisa ikut tampil!
Gara-gara udah keburu ada jadwal manggung di tempat lain yang nggak bisa ditinggal, Fathur terpaksa harus absen dari penampilan Suara Dawai kali ini. Brb pusing. Manggung tanpa Fathur? Pengalaman kami manggung nggak full-team (tanpa Dhika pernah, tanpa Nanta pernah) rasanya selalu kering, terlalu kering bahkan, ternyata :( Masa iya tampil tapi menyuguhkan kekeringan, di panggung seperti GBB, apalagi? Aaa gimana dong. Langsung mikirin back up strategy. Rekrut pemain baru? Tambah piano? Kolaborasi sama alat-alat musik tradisional? Tapi tetep rasanya nggak sreg, banyak pertimbangan ini itu. Akhirnya kami sepakat: Nanta yang biasanya main bass, buat penampilan kali ini dia jadi main gitar, dan kami mengajak pemain bass lain untuk memainkan peran Nanta (adik kelasku di Psiko, namanya Otniel!)

Kiri ke kanan: Otniel, Dhika, Izzati (dan Dimi, biolaku), Nanta! Ini foto di ruang ganti beberapa saat sebelum tampil.
Alhamdulillah, nggak butuh waktu lama untuk Otniel bisa menghapal lagu plus bagian yang harus dia mainkan, plus dengan feel-feelnya. Azeg. Fathur yang meski nggak akan ikut tampil tapi tetap setia ikut latihan pun akhirnya bilang bahwa kami bisa tetap aman buat manggung di GBB dengan format yang di”edit” seperti itu. Fiuh.
Nah…. tapi, sesungguhnya aku merasa masih ada yang kurang… atau tepatnya, sesungguhnya aku masih menyimpan rasa penasaran! Karena dulu di Kak Ammy aku main biola selalu rame-rame dengan yang murid-murid yang lain (minimal duet), jadi aku masih sangat merindukan main biola yang nggak cuma sendiri, tapi berdua, bahkan bertiga, berempat, berlima :”) (Rasa penasaran dan rindu aku ini sempat terpuaskan untuk pertama kalinya di akhir tahun 2015: anak-anak Suara Dawai featuring teman-teman Psymphony (klub peminatan musik di Psiko) ramai-ramai main lagu Sumatra Medley (yang main biola ada lima orang!). Tapi setelah itu belum sempat lagi… Jadi gimana nggak (masih) kepingiiiiin banget bisa main rame-rame lagi, apalagi di panggung GBB??? (Teuteup yah, si panggung GBB ini jadi poin penting, hahahah)
Akhirnya, dengan nekat... aku pun mengajak Kezia dan Claudia (alias Keci dan Clau, adik kelasku juga di Psiko), duo violinis tim pemusik Arkamaya, untuk ikut main sama Suara Dawai. Kenapa nekat? Karena itu H-….seminggu??? acara; dan dengan sekian banyak lagu tarian yang harus mereka mainkan untuk acaranya sendiri, lagu yang mau aku ajarin ke mereka untuk ikut mainin… jumlahnya DELAPAN, dimedleykan :’)
AH TAPI KARENA PENASARAN… aku pokoknya beranikan diri ngajak mereka, eh, dan ternyata, mereka mau! Siangnya ngajak, malamnya kami langsung mulai latihan :’) Salut banget sama Keci dan Clau yang meski pastinya udah capek jiwa raga dengan latihan mereka sendiri yang sangat intens, masih menyanggupi ajakanku DAN langsung menyerap materi lagu Suara Dawai yang aku cekokin ke mereka tanpa ampun. Ditemani angin semriwing dan hujan besar yang beberapa kali turun, kami latihan setiap hari (dua-tiga jam sebelum mereka lanjut latihan dengan para penari). Selama (kalau nggak salah) empat hari, kami memaksimalkan jam-jam latihan untuk transfer lagu, ngapalin, nambah aransemen (pecah suara), daaaaan… latihan joget, huahaha. Karena aku benar-benar menekankan: please please please feel the music, play it with your heart, enjoy it and… dance to it :’) Hahaha dasar ih sateh, loba kahayang! Si banyak mau :))) Tapi biarin ah; karena itu lah yang aku percaya bisa membuat musik Kak Ammy, musik Suara Dawai, dan musik kami keseluruhan jadi menyenangkan dan bisa dinikmati oleh mereka yang melihat dan mendengarkan!
Singkat ceritaaaa, (perasaan udah disingkat-singkat tapi kok tetep panjang aja ya ini cerita) terciptalah formasi terkeren Suara Dawai (sejauh ini) (yang sadly tanpa Fathur, hiks hiks) (Tapi Fathur ikhlas dan bilang justru berkat dia gak bisa ikut lah formasi keren itu akhirnya bisa tercipta) (supaya cepet, kami iyain ajaaa) (hehehehe tapi nggak ding, bener juga). Manggung lah kami di GBB, membawakan lagu Java Medley! Medley 8 buah lagu-lagu daerah di pulau Jawa, mulai Jawa Barat hingga Jawa Timur plus Madura, yang diaransemen oleh Kak Ammy Kurniawan (dan dimainkan oleh kami murid-muridnya, di penampilan-penampilan Ammy Alternative Strings di sejumlah acara, sejak tahun 2009… kalau aku tidak salah) dan dikembangkan lagi oleh Fathur, Dhika, Nanta, dan aku (supaya sesuai dengan format kami yang hanya berempat).

Muka-muka senang dan lega habis tampil
Terima kasih, terima kasih terima kasih terima kasih banyak untuk semua orang yang mau direpotkan demi terwujudnya penampilan (yang kudamba-dambakan) ini. Nanta yang menyelamatkan kami dari ancaman “kering-karena-tanpa-gitar-atau-lebih-tepatnya-tanpa-Fathur-karena-Fathur-adalah-gitar-hah-gimana?” dengan permainan gitarnya yang juga ciamik, Otniel yang menyelamatkan bagian per-bass-an, Fathur yang tetap setia mendampingi latihan, turut mengajari Otniel dan menyemangati Nanta (ahaha), juga memberi evaluasi serta masukan setiap abis latihan, Clau dan Keci yang melahap habis Java Medley sampai hapal semua bagiannya, begitu serius menyimak (dan mengaplikasikan) semua masukanku (dan permintaanku, khususnya untuk joget huahaha)… (btw seolah belum cukup aja rasa deg-degan kami karena ngejar lagu selesai H-seminggu, senar biolanya Clau bahkan sempet-sempetnya putus di tengah-tengah latian! Panik dot com) Keci yang udah berkali-kali kuseret untuk main biola (ini ketiga kalinya aku “bermusik” bareng Keci!) dan begitu tekun berlatih sampai lancar, dan menjawab semua kerinduan aku untuk bisa bermain dengan “berkomunikasi” di atas panggung. Ah… terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Semoga kalian turut bersenang-senang di atas panggsung sana :”)

Aku dan Kezia (@kezsabrina)

Sila buka Instagramku @srizzati untuk cuplikan permainan kami!
Bagiku... butuh suatu “keahlian” tersendiri untuk bisa benar-benar memberikan yang terbaik, juga menikmati di saat yang sama, DAN sekaligus mengenang sesuatu yang tidak berlangsung terlalu lama. Penampilan kami nggak sampai 15 menit, dan terasa begitu cepat... tapi terlepas dari sempurna atau tidaknya penampilan malam itu; Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
aku benar-benar bahagia.
27 notes
·
View notes
Text
Sebuah pikir

(Antara ditulis di Depok atau di Bandung; 16 Januari 2016 lalu)
Kuliah di UI udah dua tahun, dan aku masih belum sempet aja berbagi tentang apa aja yang udah kudapet dari sini ya. Ada satu hal yang paling mencuat di pikiran dan hati aku, sesuatu dari dua tahun kehidupan perkuliahanku di sini yang paling sering kerasa dan paling menantang untuk dihadapi. Dan menurutku penting untuk aku bagi.
Manusia itu seberagam itu.
Aku kira hari-hari di mana aku curhat ke Ibu tentang berantem sama temen, kesel sama temen, muak sama temen, sedih sama temen, itu akan berakhir di SD… atau SMP deh setidaknya, karena drama pertemananku di SMA lumayan tidak sebanyak ketika SD dan SMP, hahaha. Aku kira begitu masuk kuliah, yay, teman baru, no more (or at least less) drama! Seriusan aku kira bakal begitu. Tapi ternyata perkiraanku salah… tet tot. Topik “pertemanan” justru malah menjadi salah satu “hot issues” yang paling sering aku curhatin dan diskusiin sama Ibu setiap kali kami ketemu atau sebatas ngobrol di telepon.
We all are different shades of colors. And it gets more and more and more interesting each day. Perbedaan itu selalu menjadi sesuatu yang unik dan menarik buatku; it never ceases to amaze me how different each and every single one of us can be, how every person can have absolutely different “patterns”, “systems”, ways of thinking, backgrounds, stories… everything. Wowza. And me trying to deal with all that, nah ini adalah suatu tantangan tersendiri.
Aku akui, perbedaan ini kadang suka bikin engap. Kenapa? Karena adanya kesenjangan antara ekspektasi yang aku punya dan realita yang sesungguhnya. Lalu itu mengarahkan ke banyak sekali pertanyaan kok dia gitu sih kok dia gini sih kenapa sih orang tuh gini kenapa sih orang tuh nggak begitu kenapa sih emangnya gabisa begini apa kenapa sih emangnya gabisa begitu apa, kenapa kenapa kenapa which is, setelah dipikir-pikir dan direnungkan, ya kembali lagi jawabannya karena memang we all are simply different; whatcha gonna do with that? Moreover, kita nggak bisa memaksa orang untuk (selalu) berlaku seperti yang kita mau. We just have to find the best way(s) to deal with it.
Dan yang selalu Ibu bilang, untuk jawaban dari kalimat terakhirku barusan: sabar. Dan ikhlas.
-
Jadi buat adik-adik yang baru masuk kuliah, akan masuk kuliah tahun depan, atau teman-teman yang sudah kuliah dan mendapati diri sendiri manggut-manggut ketika baca tulisan ini (boleh kan aku positive thinking HEHE), embrace yourselves. Diversity is/can be/will be one major challenge. It can be very surprising, even exhausting and sometimes frustrating, but then again it’s what makes all of us learn. Hang in there. Hang in there.
75 notes
·
View notes
Text
Kita Tidak Pernah Benar-Benar Ingin Mengucapkan “Sampai Jumpa Lagi”

Apabila dipikir-pikir, apakah kita benar-benar menginginkannya, kala kita berucap: "Sampai jumpa lagi"?
Ini tentang keputusan, bukan tentang perpisahan, yang pernah kita sama-sama sepakati.
"Sampai jumpa...!" "Ya, sampai jumpa lagi...!"
Yang benar saja.
...Melafalkan itu saja, kau berlatih berhari-hari demi bisa menatap kedua matanya lekat Berusaha kuat. Padahal pilu dan ngilu sampai ujung jemarimu Terutama ketika kau dapati: dia t'lah kembali berpuisi tapi bukan untukmu lagi.
-
Apabila dipikir-pikir, apakah kamu benar-benar menginginkannya, sekali, dua kali, tiga kali, berjumpa? Lagi? Apalagi setelah kau sadari: khatam kau cintai, dia kini merdeka dan mungkin, sudah kembali berbahagia. (Akhirnya)
- (Depok, 27 Juli 2017)
95 notes
·
View notes
Text
Bukan Tentang Hujan, Melainkan Tentang Kekasihku, di Bulan Maret hingga Juni (2)

Aku sering denger kata ‘skripsi’ diplesetin jadi beragam bentuk, salah satunya adalah “skripshit”; saking pusingnya orang-orang sama hal yang satu ini barang kali ya, hahaha. Aku pun nggak jauh beda (pusing pisan aslina), dan jujur nyebut kata “skripsi” selama lagi nyusun skripsi kemarin itu nggak tau kenapa aku beneran suka takut/ngeri/bergidik/gak berani sendiri! Tapi aku nggak mau menyebutnya jadi skripshit juga haha, selain karena artinya makin jelek (dan selalu diajarin Ibu buat sebisa mungkin mengatakan hal-hal yang baik), dan semangatku ikut kebawa jelek, jadi aku plesetin menjadi bunyi yang lebih imut dan menyenangkan (?), yang kalo disebut berkali-kali tetep nggak membawa efek stres dan membebankan: skripik!
...alias Skripsi? Pusing tapi Asik.
. . . . (((yeaHEHEHEHEHE I just made that one up)))
Nah, tulisan ini adalah untuk menjelaskan secara lebih lanjut, kalau-kalau ada yang bertanya… apa sih persisnya yang aku lakukan untuk skripsiku kemarin?
Sejak awal disusun, skripsiku ini menjadi suatu tantangan tersendiri; dia menjadi cermin. Jauh sebelum benar-benar aku kerjakan, aku tahu pasti bahwa aku ingin skripsiku bukan cuma sekadar tugas akhir aja, yang tanpa ada makna apa-apa. Aku pingin skripsiku bisa jadi sesuatu yang berarti dan bermakna, setidaknya untuk aku sendiri. (Ih banyak maunya ya hahaha) Gara-gara itu juga, proses penyusunannya pun boleh dikata cukup pelik. Tapi aku bersyukur karena dia mewakili diri aku, dan hati aku; dia mewakili hasrat aku dalam salah satu yang paling senang aku lakukan dari dulu hingga kini, hasrat yang bisa membawa aku ke titik di mana aku berada hingga sekarang. Mau dibilang skripsiku adalah curhatku juga nggak masalah (sering diledek gitu hahaha), karena toh memang benar, skripsiku ada curahan hatiku dong. Kenapa sih ribet banget dan muluk banget, perlu pingin bikin yang berarti dan bermakna segala? Penelitian S1 mah nggak harus repot-repot amat lah? Sebenernya buatku pribadi, jawabannya nggak muluk-muluk amat kok: supaya seneng ngerjainnya. :)
-
Jadi, secara sederhana, yang aku lakukan adalah: aku meneliti efek dari menulis pada orang-orang yang habis mengalami putus cinta. Lebih spesifiknya lagi, aku mencari tau apakah menuliskan pengalaman putus cinta punya pengaruh terhadap distres subjektif dan suasana hati yang dirasakan seseorang. Ada sebuah konstruk tentang sebuah bentuk/aktifitas pengungkapan pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan bahkan traumatis secara tertulis—yang sudah sejak tahun 1986 diteliti—yang dikatakan baik untuk semacam “terapi” buat mereka yang mengalami. Cukup banyak hasil penelitiannya yang membuktikan kalau dengan “membahas” pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan itu dalam bentuk tulisan, dan melengkapinya dengan sedetil dan sebanyak mungkin emosi yang dirasakan, seseorang bisa jadi semakin membaik kondisi kesehatannya; baik fisik maupun psikologisnya.
Kenapa harus ke orang yang putus cinta, sih? (Sosoan aja dulu bakal ada yang nanya)
Karena kupikir, “cinta” secara umum saja adalah salah satu hal yang mungkin bisa jadi terkesan sepele, tapi sesungguhnya bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk hidup seseorang. Dampak itu bisa jadi positif bisa jadi juga negatif, dan untuk yang putus cinta, sering kali yang kerasa itu negatifnya dulu nggak sih, sebelum akhirnya berubah menjadi sesuatu yang positif? Ahahaha. Kepahitan, kesedihan, dan lain-lain dan lain-lainnya yang dirasakan waktu kita putus cinta bisa kemudian merambat ke mana-mana. Kalau bahasa psikologinya sih, “mengganggu keberfungsian”. Sesederhana nggak bisa konsentrasi berhari-hari karena kepikiran si dia mulu, misalkan, atau berhari-hari kerjaannya ngeliatin media-media sosial si dia terus buat tau dia lagi ada di mana dengan siapa sedang berbuat apa, sampe lupa belajar atau bikin pe-er (hehe udah lama ya gak denger kata “bikin pe-er”). Ahaha. Aku merasa perkara cinta ini salah satu sumber stres yang kayak cengek (cabe): boleh jadi kecil tapi begitu digigit puedasnya bukan mainnnn. Aku ngomong ini juga karena aku pernah merasakannya sendiri (I’d be lying to say otherwise!) :D
Jadi, setelah selesai merampungkan segala yang terlebih dahulu harus dirampungkan untuk penelitian (studi literatur, pemantapan latar belakang penelitian, studi literatur lagi, merancang prosedur penelitian, nyari dan adaptasi alat ukur, dan sebagainya), mulailah aku bertualang mencari bala tentara untuk mengajak Negara Api berperang calon-calon partisipan penelitian skripsiku; orang-orang yang kira-kira mau aku buka luka lamanya ha ha ha. Aku bikin dan menyebar kuesioner yang isinya “Anda putus cinta? Sama, saya juga” menyatakan pencarianku akan mahasiswa/i UI yang tiga bulan terakhir mengalami putus cinta atau perpisahan dengan orang yang mereka cintai, dan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar diri mereka di kuesioner itu. Alhamdulillah, yang merespons kuesionerku cukup banyak, jumlahnya tembus angka 300 (eeee bukan berarti aku mensyukuri fakta bahwa di bulan April, terdapat lebih dari 300 anak UI yang putus cinta ya…. eh…. aduh, ya gitu lah). Setelah aku sisir dan pastikan kembali siapa saja orang-orang yang datanya betul-betul sesuai dengan kriteria calon suami idaman partisipan penelitianku, satu per satu dari mereka pun aku hubungi buat aku ajak makan dan bikin konferensi
Nah, curhat sedikit ya (lah daritadi apaan?), di sini nih bagian yang bikin Izzati nangis malem-malem hahaha *loh *buka kartu. Jadi, pengungkapan emosional tertulis ini prosedurnya cukup merepotkan. Secara umum, subjek harus menulis tidak cuma satu kali, tapi minimal tiga kali, selama tiga hari berturut-turut. Aku pakai prosedur yang persis seperti itu, dan karena penelitianku pakai desain laboratory, artinya subjek harus datang ke tempat yang udah aku sediakan untuk menjalani penelitiannya. Jadi, dari ratusan orang-orang yang sudah merespons kuesionerku itu, aku harus mencari orang-orang yang mau DAN bisa untuk dateng ke lab komputer Psiko selama tiga hari berturut-turut, tanpa bolos satu hari pun! Dan tentunya ini sama sekali bukan perkara mudah, mengingat kesibukan mahasiswa tentu saja bukan cuma kuliah!
Singkat cerita (aku sempet menuliskan proses seperti apa yang aku lalui dalam menghubungi calon-calon orang sukses ini, tapi trus aku hapus lagi karena kayaknya cuma bakal nyapein kalian yang baca hahaha) (eh ada gak ya yang baca? Halo? Halo? *menyibak sarang laba-laba*), akhirnya aku mendapatkan partisipan-partisipanku! :”) (Tapi perjuangannya nggak berhenti sampai di situ, karena selama tiga hari itu adaaa aja usaha-usahaku demi memertahankan mereka hahaha) (Jangan lupa bahwa baik bertahan maupun memertahankan pun butuh usaha) *lah Sungguh, mendapati mereka satu per satu datang, sesuai dengan jadwal janjian yang udah aku tentukan, dan duduk di belakang komputer dan menjalani penelitian itu rasanya sangat melegakan! Setelah seluruh rangkaian penelitian selesai, barulah aku menjelaskan ke mereka tentang apa sebenarnya yang aku lakukan dan kenapa si pengalaman putus cinta itu aku minta mereka untuk tuliskan. Setelah semuanya jelas, dan setelah mengucap beribu-ribu terima kasih (tidak lupa memberikan mereka cinderamata yang aku siapkan sepenuh cinta), kami semua pergi makan dan bikin konferensi barulah aku melepas mereka pergi.
Aku terharu sendiri melihat hasil tulisan para partisipanku, bahkan sedikit merinding karena menyadari bahwa kisah-kisah mereka begitu beragam. Beberapa yang putus cintanya sudah terhitung cukup lama, ternyata hingga hari terakhir menulis, mereka masih berjuang. Beberapa yang lainnya menuangkan tentang jatuh bangun perjalanan hubungan yang ia dan rekannya lalui dengan amat sangat teratur dan rinci, lengkap dengan akar permasalahan, solusi, dan kenapa itu belum berhasil. Menarik banget untukku, mengetahui betapa banyak macam tantangan-tantangan yang orang-orang hadapi dalam keseharian mereka, dan untuk kasus ini, dalam perjuangan mereka dalam mencinta. Dan aku yakin, itu nggak terbatas hanya pada para partisipanku saja! Perjuangan jatuh bangun dalam mencintai dan dicintai, belum tentu bisa semuanya kita lihat dengan hanya sekelibat. Bahkan yang sengaja dikamuflasekan sedemikian rupa nyatanya banyak. Mereka yang memasang muka paling tenang, atau bahkan yang nampak seolah tidak acuh dengan dunia, bisa jadi ternyata punya luka hati yang dalam dan masih menganga.
Harapanku pribadi, terlepas dari konteks penelitian ini, semoga dengan menuliskan apa yang bisa dituliskan, hati-hati yang sesak itu bisa mendapat sedikit ruang; rasa ngilu itu bisa sedikit berkurang,
dan tentang apa yang sudah dilalui,
jadi tidak perlu lagi disimpan sendiri.
105 notes
·
View notes
Text
Bukan Tentang Hujan, Melainkan Tentang Kekasihku, di Bulan Maret hingga Juni (1)

Bulan April lalu, selama tiga minggu dalam rangka penelitian tugas akhir kuliahku, aku meminta sejumlah orang yang baru saja putus cinta untuk datang dan menulis untukku.
Sejak kecil, aku selalu percaya: masing-masing orang punya cerita tentang diri mereka yang pasti berbeda satu sama lainnya. Keragaman akan cerita masing-masing itu menjadi hal yang sangat menyenangkan, mengagumkan, dan... menghangatkan buat aku bayangkan, apalagi dengarkan. Tapi nggak semua orang bisa dan terbiasa membuka diri mereka; menceritakan hal-hal tentang kehidupan mereka, terutama hal-hal yang personal, apalagi mungkin yang menyedihkan/menyakitkan yang pernah mereka alami. Maka dari itu, mendapatkan orang-orang yang secara sukarela mau datang ke tempat dilaksanakannya penelitian tugas akhirku, dan “membahas” pengalaman putus cinta mereka, bahkan menuliskannya sedetil mungkin, lengkap dengan segala gejolak emosi yang dirasakan (apalagi atas permintaan/instruksi orang asing sepertiku!), bukan main itu membuatku kagum, terharu, dan tersentuh sekali.
Nggak hanya satu kali, tapi tiga kali! Selama tiga hari berturut-turut, orang-orang ini mencurahkan perasaan dan pikiran mereka ke dalam tulisan, tentang hubungan romantis yang sempat mereka jalani: bagaimana hubungan itu dimulai, bagaimana hubungan itu berakhir, apa yang dirasakan mengenai perpisahan itu, dan apa dampak yang mereka rasakan kini, serta hal-hal lain yang berkaitan. Sekian banyak orang aku minta untuk menggali sedalam mungkin perasaan dan emosi yang mereka rasakan mengenai their (ex)-person of significance, hubungan, dan perpisahan mereka. (Di titik ini mungkin kamu akan mulai berpikir bahwa apa yang aku lakukan adalah “mengorek” luka lama mereka) (Ya… lebih kurang benar, ha ha…).
Hasilnya, bagi aku sungguh luar biasa. Cerita yang mereka tuangkan dalam tulisan betul-betul emosional, dan betul-betul jujur. Aku sampai berkaca-kaca sendiri membaca semuanya, karena beberapa cerita betul-betul tidak disangka-sangka. Aku jadi turut sedih membayangkan bahwa ternyata di balik wajah-wajah yang tenang saat menulis itu (masih) ada hati-hati yang meringis, menahan tangis. Tapi di satu sisi aku juga turut lega karena beberapa menuliskan bahwa seiring (dan setelah) mereka menulis, mereka jadi lebih memahami perasaan dan pikiran mereka yang awalnya sempat semrawut, seperti benang kusut. Aku lega karena merasa memang seperti itulah seharusnya apa yang menulis bisa lakukan pada kita, ia membuat hujan dan badai di hati kita mereda.
Jadi, kepada seluruh partisipan penelitianku (meskipun mungkin tidak akan ada yang membaca pesan ini di sini, hehehe): terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mau memberikan waktu untuk penelitian ini, untuk aku, dan menggunakannya untuk menuliskan kembali apa yang mungkin bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk diingat-ingat lagi... Tulisan-tulisan kalian begitu jujur, dan kalian begitu berani; dan aku betul-betul berharap, terlepas dari apa pun teorinya dan hasil penelitiannya: dengan menulis, kalian bisa sedikit terbantu, hati kalian bisa sedikit terobati. Mungkin tidak sekarang; mungkin nanti. Semoga segala perjuangan kalian bisa segera tergantikan oleh banyak sekali kebahagiaan, di waktu yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi kebaikan-kebaikan untuk menghadapi apa pun yang harus kita hadapi. Terima kasih, terima kasih sekali lagi.

Sebagai seseorang yang juga pernah merasakan pahitnya perpisahan (dan pahitnya berusaha menulis tentang itu!), bagiku kesanggupan orang-orang yang kuundang ini dalam menuliskan kembali pengalaman putus cinta itu hebat, dan berani sekali. Aku merasa sangat mengerti bahwa putus cinta dan/atau perpisahan sama sekali bukan hal yang menyenangkan untuk dialami dan dihadapi, apalagi untuk diminta diceritakan berulang-ulang, terutama kalau itu pengalaman yang sangat pahit dan menyedihkan. Rasanya bisa jadi bukan main ngilu, bahkan sampai ke ujung jemarimu… dan yang membuatnya makin buruk, kejadian itu tidak langsung berhenti, tapi bisa terus berulang-ulang di kepalamu. Yang biasanya diinginkan kalau itu terjadi adalah “kabur”, lepas dari potongan-potongan gambar yang terus-menerus muncul. Kita akan mencari sebanyak mungkin distraksi: sebanyak mungkin potongan-potongan gambar lain dan suara-suara lain yang jauh, jauh lebih menyenangkan (dan sama sekali tidak berhubungan dengan kejadian!) untuk mengisi pikiran.
Terlepas dari apa pun hasil akhirnya, aku ingin bilang:
sampaikanlah apa yang harus disampaikan, keluarkanlah apa yang harus dikeluarkan.
Ketika gundah dan resah; bicarakanlah, atau, tuliskanlah!
Tidak perlu sampai semua orang tahu, yang penting cukup untuk melegakan hatimu.
70 notes
·
View notes
Text
Surat untuk Pak Tani
Pak Tani Sayang, yang berjalan di lorong-lorong kegelapan Sudahkah Bapak menemukan apa yang selama ini Bapak cari? Padi bernas dan bunga yang bermekaran, sama kah bentuknya mereka musim panen kali ini?
Bapak Tani Sayang, Bapak Tani Malang.
Aku membaca surat-suratmu. Tidak ada yang aku lewatkan. Juga sumpah Bapak dulu, tidak pernah aku lupakan. Maka maafkan aku, kekasihku, ketika aku melihat padi dan bunga yang kau janjikan bernas dan mekar di ladang orang, hujan badai kuturunkan tujuh hari tujuh malam. Cinta dan kagummu yang kau katakan sudah bulat itu, aku jejalkan keduanya dalam awan mendung dan aku gulung dengan jubah taifun. Jarak dan waktu, yang kau sebut-sebut sebagai pembentuk cinta paling ampuh kamu curangi juga. Kenapa? Apa karena aku berada di langit, dan kamu jauh di daratan sana? Apa karena Bapak gerah meladang, sehingga Bapak berlari menghindar ke laut tak berdasar, ke belantara, dan ke sabana yang mungkin lebih lega memuaskan kerinduan akan kebebasan yang bahkan Bapak tidak tahu seperti apa rupanya? Lalu kenapa setelah itu kamu tidak juga pulang kepadaku alih-alih, Bapak tidur di lorong-lorong gelap yang dinginnya membekukan urat nadimu Lorong-lorong yang tidak terjangkau nina boboku
-
Bapak Tani yang dingin, yang jiwanya mengembara bersama angin.
Tahukah Bapak berapa malam dingin aku habiskan menangisi kemaraumu? Dan untuk berapa waktu aku biarkan orbitku tetap begitu Dengan ujung jemari yang bergetar hebat saat aku sapa kembali ladangmu yang sebagian layu dan wajahmu yang muram nan kusut. Bapakku Sayang, Bapakku Malang Dalam hangat rindu yang kupakai untuk membasuh pipimu Ada jejak nelangsa yang lama mengendap di sana, entah hingga kapan.
Bapak Tani Sayang, yang telah mengembalikan kelamnya pada langit yang menurunkan hujan.
Apa yang harus aku lakukan dengan surat-suratmu yang kusut dan rikuk dan penuh noda basah, mengaburkan tinta Pilu hatiku membayangkan kau tulis ini semua sembari berurai air mata Tidak hanya kamu yang tersedu, Bapak di malam Rabu dan Sabtu dan sepanjang hari Minggu Bernas padi dan mekar bungaku masih menyanyikan namamu.
53 notes
·
View notes
Photo

Senja yang kutimang sendiri memintamu juga di sini dan langit Bali mengamini. Bali, 22 Juni 2016. (at Badung, Bali, Indonesia)
42 notes
·
View notes
Text
Bara Kartini

Tanyakan setiap wanita: siapa yang tidak membawa bara dan perjuangan dalam dirinya?
Genggaman kami selaras menuju perubahan.
Pada setiap karya kami ada kontribusi.
Pada setiap diri kami ada Kartini.
81 notes
·
View notes
Text
Gaun Jakarta

Untuk kota yang damai kunikmati dari jendela, di gedung tinggi lantai lima belas.
-
Pernah mendengar istilah: orang-orang mendefinisikan ruang?
Anakku bertanya semalam, Ayah, seperti apakah ruangan tempat Ayah bekerja? Pertanyaan wajib yang ia lontarkan tiap sore sehabis mandi. Pertanyaan yang ia bawa dari sekolahnya untuk pekerjaan rumah; pertanyaan yang berbeda setiap hari. Malam lalu pertanyaannya baru untukku, karena untuk apa gurunya tahu mengenai ruang kerjaku? Tapi ternyata ia hanya penasaran, anakku itu. Katanya, hari itu sekelasnya dibawa pergi melihat sebuah proyek konstruksi bangunan. Mereka melihat para buruh bangunan yang bergotong royong bekerja penuh semangat. Mereka juga melihat “mesin-mesin raksasa dengan cakar yang kuat”—begitu anakku mendeskripsikannya—lalu lalang. Selesai dari situ, mereka dibawa ke ruang kerja lantai 20 di sebuah gedung, yang rupanya adalah “ruangan tempat para bos memantau pekerjaan buruhnya”. Ternyata “bos” dari proyek tersebut adalah ayah dari teman anakku, dan ruangan itu adalah ruang kerjanya. Aku jadi tidak heran; sepulang dari sana mungkin hampir semua anak bertanya-tanya apakah ruang kerja ayah mereka sekeren ruangan yang baru mereka lihat.
Anakku, yang wajahnya putih terpulas bedak dan rambut wangi yang tersisir rapi, masih melekatkan matanya padaku, menunggu. Aku letakkan cangkir kopiku dan siap menjawab. Aku mengawali kalimatku: di ruang kerja Ayah, suasana ruangan ditentukan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Anakku memicingkan mata, kebingungan. Aku tarik napas sebelum melanjutkan.
Lantai tempat Ayah bekerja adalah satu ruangan besar yang tidak dibatasi dinding atau pintu; semua orang bisa melihat siapa pun dan apa pun yang mereka kerjakan di mejanya. Tempat Ayah bekerja adalah di pojok ruangan, bersama sepuluh orang lainnya yang duduk saling berhadapan di satu meja kerja panjang. Pojok kerja itu adalah pojok yang paling menyenangkan: suplai tak hingga dari sinar matahari, hanya beberapa langkah dari ruang makan dan mesin kopi, lengkap dengan area kecil berlapis karpet hijau rumput yang Ayah dan tim Ayah gunakan untuk bermain. Ini bahkan belum bagian terbaiknya, Anakku. Kau tahu? Gedung tempat Ayah bekerja itu dilapis kaca, sehingga di manapun kamu berada, apabila kamu berdiri dekat jendela, yang kamu lihat adalah pemandangan kota. Pojok kerja Ayah pun begitu: di siang hari ia suguhkan Jakarta, dan malam hari adalah kotak permata.
Punggung anakku menegak, terlebih saat ia mendengar kata permata. Aku tersenyum dan meneruskan bercerita. Di kantor, Ayah bisa memandang keluar jendela untuk waktu yang lama. Baik itu untuk memikirkan pekerjaan, maupun untuk mengistirahatkan kepala. Ayah menyaksikan langit cerah Jakarta di siang hari, melemparkan pandangan Ayah jauh ke garis cakrawala yang dibuat oleh batas langit dan lukisan kota di bawahnya. Damai sekali—macet? Tidak Ayah rasakan, Sayang, Ayah kan melihat dari atas, dari kejauhan.
Lalu setelah beberapa jam, cerah itu digantikan oleh semburat jingga, kemudian perlahan menjadi ungu... warna kesukaan ibumu. Dengar, Anakku: tidak ada yang lebih mewah dari dapat menyaksikan langit berganti warna. Ayah tidak pernah alpa menyaksikan itu semua. Jakarta dengan gaun tercantiknya.
Bagaimana dengan kotak permata? Anakku bertanya.
Aku tersenyum. Saat Jakarta berganti gaun, di situ lah perhiasan-perhiasannya turut muncul: lampu gedung dan bangunan, mobil, serta jalanan. Penuh, berbaris di bawah sana. Berkerlap-kerlip. Kalau saja mereka bukan deretan lampu mobil orang-orang yang berdesakan pulang kerja, Ayah akan katakan pemandangan itu tidak kalah damai dengan Jakarta saat cerah, Nak. Aku tertawa.
Anakku berbinar matanya. Sejurus kemudian keningnya kembali berkernyit, bingung. Ia menanyakan soal kalimat pembuka ceritaku, mengenai orang-orang yang mendefinisikan ruang. Aku tersenyum, melanjutkan cerita.
Ikutlah Ayah bekerja kapan-kapan, maka kau akan tahu. Siang hari setiap Ayah baru datang, ruangan besar itu—termasuk pojok kerja Ayah—lengang dan tenang. Masing-masing orang tekun menghadap mejanya, baik mengerjakan titah atasan maupun menonton video jenaka. Tapi semuanya tenggelam dalam kesibukannya. Sejam kemudian biasanya ada anak magang yang pasti akan bangkit dari kursinya, memegang cangkir, menghampiri mesin kopi... semua orang sudah hapal jam-jam bahaya saat kantuk menyerang, dan satu orang itu akan beraksi duluan. Ia akan kembali dengan cangkir kopi yang penuh dan mengepul panas. Lalu akan menawarkan orang-orang di pojok kerja Ayah. Saat itulah biasanya lengang pecah. Orang-orang akan meregangkan tubuh mereka, mulai berdiri, mencari makanan ringan, dan berkelakar. Ruangan jadi hidup. Pojok yang menyenangkan karena tata ruangnya, menjadi semakin menyenangkan karena orang-orang yang mengisinya.
Lalu? Apa terus begitu? Anakku menggali informasi.
Oh, tidak! Semakin malam pojok itu biasanya semakin ramai. Orang-orang masih akan bekerja, tapi suasana tidak selengang selepas makan siang. Biasanya sesudah Ashar, satu orang akan mulai melagu, bermain gitar. Lalu dapur akan penuh dengan orang-orang yang membuat kopi, atau mencari cemilan. Saat senja tamat, pojok bermain akan mulai diisi. Lagu-lagu akan semakin keras dilantunkan. Menunggu macet reda. Menikmati kotak permata.
Anakku mengangguk-angguk senang. Ceritaku harus putus di situ, sebab istriku kemudian datang membawakan baju mengaji kami yang sudah disetrika rapi. Sudah mau Maghrib. Aku mengusap kepala anakku sebelum menengadah ke atas. Langit Jakarta sudah berganti warna.
-
Depok, 14 Maret 2016.
82 notes
·
View notes
Text
Daya
Kamu takkan pernah runtuhkanku; aku punya sejuta kata.
Kamu takkan pernah hilangkanku; aku punya puisi.
Kamu mungkin telah renggut dan buat sia-sia sebanyak kamu bisa;
Tapi kamu takkan pernah ambil dariku sayap kata dan aksara.
Jakarta, 10 Maret 2016.
110 notes
·
View notes
Text
Teruntuk
...semuanya, yang sedang dikelilingi banyak tugas, tanggung jawab, kewajiban. Yang kepala dan hatinya sedang diisi berjuta pikiran, berkecamuk tak keruan. Yang tidak berhenti merasa khawatir dan takut. Yang sungkan mengambil jeda karena ingin terus bekerja. Yang mungkin senantiasa merasa bingung, butuh pegangan, butuh sandaran. Yang mungkin sedang disiksa dengan ketidakpastian. Yang sedang berjuang sendirian? Yang merasa kurang diapresiasi. Yang kesabarannya senantiasa diuji. Yang tugasnya mati satu tumbuh seribu. Yang sengaja berjalan di bawah hujan demi sembunyikan sedu. Yang gamang karena punya sejuta pertanyaan, tapi tak kunjung dapat jawaban. Yang memutar lagu sedih berulang-ulang karena hanya dengan begitu pegal hati bisa terwakili. Yang menangis malam-malam, karena saat terang kalian harus tersenyum seharian. Yang rindu pelukan ibunya, yang rindu senda gurau ayahnya. Yang rindu rumah, tapi belum bisa pulang. Yang sedang diuji oleh jarak dan waktu. Yang sedang diuji sehat jiwa serta raganya. Yang terduduk, terengah kelelahan. Yang merindukan teman. Yang berekspektasi dan dikecewakan. Yang sudah berusaha tapi mungkin terabaikan...
…jangan lupa mengambil napas, teman-teman. Jangan lupa untuk minum, jangan lupa makan. Di saat susah, ini bisa jadi sulit untuk dipercaya, tapi aku akan katakan juga: kita tidak pernah sendirian.
Menangis sangat diperbolehkan, kawan-kawan
tapi iringi juga lah dengan doa.
Ya?
360 notes
·
View notes