Text
Demokrasi Zaman Now: Deliberatif vs Agonistik
Oleh: Daniel Jeremia
Tulisan ini merupakan upaya untuk dapat menelaah konsep dan praktik demokrasi dalam masyarakat plural di era modern melalui 2 perspektif keilmuan. Demokrasi Deliberatif dari Jurgen Habermas dan Demokrasi Radikal dari Chantal Mouffe.

Sumber: www.google.com
Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani; demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan) yang artinya pemerintahan rakyat. Salah satu implementasi dari negara yang menggunakan sistem perpolitikkan demokrasi adalah dengan hadirnya deliberasi atau musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan atau konsensus. Pada zaman kita hidup saat ini, konsep dan praktik demokrasi merupakan manifestasi dari gelombang demokratisasi ketiga yang terjadi pada tahun 1974.[1] Dari kudeta di Lisbon, Portugal, demokrasi bergema menjadi sistem perpolitikkan paling banyak diterapkan di dunia, dengan kontekstualisasi masing - masing negara. Dari keagungan para filsuf Yunani, kini praktik demokrasi pun dapat kita jumpai di warung kopi. Seiring berkembangnya sistem politik demokrasi dalam kehidupan yang plural hari ini, berbagai interpretasi demokrasi pun menawarkan babak baru akan perdebatan dari para intelektual. Salah satunya adalah benturan konsep demokrasi deliberatif menurut anak emas dari mazhab Frankfurt bernama Jurgen Habermas dan demokrasi agonistik dari mazhab Essex, yaitu Chantal Mouffe.
Demokrasi Deliberatif
“Umpamanya Desa Konoha, kedai mie ramen merupakan ruang publik yang dapat digunakan untuk membangun kehidupan desa” .
Jurgen Habermas memberikan pemikiran segar yang berkorelasi satu sama lainnya, dari konsep ruang publik, komunikasi rasional, dan tentunya yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu demokrasi deliberatif. Habermas telah dianggap sebagai pemecah kebuntuan teori kritis dan modernitas, baik dari kritiknya terhadap Marx, Freud, dan sikap pesimistik para gurunya (Adorno dan Horkheimer) terhadap masyarakat modern era pencerahan, Hingga peletakkan ideologi-ideologi liberal dalam teorinya. Ia menilai bahwa praxis dalam orientasi Marx hanya berfokus terhadap aspek ekonomi dan kerja dalam menelaah modernitas, dan logika natural Marx mengenai masyarakat komunis merupakan bentuk positivistik yang baginya mengalir seperti teori – teori naturalis lainnya. Begitupula psikoanalisis Freud baginya kurang memiliki akses terhadap kebutuhan teoritis, terutama linguistik.[2] Habermas tidak begitu saja mengacuhkan pemikiran - pemikiran pendahulunya mengenai kondisi sosial. Ia melakukan rekonstruksi dari para pendahulunya tersebut melalui penelaahan terhadap dimensi komunikasi yang baginya merupakan dampak positif dari pencerahan.
Fokus Habermas untuk memperkaya demokrasi deliberatif merupakan penghubungan dimensi komunikasi sebagai jalan alternatif yang mempermudah partisipasi masyarakat sipil. Dalam bentuk masyarakat modern yang plural, deliberasi menjadi cara yang paling rasional untuk dapat memelihara hak - hak sipil bagi Habermas. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu deliberatio yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah (Hardiman, 2004:18). Ia merekonstruksi pandangan Kant dan Hegel mengenai makna dan diferensiasi rasio praktis-murni, dan menggagas rasio komunikatif sebagai wujud rasionalitas masyarakat modern. Namun, aktualisasi rasio komunikatif dalam masyarakat plural itu bukan dipraktikkan dengan komunikasi instrumental (memaksa/membujuk), melainkan komunikasi rasional. Pola komunikasi rasional yang dimiliki inidividu - individu ini yang akan berubah menjadi suatu perangkat politik, apabila terjadi suatu diskursus dalam tatanan politik demokratis antar masyarakat (civilized discussion). Arena dimana diskursus berlangsung inilah yang dinamakan rung publik (public sphere), dimana publik memperbincangakan pendapat-pendapatnya dengan bebas intervensi dari suatu golongan. Coffee Shop di Perancis merupakan gejala-gejala awal konsep ruang publik yang ditelaah Habermas. Ketika kelas atas dan kelas bawah mulai dapat memperbincangkan politik kenegaraan dengan wujud masyarakat sipil (civil society). Konsensus yang di dapat dari ruang publik ini yang nantinya akan menjadi menjadi opini publik (public opinion).
Habermas menegaskan bahwa sebuah proses intersubjektif antar masyarakat plural dan pemerintahan negara di era modern dapat menghasilkan suatu konsensus/kesepakatan yang menjadi sebab-akibat dalam kepentingan bersama, dengan prosedur-prosedur yang ada dalam ruang publik. Sehingga diskursus rasional itu menjadi diskursus etis, dapat menjadi praktik demokrasi kenegaraan, yaitu:
Tidak ada orang yang dapat mendapat pengecualian dalam melakukan kontribusi yang relevan.
Semua partisipan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kontribusi.
Partisipan harus memaknai apa yang ia katakan.
Komunikasi harus bebas paksaan dari luar ataupun dalam. [3]
Berikut skema untuk mempermudah memahami konsep ruang publik dan demokrasi Jurgen Habermas yang dibuat oleh F. Budi Hardiman.
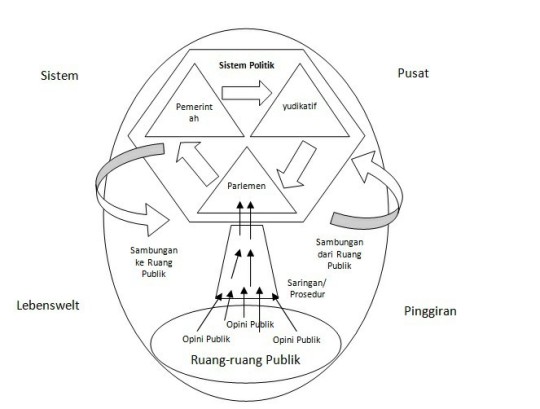
Sumber: www.google.com
Demokrasi deliberatif bukan bermakna intervensi langsung ruang publik ke dalam sistem politik (bukan demokrasi langsung) dan juga bukan depolitisasi ruang publik. Demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran politis aktif warganegara yang membangun opini mereka secara publik dalam mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung melalui media hukum (bahasa hukum). Dalam hal ini demokrasi deliberatif menghormati garis batas antar negara dan masyarakat, namun ingin agar negara hukum demorkatis mencarikan komunikasi-komunikasi politis di dalamnya (Hardiman, 2009:150)
Pandangan normatif dan etis ini didapat Habermas dengan pembaharuan terhadap tradisi demokrasi liberal. Konsep demokrasi deliberatif Habermas ini terletak pada model demokrasi prosuderalis yang mengendepankan diskursus melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan kondisi manusia.[4] Dengan syarat-syarat komunikatif proseduralis itulah kedaulatan hukum antar negara dan diskursus rasional masyarakat sipil dapat membentuk ruang publik.
Demokrasi Agonistik
“Inti dari Demokrasi adalah disensus” - Robertus Robet.
Beralih 782km ke Essex kita dapat menemukan sosok Sakura dari kelompok 7 yang bernama Chantal Mouffe. Setelah peninggalan Sasuke (Badiou), murid titisan Kakashi (Althusser) ini bersama Naruto (Laclau) mewarnai demokrasi di dunia ninja dari akar jutsu radikal. Pemikiran demokrasi agonistik Mouffe bermuara dari kritiknya akan konsep demokrasi liberal yang digagas dan diperdebatkan tradisi liberal, yaitu Habermas dengan demokrasi deliberatif dan John Rawls dengan demokrasi agregatif. Peletakan konstruksi teoritis Mouffe juga berakar dari penelaahanya terhadap awal perkembangan new social movement. Jika Habermas sudah menjelaskan bahwa rasionalitas komunikatif dalam masyarakat plural dapat menjadi konsensus dengan terbentuknya ruang publik. Berbeda halnya bagi Rawls. Menurutnya, sistem demokrasi harus berjalan dengan ketentuan hukum yang sudah diatur negara, dikarenakan tidak ada namanya argumen rasional yang memungkinkan dan merepresentasikan keseluruhan dari masyarakat plural.[5] Mouffe melihat,pandangan mereka berdua pada demokrasi terlalu sempit, dan tidak dapat melihat perbedaan prosedur antara otonomi publik dan otonomi individu. Konsep deliberatif dan agregatif justru berusaha menyeragamkan logika deduktif dan induktif masyarakat plural. Jika Rawls jatuh dalam konsep independensi suatu lembaga pemerintahan, begitupula Habermas yang tidak dapat memastikan bahwa masyarakat dapat bekerja sesuai dengan prosedural yang ia gagas. Hal ini tercantum dalam pendapat Habermas yang dikutip Mouffe:
That there are issues that have to remain outside the practices of rational public debate, like existential issues which concern not questions of “justice” but the “good life”.[6]
Argumen ini dapat kita lihat dalam realitas masyarakat dari golongan sosialita misalnya yang berkumpul dalam ruang publik bukan lagi memperbincangkan fungsi partisipatif politik yang dapat menunjang kesejahteraan bersama, melainkan untuk sekedar membahas kemewahan dari Lucinta lun.
“Kesetaraan” dan “Keadilan” dalam pengkultusan demokrasi dari tradisi liberal ini yang justru menjadi penyakit bagi demokrasi. Maka dari itu, Mouffe berusaha merombak tradisi demokrasi modern ini dengan mencantumkan 1 konsep lagi untuk memahami demokrasi, yaitu : “Perbedaan”. Suatu disensus yang terjadi dalam praktik demokrasi lah yang membuat demokrasi itu mungkin. Dalam buku yang ditulisnya bersama Laclau dengan judul “Hegemony and Socialist Strategies”, Mouffe mengemukakan tesis sentral; “objektivitas sosial dibentuk melalui tindakan - tindakan kekuasaan.” Baginya, pluralisme agonistik jauh dari membahayakan demokrasi ,konfrontasi agonis sebenarnya adalah kondisi eksistensi. Demokrasi modern spesifisitas terletak pada pengakuan dan legitimasi konflik dan penolakan untuk menekannya memberlakukan perintah otoriter.
“Salah satu new social movement misalnya melakukan kampanye anti-rokok dan melakukan diskusi bahaya rokok, dari dampak bronchitis, hingga dampak menjadi komunis. Dan mengajukannya pada pemerintah untuk menciptakan Undang - Undang larangan merokok. Apakah opini publik ini merupakan konsensus menyeluruh? Apakah seluruh masyarakat harus datang ke ruang publik? Apakah ini merupakan opini publik? Apakah ini opini?”.
Maka melalui proses deliberasi dengan tujuan menciptakan konsensus itu bagi Mouffe, sejatinya melemahkan kekuatan diri manusia, relasi sosialnya, dan bahkan membuat identitas dirinya mengalami kontaminasi oleh kesepakatan yang tunggal. Suatu konsensus dalam demokrasi itu sejatinya bersifat modus vivendi (sementara). Karena masyarakat akan selalu mengalami konflik bagaimanapun sistem pemerintahan itu. Sedamai-damainya Desa Konoha, selalu ada konflik untuk dapat melanjutkan ceritanya. Namun, deliberasi ini tidak berdampak secara langsung, melainkan membawa unsur hegemonik, dan melalui pendekatan deliberatif, kita mendapatkan masyarakat plural yang menghilangkan perbedaan – perbedaan dalam relasi sosialnya menjadi kesatuan politis yang disebut hukum.
“We are trapped in our own imagined worlds and perspectives, and that there is no way we can fully understand other people, other groups and their claims”.[7]
Bagi Mouffe, demokrasi tidak dimaknai untuk menghilangkan kekuatan dan identitas diri masyarakat, namun untuk bagaimana mengkonstitusikan kekuatan diri manusia dengan bentuk baru dan nilai-nilai demokratis. Mouffe memberikan pengenalan terhadap distingsi antara “The Political ” dan “Politics” dalam konsep demokrasi. Konsep “The political” (sikap natural manusia) merupakan bentuk bentuk inheren dalam relasi sosial manusia dengan berbagai bentuk relasi sosial yang berbeda. Sedangkan “politics” (institusionalisasi) adalah bentuk pelembagaan, praktik, dan diskursus yang selalu berusaha mengatasi konflik antar manusia yang pada dasarnya merupakan identitas dan kekuatan diri dalam “The political”. Politik selalu mengacu pada pembentukan dari suatu kesatuan dalam konteks konflik dan perbedaan, itu selalu kuatir untuk pembentukan “kita” dan penghancuran “mereka”. Dalam konsep demokrasi agonistik, lawan/kawan dalam demokrasi dinamakan Mouffe “adversary”. Adversary berarti seseorang yang pemikirannya dapat kita lawan, namun berhak untuk bertahan tanpa perlu dipertanyakan. Hal ini membedakan makna “agonistik” dan “antagonisme”. Jika masyarakat bar-bar memandang antagonisme untuk menghacurkan, maka agonistik dalam tatanan demokrasi masyarakat plural merupakan cara untuk memberikan kesamaan hak antar pendirian untuk pelaku politik tanpa harus menjadi keseragaman. Namun, Mouffe tidak pernah memaksakan masyarakat mengikuti konsepnya, karena baginya diri masyarakat bebas memilih bentuk demokrasi yang mereka mau. Baik itu dari agregatif, deliberatif, hingga agonistik.
Catatan Kaki
[1] Samuel P. Huttington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Terj. Asril Marjohan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997) hlm. 1
[2] Joel Whitebook. “The Marriage of Marx and Freud : Critical Theory and Psychoanalisis”, dalam The Cambridge Companion To Critical Theory (Cambridge University Press: Fred Rush, 2004), hlm. 92.
[3] Luke Good, Democracy and The Public Sphere. (London: Pluto Press, 2005) hlm. 73.
[4] Candra Kusuma, “Demokrasi Deliberatif Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Forum Konstituen di Kabupaten Bandung” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI, 2012, hlm. 38.
[5] Chantal Mouffe, “Deliberative Democracy Or Agonistic Pluralism”, Institute for Advanced Studies, Political Series Science, 2000, hlm. 6.
[6] Ibid
[7] Kari Karippen et. all., “Habermas, Mouffe, and Political Communication A Case For Theoritical Eclecticism”, Javnost The Public, 2008, hlm. 7.
#habermas#mouffe#democracy#demokrasi#deliberatif#agonistik#radikal#modern#diskusikamissore#ruang publik#konsensus#disensus#politik#politics#partisipasi#kesetaraan#keadilan#kebebasan#liberal#pemilu
0 notes
Text
Virtual Presentee-ism: Warta Amatir Media Daring dan Lahirnya Netizen
Oleh: Waluyo Rohmanuddin (Nama Samaran)

Sumber: http://www.statepress.com/article/2016/02/news-quiz-feb-16
SEJAK ombak besar tsunami meluluhlantakkan rumah dinas pamanku beserta keluarganya pada tahun 2004 lalu dan akhirnya mereka berhasil terselamatkan berkat informasi dari berita di televisi yang dengan cepat sampai di ruang tamu keluargaku, aku berjanji akan menghargai informasi sebesar dan dalam bentuk apapun dengan kebesaran hatiku yang luhur. Sebagai bukti nyata dari komitmenku itu, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ini aku melakukan kajian dan riset terkait beredarnya informasi di era digital ini. Apapun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun itu. Hasilnya, kini aku mengantongi 34.571 halaman jurnal yang ku kerjakan dengan tangan dan jerih payahku. Aku merangkumnya menjadi 986 halaman sebagai disertasi untuk gelar doktor di Queens College, City University of New York yang terkenal akan studi medianya.
Di sela penantianku akan penilaian yang ketat dari universitas yang memang terkenal sampai ke negeri rempah ini, teman kecilku sejak sekolah dasar Almer, menghubungiku dan berbasa-basi busuk mengenai perjalanan studiku di negeri Paman Sam itu. Kau tahu, Almer sangat mengidolakan Paman Sam (meski ia hanya tokoh fiktif propaganda Amerika untuk menjaring pemuda-pemuda pengangguran ke medan peperangan). Belakangan aku baru tahu alasannya; Ia sangat jengkel dan memusuhi tokoh fiktif propaganda milik Britania Raya. Setelah hampir tiga puluh menit percakapan dihabiskan dengan basa-basi busuk, ujung-ujungnya Ia memintaku mendiskusikan disertasi yang sedang ku tunggu hasil penilaiannya itu–padahal lulus juga belum tentu.
Entah setan apa yang lewat berbisik, aku dengan reflek mengiyakan tawaran itu. Dan bangsat, malam yang harusnya ku gunakan untuk mencari kebahagiaan virtual dengan menembak-nembaki payudara bergelambir yang berlarian di Sanhok itu, harus rela ku habiskan dengan membaca dan merangkum ulang disertasiku menjadi sekiranya 63 halaman—agar teman-teman forum diskusi Almer yang bahkan belum S1 itu tidak kelojotan membacanya.
Baru tiga belas kata terketik, pecah keributan kira-kira lima langkah dari jendela ruang kerjaku. Belasan warga sedang asyik memukuli seorang nabi palsu. Dari balik jendela, nampak beberapa bapak-bapak yang biasa ku lihat sedang main gaplek di pangkalan ojek pada ujung jalan gang Kikir—satu-satunya jalan dari pusat Kabupaten Temanggung menuju kediamanku. Ada tiga punggawa ormas Islam yang memakai pakaian serba putih, adapula menantu pak RT. Semuanya ikut memukuli, kecuali empat orang anak-anak berusia sekitar sepuluh tahun yang hanya menyumbang ludah busuk bekas mengunyah telor gulung dan ibu-ibu yang berkumpul dengan sorot mata keheranan tapi mulut bergosip.
Aku yang sedikit panik serta penasaran segera meraih baju yang tergantung di balik pintu kamar dan keluar rumah berniat menyambangi kerumunan itu. Rupanya sang nabi palsu sudah disirami Pertalite yang dijual di toko kelontong mbah Jum. “Wes lah bakar ndang, ra sah kesuwen!” teriak salah seorang punggawa ormas yang kira-kira artinya seperti ini: “sudahlah cepat bakar saja, jangan kelamaan!”. Lantas teriakan itu disahuti kerumunan dengan sorakan “bakar! bakar! bakar! bakar!”.
Dari ibu-ibu yang bergosip aku mendengar bahwa Ia diringkus di kediamannya dan ditinggal kabur oleh sekitar delapan belas orang jemaatnya. Belakangan aku mengetahui bahwa dengan bermodalkan rambut wajah yang hitam pekat serta lebat dan janggut yang panjangnya hampir menyentuh lubang udel. Ia mengaku bahwa dirinya merupakan cucu kandung nabi ummat Islam yang terakhir, Muhammad SAW. Ia berujar bahwa sang nabi ketika menerima wahyu pertamanya di gua Hiro, menyempatkan diri beranak-pinak dan dengan mukjizatnya membuat keturunannya itu tidur hingga hampir seribu lima ratus tahun lamanya. Ketika terbangun, anak nabi itu entah dengan cara apa pergi berdagang ke pulau Jawa dan menikahi seorang pedagang mebel asal Semarang. Dan dari liang kewanitaan perempuan itu, Ia dilahirkan. “Gendheng.” ucap seorang Ibu yang menceritakannya kepadaku. Ketika api disulut, kerumunan dan beberapa orang yang menepi karena penasaran segera merogoh kantong dan hampir semuanya mengeluarkan telepon genggam buatan Cina dan berdesak-desakan merekam sang nabi palsu yang dilahap api. “Viralkan, lur! viralkan” teriak orang-orang di kerumunan tersebut.
Belum setengah menit api itu berkobar, puluhan karung goni basah dilemparkan ke tubuh sang nabi palsu. Lemparan itu berasal dari tangan-tangan santri Gus Hanan, seorang ulama toleran yang cukup disegani di Kabupaten Temanggung. “Astaghfirullah, gendeng kabeh!” ucap Gus Hanan dengan sorot benar-benar marah bercampur kecewa. “Iki yo manusia to?” lanjutnya. Aku tak mendengar apa yang selanjutnya dikatakan oleh Gus Hanan karena para santrinya sibuk mengusiri warga yang berkerumun dan ibu-ibu gosip di dekatku juga ribut berbicara satu sama lain dan beberapa diantaranya memarahi anak-anaknya yang baru kembali dari kerumunan. Seketika kerumunan terpecah-pecah dan bubar menghilang satu persatu. Ibu-ibu tetap saja bergosip.
Anjing. Aku baru teringat kembali bahwa aku sedang merangkum disertasiku yang akan menjadi bahan diskusi di Rawamangun pada Kamis lusa.
Aku membeli tiket kereta ke stasiun Jatinegara dan dijadwalkan berangkat pukul tujuh pagi nanti. Artinya, aku punya waktu tujuh jam mengerjakan rangkuman ini, tentunya tanpa tidur. Ini akan sulit tapi aku sudah terbiasa bekerja dengan waktu yang mepet, sekiranya begitulah budaya belajar orang Asia di negeri-negeri adidaya. Saat melanjutkan rangkumanku, untuk sekadar mencari masukan-masukan penting aku membuka laman facebook dan melihat kembali jejak komentar pembimbing disertasi, kerabat-kerabat akademik serta chat tanpa lelah Siswanto, promotor beasiswaku yang terus mengingatkan bahwa aku di New York bukan untuk main-main.
Wedus. Ya menurutmu sepanjang tahun ini kerjaku menjinakkan kuda nil?
Baru saja laman home terbuka, di urutan feeds paling atas, temanku Neno yang kini menempuh studi Ekonomi Syariah di UIN Jakarta membagikan ulang postingan berisi video nabi palsu yang tadi dibakar warga dengan beberapa kalimat keterangan bertuliskan “Inilah akibat mengaku nabi. Belum mati saja sudah dapat azab dari Allah. Inikah tanda bahwa kita berada pada zaman dan pemimpin yang kafir? Naudzubillah. #2019GantiPresiden”.
“Bangsat, kok cepat sekali.” ucapku. Lagipula apa hubungannya dengan presiden? Entah si nabi palsu atau siapa yang gendeng. Sampai aku melihat itu, postingan tersebut sudah dibagikan oleh empat ratus ribu orang lebih. Sableng. Tapi dengan melihat itu, aku jadi teringat kira-kira sebulan lalu ada video suporter klub sepakbola asal Jakarta yang dikeroyok habis bobotoh, suporter klub sepakbola Bandung. Bahkan nyawanya tak disisakan. Dan belum sebulan berlalu, beredar rekaman amatir yang dengan nekatnya merekam musibah tsunami di Palu dan Donggala. Minatku langsung berubah dan mencoba menelusuri data-data risetku yang membahas bagaimana hal seperti itu justru jadi dilomba-lombakan oleh orang-orang dan mengapa hal tersebut sangat cepat beredar di dunia maya.
Temuan pertamaku setelah sibuk membulak-balik halaman data risetku merupakan lansiran riset data Statista (kanal daring riset statistik asal Jerman), yang memperkirakan terdapat 2,5 miliar pengguna smartphone di seluruh dunia tahun ini. Sayang aku sekarang menganggur dan masih miskin untuk mengakses kembali hasil riset berbayar itu. Smartphone melekat pada si pemiliknya hampir tiap saat, bahkan saat tidur. Didukung dengan fitur kamera yang mudah dioperasikan dan koneksi internet, rekaman-rekaman amatir makin sering muncul di dunia maya.
Lanjut mencari, aku mendapatkan potongan kuliah Stuart Jeffries (intelektual asal London, beberapa bukunya diterbitkan Verso) yang menyatakan bahwa “Smartphone sangat portabel dibandingkan kamera atau perangkat apapun, dan paling penting, smartphone menawarkan koneksi internet, ini adalah kunci bagi lahirnya fenomena yang saya sebut 'virtual presentee-ism'.” Virtual presentee-ism, yang disebut Jeffries, merupakan fenomena tentang tersebarnya pengalaman seorang perekam peristiwa pada khalayak luas. Ia merekam karena ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia ada di lokasi saat suatu kejadian terjadi. Bila disangkutpautkan, bisa saja aku kembali membaca teori hyperreality dari Jean Baudrillard. Tapi akan memakan waktu untuk mengetiknya. Lagipula kalian pasti tahu hal itu: ketika kenyataan dalam layar terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Jadi mereka merasa share dan like sebagai validasi masyarakat dalam kehidupan mayanya—terasa nyata.
Data risetku yang entah ku kerjakan di bagian mana Brooklyn tetapi tertulis “29 Juni 2017” disitu, menyatakan bahwa ada faktor budaya yang mempengaruhi ini. Beberapa diantaranya adalah faktor iliterasi dan keminiman-upaya penyaringan informasi, ditambah-tambah algoritma sosial media yang makin menjadi-jadi gilanya mempengaruhi mekanisme kognisi individu manusia era digital. Ingin makan apa saja kita mengandalkan algoritma. Kalau tak salah pernyataan ini juga dipengaruhi pidato kebudayaan Roby Muhammad di Taman Ismail Marzuki tahun lalu. Aku akan coba menontonnya lagi di Youtube.
BANGSAT. Akibat menonton video pidato kebudayaan, Aku jadi terseret-seret rekomendasi video Youtube, mulai dari kuliah-kuliah online, anak yang diazab menjadi ikan pari, tragedi petasan jumbo pemalang, hingga kata-kata mutiara Tony Blank ku tonton sampai lupa ini sudah pukul enam dan sudah pasti aku tertinggal kereta ke Jakarta. Tapir kontet, mau bilang apa aku pada Almer.
------
BARUSAN aku menghubungi Almer dan Ia bilang mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi aking. Hal ini mau tak mau akan menjadi urusannya—mungkin juga teman-temannya yang lebih percaya diri. Dan aku, mau tak mau harus menyaksikan saja dari Temanggung sini, menjadi intelektual sombong–tapi masih miskin dengan karyanya yang tebal bukan main dan kelak akan menjadi hasil studi paling berpengaruh bagi generasi Z–yang karyanya didiskusikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang konon suka mabuk setelah berdiskusi. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Mudah-mudahan setidaknya, walau diakhiri dengan mabuk-mabukan, karyaku bisa didiskusikan dengan cukup khidmat.
0 notes
Text
Bob Marley dan Kontribusinya Pada Dunia Oleh: Daniel Jeremia
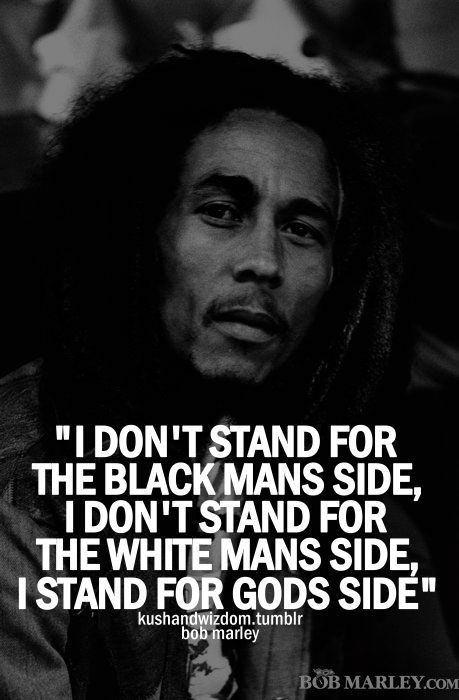
Sumber: https://www.pinterest.com/explore/bob-marley/
“One good thing about music, when it hits you, you feel no pain~” [i]
Lirik lagu di atas merupakan salah satu karya dari tokoh dunia yang akan kita bahas kali ini, ya dia adalah Robert Nesta “Marley” atau biasa dipanggil “Bob Marley”. Bob Marley merupakan salah satu aktor perdamaian dunia yang perannya masih terasa hingga saat ini, di kalangan anak muda ataupun orang tua. Fisiknya telah mati, namun ia meninggalkan harta-hartanya dalam bentuk aliran musik “Reggae, Ska , dan Rock Steady”.
Lahir di Nine Miles, Jamaica (1945), Bob sudah menjalani kehidupan yang sangat keras. Perekonomian yang sulit di daerah rural, dan rasisme yang diterima dari lingkungan karena perbedaan kulit antara ayah dan ibunya. Perpindahannya ke Trenchtown (Kingston) mengharuskannya belajar untuk dapat bertahan hidup dengan seni bela diri jalanan. Peperangan antar kartel, dan kehidupan golongan bawah yang teramat keras membesarkan Marley menjadi pribadi yang kuat.
Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, jalanan trenchtown mulai menghormati Marley dan memberinya julukan “Tuff Gong” (Gelar bagi orang terhormat di Jamaica). Di masa-masa inilah dia mulai melatih dirinya dalam bermain musik. Bersama sahabatnya Bunny, ia mulai merintis pengalaman bermusik di jalanan. Terbukanya industri musik di Amerika memberikan inspirasi bagi Bob untuk merintis kariernya lebih luas.
Musiknya mulai diterima di pasaran, walaupun Rock N Roll menjadi aliran musik yang mendominasi kala itu. Bersama The Wailers, mereka memproduksi lagu-lagu yang menjelaskan bagaimana kerasnya kondisi kehidupan di Kingston. Lagu “Trenchtown Rock” menjadi salah satu karya yang menjelaskannya.
Perjalanan musiknya seirama dengan kondisi spiritualitasnya. Marley menganut Rastafari (suatu aliran Agama Kristen di Afrika) setelah menikahi istrinya. Rasta & Reggae merupakan 2 aspek penting yang membangun karya-karya Sang Legenda.
Bob Marley dan Realisme Sosial
Karya-karya Bob Marley pada eranya, merupakan sebuah seni musik yang menginterpretasikan keadaan dunia. Menurut Chenvensky, seni tidak hanya mereproduksi kehidupan, melainkan menjelaskannya : hasil-hasil seni acapkali “mempunyai tujuan untuk melakukan penilaian atas gejala-gejala kehidupan.” [ii] Bergejolaknya rasisme, perbudakan, dan kekerasan di dunia tertuang dalam karya-karya Marley pada Era-nya. Contohnya pada lagu Buffalo Soldier (1973), berikut sepenggal liriknya:
Buffalo Soldier, dreadlock Rasta
There was a Buffalo Soldier
In the heart of America
Stolen from Africa, brought to America
Fighting on arrival, fighting for survival
I mean it, when I analyze these things
To me, it makes a lot of sense
How the dreadlock Rasta was the Buffalo Soldier
And he was taken from Africa, brought to America
Fighting on arrival, fighting for survival
Ini merupakan sebuah realitas genetik African-Americans [iii] dari dirinya yang dimasukkan ke dalam seni musik. Selain dibuat untuk mengkritisi orang-orang yang rasis terhadap kulit hitam, lagu ini juga ditujukan terhadap ego manusia yang digunakan untuk menindas hak sesamanya.
Apabila moralitas tidak dapat hadir lagi dalam kemanusiaan, maka itu akan menyebabkan “semua melawan semua”, jika ditelaah dari perspektif konflik.[iv] Tak berhenti disini, dalam lagu-lagu lain seperti “No Woman No Cry” (1975), “One Love” (1977) membuat Reggae, Jamaica, dan Negara dunia ketiga menjadi sorotan dunia.
Dalam masa-masa akhir hidupnya, kontribusi Marley semakin mendunia. Penghargaan dari PBB diterima akan kontribusinya terhadap perdamaian di Negara Dunia ketiga. Marley berhasil menyelesaikan konflik-konflik kekerasan di Afrika, dan beberapa Negara Dunia Ketiga. Ia merubah banyak stigma negatif terhadap Afro-Americans, dan orang kulit hitam di dunia.
Seorang yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan, membuka mata dunia lebih lebar akan pentingya kemanusiaan. Seorang seniman besar akan menciptakan kondisi yang diperlukannya untuk mencipta, dan kemudian mencipta dalam kondisi yang telah dibuatnya sendiri.[v]
Layaknya konsep Ahimsa dari Gandhi,[vi] seorang Bob Marley tidak menganjurkan kekerasan untuk menciptakan suatu perubahan. Ia telah berdamai dengan dunianya, dan menyemai sisi religiusitas dalam tiap karyanya. Lagu terakhir darinya berjudul Redemption Song (1980) dalam album The Wailers menjadi sekaligus pesan terakhir Marley untuk Dunia kedepannya.
“Roots, Rock, Reggae, God Bless!”
[i] Lirik lagu “Trenchtown Rock” (1975).
[ii] G.V Plekhanov, Art and Social Life (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1957) 84. 2.
[iii] Seorang individu yang mengalami percampuran Ras Afrika dan Amerika.
[iv] L.Layendecker, Tata, Perubahan, Dan, Ketimpangan (Jakarta: PT Gramedia, 1983) 396. 80.
[v] Sebuah ajaran yang menegaskan anti kekerasan.
[vi] Ignas, Kelden. 1987. Berpikir Strategis Tentang Kebudayaan. Jakarta: Prisma.
#bob marley#music#reggae#realisme#sosiologi#perdamaian#dunia#dks#unj#budaya#culture#humanity#human rights
0 notes
Text
September Hitam (Korban Tragedi 1965 dalam Kacamata Sosiologi Kewarganegaraan) Oleh: Hendi Roy

Sumber: http://www.konfrontasi.com/content/nasional/mereka-yang-menjadi-korban-sejarah-september-hitam
Setiap tahunnya, memasuki bulan september, masyarakat dunia baik di dunia nyata dan dunia maya selalu diramaikan dengan perbincangan mengenai serangkaian tragedi – tragedi yang pernah terjadi dibulan ini. Dalam dunia internasional ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan ini, Peristiwa Munchen, dimana pada tanggal 5 September 1972, pada saat diselenggarakan Olimpiade Munchen, hadir sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai kelompok September Hitam (Black September). Mereka adalah orang – orang Palestina yang menyandera dan membunuh 11 Atlet Israel dan 1 Polisi pada saat olimpiade tersebut berlangsung. Ada lagi tragedi yang terjadi di Amerika Serikat yang dikenal dengan Tragedi 9/11, dimana pada tanggal 11 September 2001 terjadi serangan teroris yang katanya dilakukan oleh kelompok militan Al-Qaeda yang membajak dan menabrakan dua pesawat ke Menara Kembar di World Trade Center, New York City. Pada peristiwa ini pun beberapa titik menjadi sasaran serangan dan banyak korban jiwa meninggal.
Di Indonesia sendiri pun September tidak dilihat sebagai bulan yang ceria saja, karena begitu banyak nya tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di bulan ini. Diawali dengan pembantaian massal yang terjadi kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, dalam tragedi tersebut tidak hanya anggota dan simpatisan tetapi keluarga yang dinilai memiliki hubungan dengan anggota PKI dibunuh, dihilangkan, atau dipenjara. Selanjutnya ada tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September 1999, dimana adanya tindakan represif dari kalangan tentara kepada mahasiswa karena melakukan serangkaian aksi untuk memprotes UU PKB (Undang – Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya), dimana posisi militer dinilai sangat leluasa untuk mengakomodir keadaan negara. Peristiwa Tanjung Priok, tragedi ini terjadi pada tanggal 12 September 1984, dimana terjadi bentrokan antara umat Islam di Tanjung Priok dengan tentara, dari peristiwa ini pun memakan korban jiwa dan luka – luka. Munir, seorang aktivis HAM yang giat memperjuangkan hak – hak kaum tertindas dan mengkritik kebijakan negara, meninggal diracuni dalam pesawat pada 7 September 2004 pada saat perjalanan menuju Belanda. Hingga kini kasus kematian nya belum jelas karena dalang dari pembunuhan ini belum terungkap. Tragedi – tragedi yang terjadi tersebut akhirnya melahirkan suatu propaganda untuk menolak lupa dan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam penyelesaian setiap kasus yang ada, itulah mengapa September tidak selalu ceria tetapi juga berwarna Hitam seperti matinya keadilan dan hak asasi manusia di negeri ini.
Disini saya tidak bermaksud untuk menjelaskan secara detail dari setiap tragedi pelanggaran HAM yang terjadi khususnya di Indonesia. Secara khusus, tulisan ini akan mencoba menjelaskan mengapa dalam pelaksanaan praktik bernegara selalu ada saja orang – orang yang menjadi korban kekerasan atau dirampas hak nya. Pada tulisan ini akan difokuskan kepada tragedi pembantaian massal pada tahun 1965 dan orang – orang yang dicap/dikira sebagai komunis atau PKI yang selalu mendapatkan diskriminasi serta stigma buruk dari masyarakat luas. Melalui pemikiran Giorgio Agamben tentang Homo Sacer dan Mesin Antropologis, saya akan coba memberikan gambaran mengapa akhirnya selalu ada pembeda dalam konteks warga negara yang baik dan yang tidak baik. Lebih jauh lagi akan diuraikan tentang wacana “anti - komunis” sebagai bentuk politisasi dalam melihat hak warga negara.
Tragedi Pembantaian 1965 dan Konstruksi Masyarakat akan wacana “Anti-Komunis”
Sebelum memulai penjelasan dalam tulisan ini, saya tekankan bahwa tidak ada maksud yang ditujukan sebagai pemantik mengenai “pelurusan” sejarah apalagi dilihat sebagai sarana untuk gerakan kebangkitan komunisme di Indonesia. Secara akademis tulisan ini hanya akan membahas proses politis dalam kerangka kewarganegaraan yang menyebabkan adanya perbedaan dalam memandang warga negara (eks tapol 1965, keluarga PKI, dan simpatisannya) dalam kehidupan sehari – hari sehingga adanya ketidaksetaraan dalam hak yang didapatkan.
Tragedi Pembantaian 1965 dimulai dengan peristiwa yang kita kenal dengan sebutan G30S, berawal dari gerakan ini akhirnya terjadi pembantaian massal yang melibatkan negara dan masyarakat sipil kepada anggota dan simpatisan PKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S, adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah perwira TNI dan segilintir anggota serta petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan maksud melindungi Presiden dari percobaan kudeta yang dilakukan beberapa jenderal angkatan darat dengan isu Dewan Jendral yang ingin menggantikan posisi Presiden Soekarno saat itu.
Secara umum mengapa akhirnya gerakan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan dan percobaan kudeta, disebabkan dibunuhnya 7 orang perwira angkatan darat yang 6 diantaranya adalah jenderal dinilai memiliki pengaruh besar saat itu dan juga adanya percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI dan beberapa perwira TNI, dengan membentuk Dewan Revolusi Indonesia dan menganulir Kabinet Dwikora yang dibentuk Presiden Soekarno. Memang terjadi kebingungan dan kerancuan terhadap peristiwa G30S ini, awalnya berniat melindungi kekuasaan presiden dan diakhir mencoba membentuk lembaga pemerintahannya sendiri. Atas dasar tersebut akhirnya Mayjen Soeharto yang saat itu menggantikan posisi Jenderal Ahmad Yani, menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S adalah PKI dan segera melancarkan operasi pembasmian kepada orang yang terlibat dengan G30S atau yang berhubungan dengan PKI serta underbouw nya. Setelah peristiwa 30 September 1965, Soeharto dan kekuasaan de facto-nya atas TNI melancarkan tindak kekerasan massif hampir di seantero gugus Nusantara yang terus berkelanjutan sampai Maret 1966. Target pembunuhan dan penahanan paksa tersebut adalah semua orang yang dituduh sebagai anggota PKI, ataupun memiliki keterkaitan tidak langsung dengan organisasi-organisasi underbouwnya PKI.[i] Tentara Soeharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semua nya dituduh terlibat G30S. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk abad keduapuluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengan nya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966.[ii]
Pembantaian kepada anggota dan simpatisan setelah peristiwa G30S dinilai sebagai hal yang wajar dilakukan oleh negara melihat tindakan kejam dan percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI. PKI dengan segala tindakan nya di masa lalu, seperti peristiwa pemberontakan di Madiun 1948 menjadi ingatan yang cukup membekas bagi masyarakat luas terutama kalangan agamis. Ditambah dengan momentum G30S rasa dendam tersebut menjadi kesadaran yang melekat bagi masyarakat hingga saat ini. Soeharto dengan legitimasi nya saat itu menciptakan kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk membenci PKI atau Komunisme di Indonesia. Rezim Soeharto terus-menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara; buku teks, monumen, nama jalan, film, museum, upacara peringatan, dan hari raya nasional. Rezim Soeharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G30S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan[iii].
Berlakunya Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 yang berisikan pembubaran PKI dan melarang segala kegiatan atau ajaran tentang Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi legitimasi yang semakin menguatkan wacana “anti-komunis” dimasyarakat. Berlandaskan peraturan ini terkadang terjadi tindakan diskriminatif dan persekusi terhadap orang yang dicap berhubungan dengan PKI dan acara - acara yang berbau dengan peristiwa tersebut, seperti yang terjadi belum lama di kantor LBH Jakarta yang melakukan seminar pengungkapan/pelurusan sejarah 1965 dianggap sebagai upaya kebangkitan PKI padahal tidak jelas bagaimana faktanya.
Persoalan yang timbul setelah dibubarkan nya PKI dan pelarangan komunisme di Indonesia adalah stigma yang terbangun dalam masyarakat bahwa orang – orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan PKI adalah “sampah” masyarakat. Mereka sering mendapatkan perlakuan tidak adil seperti tidak boleh terlibat atau bekerja untuk instansi pemerintahan, dalam konteks politik juga mereka dianggap tidak berhak untuk ikut berpartisipasi seperti dalam pemilu, dimana KTP mantan tapol (tahan politik) diberi tanda merah sebagai penanda mereka berhubungan dengan PKI. Padahal banyak sumber mencatatkan bahwa mereka yang ditangkap sebagai tahan politik terkadang tidak jelas, sebab tidak adanya proses pengadilan dan penyelidikan yang jelas, mereka ditangkap dan dipenjarakan karena dinilai berhubungan dengan PKI atau berasal dari keluarga PKI yang kadang sifatnya spekulatif. G30S sangat jelas sebagai sebuah catatan kelam bangsa ini baik pada saat peristiwa dan setelah kejadian, PKI dan beberapa perwira TNI terlibat dalam gerakan tersebut, tetapi yang menjadi persoalan adalah hanya kepada PKI semua “hukuman” ini dilimpahkan dan bahkan anggota – anggota nya yang belum tentu tahu mengenai G30S dihabisi, dipenjara, dan dirampas haknya. Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat dilematis mengingat begitu banyak gerakan pemberontakan di negeri ini, tetapi tidak sampai kepada pembantaian seluruh anggotanya. Karena menurut hemat saya, perlu ada kajian mengapa akhirnya negara (rezim orde baru) memilih langkah demikian kepada warganya.
Terlepas dari polemik peristiwa G30S dan setelahnya, disini yang perlu kita telisik bersama adalah mengenai konstruksi yang telah terbentuk dalam masyarakat selama rezim orde baru berkuasa hingga kini, dalam asusmi saya terlihat pembeda dalam masyarakat Indonesia, yang mana disebutkan sebagai Manusia Pancasilais/Manusia Indonesia Seutuhnya (wacana yang disebarluaskan oleh rezim orde baru melalui berbagai propaganda dan programnya) dan yang satu lagi adalah yang bukan Manusia Indonesia Seutuhnya, termasuk eks tapol 1965, keluarga anggota PKI, dan simpatisannya, dll. Tetapi yang paling nyentrik dan selalu timbul ke permukaan wacana dalam masyarakat adalah Komunisme atau PKI, karena dalam setiap kegiatan yang berbau kritik atas kebijakan negara atau adanya hal – hal yang diidentik dengan “Ke-kirian” dan Marxisme dianggap sebagai gerakan komunisme atau upaya membangkitkan nya kembali di negeri ini. Jadi, apapun yang berlawan dengan negara ini adalah Komunisme dan mereka yang telah dan diindikasi berhubungan dengan PKI atau Komunisme dirasa sangat wajar bila mendapatkan perlakuan diskriminatif. Pertanyaan sederhananya adalah Mengapa hal demikian selalu terjadi selama bertahun – tahun di negara yang demokratis dan plural ini? Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam melihat warga negara dan hak nya masih terjadi praktik atau perlakuan yang salah dalam masyarakat terutama negara sebagai sebuah sistem yang memiliki kedaulatan dan legitimasi yang sah.
Korban Tragedi 1965 dalam Kacamata Sosiologi Kewarganegaraan
Sosiologi Kewarganegaraan adalah salah satu perspektif baru yang dibukukan oleh dua orang yaitu Robertus Robet dan Hendrik Boli Tobi, yang menurut saya ingin kembali melihat dan coba mengkontekstualisasikan pemikiran beberapa tokoh sosial dalam melihat persoalan politis warga negara khususnya di Indonesia. Dalam buku tersebut ada ulasan mengenai pemikiran tokoh dari Italia yang bernama Giorgio Agamben, didalam pemikirannya Agamben coba menjelaskan mengenai kondisi perpolitikan dunia kontemporer dengan konsep Homo Sacer dan Mesin Antropologis. Konsep tersebut disandingkan oleh Agamben dengan melihat kedaulatan negara yang menurutnya didalamnya terdapat praktik – praktik yang perlu dipahami dalam konteks kewarganegaraan dan politik kontemporer. Sebelum mencoba mengkontekstualisasikan antara korban tragedi 1965 dengan pemikiran Agamben, saya akan coba memberikan sedikit gambaran singkat dari pemikirannya.
Agamben memulai penjelasan mengenai persoalan “manusia” atau subjek dengan menggunakan konsep modus kehidupan. Mengacu ke pemahaman Yunani Kuno, Agamben menerima pembedaan antara Zoe (Naked Life) dan Bios. Zoe mengekspresikan fakta sederhana kehidupan biasa segala makhluk termasuk manusia, binatang, dan dewa – dewa, sementara bios menandai bentuk atau laku kehidupan tertentu untuk individu atau kelompok.[iv] Disini persoalan mengenai modus kehidupan yang diberikan oleh Agamben memiliki perbedaan yang menurut saya dibedakan atas adanya pandangan politis. Zoe adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki identitas politis dan bios adalah kondisi dimana seseorang telah menerima sesuatu yang bersifat politis sebagai bagian dari masyarakat atau warga negara. Pembedaan antara zoe dan bios sebenarnya tidak terjadi mengingat keduanya adalah bagian yang sebenarnya ter-integrasi dengan diri subjek sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, namun politik dan kekuasaan menjadikannya “kabur”. Maka terjadi dua pembentukan wacana dimana ada yang disebut dengan form of life dan naked life. Di titik dimana dua kemungkinan modus kehidupan ini “jatuh” ke tangan politik, maka politik selalu memiliki dua kemungkinan: mengutamakan form of life atau malah mereproduksi naked life. [v]. Form of life adalah sesuatu hal yang diidentikan sebagai “cara yang sesuai” dalam kehidupan untuk kebahagiaan individu atau kelompok seperti berpartisipasi dalam masyarakat, kesejahteraan hidup, dsb. Sedangkan naked life adalah sesuatu kondisi dimana tidak adanya identitas politis atau hak yang dimiliki oleh seseorang dan kelompok karena adanya “kekuatan dari luar diri” yang membentuk “kekosongan” dalam hidup. Naked life inilah yang sering menjadikan persoalan dalam konteks politik suatu negara, dimana mereka sering tersingkir atau disingkirkan sebagai bentuk politisasi yang sering dilakukan oleh sesuatu yang memiliki kekuasaan seperti negara. Di sini naked life menemukan atau dapat disepadankan dengan suatu subjek historis konkret dalam apa yang disebut Agamben sebagai Homo Sacer[vi]. Homo Sacer yang menjadi “buah” dari politisasi pemegang kekuasaan dan menimbulkan persoalan ketika terjadi hal – hal yang merugikan bagi orang – orang atau kelompok yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakat.
Homo Sacer sebenarnya adalah subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi sekaligus dieksklusi keluar dari hukum.[vii] Posisi Homo Sacer berada “di tengah – tengah” dimana secara implisit tidak memiliki identitas politis (hak) tetapi juga masih dilihat eksistensinya sebagai manusia. Disini Agamben melihat kesamaan antara konsepsi Homo Sacer ini dengan konsepsi kedaulatan yang selama ini dipegang oleh kepolitikan pada umumnya. [viii] Kedaulatan dianggap sebagai kekuasaan yang sah dan memiliki legitimasi yang kuat dari “Dia” yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan hal – hal mana yang perlu dilakukan dan orang – orang yang menjalankan “perintahnya” serta tidak bisa menolak dan menggangu gugat. Didalam bentuk sebagai negara yang berdaulat, dikenal adanya “kondisi pengecualian” (state of exception) dimana negara bisa melakukan intervensi politik terhadap hukum sehingga negara bisa membuat/menetapkan hukum dan bisa untuk tidak tunduk terhadap hukum tersebut. Dengan adanya kekuatan politis dan legitimasi yang kuat inilah Negara seringkali menjadi totaliter dan menciptakan berbagai kekosongan dalam praktiknya, tidak hanya dalam aspek penetapan dan penganuliran hukum, namun juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sebab akan selalu ada dampak politisnya ketika kekuasaan tidak bisa dikendalikan.
Kekuasaan totaliter menjadi momentum di mana manusia harus menyerahkan eksistensinya kepada hukum sejarah dan kekuatan alam. Akibatnya, masyarakat totaliter hanya menjalani hidup yang serba terkontrol, niscaya dan terberi. Di sini, terror menjadi medium esensial pemerintahan totaliter untuk menyingkirkan individu tidak berguna demi kepentingan spesies manusia unggul, mengorbankan bagian-bagian demi kepentingan keseluruhan.[ix]
Dengan “kondisi pengecualian” seringkali negara mengambil sikap yang dirasa perlu untuk menjaga stabilitas (kekuasaan) nya. Namun, tidak selamanya negara mampu mengambil keputusan atau langkah yang bisa dikatakan netral dan tidak merugikan, faktanya tidak sedikit dari kejadian historis yang telah terjadi banyak korban jiwa yang meninggal, hilang, dipenjara dengan dalih menjaga keamanan dan untuk kepentingan bersama, contohnya pembantaian massal 1965. Rentetan dari kondisi politik seperti ini, dimana negara dengan kedaulatan nya yang ditunjukkan dengan “kondisi pengecualian” seringkali mereproduksi homo sacer atau naked life. Taruhannya adalah hilangnya hak – hak sebagai warga negara dengan melihat adanya demarkasi/garis pembatas antara mana yang sesuai dan tidak.
Wacana “anti komunis” yang berujung pada pembedaan dalam memandang siapa itu “Manusia Indonesia” yang sebenarnya dalam pandangan Agamben adalah hasil dari pendefinisian mengenai siapa itu subjek atau manusia, aspek kehewanian yang dihilangkan dalam diri manusia – itulah yang menjadikan manusia sebagai “manusia”, namun sebenarnya menurut Agamben ketika dalam perbandingan semacam ini, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya manusialah yang mengalami pengecualian.[x] Inilah yang disebut dengan Mesin Antropologis, dimana terjadi peng-kategorisasian dalam memandang manusia dan binatang. Dengan melakukan pendefinisian ini dalam “mesin antropologis” selalu menghasilkan sesuatu kegagalan dalam memandang siapa itu manusia dan bukan manusia. Karena dalam konteks perkembangan masyarakat dan politik, makna dan definisi akan siapa itu manusia selalu berubah, namun tidak di Indonesia sejak era orde baru hingga kini. Dalam hemat saya, bekerja mesin antropologis inilah yang menyebabkan selalu adanya tindakan diskriminasi dan pandangan yang berbeda dalam masyarakat Indonesia mengenai siapa itu warga negara. Orang – orang yang dianggap pernah terlibat dengan PKI atau hal – hal yang “Ke-kirian” selalu direproduksi dalam masyarakat sebagai bukan “Manusia Indonesia” dan mereka yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan verbal dianggap hal yang wajar karena memang orang – orang yang pernah terlibat PKI, eks tapol 1965, dan keluarganya atau bahkan orang – orang yang membahasnya dan bergerak untuk mengetahui serta membela korban dianggap sebagai Homo Sacer.
Indonesia sebagai negara yang berdaulat mampu menetapkan dan harus melaksanakan hukum yang dibuatnya, namun disatu sisi pula terjadi ambivalensi ketika ada intervensi politik seperti yang dilakukan oleh rezim orba untuk melakukan operasi “pembersihan” kepada warga negara Indonesia yang dinilai terlibat dengan PKI dan Komunisme. Padahal dalam UUD 1945 jelas dijamin mengenai perlindungan kepada warga negara Indonesia dan HAM. Pelaku dari tindak pembantaian dan pelanggaran HAM tersebut juga bebas dan lolos dari hukum karena legitimasi negara menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut.
Penutup
Pemikiran Agamben ini menjadi tawaran baru dalam melihat permasalahan saat ini dimana warga negara yang sering dipolitisasi merupakan hasil kegagalan dalam pemahaman politik kontemporer terutama negara – negara berdaulat yang mampu menciptakan “kondisi pengecualian” dan menjalankan praktik – praktik yang melanggar hukum itu sendiri. Korban tragedi 1965 adalah Homo Sacer dalam konteks kekinian, mereka mendapatkan label seperti demikian bukan serta merta karena propaganda atau konstruksi stigma orde baru kepada masyarakat. Mereka adalah orang – orang yang menjadi korban dari praktik perpolitikan negara dimana “keberadaan” mereka yang tidak jelas dan kabur dalam sejarah bangsa ini diciptakan oleh kedaulatan yang kerap kali mementingkan kekuasaan politis kelompoknya (orde baru).
September akan selalu menjadi bulan pertarungan bagi mereka yang menuntut keadilan dan mereka yang “merasa benar” atas kuasanya. Sudah 52 tahun sejak tragedi itu terjadi dan hingga hari ini tidak ada titik terang untuk penyelesaian atau rekonsiliasinya. Negara sebagai representasi dari tujuan dan keinginan rakyat, harus mampu mengambil langkah konkrit dalam masalah ini. Dalam jangka panjang, kegaduhan seperti saat ini akan selalu timbul setiap memasuki bulan september atau G30S, persoalan mengenai kebangkitan PKI dan Komunisme akan selalu mencuat ke permukaan masyarakat, karena memang hal ini lah yang menjadi batas sejauh mana kita dianggap warga negara Indonesia. Terlebih menurut saya dengan menonton film fenomenal G30S/PKI versi Orde Baru tidak menjadikan kita paham akan sejarah terlebih menjadi “Manusia Indonesia Seutuhnya”, apalagi menunduh teman sebangsa setanah air sendiri sebagai seorang komunis atau pro PKI. Alih – alih dengan menonton film tersebut sebagai jalan “meluruskan” sejarah, menurut saya lebih baik kita luruskan dulu pikiran kita yang agak “belok – belok” untuk memahami sejarah dengan minum kopi dan “ngeriung” bareng. Terakhir pertanyaan saya, sampai kapan September akan selalu hitam di Indonesia? Kapan “september ceria” itu akan datang? Apakah kita mau tetap diam menanti ketidakjelasan dari bagian sejarah bangsa ini serta menonton kegaduhan saling tuduh setiap septembernya? Terimakasih.
[i] https://www.kontras.org/buku/MENYUSUN_PUZZLE_PELANGGARAN_HAM_1965.pdf. Hlm.8.
[ii] John Roosa.Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto.Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra: Jakarta. 2008. Hlm. 5.
[iii] Ibid. Hlm. 9.
[iv] Robertus Robet & Hendrik Boli Tobi. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben. Marjin Kiri: Tangerang. 2014. Hlm. 165.
[v] Ibid. Hlm. 167.
[vi] Ibid.
[vii] Ibid. Hlm. 168.
[viii] Ibid.
[ix] Servelus Konseng. Tesis: Relevansi Pemikiran Agamben Tentang Sikap Negara Terhadap Ahmadiyah. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta. 2014. Hlm. 5-6.
[x] Ibid
Daftar Bacaan:
Konseng, Servelus. 2014. Tesis: Relevansi Pemikiran Agamben Tentang Sikap Negara Terhadap Ahmadiyah. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Robet, Robertus & Hendrik Boli Tobi. 2014. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben. Tangerang: Marjin Kiri.
Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
https://www.kontras.org/buku/MENYUSUN_PUZZLE_PELANGGARAN_HAM_1965.pdf.
0 notes
Text
Sejarah Sosialita dan Kemunculan Social Climber Oleh: Mega Mulianisa

Sumber: https://www.kompasiana.com/triay/ikutikutan sosialita_585dca0eed927300088b4568
Kemunculan fenomena sosialita sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan fenomena ini sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Sosialita dianggap sebagai gejala masyarakat kota yang lahir akibat globalisasi. Mendengar kata “sosialita” kerap kali pikiran kita terbayang sekelompok orang yang berpakaian glamour, hobi belanja barang mewah, dan senang berfoya- foya. Fenomena yang berkembang menjadi tren ini tidak lepas dari peran sosial media . Misalnya kemunculan Geng Jedar, Nia Ramadhani dan kawan- kawannya yang selalu berfoto berbalut kemewahan di instagram akhir- akhir ini menjadi perbincangan netizen. Tak jarang berbagai media massa melabeli Girls Squad ini sebagai kaum sosialita. Pun dalam kehidupan sehari- hari secara tidak sadar kita acap kali menyebut teman sejawat kita yang hobi pergi ke mall sebagai bagian dari kaum sosialita. Lantas, apa pengertian dan makna sosialita yang sebenarnya? Bagaimana mereka terbentuk?
Kata sosialita sebenarnya berasal dari kata bahasa inggris yaitu socialite, yang merupakan akronim dari kata social dan elite. Social yang berarti menjalin hubungan kemasyarakatan dan elite yang berarti kelompok orang yang terpandang atau berderajat tinggi. Dari artikel milik David Patrick & Jeffrey Hirsch yang berjudul Socialites : A History, kemunculan istilah sosialita pertama kali di dunia ada pada negara Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Pada masa tersebut dua tempat penting kemunculan istilah sosialita adalah Park Avenue dan The Nort Shore of Long Island. Pada tahun 1929 Amerika mengalami kehancuran ekonomi atau yang disebut dengan Stock Market Crash of 1929, dimana ini merupakan sebuah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika, bahkan menjadi peritiwa jatuhnya bursa saham Amerika yang terbesar sepanjang sejarah. Kejadian ini sekaligus menjadi gejala bahwa Amerika akan mengalami Great Depression. Peristiwa ini kemudian menyebabkan dibuatnya peraturan- peraturan hukum mengenai finansial dan perdagangan. Di era ini munculah kafe- kafe mewah di Amerika atau dikenal dengan istilah Cafe Society pada waktu itu. Kafe- kafe mewah ini sering didatangi oleh orang- orang elit ketika malam tiba untuk sekedar berbincang- bincang sebab pada masa itu kecil kemungkinan masyarakat kecil bisa pergi ke kafe mewah. Situasi kehancuran ekonomi menyebabkan terjadi phk dimana mana yang meyebabkan angka pengangguran meningkat sangat pesat. Orang- orang inilah yang kemudian disebut- sebut sebagai sebagai kaum sosialita pada waktu itu.
Berbeda dengan Amerika, Eropa di masa yang sama juga ada kelompok elit yang mewarnai perkembangan sosial pada saat itu, namun istilah sosialita ini belum populer . Tapi bukan berarti gaya hidup ala sosialita seperti Amerika tidak ada, gaya hidup seperti ini ada akan tetapi hanya dilakukan oleh keturunan bangsawan. Sosialita di Eropa lebih dikenal sebagai orang – orang yang berasal dari kaum bangsawan dan melakukan aktivitas sosial untuk membantu masyarakat. Contoh terkenal dari sosialita Inggris termasuk Beau, Lord Alvanley, Marchioness of Londonderry, Daisy, Princess of Pless,. Kalaupun ada sosialita yang bukan berasal dari golongan bangsawan Inggris, ia pasti memiliki koneksi dengan kaum bangsawan. Sosialita ala Eropa ini ditiru oleh seorang American Philantropist terkenal bernama Roberta Brooke Astor, seorang kaya raya dari keluarga Astor yang memiliki gaya hidup elit tapi juga seorang dermawan kepada sesama. Pengaruhnya membawa keragaman makna dari sosialita.
Kemunculan Sosialita di Indonesia
Munculnya gaya hidup ala kaum sosialita di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda, namun pada saat itu disebut sebagai “nyonya elit”. Pada masa awal pembentukan koloni, kehidupan para pegawai VOC masih sederhana, belum ada fasilitas untuk bersosialisasi seperti teater dan rumah makan. Namun, kehidupan berubah pada pertengahan abad 17, kehidupan menjadi lebih mapan dan makmur. Maria van Aelst, istri dari gubernur VOC Antonio Van Diemen yang menjabat dari tahun 1636-1645 mempelopori gaya hidup mewah dengan seringnya menyelenggarakan pesta. Kemudian fenomena ini semakin menjamur di kalangan nyonya-nyonya elit di Batavia[i]. Bahkan ada sebuah tempat yang bernama Sociteit Harmonie yaitu gedung pesta sosialita Eropa di Batavia. Kaum pribumi menyebutnya dengan “Rumah Bola” dan pada saat itu karena hanya orang-orang eropa dari kelas atas, pejabat, pengusaha dan priyayi yang boleh menjadi anggota perkumpulan eksekutif ini.
Gereja juga menjadi tempat para perempuan elite itu memamerkan kemewahan yang mereka punyai, namun kebiasaan itu bukanlah bawaan kaum borjuis di Belanda tapi lebih kepada pengaruh budaya Asia dan Portugis. De Graff dalam karyanya Oost-Indische Spigel mengatakan nyonya- nyonya elit beribadah di gereja Kruiskerk[ii] sebagai ajang pamer status sosial. Para nyonya pada saat itu berpakaian serba mewah, menggunakan perhiasan, diiringi dengan budak yang membawa kotak sirih, tempolong untuk meludah, kipas serta patung. Di acara kebaktian mereka mendapat tempat duduk terhormat dan seringkali mengobrol sambil menyirih seakan tidak memperhatikan pendeta. Pihak gereja pun enggan menegur mereka karena jika dilarang gereja tidak memperoleh sumbangan dari para istri pejabat itu.
Jean Gelman Taylor dalam buku The Social World of Batavia mengungkapkan kritikan dari Graff yang berbunyi:
“This little ladies in general, Dutch but also Half-Castes, and especially Batavia.....let themselves be waited on like princess, and some have many slaves, men and women in their service who must watch over them like guard dogs night and day...........and they are so lazy that they will not lift a hand for anything, not even a straw on the floor close to them, but they call at once for one of their slaves to do it, and if they do not come quickly they are abused”[iii].
Gaya hidup ala sosialita Amerika pada zaman VOC cenderung dilakukan oleh orang Eropa, jarang warga pribumi. Bahkan pribumi kali itu menjadi budak. Namun, berbeda dengan zaman orde baru dimana pada masa inilah kemunculan sosialita untuk orang Indonesia. Veven Sp Wardhana, Pengamat budaya dalam Tempo 15/04/2013 mengatakan bahwa kemunculan sosialita pada masa orde baru era Presiden Soeharto, sebagai dampak kemakmuran. Pada masa itu, sejumlah pengusaha meraup kesuksesan di atas rata-rata. Namun, kala itu keberadaan sosialita belum terendus dan cenderung tertutup terhadap publik. Identitas khusus yang melekat adalah mereka dari kalangan glamor, punya profesi mentereng, hingga hobi rumpi.
Pengenalan masyarakat akan makna sosialita saat ini nampaknya hampir sama dengan sosialita pada masa orba, dimana sosialita dipahami hanya sebatas orang yang hobi belanja ,menggunakan barang mewah dan sering bepergian ke tempat elit. Bedanya sosialita saat ini cenderung lebih terbuka terhadap publik bahkan hobi update di sosial media. Jika kita mendefinisikan makna sosialita ala masyarakat saat ini mungkin kita mendapatkan ciri- ciri sebagai berikut : Pertama, dari kelas sosial mereka bukanlah golongan kelas bawah, tetapi golongan kelas menengah sampai kelas atas yang sangat kaya. Kedua, kegiatan yang dilakukan biasanya berupa arisan (cenderung dilakukan oleh ibu- ibu, mulai dari arisan uang, barang, perhiasan hingga brondong), nongkrong di cafe elit (cenderung dilakukan oleh remaja rentang usia 15- 23 tahun). Ketiga, hobi pergi keluar negeri dan yang terakhir gemar menggunakan barang mewah bahkan hingga harganya mencapai ratusan juta. Robert L. Peabody mendefinisikan sosialita sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk menghibur sekaligus mendapatkan hiburan.[iv] Sedangkan, Inti Subagio mengatakan bahwa sosialita dimulai dari keluarga kerajaan di Eropa yang selalu mendapatkan perlakuan VVIP yang harus memiliki prestasi dari segi sosial seperti memiliki yayasan. Lain lagi dengan Jennifer Gromada yang mendefinisikan sosialita sebagai orang dengan kemampuan intelegensia yang tinggi dan terpelajar.[v] Ia memberi contoh seperti Mary Borden yang merupakan filantropis yang murah hati, perawat pemberani, dan penulis yang produktif .Terlepas dari banyaknya definisi yang dikemukakan oleh tokoh, terdapat adanya kesamaan yang dimaksud yakni orang dengan kelas sosial tertentu yaitu elit yang berkecimpung dengan kegiatan sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut maka jelas orang yang sekedar memiliki gaya hidup glamour tidak bisa dikatakan sebagai sosialita. Nyonya elit pada masa kolonial Belanda mungkin bisa dikatakan sebagai sosialita jika merujuk pada makna sosialita saat ini, tapi tidak bisa dikatakan sebagai sosialita jika merujuk pada definisi tokoh tersebut, sama halnya dengan Girls Squad ala Nia Ramadhani yang tidak bisa langsung kita labeli sebagai kaum sosialita.
Sosialita dan Social Climber
Suka atau tidak, sosialita tetap merupakan bagian dari masyarakat yang eksis hingga sampai saat ini, bahkan eksistensinya mempengaruhi munculnya social climber. Jika merujuk pada makna sosialita saat ini, social climber atau pemanjat sosial adalah orang yang mencoba untuk mengikuti gaya hidup para sosialita apapun caranya agar mereka bisa diakui dan diterima dikalangan masyarakat kelas atas. Social climber disebut- sebut sebagai anak tiri dari kemunculan sosialita. Fenomena ini muncul karena masyarakat mengangungkan status sosial. “ Gayanya sosialita, uangnya nggak ada” penggalan lirik lagu Roy Ricardo, Gaga Muhamad, dan Lula Lahfah yang sempat tren ini mungkin cukup menggambarkan ciri social climber dalam konteks gaya hidup, karena menurut penulis tidak semua social climber berkonotasi negatif.
Menurut Baudrillard, pola konsumsi masyarakat yang modern ditandai dengan bergesernya tujuan konsumsi yang seharusnya sesuai kebutuhan hidup kini menjadi gaya hidup. Berubahnya makna sosialita dan munculnya social climber juga dipengaruhi oleh sistem kapitalisme yang memaksa mereka untuk mengubah tujuan konsumsi tersebut. Pola konsumsi ada pada akhirnya hanya terpaku pada merk dibanding pada nilai guna dari barang tersebut dan masyarakat cenderung melakukan konsumsi simbol. Manusia ingin dianggap keberadaannya dan diakui eksistensinya oleh lingkungan dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Kebutuhan manusia untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain menjadikan manusia untuk selalu menggunakan atribut yang sedang populer.
Guy Debord dalam tulisannya Society of Spectale bagian dua “The Commodity as Spectacle” mengatakan bahwa spectacle adalah sesuatu yang membalikkan realita, yang memadukan sekaligus menerangkan fenomena keragaman yang tampak menjadi sesuatu yang luar biasa. Ia juga mengatakan bahwa spectacle ternyata bukanlah kumpulan citra akan tetapi merupakan suatu relasi sosial antar orang- orang yang dimediasikan melalui citra itu.Dengan deminikian apa yang dimaksud sebagai spectacle/tontonan disini tidak hanya sekedar pesan atau makna yang disampaikan oleh media massa seperti televisi, radio, internet, koran, dan lain sebagainya, namun bagaimana segala bentuk macam komoditas pada akhirnya membentuk pola pikir masyarakat menjadi tidak sekedar mengkonsumsi nilai dari suatu produk komoditi.
“The spectacle corresponds to the historical moment at which the commodity completes its colonization of social life. It is not just that the relationship to commodities is now plain to see commodities are now all that there is to see; the world we see is the world of the commodity. The growth of the dictatorship of modern economic production is both extensive and intensive in character”.[vi]
Menurutnya, peran kediktatoran ekonomi modern yang disodorkan pada kehidupan sosial membuat perubahan definisi dari seluruh kesadaran manusia., yang pada awalnya “concept of being” menjadi “having” hingga pada tahap “appering”. Konsep sosialita dari masa ke masa yang pada awalnya hidup elit, keturunan bangsawan dan sering berbagi adalah bentuk identifikasi seseorang menjadi sosialita. Namun konsep “being sosialita” berubah sejak masyarakat mengartikan sosialita sebatas seseorang yang memiliki gaya hidup hedon. Pada akhirnya pengertian sosialita hanya sebatas pada persoalan penampilan, representasi, dan penampakan dari luar yang menjadi alasan konsumsi suatu komoditas. Jika sudah masuk pada wilayah “tampak”(appearance), maka hal ini beriringan dengan logika tontonan (spectacle). Nilai dari having kemudian dengan segera mengharuskan munculnya fungsi prestise dan “yang paling mewah” dalam satu waktu. Orang berlomba- lomba agar mendapatkan label sosialita dengan jalan social climber dan mengonsumsi suatu barang yang dianggap bisa membentuk citra bahwa dia adalah sosialita. Hingga, pada akhirnya, orang mengkonsumsi sebuah barang, demi kepentingan tontonan, citra, dan representasi di khalayak umum.
Terlepas dari adanya pro kontra tentang keberadaan sosialita ataupun social climber,kelompok- kelompok ini sebenarnya bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Simplenya, mereka adalah kelas yang memiliki uang yang butuh identitas dan haus eksistensi. Melibatkan mereka dalam kegiatan sosial seperti membuat yayasan, santunan, bakti sosial dan lain sebagainya yang penuh dengan sorotan media adalah salah satu cara memanfaatkan sosialita untuk tujuan yang positif.
[i] Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia.
[ii] Kruiskerk adalah gereja Kristen pertama di Batavia.
[ii] Taylor, J. G. (1983). The Social World of Batavia (European and Eurasin in Dutch Asia). Madison: The University of Wisconsin Press. Hlm 41.
[iv] Anonim (2011), What is a socialite?, Town and Country, Vol. 165, hal. 124, Hearst Magazines, a Division of Hearst Communications, Inc., New York.
[v] Gromada, Jennifer (2009), Introduction, Modernism/Modernity, Vol. 16 No. 3, hal. 599-600, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
[vi] Debord, G. (1994). The Society of the Spectacle( Terjemahan . Donald Nicholson Smith. New York: Zone Books., bagian 2 nomor 42
Daftar Pustaka
Buku
Debord, G. (1994). The Society of the Spectacle( Terjemahan. Donald Nicholson Smith. New York: Zone Books., bagian 2 nomor 42
Ritzer, G., & Goodman, J. D. (2012). Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana.
Taylor, J. G. (1983). The Social World of Batavia (European and Eurasin in Dutch Asia). Madison: The University of Wisconsin Press.hlm 41.
Jurnal :
Anonim (2011), What is a socialite?, Town and Country, Vol. 165, hal. 124, Hearst Magazines, a Division of Hearst Communications, Inc., New York.
Gromada, Jennifer (2009), Introduction, Modernism/Modernity, Vol. 16 No. 3, hal. 599-600, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Web :
Socialites: A History diakses di http://www.newyorksocialdiary.com/social-diary/2007/socialites-a-history pada 30 April 2017
Sosialita Sudah Ada Sejak Zaman Orba diakses di https://m.tempo.co/read/news/2013/04/26/108476151/sosialita-sudah-ada-sejak-zaman-orba pada 30 April 2017
What is a socialite? A look into the world of the ‘It Girl’ diakses di http://metro.co.uk/2017/02/10/what-is-a-socialite-a-look-into-the-world-of-the-it-girl-6440593/ pada 30 April 2017
2 notes
·
View notes
Text
Lanskap Pemikiran dan Ide Emansipasi Kebudayaan ditengah Imperialisme Kapitalisme Global menurut J.S Kahn
Oleh: Hanan Radian Arasy
Setelah rindu, kebudayaan itu barangkali dapat saya gambarkan seperti pendulum titanium, bertabrakan dari satu sisi bulat bola pendulum yang memantul kepada pendulum lainnya sehingga memicu bunyi yang sangat bervariasi dengan getar yang mengikuti arus durasi dengan segi estetisnya. Sebab, disisi lain pendulum memiliki dorongan dengan sifat fisikal yaitu gaya tarik-menarik serta dorongan yang beradu pada tiap sisi bola pendulum. J.S Kahn atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Kahn telah berhasil dengan teliti menarik satu lanskap pelbagai wacana serta sentuhan-sentuhan umat manusia di bumi kedalam satu bingkai kebudayaan. Dititik itu, tak henti Kahn sebagai penulis yang dapat disebut karena ketajaman nalar dan daya kritisnya mampu menggali suatu bingkai potret kebudayaan menjadi suatu situs temuan genealogis sebagai upaya menelaah lebih dalam tentang fenomena sosial budaya. ketekunan itulah, bagi saya bukan perkara mudah untuk membukukan catatan holistis yang membuahkan fenomena an sich dimata awam menjadi tidak an sich melampaui karya ad contradictum yakni, dengan torehan buku tipis yang hanya berjumlah 267 halaman saja.
Hemat saya, Joel. S Kahn membuktikan sebagai public intellectual atas temuan-temuan spesifik menjadi mudah dan ringkas sebagai tawaran disaat pengamat kebudayaan mengalami problem yang lebih dianggap remeh temeh atas disiplin ilmu-ilmu lainnya, maupun sebagai upaya bentuk counter wacana yang berkembang baik pada tataran teoretis maupun level praktik dengan mengajukan sederet riset dengan pendekatan ragam kategori disiplin pada terminus Kultur, Multikultur, Post-Kultur. Terlepas dari itu semua, Kahn seperti yang telah disinggung sebelumnya, menggambarkan inti dari tulisanya dengan prinsip kuat mengenai dominasi Imperialisme-Kapitalisme-Global sehingga menambah luas wawasan kepada pembaca yang ingin diajak berkeliling dunia dengan menanggalkan suatu keyakinan naïf mengenai identitas kultural maupun berbagai prinsip pendekatan teoretis anthropnya,
Karakter penulisan Kahn telah membebaskan karyanya dari berbagai jebakan reduksionisme yang seringkali berseliweran pada medium-medium mainstream. Berangkat dari titik pijak yang telah dipaparkan pada larik-larik kata sebelumnya, boleh dikatakan perdebatan substansial telah merasuk pada level baru mengenai perhelatan emansipasi yang sering digadang-gadang oleh para ilmuwan sosial. Karenanya, tanpa membuang waktu sia-sia Joel S Kahn terjun langsung pada perdebatan mengenai locus emansipasi pada benua eropa-asia-amerika-afrika dengan bertolak pada sifat paradoksal era Post-Kolonial serta Multikultural dengan suatu simpul dominasi sistem kebudayaan global oleh identitas budaya mayoritaniarisme. Bagi saya, disjuncture dari globalisasi telah membuahkan hasil investasi pahit yakni tumbuhnya spirit imperalisme kapitalisme yang menggebu-gebu untuk menekan kebawah telah menjamur luas dipelbagai sudut dunia sebagai dominasi superioritas pada generasi millenial. Maka, peradaban dunia tidak menemukan contingency yang didasarkan pada prinsip diskursus demokratis. Pada situasi yang krusial, buku ini sangat pas sebagai pendamping yang ingin meneguk wawasan luas dari telaga kebudayaan dengan berbagai disiplin. Tak terkecuali sebagai pendamping yang tepat untuk latar belakang studi disiplin ilmu kebudayaan kontemporer yaitu antara teori dan praktik maupun anthropologi marxisme yang banyak disinggung pula pada isi buku ini.

Cover Buku | Foto: Dokumentasi Pribadi
Tentu, pemaparan itu menjadi menarik tatkala pembaca ditarik dalam relung waktu yang lampau sebagai suatu refleksi atas problem-problem fundamental atavistis. Seperti gambaran masyarakat peasantis pada tahun 1920an. Dengan kegigihanya, Joel S. Kahn memberikan suatu tawaran menarik atas problem-problem dengan mengajukan ide tentang emansipasi kebudayaan yang dapat dikembangkan secara relevan terlepas perdebatan yang masih berlanjut keteganganya dengan nama-nama pendahulunya seperti Edward Said, J.H Boeke, Talal Asad. Dan masih banyak lainnya yang merespon karya ini seperti pada anggota Mazhab Leiden maupun Mazhab Chicago. Sehingga tak heran karya ini seringkali digadang-gadang sebagai tawaran baru setelah Post-Kolonialisma mewabah di negara dunia ketiga dengan penyangsianya tanpa harus tergolong sebagai kategori Post-Strukturalisme teks.

Full Body | Foto: Dokumentasi Pribadi
Judul Buku : Kultur, Multikultur, Post-kultur Keragaman Budaya dan Imperialisme Kapitalisme Global.
Penerbit : INDeS Publishing,Yogyakarta.
Tahun Cetak : 2016, Cetakan Pertama.
Penulis : Joel, S. Kahn.
Tahun Karya : 1995.
Jumlah Halaman : XVII + 267 Halaman
Dimensi : 15 x 22 cm.
Kritik dan Konfrontasi : [email protected]
0 notes
Text
Karl Heinrich Marx: 101
Biografi
Oleh: Emil Rahmansyah
Karl Marx lahir di Trier, Prussia, pada 5 Mei 1818. Ayahnya seorang pengacara, memberikan kehidupkan keluarga kelas menengah yang agak khas. Kedua orangtuanya berasal dari keluarga rabbi, tetapi karena alasan-alasan bisnis, sang ayah telah berpindah agama ke Lutheranisme ketika Karl masih sangat muda. Pada tahun 1841 Marx menerima gelar doktornya di bidang filsafat dari Universitas Berlin, yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan para Hegelian muda, yang bersikap mendukung, namun kritis terhadap guru mereka. Marx menolak keabstrakan filsafat Hegelian, mimpi yang naif para komunis utopian, dan menolak para aktivis yang sedang mendesakkan hal yang oleh Marx dianggap sebagai tindakan politis prematur.

Sumber; critical-theory.com
Marx Menikah pada tahun 1843 dan tidak lama kemudian terpaksa meninggalkan Jerman untuk mencari suasana yang lebih liberal di Paris. Di sana dia menjumpai dua kumpulan ide yang baru, sosialisme Prancis dan ekonomi politis Inggris. Cara menggabungkan Hegelianisme, sosialisme, dan ekonomi politis yang membentuk orientasi intelektualnya unik. Juga yang sangat penting pada titik tersebut ialah pertemuannya dengan orang yang kemudian menjadi sahabat seumur hidup, dermawan, dan kolaboratnya, Friedrich Engels.
Pada 1844 Engels dan Marx melakukan percakapan yang panjang di Paris dan meletakkan dasar-dasar bagi hubungan mereka yang berlangsung seumur hidup. Karena beberapa tulisannya telah mengganggu pemerintah Prussia, pemerintah Prancis, mengusir Marx pada tahun 1845, dan dia pindah ke Brussels. Pada tahun 1849 Marx pindah ke London dan mengingat kegagalan revolusi-revolusi politis pada 1848, dia mulai menarik diri dari kegitan Revolusioneraktif dan beralih ke riset yang lebih serius dan mendalam mengenai cara kerja sistem kapitalis.
Pada tahun 1852, dia memulai studi-studinya yang terkenal di Museum Inggris mengenai kondisi-kondisi kerja di dalam kapitalisme. Studi-studi itu akhirnya menghasilkan Capital yang mempunyai tiga volume. Volume yang pertama terbit pada 1867, volume kedua diterbitkan setelah kematiannya. Pada tahun 1864 Marx menjadi terlibat kembali di dalam kegiatan politis dengan bergabung dengan Intenasional, suatu gerakan Internasional para pekerja. Perpecahan Internasional pada 1876, kegagalan berbagai gerakan revolusioner, dan penyakitnya meminta korban pada Marx. Istrinya wafat pada 1881, putrinya pada 1882, dan Marx sendiri pada 14 Maret 1883.
Materialisme Dialektika dan Historis
Oleh: Ridho Arraditya
Menyoal Materialisme Dialektika/Historis ini, saya tak akan menghadirkan banyak sesuatu yang baru melainkan hanya membahas uraian-uraian pengertian tentang pemikiran Marx yang sebelumnya sudah disampaikan secara komprehensif oleh guru-guru (besar) filsafat Indonesia. Anggaplah saya hanya membahas kembali dan mencoba membumikan uraian-uraian romo Franz Magnis-Suseno, Martin Suryajaya, Robertus Robet, dan lainnya.
Materialisme
Materialisme pada mulanya, dalam bahasan-bahasan pengantar filsafat ilmu merupakan pengertian bahwa materi adalah hakikat dari realitas. Marx merubah pandangan umum ini. Baginya, materialisme macam itu hanya benar untuk materialisme klasik hingga abad ke-18. Dalam Tesis pertamanya tentang Feuerbach, Marx menunjukkan pengertian baru dari materialisme:
Kekeliruan mendasar dari materialisme yang ada sampai saat ini—termasuk juga Feuerbach—adalah bahwa benda (Gegenstand), realitas, keindrawian, dimengerti hanya dalam bentuk obyek (Objekt) atau kontemplasi (Anschauung), tetapi tidak sebagai aktivitas indrawi manusia, praktik, (atau dengan kata lain) tidak secara subyektif.[i]
Materialisme sebelum Marx hanya memahami materi sebagai obyek indrawi belaka. Pengertian ini tak mampu menyadari bahwa obyek-obyek material itu adalah juga hasil dari aktivitas subyektif manusia. Sentralitas pada obyek ini dibalikkan oleh Marx dengan menunjukkan peran sentral subyek, manusia, dalam konstitusi materialitas hal-ikhwal. Dengan pendekatan yang dapat disebut sebagai “materialisme subyektif” inilah Marx lantas dapat menunjukkan sesuatu, selain obyek material, yang konstitutif terhadap realitas. Sesuatu itu tak lain adalah laku, kerja, praxis.
Materialisme Marx adalah pengertian bahwa keseluruhan obyek yang menyusun realitas ini tak lain adalah efek dari aktivitas subyek. Dipahami dalam kerangka ini, tak ada yang sepenuhnya natural dalam realitas keseharian. Sebagai contoh, Martin Suryajaya mencontohkan hal ini kepada hal-hal seperti kenaikan harga sembako, hutan-hutan yang jadi gundul di Kalimantan, serta pemanasan global, tiada lain adalah efek dari konfigurasi aktivitas manusia. Mengutip Njoto, sikap kritis yang menolak untuk memandang realitas secara natural dan mengakui adanya intervensi subyektif yang justru mengkonstitusi kenyataan sehari-hari inilah yang menurutnya disebut sebagai konsepsi materialis.

Sumber: us.123rf.com
Dialektika
Kita juga tahu bukan Marx yang pertama kali berbicara mengenai dialektika. Sejak Platon, pemikiran filosofis senantiasa dicirikan dengan sifat dialektis. Sokrates, junjungan Platon, sendiri berfilsafat dengan dialektika, dengan dialog (ingat: asal kata Yunani dari dialektika adalah dialegesthai yang artinya “dialog”). Namun dari Hegel lah Marx menimba pelajaran mengenai dialektika. Pengandaian dasar dialektika Hegel adalah relasionalisme internal, yakni pengertian bahwa keseluruhan kenyataan, dipahami sebagai manifestasi-diri Roh, senantiasi terhubung satu sama lain dalam jejalin yang tak putus. Inilah yang biasanya kita kenal sebagai dialektika antara tesis-antitesis-sintesis. Dialektika inilah yang dimengerti Hegel sebagai dinamika internal dari realitas dan pikiran.
Dalam suatu buku yang pernah saya baca, entah buku apa, seingatku Pengantar Filsafat nya Louis Katssoff. Dialektika dicontohkan sebagai sebuah biji pohon semangka yang ingin merubah dirinya menjadi pohon semangka yang dapat berbuah secara utuh. Untuk menjadikan dirinya sebatang pohon semangka, ia pertama-tama harus menegasikan dirinya yang lama, yang berbentuk biji itu. Kemudian tumbuhlah batang dari inti biji itu melalui retakan-retakannya. Dirinya yang berbentuk biji adalah tesis, penegasian dirinya yang masih berbentuk biji tadi adalah antithesis. Merubah bentuknya yang biji menjadi batang pohon itu tidak serta merta membuang hakikatnya sebagai biji, ia hanya secara tak kasat mata lagi berbentuk biji. Namun secara hakikat, dirinya yang berbentuk biji tadi telah bersatu-padu dan mentransformasikan dirinya menjadi batang.
Lantas bagaimana posisi Marx pada fase penggarapan Kapital terhadap dialektika Hegel itu? Marx menjawab:
Metode dialektis saya, pada fondasinya, tidak hanya berbeda dari kaum Hegelian melainkan tepatnya beroposisi dengannya. Bagi Hegel, proses pemikiran, yang ia transformasikan menjadi subyek independen di bawah nama ‘Idea’, merupakan pencipta dunia riil, dan dunia riil hanyalah penampakan eksternal dari idea. Dengan saya, kebalikannya menjadi benar: yang-ideal tidak lain dari dunia material yang direfleksikan dalam pikiran manusia dan diterjemahkan ke dalam bentuk pemikiran.[ii]
Dari pernyataan ini, seolah Marx sepenuhnya memisahkan pengertian dialektikanya dari pengertian Hegel atasnya. Dalam bentuk mistisnya, dialektika digemari di Jerman sebab ia seolah mentransfigurasi dan mengagung-agungkan apa yang eksis. Dalam bentuknya yang rasional, ia merupakan skandal dan ancaman bagi borjuasi dan para jurubicaranya sebab ia mengikutsertakan dalam pemahaman positifnya tentang apa yang eksis sebuah pengakuan secara bersamaan akan negasinya, akan kehancurannya yang tak terelakkan, sebab ia memandang segala bentuk perkembangan historis sebagai apa yang ada dalam kondisi cair, dalam gerakan, dan karenanya memandang aspek kesementaraannya pula, dan sebab ia tak membiarkan dirinya dikesankan oleh apapun, [sehingga] pada esensinya bersifat kritis dan revolusioner.[iii] Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa dialektika Marx adalah saripati rasional dari cangkang mistis dialektika Hegel.
Di sini cukup dimengerti bahwa Marx berhutang budi pada pemikiran Hegel tentang dialektika sebab dengannya realitas dapat dilihat sebagai sesuatu yang senantiasa berubah, cair dan bergerak terus menerus. Realitas, dengan demikian, adalah efek dari aktivitas subyektif yang, pada gilirannya, mendeterminasi aktivitas subyektif itu sendiri. Gerak determinasi resiprokal atau gerak dialektis inilah yang juga ditekankan oleh Marx. Dialektika, sesuai dengan pendapat Njoto, merupakan metode dari materialisme Marxis. Artinya, filsafat Marx yang bertumpu pada konsepsi materialis—bahwa yang terselubung pada jantung realitas sesungguhnya tak lain adalah praxis subyektif yang jadi material—hanya dapat diekspresikan oleh satu-satunya metode yang cocok dengan karakter materialis ini, yakni metode dialektika—sebuah modus di mana bendanya itu sendiri tidak hadir dalam stabilitas yang diam, melainkan telah selalu dalam gerak determinasi bolak-balik yang tak berkesudahan.[iv]
Historisitas
Kesejarahan merupakan tema sentral dalam diskursus Marx. Kita sering mendengar tentang ramalan Marx mengenai tatanan komunis dunia sebagai hasil evolusi dialektika sejarah. Seolah-olah Malaikat Sejarah yang bekerja dari balik layar realitas tengah merancang suatu Penyelenggaraan Ilahi bagi kaum proletar sedunia. Seolah-oleh sejarah akan berpuncak pada suatu konflagrasi final antara yang-Baik dan yang-Jahat, antara proletar dan borjuasi, dan akan berakhir dalam suatu surga dunia komunis. Pandangan inilah yang dikenal sebagai historisisme, atau pengertian bahwa sejarah dipimpin oleh suatu teleologi internal.[v]
Materialisme Dialektika/Historis
Setelah kita mencapai pengertian tentang materialisme, dialektika dan historisitas dalam pemikiran Marx, kini kita dapat beranjak menuju pemahaman akan materialisme dialektis dan historis—atau apa yang kerap disebut sebagai MDH. Apapun penafsiran para komentator tentang materialisme dialektis dan historis, ada satu yang tetap, yakni bahwa semuanya mengakui bahwa materialisme dialektis dan materialisme historis merupakan ajaran yang internal dalam pemikiran Marx sendiri walaupun Marx tak pernah menggunakan term-term tersebut secara sistematis. Oleh karena pembahasan mengenai materialisme dialektis dan historis ini mengandaikan rekonstruksi atas keseluruhan teks Marx, maka saya di sini hanya akan membatasi pada pengertian tentang kedua term tersebut berangkat dari klarifikasi yang telah kita lakukan atas term materialisme, dialektika dan historisitas.
Materialisme dialektis merupakan cara berpikir Marx tentang realitas, yakni pengertian bahwa realitas tersusun oleh materi yang memiliki relasi langsung dengan subyektivitas dan relasi ini pun bergerak dalam untaian determinasi resiprokal. Dalam pengertian yang lebih sederhana, realitas adalah efek dari mekanisme perjuangan kelas. Jika, mengikuti Njoto, materialisme historis merupakan penerapan materialisme dialektis kepada kenyataan yang menyejarah, maka materialisme historis dapat kita mengerti sebagai pemahaman tentang sejarah sebagai hal yang tersusun oleh determinasi resiprokal antar subyek dan antara subyek dengan materi obyektif. Atau mudahnya, sejarah adalah efek perjuangan kelas—sebuah efek yang bergerak dalam arah ganda, kepada sejarah dan kepada kelas itu sendiri. Pembentukan kelas sosial akan dijelaskan pada bahasan berikutnya.
Menelaah Sejarah Secara Ilmiah dan Menakjubkan
Marx merupakan tokoh multidisipliner yang memang sebagai entitas, cara berpikirnya luar biasa. Tak hanya dalam tataran filosofis, Marx menjelaskan fenomena ekonomi, sosial, sampai sejarah. Untuk itu, melalui MDH, Marx menjelaskan kita mengenai struktur masyarakat dari waktu ke waktu. Singkat saja, sejarah manusia dari waktu ke waktu di determinasi oleh cara-cara produksi manusia, dan tentunya gerak perubahan yang terjadi merupakan akibat dari perubahan cara produksi manusia secara mendasar.
Marx menempatkan bangunan ekonomis pada basis pondasi struktur masyarakat, sedangkan aktivitas masyarakat seperti politik, agama, dan lainnya merupakan bangunan atas dari struktur masyarakat. Dalam hal ini, kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa ekonomi lah yang mendasari struktur-struktur sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Marx menelaah gerak sejarah melalui pandangan materialisme dialektikanya.
Tahap pertama sebagai pemilikan suku yang merupakan tahap produksi yang belum berkembang dimana orang hidup dengan berburu, memancing, peternakan dan pertanian. Oleh karena itu, struktur sosial terbatas pada perpanjangan keluarga karena ada kepala keluarga patriarkal, di bawahnya adalah anggota suku, dengan budak di bagian bawah.
Tahap kedua, yang oleh Marx dianggap sebagai Sosialisme Purba, dicapai dengan penggabungan beberapa suku menjadi sebuah negara kota baik dengan kesepakatan atau dengan penaklukan namun masih disertai perbudakan. Perkembangan kepemilikan swasta terjadi pada tahap ini namun masih sekunder karena kepemilikan komunal. Keseluruhan struktur masyarakat didasarkan pada kepemilikan komunal dan dengan kekuatan rakyat. Namun, karena kepemilikan pribadi berkembang, kekuatan komunal ini cenderung berkurang. Ini juga merupakan periode yang menandai dimulainya transformasi petani menjadi pekerja upahan.
Tahap ketiga, feodalisme, adalah di mana kaum bangsawan mendominasi para petani dengan kepemilikan tanah milik mereka. Di kota-kota, produksi skala kecil dilakukan oleh serikat pekerja. Dengan demikian bentuk utama properti selama zaman feodal disatu sisi, merupakan property berupa lahan dan di sisi lain tenaga kerja individu yang memiliki sejumlah kecil modal dapat memerintahkan pekerja lain.
Selanjutnya merupakan kapitalisme, kapitalisme dalam buku romo magnis dijelaskan merupakan transisi dari masa feodal-kapitalisme purba-kapitalisme yang mana borjuasi Prancis memperjuangkan kebebasan melawan kaum feodal yang menekankan tatanan yang sudah ada, dank arena mereka sebagai pemodal ingin memperluas usaha mereka dank arena itu berkepentingan agar masyarakat bebas mencari pekerjaan dimana modal memerlukannya.
Alienasi dan Analisa Kelas-kelas Sosial menurut Karl Marx
Oleh : Hanan Radian Arasy Sosial
“Komunisme adalah penghapusan positif atas kepemilikan pribadi dan dengan demikian atas alienasi diri manusia dan karenanya merupakan perebutan kembali yang sejati hakikat manusia dan karenanya secara sadar oleh dan untuk manusia. Inilah Komunisme sebagai naturalism yang rampung adalah humanism dan sebagai humanism yang rampung adalah naturalism. Inilah solusi definitive atas antagonism antara manusia dan alam serta antara manusia dan sesamanya. Inilah solusi sejati atara eksistensi dan esensi, antara objektifikasi dan afirmasi-diri anara kebebasan dan kebutuhan, antara individual dan spesies. Inilah solusi atas teka-teki sejarah dan tahu bahwa dirinya adalah solusi ini.”−Karl Marx,Manusripts of 1844.
Menurut Marx, Kita selama ini menerima begiu saja bahasa dan hukum dari ekonomi-politik (kapitalisme), yakni kepemilikan pribadi, pembagian kerja, modal, upah, kompetisi, pertukaran nilai dsb.[vi]Bahasa dan hukum itulah yang menyembunyikan sekaligus melegitimasi terjadinya alienasi,eksploitasi dan penindasan terhadap kelas buruh oleh kelas borjuasi. Namun, Tulisan ini tidak akan membahas seluruh aspek yang telah disebutkan. Hanya saja, poin penting utama yang akan dibahas pada tulisan ini yang sekiranya perlu diperhatikan adalah pembahasan mengenai Alienasi atau keterasingan serta analisa-kelas sesuai dengan judul diatas. Berikut, tulisan saya mulai dari Pekerjaan:
Pekerjaan Sebagai Yang-Sui Generis dari humanisme.
Mengapa kita membutuhkan pekerjaan? Apakkah kita serupa dengan hewan? Lalu, pekerjaan seperti apa yang membedakkan kita sebagai manusia yang tak serupa dengan hewan?
Pada dasarnya, pembahasan mengenai alienasi diawali dengan pekerjaan. Dalam pekerjaan keterasingan muncul sebagai problema yang menarik untuk dibahas, karena jawab Karl Marx, dalam sistem kapitalisme orang tidak bekerja secara bebas dan universal. Jadi, pekerjaan tidak mengembangkan essensi dasar kehidupan kita sebagai manusia melainkan mengasingkan manusia baik dari diri sendirinya, maupun dengan orang lain.[vii] Dan ketika kita kembalikan kepada pertanyaan yang mengawali sub-bab pembahasan kita. Pekerjaan bagi umat manusia ialah pokok yang membedakkan kita dengan hewan. Sebab, hewan bekerja memenuhi kebutuhanya secara instingtual sedangkan manusia bekerja pada hakikatnya ialah sumber aktualisasi yang bersifat essensial serta eksistensial. Maksudnya, ketika bekerja hewan secara langsung menyatu dengan alam. Sedangkan manusia memenuhi kebutuhan lewat pekerjaan didasarkan atas estetika dan proses modifikasi terhadap alam. Kendati pun demikian, premis tersebut bersifat sementara sebelum perlu sekiranya dipaparkan mengenai problema yang melingkupi essensi dan eksistensi manusia dalam bekerja yakni keterasingan sbb:
Keterasingan dari Dirinya Sendiri
Keterasingan dari dirinya sendiri memiliki tiga segi[viii]:
Keterasingan dari hasil produksinya.
Keterasingan dari arti pekerjaanya.
Keterasingan dari aktualisasi diri.
Untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai ketiga aspek tersebut alangkah baiknya disajikan kontekstualisasi dari ketiga aspek mengenai keterasingan bagi dirinya sendiri (Lihat : Franz Magnis; 87-97,1999) Maka, Sedikit saya kontekstualisasikan dengan realitas sosial disekeliling kita yang biasa kita lihat sehari-hari sebagai penghuni kampus. Saya ambil contoh ketika kita yang duduk berdiskusi dalam forum diskusi kamis sore disebut sebagai pekerja. tidak mendapatkan kebahagiaan dan sumber rasa bangga ketika berhasil merampungkan sebuah tulisan atau pekerjaan dalam menyelenggarakan forum maupun yang turut meramaikan dan mensukseskan terselenggaranya diskusi rutinan karena direnggut kepemilikanya oleh ketua forum atau pemilik forum, maka keterasingan terhadap produknya sendiri muncul disitu yang seharusnya produk atau hasil pekerjaan masing-masing dengan kategori yang telah disebutkan sebagai objektivasi pekerjaanya. Karena hasil pekerjaan terasing dari dirinya, tindakan bekerja itu sendiri pun kehilangan arti bagi si pekerja yakni kita secara ideal yang duduk berbagi kebahagiaan dan kebanggan atas produksi pengetahuan,informasi,imajinasi serta tenaga atas terselenggaranya diskusi sore ini. Kemudian, ketika kita menggantungkan nasib lapar dan haus untuk sekedar berdiskusi agar mendapat snack maupun kopi selagi ada, hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mengembangkan dirinya sendii : waktu pekerjaan atau berdiskusi selesai dan kita dapat pulang dan memenuhi kebutuhan fisik. padahal pemenuhan kebutuhan fisik sebenarnya adalah sarana untuk mengembangkan diri—dalam kegiatan yang bermakna. Dengan demikian kita menyangkal diri kita sendiri sebagai makhluk yang bebas dan Universal. Maka, berdiskusi dengan kopi dan snack disertai dengan kebahagiaan dan kebanggaan adalah solusi dititik ini terhadap keterasingan bagi kita.
Keterasingan dari Orang Lain
Ketika manusia terasing dari hakikatnya, ia sekaligus terasing dari sesamanya. “konsekuensi langsung dari keterasingan manusia dari produk pekerjaanya dari kegiatan hidupnya dari hakikatnya sebagai manusia adalah keterasingan manusia dari manusia”[EPM, MEW EB 1, 517] Pertama, dalam sistem hak milik pribadi di mana mereka yang bekerja berada di bawah kekuasaan para pemilik yang tidak bekerja, masyarakat terpecah kedalam kelas-kelas para pekerja dan kelas-kelas para pemilik. Dua macam kelas itu saling berlawanan, bukan karena sentiment emosional mereka berlawanan melainkan kepentingan secara objektif mereka saling bertentangan. Si pemilik mau tak mau harus mengusahakan untung setinggi-tingginya. Untuk itu harus mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk upah dan fasilitas pekerja lain. Sedangkan para pekerja dengan sendirinya berkepentingan mendapat upah setinggi mungkin dan syarat-syarat kerja yang baik. Kaum buruh dan para pemilik terasing satu sama lain. lebih dari itu, keterasingan juga merusak hubungan di dalam masing-masing kelas. Buruh bersaing dengan sesama buruh dan para pemilik terasing satu sama lain. Oleh karena itu Keterasingan dapat ditandai pula dengan kekuasaan uang.[ix] Sebagai penutup dari pembahasan mengenai keterasingan, muncul pertanyaan selanjutnya ialah : Mengapa sampai terjadi keterasingan dalam pekerjaan? Menurut Marx ialah hak kepemilikan pribadi yang menjadikan manusia terasing dengan pekerjaanya.[x]
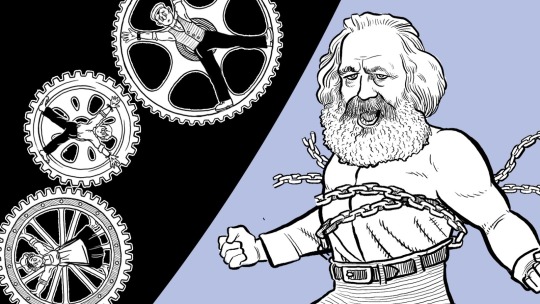
Sumber: anakadam2016.blogspot.co.id
Analisa Kelas-kelas Sosial menurut Karl Marx
Pada dasarnya, Karl Marx tak pernah menyinggung secara eksplisit mengenai kelas sosial, namun dalam gambaran perkembangan sejarah umat manusia Marx secara implisit menyinggung konsepsi yang kemudian diadopsi oleh disiplin ilmu sosiologi dan politik mengenai pembagian kategori masyarakat berdasarkan sarana produksi. pemilik tanah dengan pelayan di zaman feodalisme serta borjuis dengan proletar serta rente tanah pada sistem masyarakat kapitalisme[xi] walaupun tidak secara signifikan rente tanah melahirkan alienasi pada masyarakat karena dengan sekaligus rente tanah dapat berubah menjadi pemilik modal.[xii] Konteksnya, dapat kita lihat pada masyarakat eropa khususnya Jerman paska dikeluarkanya publikasi Manifesto Communist (Marx dan Engels) pada tahun 1800-an yang memaksakan perubahan masyarakat feodal menjadi kapitalisme. Keyakinan Marx terhadap keruntuhan kapitalisme sebagai akhir sejarah umat manusia dengan lahirnya komunisme, menghasilkan pandangan kontradiktif atau antagonisme kelas dengan suatu telos historis yang masih perlu kita kritisi dan pertanyakan ulang sehingga terbebas dari dogmatisme, Secara konkrit, Kelas-kelas membentuk kesadaran individu dimana Kelas pekerja yang cenderung progressif revolusioner dan kelas-kelas atas yang cenderung konservatif dan berupaya melakukan reparasi demi mempertahankan status quo posisinya dalam masyarakat karena menganggap perubahan adalah hal yang mengancam posisinya.[xiii]
“Agama sebagai candu masyarakat”
Oleh: Hendi Roy
Judul diatas sangat fenomenal dan juga membisingkan telinga ketika beberapa orang menyebutkan dalam berbagai diskusi, presentasi, atau bahkan hanya sekedar guyonan belaka. Kalimat tersebut terlontar dari mulut seorang tokoh ilmu sosial yang fenomenal pula, seringkali dirinya dianggap sebagai “Nabi”, “Mesias”, “Pahlawan”, dan lain – lain. Pengandaian tersebut disandingkan kepadanya sebab kontribusinya yang besar dan luas kepada dunia, baik pemikiran maupun politik praksisnya. Karl Heinrich Marx! Kembali pada pembahasan diatas, kalimat tersebut tidak serta merta dilontarkan tanpa argumentasi dan analisis yang kuat dari Marx. Tetapi, dia tidak sendiri dalam membangun pemikiran tersebut, ada tokoh lain yang mempengaruhinya dan proses sosio-historis yang melatarbelakanginya.
Pertautan dalam memandang Agama
Pemikiran Hegel pada masa ini sangat mendominasi dan bahkan banyak mempengaruhi beberapa tokoh – tokoh sosial lainnya, termasuk Marx. Namun terlepas itu semua, banyak kritik yang diberikan kepada pemikiran Hegel dalam melihat struktur masyarakat. Ludwig Feurbach salah satunya, dia adalah seorang Hegelian Muda yang menolak kepada penekanan Hegel pada kesadaran dan semangat masyarakat. Feurbach menerima filsafat materialis dan karenanya ia menegaskan bahwa yang diperlukan adalah meninggalkan idealisme subjektif Hegel untuk kemudian memusatkan perhatian bukan pada gagasan, tetapi pada realitas materil kehidupan manusia.[xiv] Kontradiksi dalam pemikiran dan aliran filsafat keduanya akan terlihat dalam memandang Agama.
Hegel memandang, dalam kesadaran diri manusia, Allah mengungkapkan diri.[xv] Baginya manusia memang mempunyai otonomi atau kebebasan dalam berpikir ataupun bertindak, tetapi dibelakangnya “roh semesta” mengungkapkan diri. Dengan demikian hal ini mengindikasikan suatu pemahaman bahwa “roh semesta” lah yang memegang kendali atas realitas kehidupan manusia. Hal ini yang kemudian di kritik oleh Feurbach, sesuai dengan landasan berpikirnya yang menganggap bahwa realitas yang tak terbantahkan adalah pengalaman indrawi dan bukan pikiran spekulatif.[xvi]
Inti dari kritik yang disampaikan oleh Feurbach adalah bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, namun sebaliknya Tuhan adalah sebagai ciptaan angan – angan manusia. Agama hanyalah sebuah proyeksi manusia. Menurutnya manusia menaruh harapan dan angan – angan nya pada suatu hal yang berada diluar eksistensi dirinya dan padahal itu merupakan hasil buatannya sendiri. Manusia tidak sadar dan melupakan bahwa agama adalah ciptaannya dan malah menyembahnya serta merasa takut kepadanya.
Sebenarnya, Feurbach ingin menyampaikan suatu anggapan tentang bagaimana manusia menjadi diri sendiri, yang diterimanya dari Hegel: untuk menjadi diri sendiri manusia harus menjadi objek bagi dirinya sendiri. Jadi, ia harus mengobjektifkan diri dengan memproyeksikan diri ke luar diri dirinya sendiri supaya dapat menghadap dan melihat hakikatnya.[xvii] Hakikat yang dimaksudkan oleh Feurbach dinyatakan melalui berbagai upaya kerja oleh manusia untuk memproyeksikan siapa dirinya sebenarnya, bukan malah bersikap pasif dan hanya menantikan dan mengharapkannya dari sesuatu yang eksistesinya berada dalam proyeksi manusia itu sendiri. Dan mencegah manusia itu sendiri dalam merealisasikan hakikatnya.
Dari pandangannya, Ia menyimpulkan bahwa manusia terasing dari dirinya sendiri karena tidak mengupayakan untuk mencapai hakikat dirinya tetapi meletakkan hakikat yang seharusnya bisa dicapai pada agama. Agama meng-alienasi manusia.
Marx, Agama dan Masyarakat
Kritik Feurbach akan agama, dianggap Marx sebagai titik terang dalam melihat sekaligus menjelaskan dasar keterasingan diri manusia. Namun, itu bukan titik final dalam menjelaskan mengapa kondisi masyarakat tetap dalam keadaan yang sama dan tertindas oleh struktur. Sebelum nantinya akan dijelaskan mengenai sumber keterasingan manusia yang sesungguhnya dalam pandangan Marx. Kita fokuskan pada kritik Marx terhadap Agama.
“Agama adalah sekaligus ungkapan penderitaan yang sungguh – sungguh dan protes terhadap penderitaan yang sungguh – sungguh. Agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu roh zaman yang tanpa roh. Ia adalah candu rakyat”[xviii]
Marx memiliki pandangan yang berbeda dengan Feurbach dalam melihat agama, Marx menganggap bahwa agama adalah bentuk pelarian masyarakat akan kondisi dan keadaan yang membelenggunya. Dengan mendekatkan diri kepada agama, manusia sebenarnya terlena dan menerima semua keadaan di dirinya. Pertanyaan yang hadir dan timbul dari kritik Marx akan Kritik agama Feurbach ada dua, pertama mengapa manusia akhirnya mengasingkan diri ke agama dan bagaimana agama mampu mengekang kesadaran diri manusia.
Manusia akhirnya mengasingkan diri kepada agama, disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam merealisasikan hakikatnya dalam realita konkrit, maka dari itu agama menjadi realisasi hakikat manusia dalam angan – angan. Marx memandang bahwa agama hanya salah satu dasar keterasingan dalam manusia, namun keterasingan manusia yang sesungguhnya lebih mendalam. Agama hanya bentuk penyegaran dalam masalah – masalah manusia, tetapi bukan sebagai landasan mencapai kebebasan bagi Marx.
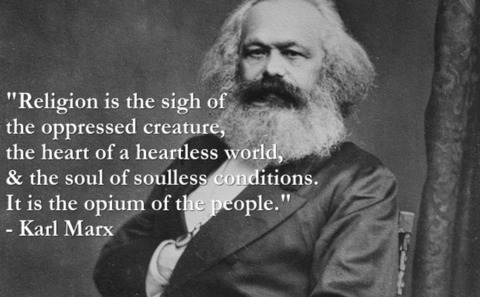
Pertanyaan selanjutnya mengapa agama mampu mengekang kesadaran diri manusia. Sebelum saya menjelaskan, perlu diingatkan bahwa penjelasan ini dalam konteks pemikiran Marx dan keadaan sosial yang melatarbelakanginya. Teori konflik dalam melihat masyarakat merupakan landasannya, dimana masyarakat yang hidup dalam keadaan seimbang dianggap sebagai masyarakat yang tertidur dan berenti dalam proses kemajuan masyarakat.[xix] Agama diletakkan sebagai “alat” dalam menciptakan kesadaran palsu pada masyarakat agar tidak terbangun kesadaran kelas dan perjuangan kelas dalam masyarakat tertindas. Struktur kapitalisme atau kelas penguasa berafiliasi dengan institusi agama untuk meredam pergolakan dalam masyarakat. Dan perebutan moda produksi bisa dihalangi oleh kelas penguasa.
Pembentukan kesadaran palsu ini dapat dilakukan dengan menggunakan ayat – ayat dalam kitab suci untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang harus bersabar dan menunggu berkat “dari sana”. Selain itu, proses sakralisasi akan sesuatu nilai yang dianggap menguntungkan digunakan dengan legitimasi oleh institusi agama. Agama memang berbeda dalam pandangan yang teologis dan sosiologis. Namun, yang bersifat “surgawi” pastinya akan berhubungan pula dengan yang “duniawi”. Agama sebagai candu masyarakat, sama seperti ketika kita meminum minuman keras atau menggunakan obat – obat terlarang, kita rileks dan merasa nyaman dengan bersikap pasif tanpa mengupayakan apa – apa. Dan itu menjadikan kita ketagihan, lagi dan lagi.
Sebagai penutup, agama sebagai candu masyarakat bukanlah kritik Marx yang mengharuskan masyarakat menghapuskan agama dan menjadi atheis. Marx, mengkritisi bahwa agama jangan dijadikan sebagai penghambat dalam mencapai kesadaran kelas dan membuat masyarakat terkungkung dalam kepasrahan hidup tanpa mengaktulisasikannya.
Catatan Kaki:
[i] Karl Marx, Theses On Feuerbach dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works: Vol II (Moscow: Foreign Languages Publishing House), 1958, hlm. 403
[ii] Karl Marx, Capital: Volume I diterjemahkan oleh Ben Fowkes (Middlesex: Penguin Books), 1979, hlm. 102.
[iii] Ibid., hlm. 103.
[iv] Martin Suryajaya, Berpikir dengan Pendekatan Materialisme Dialektis dan Historis, 2010.
[v] Ibid.
[vi]Karl Marx, “Economic and Philosophic Manuscripts of 1844” dalam Robert C. Turker (ed.), The Marx-Engels Reader 2nd ed. (New York : W.W Norton,1978).hlm70.
[vii] Franz,Magniz Suseno “Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme”(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1999).hlm87-97.
[viii] Ibid, Franz Magniz Suseno.
[ix] Ibid, Franz Magniz Suseno.
[x] Ibid, Franz Magniz Suseno.
[xi] Ibid, Franz Magniz Suseno.
[xii] Ritzer,George & Douglas J. Goodman ”Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern”hlm57-58.
[xiii] Op, Cit, Franz Magnis Suseno. hlm.112-125.
[xiv] George Ritzer, Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014, hlm. 28.
[xv] Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2016, hlm. 68.
[xvi] Ibid, hlm. 69.
[xvii] Ibid, hlm. 70.
[xviii] Ibid, hlm. 77.
[xix] Drs. D. Hendropuspito, Sosiologi Agama, Kanisius: Yogyakarta, 1990, hlm. 25.
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 18 Mei 2017, dibuat bersama - sama oleh Tim DKS.
0 notes
Text
Max Weber: 101
Oleh: Mohammad Roushan Dhamir
Max Weber (1864-1920) merupakan sosok paling terkenal dan paling berpengaruh dalam teori sosiologi (Burger, 1993; Whimster, 2001). Hal tersebut karena karya Weber begitu bervariasi dan dapat ditafsirkan secara beragam sehingga memengaruhi banyak teori sosiologi. diantara karyanya kita bisa sebut salah satunya adalah tentang nilai, tipe – tipe ideal, verstehen (pemahaman), kausalitas,dan tindakan sosial. Sosok yang lahir di Efurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864 ini berasal dari keluarga kelas menengah, yang orang tuanya memiliki perbedaan yang unik, yang membawa dampak besar pada orientasi intelektualnya. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menduduki posisi politik yang relatif penting. Sementara Ibunya adalah seorang Calvinis yang sangat religius. Oleh karena itu tak heran kita mendapatkan karya besarnya “On Capitalism, Bureaucracy, and Religion” dan “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism).

Sumber: Youtube.com
Pada kesempatan kali ini penulis akan menjelaskan 3 karya Weber, yaitu Tindakan Sosial, Etika Protestan, dan Birokrasi.
Menurut S.Turner (1963), keseluruhan sosiologi Weber didasarkan pada pemahamannya tentang tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer, 1975). Ia membedakan tindakan dengan perilaku yang murni reaktif. Mulai sekarang konsep perilaku dimaksudkan sebagai perilaku otomatis yang tidak melibatkan proses pemikiran. Stimulus dating dan perilaku terjadi, dengan sedikit saja jeda antara stimulus dengan respon2. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe: tindakan rasionalitas instrumental (Zwerk Rational), tindakan rasional nilai (Werk Rational), tindakan afektif/tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action), dan tindakan tradisional/tindakan karena kebiasaan (Traditional Action).

Sumber: 4.bp.blogspot.com
Weber mengamati bahwa agama Kristen memberikan nilai yang positif terhadap dunia material yang bersifat kodrati. Ia berpendapat bahwa meskipun orang Kristen memiliki tujuan tertinggi di dunia lain, namun di dunia ini, termasuk aspek-aspek material yang ada padanya dinilai secara positif sebagai tempat untuk melakukan usaha-usaha yang aktif. Ia sendiri menemukan sikap terhadap dunia material tersebut teramat kuat di kalangan orang-orang Kristen protestan. Weber menyatakan bahwa berbeda denga orang-orang katolik yang melihat kerja sebagai suatu keharusan demi kelangsungan hidup, maka Calvinisme – khususnya sekte puritan – telah melihat kerja sebagai panggilan. Kerja tidak sekedar pemenuhan keperluan tetapi sebagai tugas suci. Penyucian kerja berarti mengingkari sikap hidup keagamaan yang melarikan diri dari dunia. Implikasinya adalah kegiatan duniawi yang sangat intens merupakan sarana yang paling baik dan sesuai untuk mengembangkan dan mempertahankan pemilihan. Weber berpendapat bahwa karena kecendrungan tersebut, maka dapatlah dimengerti mengapa orang-orang Calvinis dalam menghadapi panggilannya di dunia memperlihatkan sikap hidup yang optimis, positif, dan aktif.
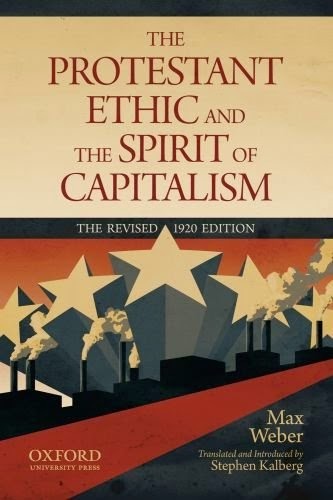
Birokrasi menurut Weber adalah sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinate) mempraktekkan control atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin”. Sebab itu, Weber juga memasukan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Kelebihan dari sistem birokrasi Weber adalah Ada aturan, norma, dan prosedur untuk mengatur organisasi. Dalam model teori birokrasi Max Weber, ditekankan mengenai pentingnya peraturan. Weber percaya bahwa peraturan seharusnya diterapkan secara rasional. Tentunya, peraturan-peraturan itu tertulis agar organisasi mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan kekurangannya adalah hierarki otoritas yang formal, yang cendrung kaku karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu.
Daftar Pustaka
Ritzer, G dan Goodman Douglas J. 2005. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenanda Media.
Soekanto, S. 1995. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 4 Mei 2017.
0 notes
Text
Emile Durkheim: 101
Fakta Sosial: Klasik tapi bukan tak Menarik!
Oleh: Hendi Roy
Terasa tidak asing namun masih sering dilupakan. Kalimat pembuka ini saya sampaikan karena memang kenyataan nya “Fakta Sosial” tidak asing bagi kita yang berkecimpung di bidang ilmu sosial, ataupun khalayak umum. Tapi berbeda pemahaman dan pengertiannya! Jadi dengan demikian – dengan segala hormat dan rasa keinginan untuk berbagi – kita harus bersama membedahnya dan memahaminya.
Teori ini dikembangkan oleh salah seorang tokoh sosial kelahiran Perancis, yang memberikan kontribusi besar khususnya bagi ilmu Sosiologi. Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis 15 April 1858. Ia keturunan pendeta Yahudi dan ia sendiri belajar untuk menjadi pendeta (rabbi). Tetapi, ketika berumur 10 tahun ia menolak menjadi pendeta. Sejak itu perhatiannya terhadap agama lebih bersifat akademis ketimbang teologis (Mestrovic, 1988). Ia bukan hanya kecewa terhadap pendidikan agama, tetapi juga pendidikan masalah kesusastraan dan estetika. Ia juga mendalami metodologi ilmiah dan prinsip moral yang diperlukan untuk menuntun kehidupan sosial. Ia menolak karir tradisional dalam filsafat dan berupaya mendapatkan pendidikan ilmiah yang dapat disumbangkan untuk pedoman moral masyarakat. Meski kita tertarik pada sosiologi ilmiah tetapi waktu itu belum ada bidang studi sosiologi sehingga antara 1882-1887 ia mengajar filsafat di sejumlah sekolah di Paris.
Selain menjadi sebuah teori ternyata Fakta Sosial merupakan sebuah Paradigma. Paradigma ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh salah satu sosiolog Perancis, Emile Durkheim. Paradigma Fakta Sosial merupakan kritik atau antitesis dari pemikiran Comte dan Herbert Spencer yang memandang ide sebagai pokok bahasan dalam ilmu Sosiologi. Menurut Durkheim, dunia ide tidak dapat dipahami secara utuh sebab hanya suatu konsepsi dan bukan sesuatu yang dapat dipandang. Hal ini berkaitan juga dengan pemisahan filsafat dan sosiologi. Fakta Sosial adalah setiap cara bertindak, yang telah baku maupun tidak, yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu.[1] “Pemaksaan dari luar” yang dimaksudkan oleh Durkheim berasal dari struktur sosial dan institusi sosial yang didalamnya terdapat nilai, norma, serta aturan yang bersifat memaksa untuk diikuti atau ditaati.
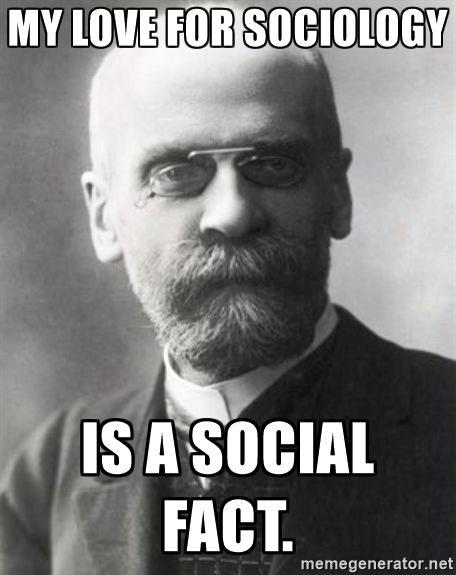
Sumber: memegenerator.net
Fakta sosial terdiri dari dua bagian yaitu, fakta sosial material dan non-material. Fakta sosial material adalah sesuatu yang ada didunia nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera bukan bersifat imajinatif. Contohnya bangunan, hukum, dan peraturan. Sedangkan fakta sosial non-material adalah bentuk ekspresi atau pemahaman yang terkandung dalam diri manusia sendiri atas yang bersifat material. Contohnya moralitas, kesadaran, dan opini. Relasi antara struktur sosial ataupun institusi sosial dan perilaku individu merupakan pokok bahasan. Konkritnya seperti yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kampus kita tercinta (UNJ) menerapkan sistem pembayaran UKT yang harus dibayarkan setiap semesternya oleh semua mahasiswa yang resmi terdaftar dalam proses perkuliahan. Pembayaran perkuliahan dengan sistem UKT ini merupakan aturan yang sifatnya memaksa, bahwasanya ketika mahasiswa tidak mampu membayar mereka tidak bisa mengikuti proses perkuliahan atau harus memilih cuti sejenak. Mungkin teman-teman bertanya mengapa UKT harus kita bayarkan selain didalam nya terdapat sanksi yang mengikat. Jawabannya adalah sebab sistem pembayaran UKT ini, telah dilegalkan atas dasar peraturan Kemenristek Dikti. Karena telah menjadi aturan yang tertulis maka dari itu kita sebagai mahasiswa tidak bisa dan terkesan sulit untuk melepaskan diri dari jeratan sistem pembayaran UKT ini. Lebih jauh lagi, proses sosialisasi dan internalisasi aturan ini ternyata awal dari terikatnya setiap mahasiswa dengan aturan ini. Fakta sosial yang dijelaskan Durkheim ini, senantiasa kita temukan dalam kehidupan sehari – hari dimasyarakat dan menjadi perlu untuk kita pahami sebagai dasar menganalisis setiap fenomena yang ada.
Beberapa poin penting yang dapat dipahami dari paradigma ini adalah (1) Bersifat memaksa dari luar individu (2) Nilai, norma, dan aturan yang mengikat disahkan dan dipahami oleh setiap individu, dan (3) Proses sosialisasi dan internalisasi menjadi landasannya. Individu yang gagal atau tidak mampu melakukan dan mentaati aturan yang ada dapat dikatakan menyebabkan disfungsi dalam keteraturan sosial (social order). Segala bentuk nilai, norma, aturan, dan peraturan digunakan untuk menciptakan dan mengikat solidaritas yang ada dalam masyarakat.
Fakta Sosial, Penentu dari keberadaan Solidaritas Sosial
Setelah memahami apa itu Fakta Sosial, sebenarnya proyek panjang atau gagasan yang lebih jauh disampaikan oleh Durkheim adalah mengenai bagaimana kehidupan sosial masyarakat dan pengikatnya bagi individu. Baik yang bersifat material atau non-material, keduanya lahir berdasarkan realitas ‘objektif’ diluar individu. Tujuan nya untuk menciptakan social order (keteraturan sosial).
Fakta Sosial bersifat mengikat dan sebagai pengendali setiap individu atau masyarakat. Mengapa demikian? Menurutnya, struktur masyarakat mempengaruhi setiap cara bertindak dan perilaku aktor atau agen. Solidaritas dalam pandangan Durkheim dibagi menjadi dua, Organik dan Mekanik. Keduanya terjadi dan ditentukan oleh sejauh mana Fakta Sosial dibentuk dan dipahami oleh individu tersebut. Solidaritas jika kita melihatnya dalam konteks hari ini semakin melemah dan tidak mengikat dalam semua aspek kehidupan manusia. Sekali lagi asumsi ini saya sampaikan berdasarkan asumsi dalam pandangan Fakta sosial. Sebagai penutup, teori ini memang sudah lama dan banyak mendapatkan kritik, tetapi kehadirannya sebagai peletak dasar dalam kajian ilmu Sosiologi sangat besar dan masih ada beberapa relevansinya dengan hari ini.
Solidaritas Mekanis: Antara Masyarakat Patrimonial dan Kegagapan Wacana Kritis
Oleh: Hanan Radian Arasy
Saya, mulai dengan praktis bahwa Durkheim telah mati. Karena itu, mari kita cukil dan belah buah seorang yang telah mati tersebut yaitu sosiolog klasik yang memberikan kontribusi dalam bidang ilmu sosiologi berparadigma fakta sosial.[2] Sekiranya, sebelum mengharapkan sesuatu yang lebih dari sang penulis, maka pembaca dimohon untuk mengurangi ekspektasi tersebut. Apes! Bukan?
Dia-lah Emile Durkheim salah seorang yang terkategori sebagai salah satu dari trias suhu dalam grand narrative sosiologi klasik diantara peneruka lainnya yang menginginkan sosiologi menjadi sui generis dari bidang ilmu pengetahuan lainnya. Mengemukakan pendapat mengenai pentingnya pembagian solidaritas kedalam 2 kategori sehingga dalam menyelaraskan aras berfikir dari macro subject atau masyarakat, mampu merengkuh titik terang antara perbedaan tersebut yakni solidaritas mekanis dan organis. Namun, seperti yang telah dituturkan sebelumnya bahwa tulisan ini bukan untuk memuaskan desire of knowledge dari ketatnya metodologis atau blok keamanan verifikasi ilmiah karena pembaca yang nampaknya secara sukar didamaikan. jika, memang ternyata penulis adalah seorang pemalas. Maka, Oke BASA BASI!
Solidaritas Mekanis
Menjogrokan sembari mengulas pokok pembahasan mengenai solidaritas mekanis sebaiknya kita terlebih dahulu mengerti alasan mengapa Emile Durkheim menciptakan konsep Solidaritas Mekanis. Pada mulanya, Emile Durkheim memang lebih tertarik terhadap suatu dimensi statis maupun establisment ilmiah untuk mengurung masyarakat dengan pola integrative yang cenderung ajeg serta biasanya terjadi dalam masyarakat tradisional atau primitive kedalam karya-karyanya[3]. Ketertarikan tersebutlah, yang menjadi reason Durkheim untuk mampu menyelaraskan cita-citanya dalam menahkodai moral masyarakat dengan ilmu pengetahuan.[4]Sehingga diperlukan kategori dalam perbedaan yang menandai perubahan dalam masyarakat dari solidaritas yang mekanis ke solidaritas yang organis. Perlu digaris bawahi, bahwa kategorisasi tersebut bukan didasarkan atas analisa sosio spasial maupun territorial. Namun, Analisa tersebut dialaskan pada sebuah penggambaran sikap semangat kolektif atau collective consiousnesss[5] atau dengan kata lain sebagai suatu tanda yang sifatnya sosial dan terletak pada masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, Durkheim melihat Solidaritas Mekanis diindikasikan pada sebuah faktor similiarities (kesamaan,kekompakan atau kepadanan) yang sangat rigid dan berlaku pada ukuran kuantitas masyarakat yang menyeluruh dan biasanya ditandai dengan suatu tuntunan moralities atau konkritnya bisa kita lihat sebagai agama,tradisi,serta kebudayaan.[6]
Antara Masyarakat Patrimonial dan Kegagapan Wacana Kritis.
Yang menjadi problema ialah bagaimana paradigma fakta sosial dipandang sebagai sebuah ideology dari ilmu pengetahuan walaupun klaim mereka ialah netral serta objektif dalam suatu peta ideology.[7] Namun, pembahasan tersebut tidak akan diperuncing akar permasalahanya maupun dibahas pada tulisan ini, tetapi yang penting ialah bagaimana mempelajari teori strukturalist Durkheim sebagai sebuah fakta sosial, tidak membuat terjebak alam fikir kita dalam suatu kebuntuan teori yang nisbi terhadap suatu bentuk model integrative masyarakat tanpa menciptakan atau mempelopori sebuah ragi pembaharuan. Disinilah salah satu kelemahan cara pandang Durkheim sehingga patut untuk mewantikan bahwa solidaritas mekanis yang bercokol pada sebuah Masyarakat khususnya di Indonesia terjebak pada suatu model masyarakat Patrimonial. Penulis menyangsikan hal tersebut bermuara pada suatu kegagapan wacana kritis yang di redam atau di halau oleh tradisi maupun kebudayaan yang konservatif. Maka, tugas saya ialah mencoba meretas kebuntuan tersebut tanpa harus kabur dari belantara pemikiran Durkheim . Seperti yang telah diulas sebelumnya, solidaritas mekanis sangatlah terlihat sebagai suatu konsepsi yang bagi penulis terdapat suatu misconception karena memandang masyarakat cenderung statis. Karena pada dasarnya, kegagalan tersebut ialah suatu kelalaian cara pandang yang tidak menjelaskan power dan knowledge sebagai suatu hubungan. Maka, jangan heran ketika solidaritas mekanis yang diusung Durkheim gagal dalam menjelaskan subordinasi yang terjadi pada masyarakat patriarkis seperti yang terjadi didaerah-daerah kecil di Indonesia maupun bahkan didunia. Secara praktis, suatu afirmasi dari solidaritas mekanis merupakan suatu strategi ilmuwan dalam melakukan generalisasi yang berlebihan karena sekonyong-konyong atau Taken for Granted terhadap suatu model konsensus serta tradisional dalam dinamika ilmu pengetahuan.
Solidaritas Organik
Oleh: Ridho Arraditya
Solidaritas Organik adalah sebaliknya Mekanis, masyarakat yang ditandai oleh soldaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer & Goodman: 1995). Solidaritas organis merupakan tipe solidaritas yang menjawab kompleksitas kehidupan kota, dimana diperlukan lebih banyak pembagian kerja seperti direktur, manager, teknisi, penjual makanan jadi, penjual bahan mentah, dan lain-lain. Oleh karena spesifikasi tipe pekerjaan tersebut, kesadaran kolektif masyarakat terkikis dan lebih bersifat individualis.
Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dinamika ruang yang menaungi praktik sosial di atasnya, di ruang kota yang terbatas dan penduduk yang kian padat mengharuskan terciptanya bermacam pekerjaan baru sehingga masyarakatnya semakin terdiferensiasi. Menurut Durkheim, peningkatan pembagian kerja mengharuskan orang untuk saling melengkapi, dan bukannya berkonflik satu sama lain. Oleh karena itu, peningkatan pembagian kerja menawarkan efisiensi yang lebih baik, yang menyebabkan peningkatan sumber daya, menciptakan kompetensi diantara mereka secara damai. Kompetisi yang kurang dan diferensiasi yang tinggi memungkinkan orang bekerja sama dan sama-sama ditopang oleh sumber daya yang sama. Oleh karena itu, diferensiasi justru menciptakan solidaritas organis mengarah pada bentuk yang lebih solid dan lebih individual daripada masyarakat yang dibentuk solidaritas mekanis. Untuk itu, hukum yang terbentuk oleh solidaritas organis justru kontra-represif, ia bersifat restitutif.

Sumber: Dosenpendidikan.com
Totemisme

Sumber: Scoop.it
Karena Durkheim percaya bahwa masyarakat adalah sumber agama, dia terutama sangat berminat pada totemisme. Totemisme adalah sisstem agama dimana sesuatu, bisa binatang dan tumbuhan, dianggap sacral dan menjadi simbol klan. Durkheim memandang totemisme sebagai bentuk agama yang paling sederhana dan paling primitive dan percaya bahwa totemisme terkait dengan bentuk paling sederhana dari organisasi sosial. Durkheim berpendapat bahwa totem tak lain adalah representasi dari sebuah klan. Individu yang mengalami kekuatan sosoal yang begitu dahsyat ketika mengikuti upacara suku atau klannya akan berusaha mencari penjelasann atas pengalaman ini. Ia percaya bahwa upacara bersama itu sendirilah yang menjadi penyebabnya.
Catatan Kaki:
[1] Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 6.
[2]Ritzer,George. “Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda” (Depok:Raja Grafindo Press 2013).hlm.13
[3] Ritzer,George dan Douglas J. Goodman “Teori Sosiologi daj Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial PostModern”(Yogyakarta: Kreasi Wacana,2012)hlm.18-20.
[4] Ibid, Ritzer George.
[5] Ibid, Ritzer, George.
[6] Durkheim,Emile “The Division of Labour In Society”(New York : The New York Press,1984)hlm.43-63.
[7] Ibid, Ritzer, George
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 27 April 2017, Dibuat secara bersama - sama oleh Tim DKS.
0 notes
Text
Negeriku, Menjejak Kapitalisme Maju dan Ketimpangan Berkelanjutan: Sebuah Analisis Sosio-spasial dalam David Harvey
Oleh: M.Muslim Ridho Arraditya
Pada dasarnya sejarah dari masyarakat didasari dandapat dianalisa dalam 3 faktor utama, yaitu waktu, ruang, dan kekuasaan. Sayangnya, dalam disiplin-disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, ruang menjadi salah satu faktor yang sering terabaikan. Pemahaman sosial-keruangan mengungkap hal-hal yang meliputi ketiga faktor tersebut dalam fenomena kemasyarakatan, dan mengungkap secara mendalam praktik-praktik keruangan seperti pembangunan, perampasan lahan, serta interaksi sosial yang terjadi didalamnya. Ruang (juga waktu) tidak hanya lingkungan dimana manusia dan masyarakat berada, ia secara konstitutif membentuk organisasi sosial dan struktur yang berlaku diatasnya.
Ruang dan masyarakat adalah suatu hal yang resiprokal. Dunia sosial maka merupakan salah satu yang membuat ruang sendiri, entah itu ruang produksi, konsumsi, sirkulasi, representasi, rekreasi dan kesenangan, atau bermain dan imajinasi. Ruang diciptakan untuk memberlakukan, untuk mewujudkan dan untuk melambangkan mimpi, aspirasi dan prestasi masyarakat di setiap tahap perkembangan. Jenis ruang yang diproduksi dan dibuat memiliki konsekuensi untuk kuantitas dan kualitas hubungan sosial. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, didorong, dilarang dipengaruhi oleh desain, bentuk, ukuran, organisasi dan akhirnya mengkontrol bagaimana ruang dibatasi dan difungsikan.
David Harvey, seorang geografer-Marxist mencoba menganalisis dan mengkritisi praktik keruangan di era kontemporer ini. Teori-teorinya memberikan sumbangan pemahaman bagaimana ruang yang kita tinggali sekarang diproduksi oleh modal. Tujuan Harvey ialah untuk memetakan kondisi mutakhir dari kapitalisme global dan peran yang mungkin dimainkan oleh “imperialisme” baru didalam kapitalisme global. Ia berusaha menyingkap transformasi-transformasi apakah yang ada dibalik semua gejolak dan perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat di permukaan ini.

Sumber: Thefamouspeople.com|David Harvey
Ruang dalam Harvey
Harvey mengembangkan teori “the production of space” tentang peran ruang dalam akumulasi kapita dan sirkulasi kapital. Artinya, akumulasi modal berlangsung dalam konteks historis dan geografis yang menimbulkan bentuk-bentuk spasial tertentu. Pada inti dari analisis Harvey ia menjelaskan ruang (dan waktu) di mana proses material dan hubungan sosial dianggap penting untuk melihat atau mempertanyakan urbanisasi. Menurut Harvey, baik ruang dan waktu harus dianggap sebagai kategori dasar dari eksistensi manusia. Mereka tidak dapat dipisahkan dari proses material. Untuk memahami ruang (dan waktu) maka, menurut Harvey, harus menyelidiki proses material dan praktik yang membentuk dasar reproduksi kehidupan sosial. Setiap mode produksi maka akan menghasilkan konsepsi sendiri dari ruang dan waktu. Harvey menegaskan bahwa konsensus yang ada saat ini berada didalam ruang dan waktu dan dibangun secara sosial. Perlu ditekankan, sebagaimana menurut Harvey, perspektif materialis ini berguna untuk menganalisis peran ruang dan waktu dalam kehidupan sosial.
Ruang kemudian, menurut Harvey, dipahami sebagai “diproduksi, dibentuk, dicetak dan digunakan dalam zaman dan masyarakat tertentu. Bentuk-bentuk ruang yang membutuhkan waktu tidak hanya mewakili cara produksi tetapi melambangkan aspirasi budaya suatu masyarakat tertentu pada waktu tertentu serta tatanan sosial yang ada.[i] Ruang geografis maka menurut Harvey tidak boleh dipisahkan dari masyarakat tetapi harus dipahami sebagai produk dari hubungan sosial dan praktek sejarah, karena mereka menjadi tertanam dan diinternalisasi dalam bentuk spasial dan struktur. fokus asli Harvey, proyeknya, materialisme historis-geografis, adalah untuk menganalisis peran ruang dibawah sistem kapitalisme.
Apa yang Harvey kerjakan adalah spasialisasi konsep-konsep Marx melalui pertimbangan produksi ruang, khususnya penciptaan ‘lingkungan’ kota sebagai kondisi yang diperlukan untuk, atau produk dari proses akumulasi, sirkulasi dan konsumsi kapital. Proyek Harvey kemudian adalah untuk mengembangkan ‘paradigma produksi’ Marx untuk memasukkan produksi ruang sebagai unsur penting dalam produksi dan reproduksi kehidupan sosial. Sebagaimana menurutnya:
Capital is a process and not a thing. It is a process of reproduction of social life through commodity production, in which all of us in the advanced capitalist world are heavily implicated. Its internalised rules of operation are such as to ensure that it is a dynamic and revolutionary mode of social organisation, restlessly and ceaselessly transforming the society within which it is embedded. The process masks and fetishises, achieves growth through creative destruction, creates new wants and needs, exploits the capacity for human labour and desire, transforms spaces, and speeds up the pace of life. It produces problems of over-accumulation for which there are but a limited number of possible solutions. (Harvey, 1990: 343)
Pada intinya, Harvey berupaya untuk memberikan pandangan ekonomi-politik ruang dibawah kapitalisme dan wawasan yang penting untuk analisis produksi, lokasi dan distribusi ruang tertentu dalam era tertentu (kapitalisme industri). Ini berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis produksi ruang perkotaan sebagai bentang sosial dimana ruang reproduksi selalu dibentuk dan dicetak oleh perjuangan kelas dan konflik. Menurutnya:
Ideas about environment, population, and resources are not neutral. They are political in origin and have political effects” (Harvey, 1977: 237).
Ruang Kapitalisme Industri
Dengan demikian Harvey berpendapat bahwa akumulasi kapital menuntut bentuk perkotaan yang memfasilitasi ekstraksi surplus value lebih efektif dengan mengorganisir suatu bentuk spasial dari perkotaan sebagai pusat produksi, sebagai lokasi untuk konsumsi, seperti memfasilitasi peredaran modal dan untuk reproduksi tenaga kerja. Hal ini kemudian menjadi alasan Harvey untuk mencoba untuk mengembangkan ekonomi-politik ruang sebagai sarana untuk mengembangkan analisis Marx tentang kapitalisme untuk memberikan penjelasan bagaimana bahwa kota menjadi ruang-kunci kapitalisme modern yang memerlukan hubungan sosial, struktur dan proses. Itulah bagaimana kota-kota menurut Harvey merupakan bentuk spasial sekaligus produk dari kapitalisme.
Secara Krusial, menurut Harvey – yang bertolak dari Marx – kebutuhan modal industri (untuk meminimalkan biaya sirkulasi, memaksimalkan ketersediaan tenaga kerja, akses ke pasar dan bahan baku, dll) memerlukan lokasi produksi yang terkonsentrasi secara rasional, dan semua yang berhubungan kegiatan dalam kota-kota besar. Kapitalisme mendominasi urban dengan memproduksi ruang dan struktur ruang yang diperlukan untuk menghasilkan surplus value yang secara bersamaan, mengarah ke pembangunan ‘lingkungan’.[ii]
Lagi-lagi mengembangkan teori Marx, Harvey Marx berusaha menunjukkan bagaimana kebutuhan akumulasi modal memiliki konsekuensi akan investasi dan penciptaan infrastruktur fisik dan sosial, mulai dari perkotaan maupun di daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan alat-alat produksi. Hal ini kemudian menyebabkan terciptanya – yang dalam bahasa Harvey disebut sebagai – ‘ekonomi ruang’.
Problema Overakumulasi
Kapitalisme mampu bertahan hidup sedemikian lama melewati berbagai krisis dan reorganisasi serta lolos dari prediksi-prediksi suram dari kalangan kiri (maupun kanan) yang meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh tak lama lagi. Daya tahan kapitalisme ini sungguh merupakan suatu misteri yang menuntut penjelasan. Salah satu yang berusaha memberikan penjelasan itu, adalah Lefebvre yang beranggapan bahwa dirinya telah berhasil menemukan kunci penjelasannya melalui pernyataan terkenalnya bahwa kapitalisme bisa bertahan hidup lewat penciptaan perluasan ruang (production of space),[iii] namun sayangnya Ia gagal untuk menjelaskan secara tepat bagaimana atau mengapa hal itu bisa demikian.
Dalam konteks ini, Harvey telah mengusulkan suatu teori mengenai ‘spatial fix’ (atau lebih tepatnya ‘spatio-temporal fix’) terhadap kontradiksi-kontradiksi internal yang rentan-kritis dalam akumulasi kapital.[iv] Bertolak dari Marx, inti utama dari argument ini terkait dengan tendensi kronis dalam kapitalisme mengenai tendensi kejatuhan tingkat laba untuk menciptakan over akumulasi. Krisis semacam itu biasanya ditandai dengan terjadinya surplus kapital (dalam bentuk komoditi, uang atau kapasitas produksi) dan surplus kekuatan tenaga kerja yang mengiringinya, dibarengi dengan ketiadaan cara-cara untuk menggunakan surplus-surplus itu secara menguntungkan.
Surplus-surplus semacam itu secara potensial bisa diserap lewat (a) pengalihan temporal dalam bentuk investasi dalam proyek-proyek kapital jangka panjang atau belanja-belanja sosial (seperti pendidikan dan riset) yang akan menunda masuknya kembali nilai-nilai kapital ke dalam sirkulasi kapital, (b) pengalihan spasial melalui pembukaan pasar-pasar baru, kapasitas-kapasitas produksi yang baru, dan sumber daya, peluang-peluang sosial dan tenaga kerja yang baru, atau (c) kombinasi dari keduanya.[v]

Sumber: rizalakbar.iaitfdumai.ac.id
Sirkuit Kapital
Sirkuit Kapital merupakan upaya pendekatan Harvey menjelaskan hubungan antara relasi-relasi sosial dan ruang yang dibangun dibawah atap kapitalisme. Ia mengembangkan mode produksi Marx dan membagi praktik sosial-keruangan dalam era kontemporer kedalam tiga sirkuit, yakni primer, sekunder, dan tersier. Bertolak dari Marx (lagi), Harvey berpendapat bahwa persaingan tanpa regulasi antara kapitalis menyebabkan krisis overakumulasi dalam ‘sirkuit premier’ modal (sektor industri) dan penurunan dalam realisasi nilai lebih (surplus value).
Salah satu cara untuk mengatasi krisis periodik overakumulasi dan mencapai kondisi yang lebih menguntungkan untuk produksi nilai lebih adalah untuk menginvestasikan modal atau ‘mengalirkannya’ ke sirkuitlain, yakni sirkuit sekunder dan tersier. Maksud Harvey adalah bahwa investasi di sirkuit sekunder dan tersier menjadi menguntungkan bagi pemodal untuk berinvestasi di daerah yang memiliki potensi untuk menghasilkan kondisi yang akan membantu akumulasi dan keuntungan berikutnya, serta memastikan reproduksi mereka sebagai kelas dominan dalam masyarakat. Dengan demikian penting untuk memperjelas bagaimana Harvey mendefinisikan ‘sirkuit kapital’ sebagai alat untuk menyelidiki pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang merupakan lingkungan buata, serta bentang perkotaan di bawah kapitalisme.
Untuk melihat sirkuit kapital secara komprehensif mari kita lihat skema sirkuit kapital berikut ini:
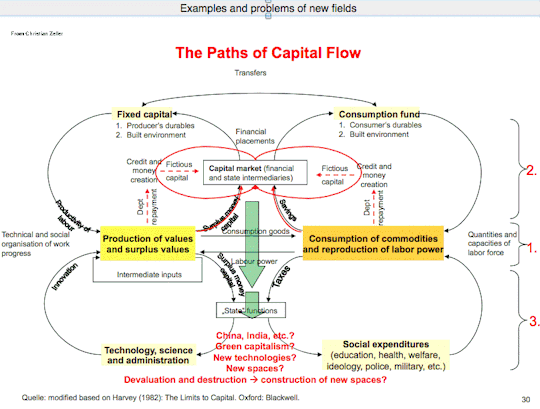
Sirkuit primer untuk Harvey adalah semua sarana yang dibuat untuk mengekstrak nilai surplus. Ini termasuk perpanjangan hari kerja atau reorganisasi proses kerja yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja ini. Organisasi dari pembagian kerja dan investasi dalam barang-barang modal tetap seperti mesin juga termasuk dalam sirkuit primer kapital.
Dalam sirkuit sekunder, arus terbagi menjadi kapital tetap untuk produksi (pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan dsb) dan penciptaan suatu dana konsumsi (consumption fund) sebagai misal perumahan. Pemanfaatan gabungan seringkali mungkin dilakukan (jalan tol bisa dimanfaatkan baik untuk aktivitas-aktivitas produksi maupun konsumsi).[vi] Porsi-porsi tertentu kapital yang mengalir ke sirkuit sekunder ditanamkan dalam bentuk tanah dan menjadi aset-aset bank yang menempati suatu tempat – suatu lingkungan yang dibangun untuk produksi dan konsumsi (segala hal mulai dari kawasan-kawasan industri, pelabuhan dan bandara, jaringan-jaringan transportasi dan komunikasi untuk sistem pembuangan limbah dan air, perumahan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah). Investasi-investasi ini biasanya menjadi suatu inti fisik dari suatu kawasan. Ringkasnya, investasi-investasi itu memainkan suatu peran fundamental di dalam produksi regionalitas. Sederhananya, investasi-investasi itu lebih dar sekedar suatu sektor minor dalam ekonomi. Investasi-investasi tersebut bisa dan memang menyerap sejumlah besar kapital dan tenaga kerja, terutama, sebagaimana kita lihat, ketika terjadi ekspansi geografis. Harvey memperjelas:
Fixed capital in the built environment is immobile in space in the sense that the value incorporated in it cannot be moved without being destroyed. Investment in the built environment therefore entails the creation of a whole physical landscape for purposes of production, circulation, exchange and consumption. We will call the capital flows into fixed asset and consumption fund formation the secondary circuit of capital. (Harvey, 1978: 106).
Di sirkuit tersier surplus kapital diarahkan ke belanja-belanja sosial (social expenditures) dan riset serta pengembangan, maupun pendidikan. Maka, menurut Harvey:
comprises, first, investment in science and technology (the purposes of which is to harness science to production and thereby to contribute to the processes which continuously revolutionise the productive forces in society) and second, a wide range of social expenditures which relate primarily to the processes of reproduction of labour power. The latter can usefully be divided into investments directed towards the qualitative improvement of labour power from the standpoint of capital (investment in education and health by means of which the capacity of the labourers to engage in the work process will be enhanced) and investment in the co-optation, integration and repression of labour by ideological, military and other means. (Harvey, 1978: 108)
Begitulah produksi ruang dibawah atap kapitalisme dalam pandangan Harvey melalui kacamata sirkuit kapital ini. Hal ini memiliki relevansi yang melekat pada praktik pembangunan kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta, yang mana akan saya bahas dan jelaskan lebih lanjut dalam diskusi kali ini. Seperti halnya banyak teoretisi kritis lainnya, Harvey menawarkan langkah praxis pengentasan ketimpangan berkelanjutan ini dalam Hak atas Kota.
Hak Atas Kota

Sumber: twitter.com/ourcity
Terminologi hak atas kota ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh sosiolog Prancis, Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre, hak atas kota tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai hak untuk bersih, bebas polusi, bebas macet, tanpa gedung-gedung pencakar langit, langit cerah dengan awan putih yang menghiasi kanvas biru raksasa nan eksotik. Jika seperti itu makna dari right to the city, maka kita sebenarnya sedang membangun sebuah ilusi, karena ingin menyelesaikan problem kekinian dengan panduan atau rujukan ke masa lalu yang sebenarnya tidak kompatibel. Konkretnya, menyelesaikan banjir di Jakarta dengan merujuk pada master plan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda, adalah sebuah kekonyolan intelektual.
Bagi Lefebvre (Sugranyes and Mathivet 2010), hak atas kota berarti hak terhadap kota itu sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian. Dengan pengertian ini, maka hak atas kota itu tidak sekadar dimaknai bahwa warga miskin berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, misalnya, tapi juga warga miskin tersebut memiliki hak untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut. Singkatnya, penduduk miskin yang menetap di kota tersebut bukan hanya pelaku pasif dari sebuah perubahan, tapi aktif terlibat dalam proses perubahan itu.[vii]
Dengan demikian, titik tolak dari hak atas kota, adalah partisipasi rakyat terhadap pembangunan kotanya. Menurut Harvey, hak atas kota itu bukanlah sebuah inisiatif atau kerja individu dan kelompok, tapi lebih merupakan inisiatif dan kerja kolektif dari rakyat. Mengapa partisipasi rakyat merupakan tolak-ukurnya? Di sini kita mesti menempatkan makna right to the city ini pada konteks pembangunan kota yang neoliberalistik selama beberapa dekade terakhir. The right to the city merupakan cap atau simbol dari sebuah perjuangan melawan neo-liberalisme. Right to the city merupakan sebuah perspektif politik baru untuk melawan sebuah proses pembangunan perkotaan ala neoliberalisme, seperti privatisasi ruang perkotaan, komersialisasi penggunaan kota, mendominasinya kawasan-kawasan industri dan perdagangan. Upaya alternatif pembangunan dan distribusi perencanaan secara demokratis-berlawanan dari arah pembangunan kekinian diyakini oleh Harvey sebagai jalan keluar atas ketimpangan ruang.
Kebon Jeruk, April 2017
*M. Muslim Ridho – adalah Pemuda gondrong, kurang tidur, dan sedang menempuh pendidikan di Program Studi Sosiologi Pembangunan, Universitas Negeri Jakarta.
Catatan Kaki:
[i] Andrzej Zieleniec, Space and Social Theory (London: Sage Publication, 2007), hlm. 99
[ii] Ibid. hlm. 101-102
[iii] H. Lefebvre, The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relation of Production, terj. F. Bryant (New York: St Martin’s Press. 1976).
[iv] David Harvey, Imperialisme Baru (Yogyakarta dan Jakarta: Resist Book dan Institute for Global Justice, 2010), hlm.98
[v] Ibid. hlm. 121
[vi] Ibid. hlm. 123
[vii] Coen Husain Pontoh, Hak Atas Kota (Indoprogress, 2013)
Daftar Pustaka:
Harvey, David. 2010. Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer. Yogyakarta dan Jakarta: Resist Book dan Institute for Global Justice
Prasetyo, Arif. 2016. Skripsi Pembangunan Mall di Jakarta 2007-2013: Tinjauan Kritis Mode Produksi Ruang Lefebvre. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi
Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Zieleniec, Andrzej. 2007. Space and Social Theory. London: Sage Publication
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 13 April 2017.
0 notes
Text
Hoax dan Simulacra Media
Oleh: Hanan Radian Arasy
Hari ini, siapa yang tidak mengenal media khususnya internet? kebanyakan dari kita tentu memiliki instrument baik berupa smartphone ataupun gadget lainnya untuk mengakses sebuah layanan internet sehingga mempermudah dan menyederhanakan ukuran kuantitas jarak nampak begitu dekat. Hubungan relasi sosial dan pekerjaan dengan adanya internet membuat kita semakin mudah serta tetap terhubung walau jarak menghalangi kita. Namun, pertanyaanya ialah apakah dengan kehadiran internet apalagi media sosial benar-benar berdampak pada efisiensi didalam essensi kehidupan kita yakni kerja dan interaksi? atau sebenarnya kita termanipulasi dalam sebuah fantasi homo hoaxicum? Atau bahkan internet sebagai gelombang pasang informasi pada Generasi Milleniel berujung kesadaran semu?

Sumber: jiyongi-yeoja.blogspot.co.id
Homo Hoaxicum
Mengapa kita memilih jalan aman walau keliru untuk berbohong? mengapa hasrat pencapaian kita berubah dari waktu ke waktu? Secara leksikal Istilah Homo Hoaxicum berasal dari bahasa yunani yang berarti homo atau manusia dan Hoaxicum dari kata hocus pocus dan bertransformai menjadi hoax yang berarati berkata dusta. dititik inilah, kita mengetahui bahwa bagaimana manusia didalam struktur sosial (baca : suatu aturan yang mengikat) di masyarakat atau konteks yang melingkupinya memiliki kemampuan untuk tidak mengatakan hal yang sesungguhnya atau kejujuran. Hemat saya, ‘berbohong’. Meminjam term Michael Foucault seorang filosuf berkebangsaan perancis yang mendefinisikan kehidupan manusia untuk mengabaikan,mengabstraksi,membuat topeng,menyembunyikan atau memproduksi kebenaran yang hanya versi dirinya sendiri[1].
Menjadi masalah ialah bagaimana ketika kita membayangkan bahwa sifat dasar manusia yang mampu berdusta itu ditopang oleh suatu arus informasi yang selalu menuntut pembaharuan dari waktu ke waktu. Secara kumulatif, bahwa kebenaran selalu diproduksi-dari waktu ke waktu beriringan dengan pembaharuan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ialah apakah ada kebenaran yang hakiki? tentu saja tidak. karena segala kebenaran adanya ialah politisasi yang sifatnya kontitusional (Lihat : Derrida,1978:230). dititik inilah kesimpulan bahwa kehidupan kita didunia ialah untuk terus berjalan dari satu titik ke titik lainnya untuk terus berbohong serta menggapai suatu kebenaran yang tidak final!
Simulacra Media
Kita telah berada pada zaman simulasi! begitulah, isi orasi Jean Baudrillard seorang sosiolog ekstrem di era 1980-an.[2] Menurutnya, kita tidak lagi didominasi oleh nilai-nilai produksi seperti kerja. Namun hari ini masyarakat telah dikontrol oleh dominasi media,model sibenetika,sistem pengendalian,komputer,hiburan,industry pengetahuan[3] dan lain sebagainya. Baginya, di zaman simulasi yang beriringan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital tiada suatu hal yang riil atau jangan-jangan segalanya ialah kebohongan dan kebenaran itu sirna seluruhnya[4] Penjelasan baudrillard mengenai hal tersebut ialah pada tahap simulacra dan hyperreality. Saya ambil contoh ketika kita sedang menonton sinetron kita ikut larut sedih kedalam jalan cerita yang dibuat oleh sutradara. Padahal, sinetron hanyalah cerita fiktif. Dititik itulah suatu pergeseran antara yang riil dan yang semu lebur menjadi satu dengan kata lain kabur sehingga kita tidak bisa membedakanya. Ulang dan pinjam Baudrillard, simulacra media dan hyperrealitas.[5] Di titik ini mari kita bayangkan, berapa waktu luang yang kita gunakan untuk mengoperasikan televisi? berapa waktu luang yang kita gunakan untuk menggengam dan mengoperasikan telepon genggam? berapa waktu luang yang kita gunakan untuk berselancar didalam dunia maya atau internet? inilah zaman kebohongan dan kita larut dalam kebohongan tersebut.
Kembalinya yang sosial

Sumber: rahmamutihidayah.wordpress.com
Pada dasarnya, internet diciptakan untuk memudahkan manusia dan membuat bumi lebih kecil. namun kenyataanya dunia memang lebih kecil tanpa internet. sebelum adanya internet, manusia berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung didalam kehidupanya masing masing atau didalam kehidupan bermasyarakatnya. kesadaran manusia dalam pembangunan secara matang tertuju pada suatu tatanan material kehidupan nir-maya. Maka, perlu dipertegas bahwa realitas sosial adalah kunci untuk keluar dari pelbagai urusan dunia yang mengaburkan batas-batas yang riil dan yang semu tersebut. kembalinya yang sosial dimaknai bahwa kehidupan maya dalam media massa dan sosial hanyalah bersifat sekunder bukan malah menggantikan aktivitas primer praktik kehidupan sosial kita. Karena perubahan dan kebermanfaatan kita tidak bisa diukur dan ditukar hanya dengan basis mikroelektronik bukan? kita membutuhkan kenyataan untuk berinteraksi antar sesama namun bukan berarti kita tersubordinasi oleh teknologi yang pada mulanya kita ciptakan untuk mempermudah kita. Karena yang hakiki tidak akan pernah ada dalam sosial media ataupun media massa. kita tentu tahu, bahwa kebenaran di medium elektronik seperti analogi mie instan; lama kelamaan akan melar dan tidak bisa kita rasakan lagi enaknya. Bahkan, berdampak pada kesehatan kita. Ingatlah tuan-tuan dan nona-nona, bahwa cinta bukan sekedar basis mikroelektronik atau emoji berserakan….
Jakarta, April 2017.
Catatan Kaki:
[1] Michael Focault, “Discipline and Punish : The birth of prison”(London : Penguin,1991) hlm,194.
[2] George Ritzer, “Teori Sosiologi dari klasik hingga Postmodern” (Yogyakarta : Kreasi Wacana,2012) hlm,678-679.
[3] ibid
[4] ibid
[5] Ibid
Daftar Pustaka:
Foucault,Michael. “Discipline and Punish : The birth of prison” (1991,London:Penguin)
Ritzer,George. “Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik hingga Perkembangan Teori Sosial Postmodern” (2012Yogyakarta:Kreasi Wacana)
[*] Penulis adalah pelajar abadi yang gemar nyemil-nyemil lucu apalagi minum-minum unyu di Kedai Literasi Gerakan Aksara, saat menulis senang mendengarkan lagu Folk Jazz/Post-Rock yang didendangkan oleh band indie asal Indonesia yaitu The Trees and The Wild. Rutinitas sehari-harinya sebagai mahasiswa di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dan Bergiat aktif di Komunitas Diskusi Kamis Sore. Serta berjejaring dengan Jaringan Mahasiswa Sosiologi Se-Jawa dan Bangkok International University of Thailand (Forum EP’s) dan Terdaftar kedalam International Journal of žizekian Studies dengan notasi [HRA].
Surat Menyurat: [email protected]
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 6 April 2017.
0 notes
Text
Sosiologi (Dan) Sastra: Sebuah Telaah Kemanasukaan Atas Realitas Dan ‘Realitas’
Oleh: Tyo Prakoso

Sumber: azwarsutanmalaka.wordpress.com
/1/
JIKA SAMPEYAN beranggapan bahwa sastra lebih baik ketimbang wahana tong setan di pasar malam dan benda bernama deodoran—dus karenanya Sampeyan memandang sastrawan lebih mulia ketimbang pengendara tong setan atau buruh pabrik, maka sebaiknya Sampeyan sudahi saja membaca tulisan ini, jika Sampeyan tidak ingin terserang ayan tiba-tiba, dan siuman menjadi anggota dewan, dan kembali semavut dan tak pernah kembali bangun lagi.
Lekaslah sobek dan uwel-uwel kertas ini, dan masukkan ke dalam mulutmu. Lalu kunyahlah sebanyak tiga puluh tujuh kali dengan gigi geraham dan taringmu secara bergantian di mana saban satu kali kunyahan diharuskan merapal nama-nama orang yang pernah menyakitimu. Kemudian telanlah dengan dorongan air liurmu. Lalu tunggu beberapa saat: (1) maka saya akan menempelengmu—sebagai wujud solidaritas terhadap pengendara tong setan atau buruh pabrik yang Sampeyan lecehkan pekerjaannya. (2) Saya juga akan menginjak-injak buah zakarmu—sebagai wujud solidaritas, bahwa Sampeyan tahu, menjadi pengendara tong setan itu tidak gampang, meski tidak ada aturan yang mengharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuknya dan musti bersaing dengan aneka wahana-hiburan yang lebih modern, olehnya tidak berpenghasilan memadai untuk sekedar hidup selama tiga puluh hari dalam sebulan dan membiayai satu pasangan hidup dan dua buah hati—dan supaya Sampeyan juga paham, memangnya siapa sih yang mau jadi buruh pabrik dengan 10 jam kerja dan menghasilkan berkardus-kardus deodoran dalam satu hari kerja tapi hanya dibayar sepersekian dari apa yang sudah dihasilkan, dan selalu dijadikan kambing-hitam bila macet karena berdemo menuntut hak sebagai buruh pabrik untuk menolak perbudakan modern (outsourching) dan upah murah. Kalau bukan bangsat, apa namanya?
Sampai di sini, apa Sampeyan tetap beranggapan sastra dan sastrawan lebih baik dan mulia?
/2/
BILA SEBUAH karya sastra cerita pendek, misalnya ditulis karena seseorang punya sesuatu yang hendak disampaikan kepada orang lain dan berkaitan dengan realitas yang melingkupinya semisal, galau dan menangis bombai karena mantan kekasihnya ingin menikah dan apa yang hendak dikatakannya itu dikirim ke redaktur untuk diseleksi, disunting dan kemudian ditayangkan misalnya ke Kedai Literasi @gerakanaksara, tentu saja dengan harapan dibaca khalayak ramai, maka ada sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab: kenapa musti menulis sastra? Kenapa ia tak menulis reportase jurnalisme atau risalah atau surat pembaca?
Hemat saya, deret pertanyaan di atas membawa kita pada persoalan klasik dan pelik, yakni sastra dan realitas—secara filosofis dan esensial, ialah sastra hadir di tengah masyarakat, olehnya bersinggungan dengan realitas dan ‘realitas’ yang ditampilkan di dalam sastra. Catatlah saban kata ‘realitas’ yang tertulis disertai dengan tanda kutip (‘’) itu merujuk pada kenyataan yang coba ditampilkan melalui teks (sastra), sedangkan realitas tanpa tanda kutip (‘’) ialah kenyataan an sich yang dihadapi seseorang dalam lingkup sosialnya.
Oleh karena itu, izinkan saya berusaha untuk mendedah persoalan sastra dan sosiologi. Jika di sini saya gunakan istilah ‘sosiologi’, itu bukanlah karena hanya sosiologi yang bersentuhan dengan realitas, melainkan karena saya ingin mempersoalkan-cum-mempertanyakan, meminjam konsep imperatif kategoris-nya Kant; antara sastra dan yang-bukan sastra ketika dihadapkan vis a vis dengan realitas—atau dengan jalan lain, saya berusaha menampil persinggungan dikotomi antara fakta dan fiksi dalam pemahaman bahwa sastra dibangun dari fiksi, dan yang-bukan sastra (semisal hasil kajian atau penelitian sosiologis) tidak.
Adalah sebuah hal yang sia-sia bila kita berusaha untuk mendefinisikan sastra. Guru besar sastra dan orang yang memiliki peran besar dalam upaya membuat garis narasi kanonisasi sastra modern Indonesia, A. Teeuw, pun mengakui hal tersebut. “Secara intuisi kita semua sedikit banyaknya tahu gejala yang hendak disebut sastra, tetapi begitu kita coba membatasinya, gejala itu luput lagi dari tangkapan kita,” tulis Teeuw (Teeuw, 2013:19—miring oleh penulis). Namun bagaimanapun, kiranya perlu membuat batasan yang sumir, yakni sastra ialah apa yang tertulis—dus lawan dari apa yang lisan. Setiap batas itu tentu ambivalen, memang. Karena banyak apa yang tertulis tapi tetap tak bisa masuk ke dalam apa yang kita kategorikan sebagai sastra. Meski begitu batasan tersebut dapatlah membantu kita untuk menerka bahwa sastra melulu berkaitan dengan keberaksaraan—sebagai lawan dari keberlisanan.
Dengan demikian, inilah hal utama yang saya persoalkan: (1) sastra hadir secara vis a vis dengan realitas. Di saat yang bersamaan, (2) sastra merupakan realitas itu sendiri—sebagai produk budaya populer dalam sistem kapitalisme, olehnya diciptakan sebagai komoditas yang pada dirinya terdapat nilai-tukar dan nilai-guna—karena penulis sastra pun ialah bagian dari realitas, ia berusaha untuk meresponnya dalam proses alienasi-aktualisasi dengan cara (3) menghadirkan ‘realitas’ di dalam tulisannya—tentu ada realitas di dalam sastra, bernama ‘realitas’. Yang terakhir inilah yang menjadi titik-persoalan dalam tulisan ini. Sebab, dengan argumen bahwa ‘realitas’ berbeda dengan realitas an sich. ‘Realitas’ telah terkondisikan dengan proses-kreatif seorang sastrawan dalam menghasilkan tulisannya.
Sampai di sini, saya rasa kita bisa memahami pertanyaan di atas perihal mengapa seseorang menulis sastra—bahwa jawabannya ialah sastra merupakan satu cara dari sekian banyak cara untuk menghadirkan realitas ke dalam teks—kita sebut ‘realitas’. ‘Realitas’ itu merupakan tawaran oleh sastrawan guna berdialog dengan ‘realitas’-‘realitas’ yang lain dan juga realitas an sich itu sendiri, tentu saja. Oleh sebab teks tersebut menampilkan ‘realitas’ hasil kreatif sastrawan—tentu di sana ada ‘ideologi’, ‘imajinasi’, ‘harapan’, ‘gugatan’, dst… dkk… yang memantulkan pikiran sastrawan tersebut sebagai anggota masyarakat dari realitas yang melingkupinya. Inilah hubungan osmosis antara realitas dan sastra yang dimaksud.
Maka oleh sebab itu, realitas an sich menjadi titik-tolak, terminus a quo, dan sekaligus titik-tuju, terminus ad quem, untuk kemudian ‘realitas’ terhadirkan berkat kerja-kerja kreatif-ideologis seorang sastrawan. Dalam kaca mata demikianlah, hemat saya, sastrawan sama tapi tak serupa dengan pengendara tong setan atau buruh pabrik di atas. Karena apa yang dihasilkan oleh sastrawan ialah bagian dari realitas itu sendiri—setara dengan debar-ketakutan ketika mengendarai tong setan atau aroma mint deodoran—sebagai nilai-guna yang kemudian menjadi nilai-tukar karena teringkus dalam sistem kapitalisme. Inilah satu dari sekian alasan saya mengapa mengatakan bahwa sastrawan tidaklah lebih baik ketimbang pengendara tong setan atau buruh pabrik.
Sampai di sini saya harus katakan, bahwa untuk mendefinisikan apa yang dipaparkan di atas, saya meminjam kosakata bahasa Jawa, yakni kata Pasemon—yang, kira-kira, berarti sebuah siasat. Dapatlah dikatakan sastra adalah pasemon. Artinya pilihan menulis sastra (dus, alasan mengapa bukan-sastra, tentu saja) ialah sebuah pasemon seorang sastrawan ketika berhadapan vis a vis dengan realitas an sich. Bahwa pada sosok sastrawan hal tersebut membuncah. Karena itulah frase sosiologi dikaitkan di sini.
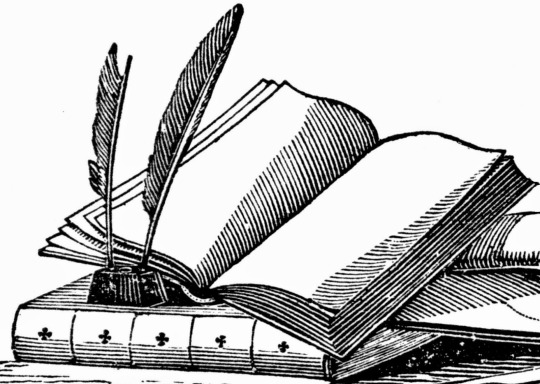
Sumber: http://dedd157.blogspot.co.id
/3/
Pada 1978, Sapardi Djoko Damono penyair-cum-akademisi sastra Universitas Indonesia, memperkenalkan apa yang disebut ‘Sosiologi Sastra’ melalui bukunya yang berjudul Sosiologi Sastra dalam sejarah kesusastraan modern Indonesia—dus, upaya mendedah teks sastra dengan pendekatan sosiologi.
Menurut Sapardi, karena sastra tidak jatuh dari langit, tetapi diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, dihayati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada tiga hal yang terlibat dalam proses tersebut, yakni sastrawan, karya sastra, dan pembaca. Sastrawan dan pembaca adalah anggota masyarakat—merupakan salah dua komponen utama dalam sosiologi sebagai ilmu. Mereka terikat oleh kelompok sosial tertentu menyangkut pendidikan, agama, adat istiadat, dan segenap lembaga sosial yang melingkupinya. Mereka kita anggap memiliki kaitan-kaitan—kalau tidak boleh disebut keterikatan—dengan konsep-konsep seperti teritorialisme, primordialisme, sektarianisme, dan isme lainnya yang merujuk pada kesepakatan (konsensus) hidup bersama dalam lingkup sosial.
Sastrawan dan karya sastra dan (khalayak sidang) pembaca tercakup dalam masyarakat—semua itu membentuk struktur kesusastraan yang sekaligus menjadi substruktur masyarakat. Lantas, acapkali dalam masyarakat terjadi perubahan—yang memang selalu terjadi demi keberlangsungan keberadaannya karena itu sebuah keniscayaan—semua unsur dalam strukturnya juga akan mengalami perubahan. Berdasarkan situasi demikian Sosiologi Sastra mendekati karya sastra.
Lebih lanjut, karena sastra berusaha membidik hal-ihwal yang jarang atau mungkin tidak terpahami oleh ilmuwan yang menempatkan manusia sebagai objek keilmuwannya—dan terdiskreditkan dengan frase hanya fiksi, misalnya. Olehnya, Sosiologi Sastra menawarkan sebuah siasat untuk hal tersebut. Setidaknya bila kita sepakat bahwa penyelidikan yang dilakukan terhadap struktur masyarakat tertentu, dan penyelidikan tentang tingkah-pola yang timbul dalam struktur tersebut, telah terbukti memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada kita. Pun bahwa sastra memiliki sumbangan berharga, itu betul, tentu saja—ketika mampu mengangkat aspek sosial manusia. Karena hanya sastrawan jebul yang gagal menyusup dalam alam kesadaran sosial masyarakatnya—sebab dari sana lah konsepsi dan ide kreatif sebermula. Dengan pra-posisi bahwa sastrawan yang gak jebul-jebul amat pun tentu saja menyumbangkan pemikiran di dalam karyanya ke dalam kehidupan manusia berhadapan dengan realitas an sich, dalam situasi demikianlah Sosiologi Sastra bekerja.
Namun, perkara Sosiologi (dan) Sastra, andai kata yang dipersoalkan ialah ‘ilmiah’ atau tidak, saya enggan menanggapinya. Yang menarik bagi saya ialah cara kerja keduanya (sastra dan sosiologi). Kita mafhum bahwa keduanya memiliki bangunan filsafatnya masing-masing sehingga ia disebut sebagai ilmu (sastra sebagai ilmu, dan sosiologi sebagai ilmu). Yang perlu disoroti—dalam hal membicarakan sosiologi sastra—ialah objek kajiannya, yakni manusia dan dalam lingkup sosialnya.
Perbedaan mendasarnya ialah sosiologi mencoba membidik realitas, sedangkan sastra membidik ‘realitas’. Artinya, sosiologi mencoba menelaah manusia dalam lingkup-sosialnya—dan sastra mencoba menangkap pantulan realitas yang dihadirkan oleh penulis di dalam karyanya, ‘realitas’—karena sastrawan ialah bagian dari realitas (objek dalam kajian sosiologi), karena apa yang dihadirkan oleh sastrawan dalam bentuk teks ialah ‘realitas’—sebagaimana sudah saya dedah di bagian sebelumnya. Sampai di sini, upaya Sosiologi Sastra yang diperkenalkan Sapardi dalam jagat sastra Indonesia modern menjadi relevan. Artinya, frase sosiologi di titik ini digunakan untuk memahami ‘realitas’ di dalam karya sastra.
Sebagai lintasan sejarah, sebermula pada periode 1960-an Sosiologi Sastra hadir sebagai sebuah metode dalam penelitian sastra di Eropa. Sosiologi Sastra muncul belakangan setelah orang mempelajari sastra secara struktural. Dengan kata lain, sosiologi sastra muncul setelah kajian strukturalisme sastra jenuh.
Bourdieu dalam Encydopedia of Sociology (1992) menyebutkan bahwa hubungan antara sosiologi dan sastra “sebagai pasangan yang lucu” (1992: 106)—sebuah mekanisme yang lebih banyak dianggap sebagai skeptis dan sebuah cibiran di antara keduanya untuk peroleh simbiosis-mutualisme intelektualitas. Hemat saya, skeptisme ini karena bagi sejumlah kalangan (dalam hal ini sosiolog) masih beranggapan bahwa karya sastra belum bisa menjadi sumber informasi dalam kerja intelektualnya. Hal ini dikarenakan anggapan sastra adalah fiksi—hemat saya, itu betul, namun tidak seluruhnya. Sebab, sebagaimana sudah didedah di bagian sebelumnya, keterkaitan dan hubungan osmosis antara realitas dan ‘realitas’.
Sialnya, seperti seekor ajak berusaha mencium duburnya, anggapan bahwa karya sastra tidaklah bisa didekati dengan perangkat ilmu sosial juga mendominasi kalangan (kritikus) sastra. Paradigma konvensional yang menganggap karya seni (juga karya sastra, tentu saja) semata-mata merupakan kompetensi individual (baca: hasil imajinasi semata, olehnya disebut fiksi, tentu saja), yang ditanamkan sejak berkembangnya aliran “seni untuk seni”—ternyata memiliki peranan yang menentukan mengapa upaya mempertemukan sastra dan sosiologi tak bertepuk sebelah tangan tapi saling menepuk pipi sendiri. Sebuah upaya yang (tak) sia-sia.
Dalam situasi bebal yang demikianlah Sosiologi Sastra hadir dan menemukan konteksnya. Perhatian “sastra untuk sastra” dianggap tidak berdampak luas, dan tidak jelas sasaran karya sastra itu sendiri, sehingga membuat karya sastra seperti sebuah wahyu Tuhan yang tidak bisa membumi di masyarakat—yang notabene adalah pembacanya. Sastra dianggap hanya sekedar lamunan belaka dan imajinasi dan… dan fiksi, tentu saja—bukan sebuah proses yang bergerak di tingkat habitus, komunitas, dan masyarakat dalam ranah arena (meminjam konsep Fields Bouerdieu). Anggapan konvensional yang bebal ini mesti diguncang. Sosiologi Sastra hadir untuk melakukannya.

Meskipun demikian, dalam kilasan historis ranah sosial dan sastra, selain sebagaimana sudah dikatakan di atas, bahwa saya menduga munculnya atas kerisauan studi sastra struktural yang dekaden—karena getaran ‘seni ekspresif’ juga banyak andil dalam pemunculan sosiologi sastra. Getaran seni yang mulai melirik teori sosial, mengimbas dalam bidang sastra. Sedekat yang saya tahu, penggunaan teori-teori sosial dalam bidang sastra sesungguhnya sudah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles. Tengoklah buku yang berjudul Republik, dilukiskan bagaimana mekanisme antarhubungan karya seni dengan masyarakatnya. Di dalam magnum opus-nya inilah acapkali disebut pembahasan paling tua antara sastra dan realitas.
Walaupun begitu, sastra dalam pembahasan tersebut meliputi puisi semata dan dalam tarik nafas yang sama dengan karya seni, semisal patung dan seni arsitektur. Bagi Plato, karya seni semata-mata merupakan tiruan (mimesis) yang ada dalam dunia idea. Jadi, karya seni merupakan tiruan dari tiruan—oleh sebab itu secara hierarkis seni berada di bawah kenyataan. Dengan demikian, kualitasnya lebih rendah dari karya seorang tukang. Dalam pemahaman Plato, karya seni mengondisikan manusia semakin jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Maka kesimpulan Plato, seniman harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat. Dalam kerangka filsafat Plato, hasil karya seniman merupakan racun bagi alam idea manusia yang berfalsafah ugahari itu.
Tentu saja filsafat idea Plato yang semata-mata bersifat praktis terhadap seni dan realitas an sich ditolak oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, karya seni justru mengangkat jiwa manusia, yaitu melalui proses penyucian (katarsis). Sebab karya seni membebaskan manusia dari nafsu yang rendah. Aristoteles beranggapan, bahwa dalam upaya memahami kenyataan atawa realitas an sich, seni didominasi oleh penafsiran—karena itu baginya seni adalah kata-kerja. Karenanya seniman mesti tidak semata-mata meniru realitas, tetapi menciptakan dunianya sendiri sehingga manusia dapat mencapai keugaharian. Ini perbedaan secara prinsip antara kedua murid soko-guru Socrates itu dalam mempersoalkan seni dan realitas.
Dalam kebudayaan Barat, khususnya pada Abad Pertengahan, apa yang diungkap Aristoteles mengenai katarsis diterima sebagai dasar estetik dan filsafat seni. Oleh sebabnya, ciri karya seni pada saat itu seni mencoba meniru alam sebagai ciptaan Tuhan (The Great Modern)—dus, karya seni mencerminkan keindahan Tuhan, manusia hanya menciptakan kembali, manusia sebagai homo-artifex.
Setali tiga uang, di Nusantara, misalnya—untuk tidak menyebut Timur dan tidak berkehendak beroposisi-biner antara Barat-Timur—hal tersebut tampak dalam puisi-puisi Jawa Kuno—melalui konsepsi persatuan antara manusia dengan Tuhan lewat keindahan; sebagai penjelmaan Tuhan (manunggaling kawula gusti). Itulah mengapa sastra Jawa Kuno (yang berpusat di Keraton, tentu saja) banyak yang mengungkapkan realitas estetik Ketuhanan. Sastrawan mencoba memahami realitas dengan berbagai symbol ketuhanan yang diciptkan.
Sampai di sini, hemat saya, itik-temu dan titik-pisah antara Plato-Aristoteles ialah hubungan bagaimana seorang seniman dalam menghadapi vis a vis dengan realitasnya dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Sampai di sini, apa yang sudah saya paparkan di atas perihal lingkup sastrawan, realitas, dan ‘realitas’, menjadi relevan. Dan saya harap menjadi simpul olehnya. Paparan di atas ialah historisitas argumen dasar tulisan ini yang sudah sedari awal dikemukakan.
Kembali ke dalam lintasan historis kebudayaan Barat, dengan demikian legitimasi sastrawan sebagai pencipta sesungguhnya tampak sesudah abad ke-18—dengan anggapan manusia sebagai pencipta (karya seni) yang otonom. Puncaknya terjadi abad ke-19, pada Abad Romantik, dengan menonjolkan individualitas sastrawan, dengan berkembangnya puisi-puisi lirik—puisi yang mengedepankan perasaan liris terhadap sosok Aku yang resah terhadap realitasnya. Hemat saya, semangat lirisme dalam karya seni Barat ialah irisan dalam semangat rasionalisme ilmu pengetahuan di Barat—aku berpikir, maka aku ada: ialah adigium kunci untuk memahami perjalanan sejarah estetika Barat.
Perkembangan selanjutnya, buah dari individualitas tersebut ialah karya seni dinilai berdasarkan atas kebaruan dan penyimpangannya terhadap karya-karya sebelumnya. Individualitas menjadi penggerak dalam laju lokomotif sejarah kebudayaan estetika Barat. Lambang aktivitas kreatif bukan lagi cermin, peneladanan, atau peniruan, melainkan pelita yang memancarkan sinar dalam proses berkesenian. Dengan memahami lintasan sejarah di atas, maka oleh sebab itu tampak dikotomi pandangan terhadap karya seni (juga sastra), yakni (a) karya sebagai dunia yang otonom—yang kerap disederhana dengan slogan “seni untuk seni”, yang kemudian tampak dalam aliran strukturalis dan sejumlah variannya, dan (b) karya seni sebagai dokumen sosial—“seni untuk opo kui…” seperti berbagai penelitian yang dilakukan oleh aliran Marxis, psikologi, dan peneliti sosiologi yang lain.
Antitesa terhadap situasi demikian ialah paradigma yang menunjukkan melalui konsepsi-konsepsi yang timbul sesudah strukturalisme (klasik) mengalami stagnasi; maka muncullah paradigma strukturalisme genetik, semiotika, resepsi, dan interteks—yang kemudian direduksi dengan frase ‘post-strukturlisme’—dalam geliat demikianlah sosiologi sastra hadir.
Salah satu buah orisinalitas hal tersebut ialah sikap kritis pembacaan terhadap teks, menjadi bagian dari kacamata sosial politik. Karya sastra bukan semata-mata kualitas otonom individu atau dokumen sosial, melainkan melampaui keduanya—yakni (1) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dan olehnya (2) sebuah karya yang memiliki kapasitas untuk mengguncang jalan yang stagnan. Maka dapatlah dibaca dengan neraca teks-konteks-teks-konteks-teks… konteks-teks. sebuah dialektika yang berujung pada anti-tesa…
Dalam situasi yang demikianlah paparan saya perihal realitas an sich dan ‘realitas’ di atas menemukan konsepsinya. Artinya, sebagaimana sudah saya katakan, bahwa Sosiologi Sastra (1) hadir tidak dalam ruang hampa dan olehnya (2) mencoba menjawab kejenuhan dalam lingkup pembacaan karya sastra dengan menggunakan perangkat keilmuan sosiologi—bagaimana mendorong imperatif kategoris: “sastra adalah fiksi” dan “sosiologi adalah fakta” ke tepi jurang kebebalan—saran saya, silakan ubah kata ‘sosiologi’ tersebut dengan bidang keilmuan lainnya yang Anda anggap selalu mengedepankan kata ‘ilmiah’ dan menunjuk-hidung sastra adalah fiksi olehnya ada batu persoalan yang membuat karya sastra laiknya kitab suci yang tak elok dibantun dalam kegiatan intelektualisme.
Sampai di sini persoalan belum selesai, tentu saja. Salah satunya ialah penggunaan istilah ‘Sosiologi Sastra’ (Sociology of literature), agaknya perlu diselidiki. Sebab ada ambigiuitas di sana. Perihal tata-cara menggunakan perangkat tersebut. Bila kita sepakat bahwa sosiologi sastra adalah metode yang memanfaatkan faktor sosial sebagai pembangun sastra, maka konsekuensi logisnya ialah faktor sosial diutamakan untuk mencermati karya sastra—tepat di situ titik persoalannya. Menurut Umar Junus, sebagai sebuah metode sosiologi sastra memiliki dua corak, yaitu (1) sociology of literature dan (2) literary sociology (1986 : 2).
Jika Literary Sociology mengacu pada pandangan sastra sebagai gambaran kehidupan sosial—oleh karena, pijakannya terletak pada fenomena sastra, untuk memahami gejala sosial di luar sastra tapi yang hadir di ‘realitas’ (teks sastra), maka Sociology of Literature malah memanfaatkan fakta sosial untuk menelusuri sastra. Artinya, bila yang pertama menyelediki yang-sosial yang terdapat di dalam teks sastra—dalam hal ini ‘realitas’, maka yang kedua menghendaki teks sastra (‘realitas’) harus menampilkan fakta sosial realitas an sich. Meskipun keduanya saya pikir memiliki keterkaitan perihal menggunakan sastra sebagai alat memahami tingkah pola manusia.
Tentang hubungan antara sosiologi dan sastra, Swingewood dalam buku berjudul The Sociology of Literature (1972) mengetengahkan pandangan yang positif perihal tegangan yang kerap muncul di antara keduanya. la memandang anggapan sastra sebagai sekedar bahan sampingan saja untuk memahami masyarakat—ialah sebuah pijakan yang klise. Ia pun mengingatkan bahwa dalam melakukan analisis sosiologi terhadap karya sastra, kritikus sastra harus berhati-hati mengartikan slogan “sastra adalah cermin masyarakat”. Di sana ada ambiguitas. Karena yang luput dari Swingewood ialah proses-kreatif sastrawan memiliki pola yang tidak serupa muka yang dipantulkan cermin, melainkan osmosis dengan berbagai hal yang melingkupinya—inilah yang di atas disebut pasemon.” Oleh sebab hubungan pengarang, kesadaran, dan tujuannya memilih sastra dan bukan ialah komponen satu-kesatuan yang tak bisa dilupakan, namun hubungannya tak sesederhana yang kita bayangkan. Olehnya, hemat saya, frase pasemon menjadi tepat—dus, karena itu juga sosiologi digunakan untuk memahami setiap kelok pasemon tersebut.
Memang setiap kelok selalu memberikan kejutan dan kedutan. Namun bagi saya jelas, sebagaimana yang sudah saya tuliskan, dan bila Sampeyan membacanya dengan cermat ini untuk ketiga kalinya dalam tulisan ini—realitas an sich menjadi titik-tolak, terminus a quo, dan sekaligus titik-tuju, terminus ad quem—pada batang-tubuh ‘realitas’ keduanya terbantun. Karenanya, bagi saya, seorang sastrawan berdiri di dua kaki yang berpijak pada realitas an sich dan ‘realitas’. Meski sastrawan bukanlah dewa, tentu saja, melainkan serupa dengan pengendara tong setan atau buruh pabrik dalam hal alienasi dan aktualisasi.
Di titik ini saya malas mempersoalkan benturan dan pertautan antara slogan “sastra untuk sastra” dan “sastra untuk opo kui…”. Namun, di lain kesempatan, saya harap ada yang mempersoalkan hal tersebut—karena dalam sejarah sastra modern Indonesia hal tersebut belum lah benar-benar ‘selesai’—sambil menimbang-nimbang fakta sejarah kebudayaan Indonesia yang menunjukkan bahwa mereka yang pertama-tama menolak/menampik realitas an sich dalam ‘realitas’ adalah mereka yang kembali merengkuh dan memeluk realitas an sich dalam ‘realitas’ ketika politik tidak lagi menjadi panglima dan revolusi benar-benar dibenamkan dalam laju pembangunanisme. Lebih terangnya begini: mereka yang mendengungkan metode Ganzheit di tahun 1971 (sebuah metode yang mempertanyakan struktural-formalis dalam menghadapi selarik puisi) dan Sosiologi Sastra di tahun 1978 (perangkat ilmu sosial dalam mendedah karya sastra, dan sudah dibahas di atas) dan sastra kontekstual di tahun 1983 (upaya mengembalikan sastra ke tengah-tengah masyarakat, realitas an sich)—ialah mereka-mereka juga yang di tahun 1960-an dengan teguh dan bijak bestari menolaknya. Kalau bukan Asu Teles, apa namanya, Su?
Apakah ini yang disebut dengan amnesia-sejarah? Saya tidak yakin, dan saya tidak ingin menyebutnya sebagai amnesia. Tidak adil, cuk. Yang saya tahu, sastra tidak pernah benar-benar clear and clean dengan Politik (dengan P besar, bila merujuk Ranciere), melainkan sastra berhadap-hadapan, vis a vis antara Politik dan yang-politik (dengan p kecil). Artinya, sastra tidak pernah bisa lepas dari kondisi vis a vis kekuatan politik dan oposisi-biner ideologis dalam palagan sejarah Indonesia. Akhirnya, bagi saya, karena itulah sastra menjadi menarik. Ia tidak akan benar-benar menjadi sekedar sastra.
/4/
JIKA SAMPEYAN masih juga keukeuh bahwa sastra dan sastrawan lebih mulia ketimbang wahana tong setan dan deodoran, silakan baca kalimat di bawah ini dengan melantunkan kidung kesedihan para pemurung yang pernah tercatat di buku sejarah sambil merancap dengan pelumas air matamu:
“Tinggalkanlah, jika dia memang cinta sejatimu, dia akan kembali dengan cara mengagumkan,”—Tere Liye, Rindu.
Jelek, kan?
Saran saya, lebih baik Sampeyan pakai deodoran sambil naik tong setan—itu jauh lebih berfaedah ketimbang Sampeyan bergumul dengan kalimat-kalimat serupa di atas, bila Anda masih juga beranggapan sastra sekedar sastra.

Sumber: Merdeka.com
Atau apalagi? Mungkin itulah alasan utama saya mengapa sedari awal kukatakan kepadamu, wahai Pecinta Sastra dan Pengikut Akun Line @Kumpulan_Puisi yang Budiman, menjadi sastrawan dan pengemudi tong setan dan buruh pabrik itu sama saja. Hanya berbeda nasib dan takdir. Selebihnya sama, produk budaya… []
Jatikramat, Maret-April 2017
*Tyo Prakoso—pembaca dan perajin tulisan. Buku pertamanya berjudul Bussum dan Cerita-cerita yang Mencandra (2016) dan buku keduanya akan mengudara di kuartal ketiga tahun ini.
Post-script: Naskah ini hasil re-writing dari naskah awal yang didiskusikan dalam forum DKS, UNJ pada akhir Maret lalu. Karenanya kepada kawan-kawan DKS dan pihak yang datang, saya ucapkan terima kasih atas komentar, kritik, dan masukkan yang sangat bermanfaat bagi naskah yang kini ditampilkan—terutama perdebatan perihal Sastra populer dan Sastra sebagai produk (budaya) populer. Selebihnya tanggung jawab atas seluruh isi tulisan sepenuh berada di pundak saya— T.P.
Daftar Pustaka:
Borgatta, Edgar F. and Rhonda J. V. Montgomery. Encyclopedia of Sociology Second Edition (Edisi Pertama tahun 1992). Macmillan Reference USA: New York, 2000.
Damono, Djoko Damono. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: 1984.
______________________ “Sastra, Citizen, Netizen” makalah dalam Seminar Nasional Sosiologi Sastra “Sastra dan Perubahan: Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Sastra” Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 10-11 Oktober 2016.
Kuntowijoyo. “Sastra Indonesia Mencari Arah” dalam Budaya dan Masyarakat. Tiara Wacana: Yogyakarta. 1987.
Swingewood, Alan and Diana Laurenson. The Sociology of Literature. MacGibbon and Kee: London. 1972.
Teeuw. A. Sastra dan Ilmu Sastra. Pustaka Jaya: Bandung. 2013.
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 30 Maret 2017 dan telah dipublikasikan juga di laman gerakanaksara.blogspot.co.id
0 notes
Text
Si Penulis Nyamuk Asal Kebon Jeruk: Gie, Sang Idealis-Kritis yang Menentang Dehumanisasi
Oleh: Gugun Gunaedi
Jujur saja, tulisan ini tidak akan selesai jika tidak ditopang dengan alunan lagu dari Joan Baez yang berjudul Donna Donna serta asupan kopi hitam dan gu**dang gar**am filter (tidak boleh menyebut merk)! Sesungguhnya tulisan ini jauh dari kata sempurna, karena sempurna hanyalah milik Andra & The Backbone. Tulisan ini didedikasikan untuk Guru Lintas Alam saya, Gie! Selamat membaca…
“….Mahameru berikan damainya, didalam tugu Arcapada. Mahameru sebuah rentetan tersisa, puncak abadi para dewa…."
Itulah sepenggal lirik lagu dari grup band Dewa 19 yang berjudul Mahameru untuk mengawali tulisan ini. Pada lirik tersebut Mahameru memang memberikan damainya, entah damai dalam keadaan sesaat karena melihat keindahannya, atau damai selama-selamanya dan menyatu dengan ukiran bentang alamnya. Ya, itulah yang dirasakan Gie.
Perkenalan singkat tentang Gie dan pergolakan pada fase remaja
Soe Hok Gie adalah manusia biasa keturunan Tionghoa yang dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1942 di Jakarta, dimana perang tengah berkecamuk sangat dahsyat di kawasan Asia-Pasifik. Gie, sapaan akrabnya--walaupun di dalam film GIE besutan Riri Riza dan Mira Lesmana Gie lebih memilih dipanggil Soe ketika berkenalan dengan Soemitro-- mulai bersekolah di Sin Hwa School[1] pada umur lima tahun, lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Strada, setelah itu melanjutkan studinya di SMA Kanisius dan kelak setelah lulus menjadi bagian mahasiswa Sejarah Universitas Indonesia (kelak ia akan menjadi dosen di tempat tersebut). Pergolakan pemikirannya mulai terbentuk pada saat Gie duduk di bangku SMA. Pada fase ini ia telah banyak melahap buku-buku sejarah, sosial, filsafat dan sastra. Atas hal itulah Gie remaja sudah mengenal tokoh-tokoh seperti Gandhi, Kahlil Gibran, Lenin, Karl Marx hingga Friedrich Nietzsche. Pada masa itu pula Gie sangat gemar menulis catatan harian— kelak catatan hariannya tersebut dibukukan oleh LP3ES pada tahun 1983 atas seizin dari sang kakak, Arief Budiman--. Kegemaran Gie dalam hal menulis nampaknya menurun dari sang ayah. Gie tumbuh dalam sebuah kultur keluarga yang ramah akan ilmu pengetahuan. Ayahnya, Soe Lie Piet adalah redaktur dan jurnalis dari berbagai surat kabar dan majalah. Sang ayah juga seorang penulis yang produktif di eranya.[2] Kegiatan yang berbau literasi memang telah akrab dalam diri Gie. Di dalam buku Catatan Seorang Demonstran Gie kerap acapkali mengunjungi toko buku dan menulis catatan hariannya pada malam hari, --maka dari itulah secara sepihak saya memberi judul tulisan ini Si Penulis Nyamuk Dari Kebon Jeruk, dimana binatang ini identik keluar pada malam hari-- (semoga tidak terjadi kecemburuan sosial dalam bangsa kelalawar yang tidak dimasukkan ke dalam judul tulisan ini, Aamiin…). Pada fase remaja inilah jiwa ke-kritis-an Gie lahir dan tumbuh. Ia sempat berdebat alot --sealot kerupuk warteg yang tempatnya dibiarkan terbuka—dengan salah satu guru di SMA-nya. Gie berdebat dengan gurunya yang bernama Pak Effendi, guru Bahasa Indonesia di SMA Kanisisus. Perdebatan itu terjadi akibat keitdaksepahaman antara Gie dengan gurunya mengenai siapa pengarang prosa “Pulanglah dia si anak hilang”. Gurunya mengatakan bahwa pengarang prosa dari “Pulanglah dia si anak hilang” adalah Chairil Anwar, namun Gie membantahnya dengan argumen bahwa prosa tersebut dikarang oleh Andre Gide sedangkan Chairil Anwar hanya menerjemahkannya saja. Akibat perdebatan yang tak seimbang tersebut Gie meluapkan kekesalannya dengan menulis di catatan hariannya:
“Tentang karangan saja dia lupa. Aku rasa dalam hal sastra aku lebih pandai. Guru model gituan. Yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau”[3]
Gie memang dikenal idealis terhadap apa yang ia anggap benar. Dan karena sikapnya itu Gie merasa terasingkan dan jiwanya merasa sepi, namun Gie telah memutuskan bahwa akan bertahan dengan prinsip-prinsipnya, yaitu lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan.[4] Quote atau slogan semacam itulah yang sekarang masif kita lihat di status berbagai kalangan di media sosial serta tulisan diatas meja mahasiswa dalam ruang kelas.
Idealis muda yang menentang dehumanisasi
Nah, pada bagian ini anggur merah, ehh. intisari –maksudnya-- dari tulisan akan dibeberkan secara kurang mendalam, karena yang dalam adalah palung laut. Monggo di-read…
Sebelum lebih dalam menyelam ke palung laut, saya akan memberikan definisi apa itu dehumanisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dehumanisasi adalah penghilangan harkat manusia. Dehumanisasi merupakan antitesa dari humanisasi, yang dalam pengertian singkat, padat dan jelasnya adalah memanusiakan manusia. Bagi pejuang pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, dehumanisasi yaitu penindasan yang tidak manusiawi, apa pun alasannya, dan merupakan sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan.[5]
Tidak semua kematian dapat meraibkan kehidupan. Ya, rasa-rasanya memang begitu (Kalo enggak gitu, ya tolonglah gituin…). Kematian bisa berkata lain, “yang pernah hidup tetap hidup”. Inilah sebuah dunia paradigma atau memoar yang membuat kita masih tetap bisa “hidup bersama”, mengenang mereka para manusia ekstrak –lintas alam--, yakni mereka yang menjadi sari pati bagi dunia ini. Tengoklah wacana-wacana filsafat yang hingga detik ini masih terus “dihantui” Socrates, Thomas Aquinas, Immanuel Kant ataupun Jean-Paul Sartre. Pemikiran filsafat mereka masih menjadi kiblat filsafat dan etika hingga sekarang. Begitupun ketika kita membicarakan teori relativitas, yang diingat pastilah sosok bapak tua berambut putih yang lidahnya selalu menjulur, abah Albert Einsten! Komunitas sastra juga tetap merindukan Kahlil Gibran dengan The Prophet yang imajinatif ataupun W.S Rendra dengan burung meraknya.
Leonardo da Vinci, Mozart John Lennon juga Kurt Cobain akan selalu dikenang para penikmat seni. Para humanis juga akan tetap hidup bersama semangat Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr dan Mother Teresa.[6] Ketika kita membicarkan pergerakan mahasiswa angkatan ’66 maka yang terlintas di benak kita adalah 3 suku penggalan kata: Soe – Hok – Gie. Ya, sang demonstran yang moralis! Intelektual muda yang begitu bergairah, gigih, dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan serta menentang setiap tindakan dehumanisasi dan dekandensi moral. Sikap kritis Gie dalam menentang dehumanisasi bukanlah tanpa alasan. Setidaknya ada 3 penguatan dalam menganalisis permasalahan ini. Penguatan pertama, Gie menilai bahwa pada rezim Orde Lama dibawah kekuasaan Soekarno telah terjadi ketimpangan serta ketidakadilan yang mencekik leher masyarakat bawah. Hal itu dibuktikan dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, melonjaknya pengangguran, korupsi yang merajalela dan hal itu sangat kontras dengan kehidupan di dalam Istana Negara yang menurut Gie (di dalam catatan hariannya) sedang berfoya-foya ditemani para selir. Penguatan Kedua, (mungkin disini Gie sangat subjektif) Gie menilai Soekarno sebagai pemimpin yang immoral dengan gila kekuasaan dan gila wanita. Wow, kritik yang sangat tajam kepada individu sekaliber Soekarno! Dalam hal ini Gie mempunyai pendapatnya sendiri mengenai Soekarno, yaitu:
“Sebagai manusia saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Bagaimana ada pertanggungjawaban sosial-isme melihat Negara dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Bung Karno sebagai Ariwijadi penuh humor-humor dengan mop-mop cabul ada punya interes yang begitu immoral … Kesanku hanya satu, aku tidak bisa percaya dia sebagai pemimpin Negara karena ia begitu immoral.”[7]
Penguatan tiga, Gie menganggap Soekarno sebagai raja Jawa yang se-enaknya dalam bertindak. Jadi Soekarno mempunyai 3 aspek. Gelar raja-raja Jawa juga sama dengan gelar politik (Kawula ing tanah Jawi),[8] tentara (Senapati ing ngalaga),[9] dan agama (Syekh Sahidin Ngabdulrachmad).[10] Presiden Soekarno adalah lanjutan daripada raja-raja tanah Jawa. Karena itu dalam tindakan-tindakannya ia bersikap seperti raja-raja dahulu. Ia beristri banyak, mendirikan keratin-keraton dan lain-lain.[11] Ditambah pula terciumnya kediktatoran Soekarno yang tertuang dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 semakin bulat tekad Gie dalam menentang kekuasaan Soekarno. Dalam perspektif Machiavelli, fokus politik itu hanya pada kekuasaan, dan politik itu hanya pada kekuatan, dan politik bukanlah tempat yang tepat untuk menyemai benih-benih moralitas. Politik harus dilepaskan dari kewajiban moral. Franz Magnis Suseno menilai bahwa bagi Machiavelli politik dan moral merupakan dua bidang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya.[12] Selaras dengan Gie yang konsisten memperjuangkan moralitas diatas kekuasaan, Bertrand Russel secara elegan menyatakan bahwa cinta akan kekuasaan, seperti nafsu, merupakan suatu alasan yang begitu kuat sehingga mempengaruhi tindakan kebanyakan orang lebih daripada yang seharusnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa etika yang akan menimbulkan konsekuensi yang paling baik adalah etika yang membenci cinta akan kekuasaan lebih daripada yang dapat dibenarkan oleh akal budi.[13] Pernyataan Russel tersebut seakan-akan menjadi pembenaran bagi perjuangan moral Gie. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh Gie ini, saya akan mengambil pandangan hubungan antara penindas dan tertindas dari Freire. Freire mengingatkan bahwa status, kekuasaan dan dominasi dari penindas tidak mungkin ada tanpa eksistensi kaum tertindas. Dia meletakkan pemahaman kesalinghubungan ini satu langkah ke depan dalam konsepsinya, bahwa penindas dan tertindas merupakan manifestasi dari dehumanisasi. Freire mengklaim bahwa tugas kemanusiaan kaum tertindas adalah membebaskan dirinya sendiri dari penindas-penindasnya.[14] Disini Gie memposisikan dirinya sebagai orang yang tertindas dan selalu konsisten dengan para kaum yang tertindas. Bahwasanya tak ada yang lebih mulia selain membela kaum-kaum tertindas. Gie bukan sekedar mengecam dan membenci kekuasaan yang selalu diyakini sebagai biang raibnya konteks kemanusiaan. Namun lebih dari itu ia bertindak dengan melangsungkan berbagai protes serta demonstrasi secara masif bersama kalangan mahasiswa lainnya yang mengakibatkan rezim Orde Lama dibawah kekuasaan Soekarno tumbang dari singgasana perpolitikan Indonesia. Kekuasaan dalam perspektif Gie selalu dan pasti non-humanis! Segala hal yang tak seimbang adalah bentuk penindasan antara mereka yang (mengutip kosa kata dari Friedrich Nietzsche) superior—berkuasa-- terhadap mereka yang inferior—budak--. Menurut Erich Fromm didalam bukunya yang berjudul Escape from Freedom menjelaskan bahwa otoritas merupakan hubungan superioritas dan inferioritas. Ada pihak yang memandang kuat dan hebat, dan ada pihak yang memandang (terpaksa) tunduk dan mengakui sang superior.[15] Realitas semacam itulah yang muncul pada pemerintahan Soekarno. Gie menganggap pemerintah (read: Soekarno) telah sewenang-wenang dalam kepemimpinannya, sedangkan rakyat harus (dipaksa) tunduk dengannya. Atas dari itulah Gie selalu memposisikan dirinya dipihak rakyat yang tertindas. “Aku bersamamu orang-orang malang” ungkapnya….
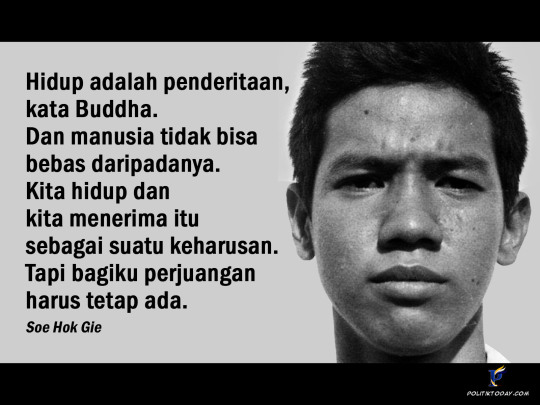
Sumber: Politiktoday.com
Peng-ibaratan Gie adalah seorang Nahkoda
Ibarat nahkoda di tengah laut Samudera Hindia, Gie adalah nahkoda yang terus menerjang ombak-ombak ganas bernama dehumanisasi. Namun sayang, belumlah selesai tugas menepikan kapal yang ia kemudikan Gie wafat dalam usia yang masih muda. Sangat muda mungkin….
Salam perpisahan untuk si penulis nyamuk
Dengan segala hormat, Gie, saya akan menutup tulisan ini dengan salam perpisahan…Selasa, 16 Desember 1969, mungkin pada hari itu Indonesia sedang diguyur air. Bukan! bukan air hujan yang mengguyur bumi Indonesia, melainkan Indonesia sedang diguyur air mata duka, air mata yang melambangkan kepedihan amat mendalam. Tepat pada tanggal itu sosok pemuda yang dikenal sebagai tokoh pergerakan mahasiswa angkatan '66 yang dikenal sangat kritis dan humanis, pecinta alam yang ulung (Pendiri Mapala UI) dan salah satu anggota dari GeMSos (Gerakan Mahasiswa Sosialis)[16] yang bernama Soe Hok Gie menghembuskan nafas terakhirnya di atap pulau Jawa, --Mahameru-- puncak dari Gunung Semeru. Dia meninggal bersama kawan seperjuangannya, Idhan Lubis, karena menghirup gas beracun yang keluar dari kawah Mahameru. Jenazahnya “ditemani” sehari semalam oleh sahabat karibnya dalam melakukan pendakian, Herman Lantang. Namun hingga saat ini tagline, perjuangan dan cita-citanya dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang terbabas dari hal-hal yang berbau dehumanis belum sepenuhnya terwujud. Terkhusus bagi mahasiswa, Gie memimpikan tidak ada mahasiswa yang mementingkan ras, golongan, agama, suku ataupun ormasnya. Bagi Gie, mahasiswa adalah individu yang diharuskan bebas, ber-idealis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga kejujuran.
Mahameru, pada tanggal 16 Desember 1969 menjadi saksi. Indonesia kehilangan sosok pemuda yang kritis pada zamannya. Pemuda yang bernama Soe Hok Gie itu kembali menyatu bersama alam dengan damai. Dingin dan hempasan pasir Mahameru menyelimuti jasad Gie yang telah membiru dan kaku. Atas wasiat Gie sewaktu masih hidup, tulang belulangnya di kremasi, lalu di taburkan di "lembah kasih" Mandalawangi, Gunung Pangrango, yang menjadi tempat pelarian Gie dalam mencari kesunyian. Kini ia meninggalkan karya-karya tulisan, harapan dan prinsip hidup untuk para pemuda di Indonesia.Atas nama alam raya yang terbalut selimut kerinduan. selamat jalan Gie…
"Mahkluk kecil kembalilah dari tiada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaanmu" Soe Hok Gie 1942-1969 !
Catatan Kaki
[1] Sin Hwa School adalah sekolah dasar yang diperuntukan untuk keturunan Tionghoa
[2] Agus Santosa, Memoar Biru Gie, Yogyakarta: Gradien Books, 2005. Hlm 20
[3] Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, Jakarta: LP3ES, 1983. Hlm 64
[4] Ibid Hlm 166
[5] Listiyono Santoso, Epistemologi Kiri, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015. Hlm 130
[6] Agus Santosa, Memoar Biru Gie, Yogyakarta: Gradien Books, 2005. Hlm 20 .Telah disadur oleh penulis guna kepentingan tulisan ini
[7] Ibid. Hlm 117 csd
[8] Bahasa Jawa, kaula (abdi) tanah Jawa
[9] Panglima pertama: gelar yang digunakan oleh Raja Mataram
[10] Gelar Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin agama
[11] Ibid. Hlm 94
[12] Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, 2000, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 8
[13] Bertrand Russel, Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial Baru, 1988, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 205
[14] Ibid. Hlm 133
[15] Erich Fromm, Escape from Freedom, 1969, Avon Books, New York, Hlm 186
[16] GeMSos adalah underbow dari Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan Sutan Sjahrir
Daftar Pustaka
- Fromm, Erich. 1969. Escape from Freedom. Avon Books, New York
- Russel, Bertrand. 1988. Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Santosa, Agus. 2005. Memoar Biru Gie. Yogyakarta: Gradien Books
- Santoso, Listiyono. 2015. Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Soe Hok Gie. 1983. Catatan Seorang Demonstran. Jakarta: LP3ES
- Soe Hok Gie. 2005. Zaman Peralihan. Depok: Gagas Media
- Suseno, Franz Magnis. 2000. Kuasa dan Moral. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
P.s: Penulis adalah manusia biasa yang secara konsisten bernapas dengan paru-paru,Tidak ada spesifikasi khusus, melainkan hanya berjenis kelamin laki-laki,Sila kontak : [email protected], @gugungunaedi (twitter) atau gudangkata20.blogspot.com
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 23 Maret 2017.
0 notes
Text
Perempuan Bergerak
Oleh; Risti Sere Utami
“Perempuan tidak semata-mata dilahirkan, perempuan adalah suatu proses menjadi. Dan proses menjadi tidak akan pernah berakhir.” –Rosemarie Putnam Thong
Jika membicarakan gerakan perempuan pasti tidak bisa dijauhkan dengan gelombang gerakan feminisme. Artinya kita harus tahu terlebih dahulu, sebenarnya apa itu feminisme? feminisme adalah perjuangan kaum perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik dalam hal politik, pendidikan dan ekonomi. Gerakan feminisme awalnya muncul di New York, bermula saat memasuki abad ke-20, di tengah-tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja. Kaum perempuan dari pabrik tekstil mengadakan protes pada 8 Maret 1857 di New York City. Dari situlah akhirnya banyak muncul gerakan-gerakan feminisme di Eropa maupun di Amerika. yang awalnya adalah menuntut kesamaan hak dalam hal berpolitik seperti memiliki hak suara dalam pemilu dan sebagainya.

Sumber: Kumparan.com
Menurut kaum feminis, ketertidasan perempuan dalam berbagai bidang berasal dari budaya yang dinamakan patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Sehingga menyebabkan perempuan selalu berada dalam posisi yang dipinggirkan. Hal ini disebabkan ada yang dinamakan bias gender, bias gender adalah saat perempuan dan laki-laki dikonstruksi memiliki sifat yang tetap yakni perempuan yang feminin (halus, lembut, sopan, dsb) dan laki-laki yang maskulin (tangguh, kuat, perkasa, dsb) pembedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu diibaratkan sebagai sosok yang lemah dan laki-laki adalah sosok yang kuat, jika hal ini terus dipercaya maka perempuan akan kehilangan jati diri mereka sebagai manusia yang merdeka dan menyebabkan sering terjadi kesewenang-wenangan terhadap hak perempuan. Kondisi inilah yang menjadi perhatian kaum-kaum feminis di dunia.
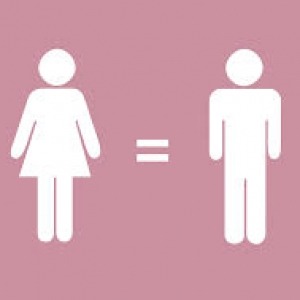
Sumber:m.mrol.com
Berbicara mengenai Gerakan Perempuan di Indonesia, perkembangannya sebetulnya sudah dijelaskan oleh Soekarno. Menurut Soekarno dalam salah satu materi yang disampaikannya dalam Kursus Perempuan di Yogyakarta pada tahun 1947 yang berjudul Wanita Bergerak, beliau menyebutkan bahwa pergerakan perempuan ber-evolusi, dan evolusi tersebut memiliki tiga tingkatan.
Tingkat pertama adalah pergerakan menyempurnakan “keperempuanan”, yang lapangan usahanya semisal memasak, menjahit, berhias, bergaul, memelihara anak dan sebagainya. Tingkat kedua, yaitu pergerakan feminisme, yang wujudnya ialah memperjuangkan persamaan hak dengan kaum laki-laki. Programnya yang terpenting adalah hak untuk melakukan pekerjaan dan hak untuk pemilihan. Tujuannya yang terakhir adalah persamaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan, diatas lapangan hukum-hukum negara dan adat-istiadat. Pergerakan feminis itu juga sering dinamakan pergerakan “emansipasi perempuan” dan aksinya bersifat menentang kepada kaum laki-laki. Tingkat ketiga adalah pergerakan sosialisme, dimana perempuan dan laki-laki bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk mendatangkan masyarakat sosialistis, dimana perempuan dan laki-laki sama-sama sejahtera, sama-sama merdeka.
Lalu pertanyannya sekarang adalah seberapa relevan isu feminisme dengan kondisi masyarakat di Indonesia sekarang? Jika ditarik lagi ke belakang, toh Indonesia memang memiliki budaya yang egaliter. Perempuan di desa-desa membantu suaminya bekerja ke sawah bukan karena takut oleh suaminya, tetapi lebih karena keinginannya supaya keluarganya bisa makan sehari-hari. Lalu sebenarnya dari mana dan untuk siapa kaum feminis bergerak?
*Tulisan ini dibuat untuk Diskusi Kamis Sore tanggal 9 Maret 2017.
0 notes
Text
Kajian Post-Strukturalisme; Pengantar Kritik Bahasa & Pengetahuan
Oleh: Hanan Radian Arasy

Bahasa merupakan teknologi yang kita gunakan dalam berinteraksi, hal tersebut merupakan suatu realitas yang tak jarang tidak disadari oleh sebagian orang darimana asal bahasa,untuk apa bahasa dibuat,dan fungsi laten yang dapat diperoleh dengan mengetahui bahasa.
Kedudukan Bahasa
Carrol (1961:10) Meyebutkan secara jelas sebuah definisi dari bahasa yakni “system bunyi atau urutan bunyi vocal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu,peristiwa, dan proses yang terdapat di sekitar manusia” Keberadaan Bahasa sangat didukung oleh beberapa literature sosiologis yang melakukan pendekatan Etnometodologi dengan melakukan penguraian kemampuan-kemampuan praktikal para partisipan (anggota) yang berasal dari realitas. ada satu penekanan bahwa sesuatu atau kejadian didalam realitas tidak memiliki makna sendiri. Gejala itu Hanya memiliki makna apabila manusia menjadikanya bermakna. inilah yang disebut fenomenologi[1]. Dalam struktur kognisi pendekatan etno-fenomenologi yang menempatkan ‘bahasa’ sebagai interpretasi dari realitas yang dilihat manusia dan dapat ditangkap oleh akal dan apa yang telah ditangkap oleh akal manusia tersebut akan dijewantahkanya ke dalam ‘bahasa’. melalui bahasa kita memperoleh banyak pengetahuan tentang dunia, pengetahuan yang kita miliki begitu saja, dan bersama orang lain yang juga menggunakanya.Jadi, Dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat vital didalam kehidupan berinteraksi manusia dengan objek lain yang pernah ia lihat sebagai produk dari citraan inderawi yang dimiliki oleh manusia.
Bahasa sebagai identitas
W.G Sumner (1940) menyebutkan bahwa dalam Kelompok sosial in group dalam hal ini kita dapat menggunakan istilah ethnocentrism[2]. ada pola keterikatan kelompok terhadap anggotanya yang berdampak pada anggotanya untuk merasa berada dalam kelompok tersebut hal ini yang dijadikan landasan bahwa setiap manusia ingin mendapatkan identitas tentang keberadaanya (sense of belonging). Hal ini yang pula yg dapat dijadikan interelasi antara bahasa dan manusia yang memiliki ego untuk menunjukan eksistensi dan jatidirinya. maka dengan kata lain sikap yang dimiliki manusia untuk berhasrat memiliki identitas itu menjadi pengaruh terhadap produk citra dari apa yang ditangkap inderawi dan dijewantahkanya kedalam ‘bahasa’. inilah yang menjadi beberapa produk-produk identitas berupa symbol,bahasa khusus,dll. yang dapat dimaknai khusus oleh anggota kelompoknya, dan jadi cikal bakal perbedaan yang mendasar antara kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat-disebabkan adanya perbedaan interpretasi makna terhadap realitas kehidupan.
Kavling Sosial
Berdasarkan teori evolusi, masyarakat perlahan-lahan menuju ke arah modern dimana hal ini akan ditemukan kompleksitas yang terbentuk oleh seleksi-seleksi sosial yang sudah ada sebelumnya. Michael Foucault dalam teori wacana yang tersohor menjelaskan tentang jalinan hubungan antara pengetahuan,bahasa & tindakan yang kemudian ia sebut sebagai praktik diskursif-artinya,kehidupan sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dipromosikan oleh wacana-wacana.[3]Sebagai ringkasan, argument Foucault adalah bahwa identitas ditentukan oleh wacananya-manusia tahu apa yang mereka fikirkan,tuturkan dan lakukan. dan dengan implikasi wacana yang berbeda-beda didalam kehidupan sosial. maka orang-orang bersikeras untuk mempertahankan identitas dan memperoleh kekuasaan atas wacana orang lain. hal ini diakomodir dengan adanya kavling-kavling sosial atau bidang pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan. dengan kata lain bidang pengetahuan (biologi,fisika,sosiologi,hukum,ekonomi,dll) tercipta tak sepenuhnya obyektif-ada subjektivitas didalam bidang pengetahuan demi memperoleh tempat dan legitimasi didalam masyarakat. begitu pula dengan institusi,lembaga dan pranata yang ada, mereka semua mencoba mencari tempat didalam masyarakat dan berupaya mendapat legitimasi bahwa masyarakat membutuhnkanya. dan dengan cara apa mereka mendapatkan perhatian terhadap masyarakat? tentu dengan wacana (Pengetahuan,bahasa dan tindakan) yang mereka manipulasi sebagai upaya promosi-promosi identitasnya dan bagi marxian adalah untuk menggapai keuntungan material. inilah faktor mengapa kavling sosial menjadi studi yang begitu penting demi terwujudnya informasi bagi masyarakat dan khalayak umum agar tidak terjadi ketidakseimbangan dan dominasi yang mendorong keresahan masyarakat itu sendiri, karena pada hakikatnya masyarakat hanya dijadikan lahan luas demi meraup keuntungan.
DAFTAR PUSTAKA
Sunarto,Kamanto “Pengantar Sosiologi : Edisi Revisi”.2004.Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
PIP Jones “Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme”.2009. Jakarta: Obor
[1] PIP Jones “Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme”(Jakarta: Obor, 2009), hlm 162.
[2] Sunarto,Kamanto “Pengantar Sosiologi : Edisi Revisi”(Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,2004)hlm130-131.
[3] Op Cit, hlm 202-204
0 notes
Text
Menonton Zizek
Oleh: Hanan Radian Arasy
�

Koleksi: Melville House | 2015
Happy pub day (okay, day after pub day) to Slavoj Zizek’s TROUBLE IN PARADISE! Today’s #PubDayDish is apple cider bread w/cinnamon.
SLAVOJ ZIZEK seorang filsuf abad ke-21 yang terkenal sebagai ‘Elvis Persley’ di dalam studi kebudayaan, yang mempersembahkan sebuah film dengan beberapa sentuhan sinematografi yang asik, film itu berjudul The Pervert Guide to Ideology – what’s ideology? (2012, Directed by Sophie Fiennes). Sungguh menarik di bagian awal film tersebut bagaimana tampak Zizek di depan tong sampah mengoceh dengan logat khasnya guna memperkenalkan tokoh di dalam film yang bernama John Nadal—seorang yang diilustrasikan sebagai ‘subjek-murni’ yang terbebas dari berbagai penyusutan material konten, yakni seorang pekerja tanpa rumah yang terlontang-lantung, dan menemukan sebuah kacamata ajaib di dalam sebuah gereja yang sudah absen diisi oleh kegiatan para jemaat. Kacamata tersebut mengajak John Nadal untuk melihat The Real[1], yang bagaimana kacamata tersebut mengajak penggunanya melihat realitas sosial pada jalan The Real-nya terbentuk.
Ada poin yang amat menarik ketika dimensi kacamata tersebut digunakan untuk melihat beberapa realitas seperti papan iklan, gambar wanita, dan uang yang digenggam seorang pedagang buku—dengan fungsi kacamatanya sebagai ‘kritik-ideologi’ maka beberapa objek penglihatanya berubah menjadi suatu kenyataan dimana papan iklan tersebut berubah menjadi layar abu bertuliskan Obey, lalu gambar wanita berubah menjadi sebuah tulisan “Marry and Produce”, serta Uang yang digenggam seorang pedagang buku berubah menjadi sekumpulan kertas bertuliskan “This is your God”. Cukup sampai di sini Zizek sebagai seorang Psychoanalisis dan filsuf Hegelian Marxist, Theolog Christiany dan pula seorang kritikus kebudayaan yang sering berkecimpung di dalam teori kebudayaan dan pula medium Film memberikan warna dominan pada film ini.

Lantas, belum selesai sampai di situ, Zizek menjelaskan bahwa bagaimana dan mengapa kita harus terbebas dari “Ideology”. Menurutnya, subjek yang terbebas dari ideology—dus bagi penulis sendiri—sebagai selubung kekuasaan di dalam mekanisme berpikir yang terindoktrinasi (KERASukan kepala[2]). harus mampu menolak spontanitas, karena menurut Zizek, Ideologi memberikan rasa nyaman yang diendapkan pada dimensi ketidaksadaran manusia sehingga akan terasa sakit ketika seseorang mencoba keluar darinya. Zizek memberikan kodifikasi melalui beberapa penanda dan pertanda di dalam pengada kehidupan kita yang seringkali berseliweran begitu saja. Menurutnya “Menjadi diri sendiri”,”Mengikuti hasratmu”, ”Realisasikan kebenaran potensialmu” dsb. adalah pertanda dari kenyataan atau dengan bahasa psychoanalisa-nya Zizek sebagai pembaca Lacan, yakni “The Real” ialah kediktaktoran di dalam demokrasi.
Kembali pada permasalahan subjek yang terbebas dari selubung kekuasaan mekanisme berpikir yang terindoktrinasi (KERASukan kepala) atau di dalam konseren seorang Zizek sebagai ideologi menjelaskan bahwasanya tak hanya sekedar rasa sakit untuk mampu membayar kebebasan itu.

Lantas apalagi kang Zizek!? Dengan logat-khas-Sunda-dibalur-dengan-medok-tegalannya, Zizek menjawab pertanyaan saya sebagai penulis rehal film ini, bahwa, perlu pengalaman luar biasa dan amat menyakitkan untuk bisa keluar dari ideologi. Sebagai analogi, John Nadal— ‘tokoh’ dalam film tersebut—berkelahi dengan teman terbaiknya John Armiitaj hanya untuk mencoba menawarkan bagaimana kacamata yang sudah digunakan John Nadal dapat pula digunakan oleh kawan karibnya itu. Baku Hantam terjadi karena John Armiitaj menganggap tawaran John Nadal irrasional dalam sudut pandang Zizek yang seakan-akan berasal dari kenyataan menyebutkan bahwa John Armitaaj tidak mau menggunakan kacamata yang ditawarkan dengan John Nadal karena kesetubuhanya dengan wellbeing di dalam spontanitas seorang John Armitaj.
“The paradox of liberation that we have accept is like an extremly violations; you must to be free and force to be free. If you’re still believe the spontaneous wellbeing or whatever you’ll never be free.” Begitu Zizek berujar. Apa artinya? Silakan tanya Mas Gugel saja.
Dibuang sayang: Nampaknya John Nadal terlampau serius dan ‘kamerad’ (dengan tanda kutip), sehingga menjadi lupa untuk berfikir jail dan asik. Jika diizinkan untuk memberi catatan untuk Zizen dan narasi yang dibangun oleh saduran director film ini, saya menganjurkan ketika Nadal berada dalam gereja menemukan berapa banyak kacamata yang jumlahnya tak terhitung. Namun dengan egoistis-nya Nadal hanya mengambil satu kacamata. Mungkin sebagai seorang pria ia kurang rakus, serius dan terlampau ‘kamerad’ (dengan tanda kutip). Maka, saya menganjurkan untuk Nadal kembali ke gereja mengambil seluruh isi kotak dengan banyaknya kacamata, dan membuangnya secara jail dipelbagai tempat di ujung dunia ini sebelum akhirnya pecah karena diinjak badan besar John Armitaaj. Begitulah… []
Rawamangun, November 2016
*Hanan Radian Arasy, Pelajar-abadi yang berafiliasi langsung dengan padepokan Gin-Cun—sebuah padepokan yang berdiri di seberang Pasar Pendidikan Rawamangun, yang sering disuguhi kudapan di kedai kopi Gerakan Aksara.
Laman Film: https://www.youtube.com/watch?v=5Ch5ZCGi0PQ
[1] Secara singkat The Real adalah isitilah yang merujuk pada gambaran intelektual Psychoanalisis yakni Lacan sebagai fase sebelum The Symbolic yang merujuk pada hakikat dunia dimana kita ada sebelum kita lahir. (Le Poe Seminaire: Jaqcues Lacan in 1950)
[2] Istilah yang sengaja digunakan oleh penulis untuk merujuk pada penyangsian sebuah gagasan yang tidak orisinil.
0 notes
Text
Gagasan Reflektif dari “Masalah Remeh – Temeh Kehidupan Sehari – hari” menjadi Makna Sosial dalam Masyarakat; Pendidikan Berbasis Kebudayaan Lokal Masyarakat Indonesia

Sumber Gambar: http://blog.unnes.ac.id/novita3011/?paged=2
Oleh: Hendi Roy
“Pendidikan adalah, ditunjukan untuk humanisasi diri dan sesama, melalui tindakan sadar untuk mengubah dunia” – Paulo Freire [1].
Gagasan yang disampaikan oleh Freire diatas sangat emansipatoris dan menunjukkan bahwasanya melalui pendidikan Manusia bisa menjadi “Manusia” seutuhnya dan bahkan mampu merubah keadaan dunia. Ketika membaca konsepsi diatas, saya termenung sejenak dan berpikir, lalu bagaimana melihat pendidikan hari ini? Apakah konsepsi tersebut sejalan dengan praktik pendidikan dan realitas sosial hari ini? Dan, menurut saya tidak perlu melihatnya jauh dalam scope global, tengoklah berbagai fenomena sosial dinegara kita tercinta ini, Indonesia. Diberbagai media massa, banyak orang – orang intelek (katanya) tidak menggunakan kemampuan berpikir mereka dan gagasan dari pengetahuannya untuk menjadikan keadaan sosial masyarakat harmonis dan sejahtera. Tak lebih mereka saling bertarung dengan sengit untuk mencapai kekuasaan tertinggi dan saling menjatuhkan satu sama lain. Jika kalian tidak percaya, nyalakan televisi atau buka telepon pintar kalian yang pastinya terhubung dengan internet, lihatlah begitu ciamik nya para “Pasangan Pemimpin” itu membungkus gagasan dan program mereka yang lagi – lagi katanya mampu merubah keadaan masyarakat ibukota dengan jargon – jargon dan praktik blusukan mereka dan pastinya terlihat jelas dalam “Adu Argumentasi” mereka beberapa saat lalu – dan “baku hantam” terjadi untuk menjatuhkan yang lain. Benar adanya memang, secara naluriah manusia selalu ingin memiliki kekuasaan dan ingin memiliki banyak kekayaan secara materil maupun non-materil, tetapi apakah sepakat kalian semua yang membaca tulisan ini ketika semua itu dilakukan tanpa pencerdasan dan tindakan untuk kepentingan bersama? Dan, lagi – lagi tetap dengan kondisi yang sama, “Si miskin dengan senyum dan harapan semu nya, lalu Si Kaya dengan tawa bahagia dan langkah pastinya menerjang masa depan gemilang”. Sungguh miris!!! Tetapi jangan pesimis bahwasanya masyarakat yang cerdas dan kritis masih dapat diwujudkan dengan Pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Karena pendidikan adalah senjata terkuat yang ada, menurut Nelson Mandela.
Beberapa minggu lalu ketika diminta dengan penuh hormat oleh salah seorang Dosen Pengampu mata kuliah untuk membuat esai – padahal itu untuk nilai akhir – saya, kembali teringat akan satu penerapan sistem dalam dunia pendidikan yang bersinggungan dengan kebudayaan lokal. Betul sekali, Pendidikan berbasis kebudayaan lokal (kearifan lokal). Hal ini sangat menarik dan unik melihat bahwa pendidikan hari ini telah dikooptasi oleh berbagai kepentingan, dan paitnya lagi komersialisasi dalam dunia pendidikan pun tiada henti dan ujungnya. Mengapa sangat menarik dan unik? Karena ini merupakan satu langkah praksis, melihat bagaimana budaya lokal hari ini makin “terpinggirkan” posisinya dengan adanya Budaya Populer yang sangat “populer” dikalangan masyarakat. Disamping itu, dalam hemat saya terlintas bahwa gagasan dan langkah ini dalam sistem pendidikan setidaknya adalah upaya untuk melakukan kembali penguatan makna sosial bagi para pelajar dengan nilai – nilai sosial dalam budayanya.
“Yang saya maksud dengan kebudayaan disini adalah lingkungan aktual untuk berbagai praktik, representasi, bahasa dan adat-istiadat masyarakat tertentu. Yang juga saya maksudkan adalah berbagai bentuk akal sehat yang saling kontradiktif yang berakar dalam, dan membantu membentuk, kehidupan orang banyak” [2].
Saya mengutip salah satu konsep kebudayaan yang disampaikan oleh Stuart Hall, salah satu pemikir dari Mazhab Birmingham. Dalam pandangan Hall, kebudayaan adalah hasil akumulatif dari tindakan dalam masyarakat yang tercerminkan melalui bahasa, adat istiadat, pemikiran, nilai – nilai filosofis kehidupan yang pada dasarnya adalah gambaran atau proyeksi dari masyarakat tersebut. Dalam implementasinya pun kebudayaan sangat bersinggunga dengan aspek – aspek lain di masyarakat, seperti dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Maka, berbanggalah kalian dengan bangsa Indonesia yang mampu melakukan penerapan pendidikan dengan berbasis pada kearifan lokal (kebudayaan lokal). Setidaknya, pemerintah masih punya kepedulian akan kebudayaan lokal masyarakat, terlepas lebih seringnya mereka duduk tenang dikursi “keemasan” sana.
Masyarakat Indonesia tersebar secara luas diberbagai wilayah yang memiliki ciri khas masing – masing dalam kehidupannya sehari –sehari. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dengan hampir memiliki 300 lebih suku dan 500 bahasa daerah menjadikannya sangat beragam dalam hal nilai – nilai yang berkembang dalam masyarakat [3]. Setiap daerah dengan ciri khas nya masing – masing menciptakan keunikan yang membedakannya dengan daerah lain. Sebagai contoh kebudayaan yang dimiliki masyarakat Jawa, masyarakat Jawa yang sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara baik melalui pola transmigrasi maupun kesadaran sendiri, namun masih mempunyai ikatan batin yang kuat terhadap budayanya, sehingga interaksi sosial tetap dalam sikap yang nJawani, walaupun tidak terekspresikan dalam budaya yang utuh [4]. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa tersebut adalah satu dari segelintir budaya – budaya lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Dalam implementasi budaya – budaya lokal tersebut terlihat dari praktik yang dilakukan dalam segala aspek kehidupan mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, pariwisata, lingkungan, dsb.
Ciri khas akan suatu kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai – nilai masyarakat dan filosofi hidup yang sering mendapatkan sebutan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya [5]. Secara tidak langsung kearifan lokal kebudayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mempraktikan perilaku dan tindakan sehari – hari nya yang berkaitan dengan nilai – nilai yang tertanam dalam dirinya dalam ruang tertentu.
Kontekstualisasinya memang dapat kita temukan dalam berbagai ruang dalam masyarakat. Sebab, hari ini setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari kebiasaan yang melekat dalam identitas sosialnya. Namun, derasnya arus globalisasi dan modernitas hari ini menjadikan pergeseran dalam memaknai kebudayaan lokal tersebut. Masyarakat mulai terbawa oleh ombak – ombak budaya populer dan menjadikannya sebagai acuan dalam praktik kehidupan sehari – hari nya. Identitas sosial akan kebudayaan lokal mereka pun mulai luntur dan tidak lagi terlihat eksistensisnya. Melihat fenomena itu, akhirnya dilakukan upaya untuk menyadarkan kembali tentang pentingnya memaknai kebudayaan lokal dalam implementasinya sehari – hari. Salah satunya melalui ruang pendidikan yang hari ini menjadi kebutuhan akan masyarakat karena telah mengakar dalam konstruksi realitas sosial.
Pengertian pendidikan berbasis kearifan lokal disampaikan oleh Jamal Ma’mur yang mengatakan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik [6]. Pertarungan antara budaya lokal dan budaya populer sering menjadikan pergeseran akan pemaknaan kebudayaan dalam masyarakat. Dengan demikian melalui ruang pendidikan, kearifan lokal atau kebudayaan lokal coba untuk dikembalikan lagi posisi idealnya. Hal ini juga telah diatur oleh Perundang-undangan pemerintah yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
Melihat upaya diatas kita teringat dengan konsepsi pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa dalam setiap sejarah umat manusia barangsiapa yang menguasai basis materil dalam masyarakat, pastinya akan menguasai pula gagasan atau ide yang berkembang dalam masyarakat. Mengapa demikian, sebab hari ini basis materil dari masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi dalam pendidikan dan kebudayaan pun seperti itu. Siapa yang menjadi atau menguasai suatu pengetahuan dan kebudayaan dalam masyarakat akan menentukan gagasan dan ide yang diproduksi kedepannya.
Contohnya dari penerapan sistem pendidikan berbasis kearifan lokal ditemui dalam masyarakat Purwakarta, yang dipublikasi dalam suatu artikel di laman website.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan sempat memberikan pemaparan terkait sistem pendidikan yang diterapkan di daerah kepemimpinannya dalam forum International Young Leader Assembly di markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejumlah peneliti dunia tertarik untuk mengkaji sistem yang berbasiskan kebudayaan Sunda tersebut.
"Mereka tertarik untuk meneliti, dan saya persilakan mereka untuk datang ke Purwakarta untuk meriset bagaimana sistem pendidikan yang telah diterapkan," ujar Dedi melalui keterangan tertulis diterima Dream, Jumat, 21 Agustus 2015.
Dedi mengatakan sistem pendidikan tersebut sengaja dibuat sebagai terobosan dalam menanamkan nilai-nilai kebudayaan Sunda di kalangan pelajar. Dia mengaku bersyukur langkah terobosan tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari dunia internasional.
"Syukur Alhamdulillah, penerapan pendidikan yang berbasis kebudayaan Sunda mendapatkan perhatian lebih, ke depan mutu pendidikan akan meningkat lagi," ungkap Dedi.
Sistem pendidikan di Purwakarta mewajibkan setiap siswa untuk melakukan beberapa kegiatan seperti masuk sekolah pukul 06.00 WIB dan membawa bekal makanan dari rumah.
Selain itu, siswa wajib membuat tas sendiri, memelihara hewan ternak dan bercocok tanam sebagai bentuk pembangunan karakter yang mandiri.
Sistem tersebut ditunjang dengan pendidikan membentuk mental spiritual. Cara tersebut ditempuh melalui kewajiban menjalankan puasa dua kali dalam sepekan, baca tulis Alquran dan mendirikan Salat Duha [7].
Pemerintah daerah Purwakarta sadar dan yakin bahwa dalam pendidikan sejak dini pun para pelajar harus memiliki pemahaman kembali akan nilai – nilai masyarakat dan filosofi kehidupan yang ada didaerahnya. Dengan menggagas kebudayaan khas masyarakat sunda yang kental akan nilai kreativitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya, masyarakat terkhusus pelajar – pelajar sekolah diajari dan dibimbingan dalam pembuatan berbagai alat – alat yang menunjang proses pembelajaran mereka seperti tas. Hal ini dilakukan agar setidaknya mereka memaknai bahwa alam menyediakan kebutuhan mereka jika mau mengelolahnya dengan bijak dan arif. Selain itu, penguatan akan mental spiritualitas dilakukan pula sebab nilai – nilai yang terkandung dalam ajaran leluhur dan agama akan menjadi bekal yang baik nantinya ketika mereka harus bersaing dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya.
Dengan demikian, sistem pendidikan dijadikan sebagai ruang praktik dalam menimbulkan kembali makna dari nilai – nilai kehidupan masyarakat. Terlepas dari bagaimana proses berjalannya dalam pendidikan hari ini, namun ini menjadi suatu proyek bagi masyarakat terutama para pelajar bahwa mereka perlu mempelajari dan mengingat kembali segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan lokal mereka selain dari pengenalan dan sosialisasi dari orang tua. Kebiasaan sehari – hari yang menjadi konstruksi dalam masyarakat menjadi penting dalam melihat kembali nilai – nilai positif yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.
Gagasan Reflektif dari “Masalah Remeh – Temeh Kehidupan Sehari – hari” menjadi Makna Sosial dalam Masyarakat
Sub-bab ini mungkin terkesan mengawang – awang dan sulit dipahami bagi orang yang membacanya. Tetapi, saya akan mencoba untuk “membumikan” nya dengan menggunakan kerangka berpikir Raymond Williams serta kontekstualisasinya terkait bahasan tulisan ini. Pertama sebelum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Williams mengenai konsepsi kebudayaannya, perlu dipahami bahwa gagasan ini lahir sebagai bentuk kritik keras terhadap Matthew Arnold yang memberikan konsepsi akan kebudayaan atau budaya elitisme. Bagi Arnold, Kebudayaan adalah sebagai “hal terbaik yang telah dipikirkan dan dikatakan di dunia ini” [8].
Williams memiliki pandang yang berbeda mengenai kebudayaan dengan Arnold. Raymond Williams mengembangkan suatu pemahaman yang menekankan karakter keseharian kebudayaan sebagai “keseluruhan cara hidup”. Williams secara khusus memberikan perhatian pada pengalaman kelas pekerja dan bagaimana mereka secara aktif mengkonstruksi kebudayaan mereka [9]. Jika kita kontekstualisasikan dengan tulisan ini, terdapat titik temu bahwasanya kearifan lokal yang dipraktikan dalam ruang pendidikan adalah seluruh perilaku dan tindakan khas yang dimiliki komunitas masyarakat dalam wilayahnya masing – masing yang berangkat dari konstruksi nilai – nilai yang mereka miliki. Kearifan lokal atau kebudayaan lokal adalah suatu praktik “keseluruhan cara hidup” yang dilakukan oleh tiap generasi yang ada dalam kehidupan sosial mereka.
Proses kontruksi sosial yang nantinya menjadikan pemaknaan sosial dalam diri masyarakat berlangsung sejak lama. Namun, proses perubahan sosial yang dinamis dalam masyarakat hari ini yang sangat kompleks terkadang menjadikan masyarakat melupakan nilai – nilai yang ada dalam kehidupannya. Padahal sebenarnya nilai – nilai tersebut mengandung filosofi tersendiri yang sangat berguna dan nanti nya pasti menentukan proses kehidupan kedepannya. Itulah mengapa penting hari ini bahwa kebudayaan lokal perlu mendapatkan perhatian penting dalam ruang – ruang kehidupan lainnya termasuk dalam pendidikan. Sebab seperti kritik yang diberikan Williams untuk Marx, Ia menjelaskan bahwa apa yang biasanya dianggap sebagai superstruktur, seperti budaya dan politik, sebenarnya merupakan “basis”. Ditambahkannya kemudian bahwa “basis” merupakan konsep yang lebih penting untuk digali apabila kita mau memahami realitas dari proses budaya karena “basis adalah keberadaan sosial yang nyata seorang manusia” [10]. Dengan melihat bahwa kebudayaan dan prosesnya sebagai sesuatu yang penting dalam menentukan gagasan dan ide yang berkembang nantinya, maka memang perlu bahwa implementasinya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat.
Contoh lain dari peng-implementasian kearifan lokal atau kebudayaan adalah dalam Skripsi yang ditulis Agung Wahyudi.
SMK Tri Hita Kirana (THK) merupakan salah satu satuan sekolah diprovinsi Bali yang mengembangkan kearifan lokal di Bali. SMK THK mengambil kearifan lokal dari desa pakraman dan banjar berupa nilai yang disebut “cucupu manik” (isi dan wadah). Inti dari nilai tersebut pada intinya mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dengan cara berinteraksi kepada sesama dan berinteraksi kepada sang pencipta. Nilai tersebut menjadi pedoman SMK THK dalam menjalankan roda pendidikan. Cucupu manik di ambil dari daerah setempat dan ditanamkan pada warga SMK THK dengan tujuan agar peserta didik yang nantinya diharapkan dapat menguasai berbagai ilmu tanpa melupakan dari mana mereka berasal dan dari mana mereka diciptakan. Selain itu tujuan lain untuk membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi.
Satuan Pendidikan mengengah pertama juga menerapkan kearifan lokal dalam kegiatan pembelajarannya. Salah satunya adalah SMP Bojonegoro yangterletak di Kabupaten Jepara juga menerapkan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pelajaran keterampilan mengukir. Pada pertemuan awal dikenalkan jenis-jenis mata ukir, kemudian jenis-jenis ganden (palu yang terbuat dari kayu). Selanjutnya diberi pelajaran cara mengukir pada media kayu yang berbeda karena ada kayu yang keras dan ada pula kayu yang lunak. Pelajaran yang lain adalah cara menggambar berbagai jenis pola seperti bunga, burung, dan lainnya. Mulai kelas 1 sampai kelas 3 diberikan materi yang berbeda, misalnya membuat asbak, pedang-pedangan dari kayu, sampai membuat ukiran ornament untuk meja dan kursi.
Pada saat ujian akhir siswa diminta untuk membuat karya ukir dengan berbagai macam pola yang telah ditentukan. Keterampilan tersebut diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk melestarikan kearifan lokal Kabupaten Bojonegoro yang berupa seni ukir karena Bojonegoro sangat terkenal sebagai penghasil ukiran kayu jati [11].
Penerapan kearifan lokal dalam sistem pendidikan diatas adalah contoh bahwa dari kebiasaan sehari – hari akhirnya menjadi sebuah kontruksi sosial dalam masyarakat. Bagaimana pada akhirnya nilai – nilai dalam masyarakat penting untuk diperhatikan. Mungkin memang hal yang “remeh-temeh” mengenai persoalan untuk membangun interaksi dengan sesama dan pencipta (Tuhan), tetapi jauh dari pada itu ada nilai – nilai kehidupan yang ditanamkan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri dalam masyarakat terlebihi kita pun harus memiliki keyakinan dan kepercayaan akan ajaran yang kita anut. Begitu juga dengan masyarakat Jepara yang mengajarkan mengenai teknik ukiran kayu yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat adalah usaha memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada generasi penerus, bahwa produk kebudayaan yang dihasilkan mereka tidak kalah dengan produk luar, nilai kemandirian dan kreativitas sangat ditonjolkan disini.
Penutup
Sebagai penutup dari tulisan ini, saya mencoba untuk kembali melihat bahwa kearifan lokal yang dianggap “masalah remeh – temeh dalam kehidupan sehari – hari” ternyata memiliki nilai – nilai kehidupan dan filosofi tersendiri dalam merendam guncangan budaya populer hari ini dan sisi individualistik. Dan pendidikan sebagai ruang yang dianggap sangat berpengaruh dalam proses kehidupan masyarakat merupakan sarana untuk implementasinya. Melalui penerapan kearifan lokal atau kebudayaan lokal masyarakat dalam ruang pendidikan, merupakan salah satu langkah praksis untuk kembali melihat kebudayaan sebagai suatu hal yang penting dalam sejarah umat manusia. Selain itu, melalui sistem penerapan pendidikan berbasis kearifan lokal ini bukan hanya sekedar pemenuhan kurikulum saja, tetapi daripada itu ada makna sosial yang terkandung dalam setiap kebudayaan yang ingin disosialisasikan kembali. Penguatan makna sosial ini adalah gagasan yang penting dilakukan mengingat keadaan sosial budaya hari ini telah banyak mengalami pergeseran. Kembali mempelajari “kebiasaan hidup sehari-hari” adalah penting untuk menjadikan kita “manusia seutuhnya” yang mengenal kebudayaan lokal daripada kebudayaan luar.
Referensi
[1] Dikutip dari Listiyono Santoso, dkk (2015), ‘Epistemologi Kiri’ (Ar-ruzz Media: Yogyakarta). Hal. 130.
[2] Dikutip dari Chris Barker (2013), ‘Cultural Studies Teori dan Praktik.’ (Kreasi Wacana: Yogyakarta). Hal. 8.
[3] Dikutip dari Respati Wikantiyoso dan Pinto Tukuko (2009), ‘Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota: Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Bekelanjutan’ (Grup Konservasi Arsitektur dan Kota: Malang). hlm. 6).
[4] Dikutip dari GKR Wandasari (2013), ‘Aktulialisasi Nilai-Nilai Tradisi Budaya Daerah Sebagai Kearifan Lokal Untuk Memantapkan Jatidiri Bangsa’ (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta). hlm. 2.
[5] Dikutip dari Respati Wikantiyoso dan Pinto Tukuko (2009), ‘Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota: Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Bekelanjutan’ (Grup Konservasi Arsitektur dan Kota: Malang). hlm. 7.
[6] Agung Wahyudi (2014), ‘Implementasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal Di Sd Negeri Sendangsari Pajangan’ (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta). hlm. 3.
[7] (kaskus.co.id, 2015).
[8] Dikutip dari Chris Barker (2013), ‘Cultural Studies Teori dan Praktik.’ (Kreasi Wacana: Yogyakarta). hlm. 38.
[9] Dikutip dari Chris Barker (2013), ‘Cultural Studies Teori dan Praktik.’ (Kreasi Wacana: Yogyakarta). hlm. 39.
[10] Rianne Subijanto (2014), ‘Kritik terhadap Klaim “Kritis” Cultural Studies, Political Economy of Culture, dan Critical Theory, Indoprogress: Jurnal Pemikiran Marxis. Vol. I Nomor 01 (Resist Book: Yogyakarta). hlm. 74.
[11] Agung Wahyudi (2014), ‘Implementasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal Di Sd Negeri Sendangsari Pajangan’ (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta). hlm. 6
0 notes