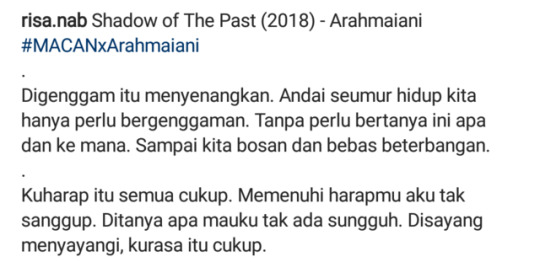it's said there isn't anyone you couldn't learn to love, once you've heard their stories
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Orang-Orang Biasa
"Ada banyak orang kaya di Kamboja ya?”,komentar ibuku kepada Chorrn, supir sewaan dari hotel yang membawa kami tergesa-gesa menuju kawasan Royal Palace dan Killing Fields sebelum matahari terbenam.
“Oh, really? What makes you thinks so?”, Chorrn malah balik bertanya, jelas terkejut. Pemandangan jalanan di ibukota Kamboja itu nampak mirip dengan kota-kota lain di Asia Tenggara tetangganya- banyak manusia dan lebih banyak lagi motor. Phnom Penh jelas merupakan kota yang ramai dan sepertinya mulai dilirik oleh investor dari negara-negara tetangganya. Banyak terlihat showroom kendaraan merk Jepang dan Eropa, pom bensin yang mudah dijumpai dan klinik modern dengan tulisan mandarin. Walaupun begitu, gedung pencakar langit dengan tulisan SAMSUNG besar-besar tetap terlihat mencolok, di perempatan lampu merah terlihat anak-anak kecil tanpa alas kaki yang meminta-minta. Beberapa di antaranya menggendong bayi yang masih keliatan merah.
“Lihat saja. Ada banyak mobil bagus berlalu lalang. Lexus, BMW... Oh lihat saja mobil sebelah kita!.”, tambah ibuku lagi. Sedikit terlalu bersemangat. Chorrn tertawa kecil sebelum menjawab “Hanya orang kaya saja yang punya mobil bagus, Mam! Kamboja masih negara miskin. Pemerintah saja yang kaya, rakyatnya tidak!.” Foto Raja Sihamoni yang dipasang di billboard besar-besar dekat pinggiran sungai Mekong menyambut kedatangan kami di pelataran taman di depan Royal Palace. Biksu-biksu berpakaian oranye berjalan sambil memegang payung. Hari ini suhu hanya menunjukkan 36 derajat tapi matahari yang aku rasakan terlalu terik. Mengernyit dan sedikit menggerutu mengenai pemilihan warna balok yang dicat kuning, seolah ingin mendukung teriknya panas matahari yang sudah sangat menyengat. Beberapa turis terlihat sedang berpiknik di bawah naungan pohon. Hari itu memang panas sekali. Beberapa anak kecil berambut kecoklatan berumur tak lebih dari sepuluh tahun berlarian mendekati kami sambil menyosongkan kemasan biji. “Feed birds, mam!”, teriak mereka. Di taman itu memang ada banyak sekali burung merpati. Tanpa menghiraukan tolakan untuk membeli makanan burung, anak-anak itu tetap gigih mengejar-ngejar kami. Tahu itu tak akan berhasil. salah satu anak berganti taktik dengan sengaja memberikanku dua bungkus makanan burung ke tanganku, seraya berkata “For you. Free.” Setelah itu mereka tetap mengikuti kami tapi kali ini dengan diam-diam tanpa mengeluarkan kata. Strategi mereka berhasil, dengan terkekeh geli akhirnya aku menyodorkan beberapa riel.
These kids know how to survive.
Phnom Penh, 2015
2 notes
·
View notes
Text
Pahlawan Tak Diperlukan di Masa Pandemi
Apa persamaan perang dan pandemi? Selain mendatangkan banyak kematian secara singkat, perang dan pandemi juga sering menghidupkan imaji tentang (ke)pahlawan(an).
Kisah para dokter dan perawat yang wafat karena terpapar COVID-19 tidak pernah tidak memantik keharuan. Sulit untuk tidak hormat kepada Dr. Michael Robert Marampe yang merelakan agenda pertunangannya ditunda, mula-mula sementara karena hendak fokus menangani pandemi, dan akhirnya selamanya karena ia meninggal. Rekaman-rekaman yang memperlihatkan tenaga medis yang kelelahan, yang dengan APD tebal dan bikin gerah masih berusaha menghibur diri dengan menari atau bernyanyi, kian mempertebal imajinasi tentang tenaga medis serupa prajurit yang tiarap dalam sepi no man’s land.
Tindakan-tindakan menggugah seperti itu sangat berlimpah, dan itu bukan monopoli para tenaga medis.
Sebuah keluarga berstatus ODP di Minahasa Utara memilih pergi ke hutan untuk mengisolasi diri karena enggan merepotkan atau membuat cemas tetangganya. Belum lama saya membaca suami istri yang baru punya bayi, keduanya bekerja sebagai ojol, tak punya tempat tinggal karena tak sanggup membayar kontrakannya di Jakarta. Mereka terlunta-lunta di sekitar Sarinah, dan rekan-rekannya sesama ojol membawa mereka ke salah satu basecamp komunitas. Seorang ojol perempuan kemudian berbaik hati menyediakan kamar kosnya untuk bayi dan ibunya itu.
Kisah hangat di masa pandemi seperti itu jumlahnya tak terhitung. Kebanyakan tak akan pernah kita ketahui karena tak sempat dicatat wartawan atau diceritakan mereka sendiri di media sosial. Boleh jadi karena mereka tak menganggap dirinya, juga tindakannya, sebagai istimewa. Barangkali bahkan mereka melakukannya nyaris tanpa alasan: memangnya butuh alasan untuk membelikan nasi bungkus kepada orang yang sedang kelaparan?
Keep reading
311 notes
·
View notes
Text

Tentang Suatu Safar (1)
Aku pingin Vietnam sih sha..
Kuy?
Kuy!
Sudah lama sekali tidak melintasi batas. Ajakan Iluk untuk bertamasya langsung tanpa babibu aku iyakan dengan terlalu antusias. Benar-benar sudah terlalu lama! Bukannya hidup kembali membosankan, hidup memang selalu bikin jenuh.. tapi kali ini aku butuh.. perlu keluar dari rutinitas. Tidak mau aku ikut-ikut menjadi manusia yang membosankan: dengan bahan obrolan penuh kepenatan, keluhan mengenai hal remeh temeh. Aku ingin petualangan!!! Kembali memegang dan menyentuh ranah asing yang selalu terasa familiar. Lagipula aku selalu ingin kembali merasakan nangkring di kursi pendek jalanan Hanoi sambil menyesap kopi hitam. Mendengarkan nada bahasa Viet yang nyaring di kuping sambil menerka-nerka maksudnya. Aku juga kangen makan sayur segarnya! Berkat Iluk, rencana impromptu ini langsung termanifestasi jadi aksi. Belum seminggu, tiket sudah dipesan dan itinerary sudah jadi. Oh oh, namun bukan shastia namanya bila hidup tanpa tantangan. Dalam perjuangan mendapat tiket harga miring yang cuma muncul sekali-kali (Itu pun pada jam-jam paling absurd! Hello jam 4 pagi? Mohon maaf), ternyata aku baru menyadari bahwa pasporku sebentar lagi sudah kadaluwarsa.....
Life starts becoming fun again! Haha
Aku dan Iluk cuma tertawa acap kali menemukan kebodohan-kebodohan. Selalu sambil terbahak sambil menyelesaikan masalah: hal yang ternyata aku sadari sangat berguna dalam perjalanan yang eh ternyata banyak lika-likunya ini! Awal Januari, gagasan bahwa dunia akan kembali dilanda sebuah pandemi terasa jauuuh jauuuh sekali. Dibanding Iluk yang sudah wanti-wanti dari jauh hari (masker? cek. vaksin? cek. handsanitizer? cek), aku baru merasakan kecemasan H-2 keberangkatan. Eh eh scrolling timeline twitter terasa mulai tidak menyenangkan. Tapi waktu itu kondisi belum bereskalasi hingga separah ini maka yasudah kami berangkat.. sambil selalu mengingatkan agar hati-hati jangan menyentuh pegangan pintu di bandara dan eits pegangan eskalator juga dijauhi!
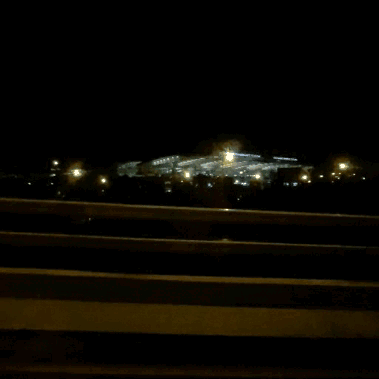
Sesaat setelah landing di Hanoi, kami tertawa terbahak-bahak. Sungguh surreal dan aneh. Dari awal memang pertemananku mengenal Iluk serta tempat-tempat yang berhasil kami kunjungi bisa bikin kening orang yang paling licin berkerut heran. Dan yang paling aneh, selalu saja ada hal yang bisa bikin aku tertawa sampai sakit perut kalau bareng Iluk. Keluar dari bandara, waktu sudah nyaris pukul 10 malam, kami mencari jemputan kami yang ternyata adalah mas-mas berkaus ungu dengan kalung emas mencolok tergantung di dadanya. Sepertinya ia sudah lama menunggu. Tanpa basa-basi dan dengan satu-dua patah bahasa Inggris seadanya, ia langsung menuntun kami masuk mobil. Aku ingin bilang ke Iluk kalau mas-masnya mirip mafia.. tapi sepertinya malam itu aku terlalu capai untuk berspekulasi. Belum pernah sebelumnya kami pergi tanpa bagasi dan setelah menenteng tas seberat nyaris 6 kilo di punggung sambil transit berjam-jam, kami cuma pingin satu: tidur!
Lagi-lagi, hidup memang terbukti tidak mudah.
Mas mafia berkalung emas ternyata kesasar dan bingung letak di mana letak homestay kami (yang ternyata memang nyelempiiit hihi). Setelah berputar-putar di kawasan yang penuh manusia (yang juga sepertinya red district? waw tengah malam pula?) selama nyaris satu jam, akhirnya kami sampai di depan muka gang homestay.
Lelah! Seru! Campur aduk.
Hanoi cukup dingin malam itu tapi selimut kami cukup tebal. Aku tertidur pulas dengan mimpi pizza dan scrabble.

1 note
·
View note
Text
mengenai rinai hujan
Mereka yang menikmati keindahan tak terduga dari kemiskinan dan reruntuhan sejarah, orang-orang yang melihat keindahan seperti lukisan di dalam puing-puing ini– mereka pastilah orang-orang luar - Orhan Pamuk
1 note
·
View note
Text
Tentang Kata-kata
Akhir-akhir ini ada suatu gagasan yang sering banget nangkring di kepala saya. Mungkin diawali dari rasa frustasi dari keterbatasan untuk mengungkapkan apa-apa yang ingin saya maksudkan atau mungkin juga dari rasa paranoid saya yang mengada-ngada tentang bagaimana dari setiap kata yang telah meluncur dari mulut saya ini tak satu pun yang mengenai makna ingin saya sampaikan.
Nirmakna. Ish
Tapi kemudian saya menemukan kutipan Nietzsche dan saya cukup terhibur karenanya. Nietzsche mengatakan:
Kata-kata ,tak lain, hanyalah simbol bagi hubungan antara satu benda terhadap benda yang lainnya dan terhadap kita; tak pernah mereka menyentuh sedikit pun akan kebenaran yang absolut (Words are but symbols for the relations of things to one another and to us; nowhere do they touch upon the absolute truth)
Komunikasi yang diutarakan melewati media berupa kata-kata, dikatakan Nietzche: “tak pernah menyentuh kebenaran yang absolut”. Mungkin karena semua serba relatif. Tergantung antara hubungan-hubungan mereka dengan yang lain, seperti sebuah jaring laba-laba dengan bentuk yang sangat unik- terlalu banyak faktor yang memengaruhi: bahasa, pengalaman, pemaknaan, budaya. Terlalu banyak.
Kemudian bagaimana komunikasi praktis yang dilakukan manusia-manusia di bumi ini? Sampai derajat manakah mereka bisa saling memahami tanpa masuk ke dalam isi kepala masing-masing?
Walaupun dengan keadaan yang sedemikian terbatasnya toh kita, manusia mencoba juga. Kita menamai tiap suasana, tiap kesan, tiap sentuhan, setiap suara untuk kemudian mengeluarkan gagasan ini yang melayang-layang di dalam kepala dan mengatakannya. Menanamkan ide yang sama ke dalam pikiran orang lain. Untuk berkomunikasi, kita mulai menamai, dan menghubungkan.
Untuk menamai tak hanya untuk menegaskan suatu eksistensi. Lebih dari itu menamai berarti membedakan keberadaan dirinya antara satu entitas dan entitas yang lainnya.Menyatakan batas, membuat perbedaan.
Beberapa orang dari belahan bumi lain menamai beberapa perasaan yang paling spesifik, yang paling unik dengan modal bahasa yang mereka miliki. Semisal Waldeinsamkeit dari Bahasa Jerman yang berarti perasaan solitude ketika berada sendirian di hutan dan keterikatan terhadap Alam atau mungkin yang paling saya suka,dari Bahasa Jepang Komorebi- cahaya matahari yang melewati sela-sela dedaunan.

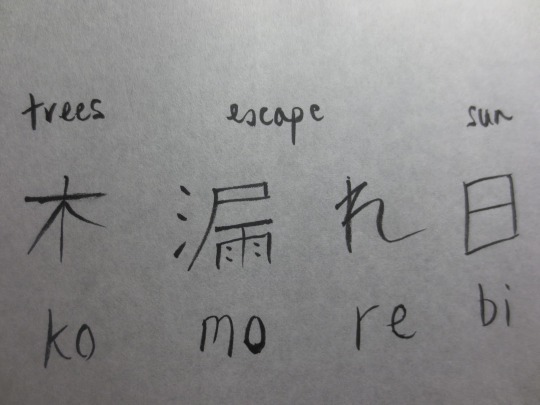
Namun penemuan ini membuat saya menanyakan banyak hal-hal lain seperti berapa banyakkah suasana, keadaan spesifik yang masih belum bernama? Apakah keadaan spesifik itu harus bersifat universal atau spesifik bagi tuiap budaya, bagi tiap kumpulan orang? Bagaimana mengenai keadaan paling spesifik yang bersifat personal- mungkin seperti, perasaan ketika mencium baju habis laundry atau perasaan ketika mendengar gemerisik bambu yang digoyang angin? Tapi hey, apakah untuk berkomunikasi kita harus selalu memakai media kata-kata? Haruskah selalu menamai?
Entahlah, mungkin memang ada batasan di tiap semua kata dari setiap bahasa. Ada sesuatu yang hanya mungkin bisa ditangkap bahkan tanpa menggunakan kata-kata. Yang melebihi itu semua.
Sesuatu yang melebihi itu semua
7 notes
·
View notes
Text
Tentang Cerita
Untuk mencapai telingamu, katanya, cerita datang dari dimensi yang amat jauh..
Dari tafsiran akan sebuah kenangan dari masa lampau atau mungkin harapan dari entah siapa di masa yang akan datang. Atau bisa jadi cuma selentingan kabar burung yang tersebar dari generasi ke generasi lewat obrolan sore yang biasa diperbincangkan sebelum datang masa di mana manusia menikmati sajian dari benda kotak bernama televisi.
Dalam satu cerita bisa ada berbagai macam kenangan mengenai manusia dan bumi. Ah, dan juga mengenai Hidup.
Begitu sentimental.
Atau mungkin karena hampir setengah dari hidup saya dihabiskan bersama seorang nenek maka saya jadi begitu menghargai harga dari sebuah cerita yang diucapkan olehnya berulang-ulang seraya matanya berbinar dan sorotnya kembali segar seakan-akan setiap helaan napas yang diambil di sela-sela spasi kata menghembuskan jiwa ke dalam kisahnya. Menjadi hidup. Menjadi nyata.
Dan saya menikmati setiap adegan, setiap kesan, setiap pemaknaan.
Maka ketika masuk masa di mana saya mulai menikmati tiap adegan kehidupan dan tiap lakon yang datang di dalamnya, saya mencoba untuk mulai mendengar. Dan membuka.
Hal yang cukup sulit. Mengingat asas praduga bersalah yang saya junjung tinggi- manifestasi kehidupan perkotaan yang serba curiga dan gelisah, menjadi gembok yang kuat dan sulit ditembus. Sebuah mekanisme pertahanan alami, saya kira, tapi seperti amatir yang bermain dengan boomerang, mekanisme itu bisa berbalik. Menghantam dan melukai.
Manusia mana yang bisa tidak bercerita atau tidak mau mendengarkan sebuah cerita?
Jonathan Gottschall dalam bukunya, The Storytelling Animals, mengatakan
1 note
·
View note
Text
Khmer oh khmer


“Berapa lama di Kamboja?”, tanya Berg. Lelaki berperawakan kurus berkulit kecokelatan, nyaris merah, berumur kira-kira empat puluh tahunan itu bertanya dengan bahasa Inggris yang kental dengan aksen Khmer. Berg, guide kami, sepertinya adalah orang etnis Khmer murni pertama yang aku temui di Kamboja. Dengan rambut panjang sebahunya yang diikat, penampilan Berg mengingatkanku dengan suku Indian dengan nama-nama lucu yang pernah aku baca di buku. Namun, wajahnya lebih mirip dengan ras India. Eksotis sekali. Dia dan leluhurnya sudah lama menetap di Siem Reap. “Dua hari.”, jawabku, sedikit malu karena perjalanan kilat yang banyak diprotes orang ini. Hah, apa boleh buat.. “Satu hari di Phnom Penh dan satu hari di Siem Reap.” “Cepat sekali! Kau tahu, belum beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan turis asing. Dia bilang dia berlibur di Vietnam selama nyaris tiga minggu dan hanya berada dua hari di Kamboja. Padahal begitu banyak yang bisa kau lihat di Kamboja, you know?”, ujarnya sambil sedikit mendesah. Nampak cukup kecewa.
Mencari pekerjaan di Kamboja memang adalah perkara yang tidak mudah. Negara yang baru beres dari huru-hara dan perang saudara pada sekitar tahun 90an ini masih merangkak dalam pertumbuhannya. Karena warisan situs Angkor, sektor pariwisata menjadi tumpuan warga di sekitar Siem Reap untuk mencari nafkah walaupun peran Pemerintah untuk mendukung rakyatnya sendiri masih sangat ragu-ragu. Belum lagi budaya korupsi, kolusi dan nepotismenya yang katanya paling jempolan (Indonesia aja kalah! *katanya lho*) Sudah menjadi rahasia umum kalau partai yang berkuasa di Kamboja saat ini didukung oleh Pemerintah Vietnam- mengakibatkan aliran imigran ilegal warga Vietnam ke Kamboja untuk bekerja di pabrik yang juga kepunyaan Vietnam dan salah satu alasan kenapa bandara internasional di Siem Reap tidak memiliki direct flight ke negara-negara strategis di wilayah Asia Tenggara.
“Semuanya harus transit lewat Vietnam atau Thailand. Jadi turis tidak tahu banyak tentang Kamboja. Apalagi kota-kota selain Siem Reap ini!” Berg pun mengakhiri curcolan kilatnya dengan hembusan napas yang sedikit disamarkan. Ia melanjutkan curcolannya dengan cerita bagaimana tetangganya yang adalah orang Vietnam lolos dari jeratan hukum walaupun telah mencuri banyak barang dari kawasan di daerahnya karena adanya “telepon dari atas”. Belum lagi berlakunya mata uang Dolar selain mata uang resmi Kamboja, Riel, sebagai alat pembayaran membuat Riel nyaris tidak berharga dan harga barang melonjak mengikuti standar dollar. Hal yang sangat sulit, mengingat pembayaran upah masih mengikuti standar Riel.
Aku membiarkan udara masuk sedikit terlalu banyak ke dalam dadaku setelah mendengarkan cerita itu. Rasanya sesak sekali melihat kejatuhan setelah kebangkitan.Di depan relik kuil Bayon tadi, baru saja Berg bercerita dengan bangganya bagaimana suku Khmer mengambil alih kekuasaan atas daerah kuil tersebut dari Kerajaan Cham. Bagiamana gagahnya pejuang Khmer yang digambarkan dengan telinga panjang melawan para pejuang Cham digambarkan khas dengan matanya yang lebih sipit. Bagaimana betapa megahnya peninggalan halaman kawasan tempat pemarkiran gajah-gajah yang dipakai untuk kendaraan sang raja yang dianggap jelmaan dewa. Betapa bahwa kawasan ini sendiri, Siem Reap berarti Pembantaian Siam- suatu monumen kenang-kenangan akan kemenangan terhadap bangsa Siam.

Pembully-an suatu bangsa oleh bangsa lain yang lebih berkuasa. Bisakah kita sama-sama hidup berbahagia saja lah?
Sesaat setelah meninggalkan kawasan Angkor, ibuku bercerita tentang anak-anak yang menjajakan oleh-oleh di pekarangan parkir kuil. Beberapa nampak memakai baju seragam dan semuanya meneriakkan hal yang sama “Madaam, please buy some souvenirs!!!” Ibuku yang sedang istirahat di mobil, tepar setelah keliling kompleks Angkor Wat yang satu situs candi itu nyaris segede Borobudur sendiri cuma bisa melambai sambil mengacuhkan anak-anak itu. Namun ada satu anak yang berganti taktik. Anak perempuan berambut panjang yang kira-kira berumur sekitar tiga belas tahunan itu menaruh barang belanjaannya di bawah dan malah mengajak ngobrol ibuku dengan bahasa inggris yang ternyata fasih. “Where are you from Mam? Malaysia?” “No, no. I’m from Indonesia. Do you know where Indonesia is?”, ibuku balik bertanya “Of course Mam. I even know your capital city and your currency.”, katanya sambil tersenyum “Oh really?” “ Yes. Oh and if i’m right, would you mind buy some of my souvenirs pleaseee?” Akhirnya di anak itu pun sukses membuat ibuku membeli beberapa gantungan kunci bergambar penari apsara. Sambil menungggu aku dan adikku datang dari tur kami keliling kuil, ibuku melanjutkan obrolannya dengan anak perempuan itu. Ternyata bahasa inggris dia pelajari dari relawan asing yang mengajar di sekolah internasional dimana ia bersekolah. Selain Indonesia, ia juga hapal nyaris semua ibukota dan mata uang di Asia dan Eropa, katanya bangga. Oh, dan juga Amerika!, tambahnya. Di daerah Siem Reap, nyaris seluruh orang kamboja yang aku temui bisa berbahasa inggris, tidak seperti jaman aku yang masih harus menggunakan bahasa tarzan karena tidak seorang pun bahkan paham arti yes dan no di Hanoi. Seperti anak lelaki Berg yang kami temui sedang membantu di kios miliknya di pasar malam, selain bahasa inggris ia juga mampu berbincang dalam bahasa perancis. Ini bercerita banyak tentang bagaimana usaha warga kamboja untuk mempromosikan pariwisata dan budaya mereka. Bahkan tanpa campur tangan dari pemerintah.
Menatap wajah sumringah Berg saat menambahkan bahwa anak sulungnya itu akan mulai berkuliah di universitas di Phnom Penh, sebuah kesadaran tiba-tiba datang bahwa dari tangan anak-anak inilah entah bagaimana nasib Kamboja semoga saja akan lebih bahagia.
Siem Reap, 20 Agustus 2015
5 notes
·
View notes
Text
I started reading about books on the abduction of G30SPKI activists few months ago, after finishing the book, my curiousity felt it was only right like to continue the whole theme while I am at it by rereading Loung Ung's memoir First They Killed My Father as a child soldier escaping the narrow death from one of the many Killing Fields in Cambodia. Then my memory came back to this place over and over again.
Suasana di Killing Fields Chong Euk pukul empat sore senin itu nyaris khidmat. Sekalipun beberapa turis berlalu lalang, nyaris tidak ada yang menaikkan suara mereka. Semua menunduk. Mata berwarna-warni yang berkaca-kaca. Semua tersedu tapi ,anehnya. tak ada air mata yang mengalir. Seakan-akan kompak mengatakan bahwa sungguh tidak ada gunanya menangisi apa yang telah lalu- menangisi badan-badan yang terkubur tanpa keadilan di bawah tanah ini. Yang penting adalah Jiwa, bukan? “Ruh yang bahagia selama-lamanya”

Aku berdiri mematung memandang sebuah papan, suara dari dalam headphone sebagai guide yang diberikan dalam berbagai bahasa di pintu depan mengucapkan selamat datang dalam nada pelan. Dalam bahasa Inggris yang fasih itu , aku bisa mendengar aksen yang kental. Sang narator adalah saksi hidup akan apa yang terjadi di tanah itu hanya beberapa dekade yang lalu. Cerita-ceritanya nyaris familiar. Seperti cerita-cerita jaman PKI dan hukuman bagi mereka yang terlibat komunisme di tanah air yang sering kudengar. Tapi manusia mana yang bisa familiar dengan cerita akan penderitaan? Adikku yang tak tahan meneruskan cerita yang pahit itu sudah menyerah. Cuma duduk-duduk dengan mata termenung memandang entah apa. Kesengsaraan yang biasanya lewat sambil lalu di kalimat buku sejarah kini berdiri sangat nyata dan bisa kusentuh. Ada suara-suara, ada kesan. Ada korban tapi tak ada pelaku.
Semak berwarna hijau tertimpa cahaya remang kekuningan dari matahari yang beranjak senja di sepetak tanah kecil yang berumput itu. Tidak begitu luas. Mungkin cuma setengah dari lapangan bola. Ada kupu-kupu dan beberapa serangga beterbangan di jalanan berbunga dengan rumput yang nampak lebih rata. Suara narator mengatakan bahwa lapangan ini adalah kuburan masal dari nyaris lebih dari seratus jiwa. Aku berjongkok di depannya.
Aku masih ingat beberapa macam bentuk pikiran yang terlintas saat itu:dari mulai keinginan untuk memulai serentetan sumpah serapah,erangan kesedihan, ketidakpercayaan, numbness hingga akhirnya kosong dan tersisa pada seonggok pertanyaan tak berarti “Apa yang bisa aku lakukan?”
Dari kejauhan ada suara riuh teriakan gembira anak-anak kecil dalam bahasa Khmer. Sepertinya ada sekolah negeri tidak jauh dari tempat ini. Secercah ironi yang terbungkus harapan itu nampak indah sekali senja itu.
180815
4 notes
·
View notes
Text
Reminder
The most important things are the hardest things to say.
They are the things you get ashamed of, because words diminish them–words shrink things that seemed limitless when they were in your head to no more than living size when they’re brought out.
But it’s more than that, isn’t it?
The most important things lie too close to wherever your secret heart is buried, like landmarks to a treasure your enemies would love to steal away. And you may make revelations that cost you dearly only to have people look at you in a funny way, not understanding what you’ve said at all, or why you thought it was so important that you almost cried while you were saying it.
- Stephen King
refrain yourself from asking personal things just out of your curiousity. especially when you dont have a slightest actual interest to their problems or life or even empathy to give to them.
it’s not a nice thing to do, you see, to put a person in position where they have to bare their heart open and just leave them once your thirst is fulfilled.
4 notes
·
View notes
Text
Life Is Hard, Kiddo- Wake Up
Singaporeans are not into the small talks- not even the Uber drivers nor the taxi drivers.
For a person that always welcomes any random conversations with strangers especially while travelling, this particular behavior hits me in a hard way.
People switch into invisible mode once they are inside MRT, at bus stop or any other public spaces. Their silent behavior loudly scream, “You do you, I do me. Thank you, now no touching, no eye contact plz .” Elevator rides are always so painfully awkward. Oh, and personal space, you don’t want to mess with that.
Communication is strictly limited mostly for economic purposes. Try to ask for direction to those smiley faces of street vendor in Bugis Street and observe how that sweet expression turns sour as they show you the way instead of showing you products that they sell. Oh, that sweet capitalist cordiality!
Thus, I decided that I don’t really like this city on my second evening. Premature decision, yes.
But as you are trapped by forest of sky scrappers, intimidated by man-made advanced technology, you oddly crave for human interactions.
It was raining as I crossed the street with my newly-bought umbrella- 7 dollars worth striped umbrella- I watched other people open up their own umbrellas. Colors suddenly popping up everywhere in the middle of grey street. Looking at clock in my phone, I noticed how my step counts nearly hit 20k. No wonder my sole felt burning. I love walking but it was only noon and I needed to spare this body for further city sighting later today. So I decided to get back to my lodging. Perhaps soaking my feet into a warm water. That would be a heaven, I thought. I walked my way passed through 24 hour Indian market called d Mustofa Center. They sell literally everything. There’s this running joke between the S’poreans how if you could not find something in Mustofa Center, it might as well not exist in this world. Well, it’s sort of true.
Then, I stepped my way into the hotel lobby. The air conditioner instantly putting my sanity intact. It was such a hot day, I couldn’t wait to hit the room and soak my soles inside cold water. That would be a heaven. I came to my room and saw a cleaning lady just about to enter. “Puan, sebentar kamarnya saya bersihkan”. she said. Seems like the hijab style that I wore and my clothing somewhat looked like the neighboring country as she kept addressing me in Malay. “Oh ya ga apa-apa”, I told her. There my Indonesian slangs gave me away. She looked at me and asked if I was Indonesian. I nodded and ask if she was one too. She proceeded to introduce herself and her story there. Named Maya and coming from Sukabumi, this year was her 12th year living in Singapore. “ Semua susah. Semua mahal”, her brows frowned as she vacuumed the room. “Lebih baik hidup di kampung halaman”, then she said as if she was talking to herself.
“Oreonya dimakan ya mbak?” , she asked while checking the room’s mini bar.
“Iya mbak.”, I answered her, remembering my rash moment a day ago when my stomach was groaning for some food that I literally grabbed anything I could find inside the hotel room which unfortunately manifested in a form of Oreo, normally priced 5 cents but it was priced 5 dollars in the hotel.
I am a moron, I know.
“Wah, itu lima dolar mbaak... sayang banget”, lamented Maya, her eyes fixed at the price list of the mini bar.
“Iya nih mbak.. kemarin buru-buru karena kelaparan .. eh pas saya cari di minimarket sini ternyata ga ada yang jual kemasan oreo satuan kaya yang saya makan”, answered me- recalling my futile efforts to find that dang Oreo.
“Yaudah ga apa-apa mbak. Deket rumah saya banyak yang jual kaya gini. Besok saya ganti aja.”, then she continued with a smile. “Sayang banget soalnya”, she added.
And then the next morning I found the same new Oreo, perching at where it supposed to be.
This act of kindness flung me into an instant contemplation right when it was the high time of me yearning the human connection.
2 notes
·
View notes
Text
Prabu Anom
Pejalan, apa kabarnya gerangan?
Bagaimana rasanya berlalu meninggalkan hati yang kerontang?
Bagaimana Dunia? Kejamkah ia?
Kadang masih kutebak-tebak bagaimana lantang suaramu menyalak di sela halaman
Bergema gema sampai ke Gurun Sahara, mendarat ke telinga rubah merah
Melesat ke bintang mencari Exupery dan pangeran kecil
Kini ia bersembunyi di sela kantor duapuluh lantai
Namecard bergantung di leher,tersentak gumam seorang penyair
Semesta bagiku dulu teringkas menjadi bunga mawar dalam kertas: merajuk rindu
Ah, semoga sehat selalu
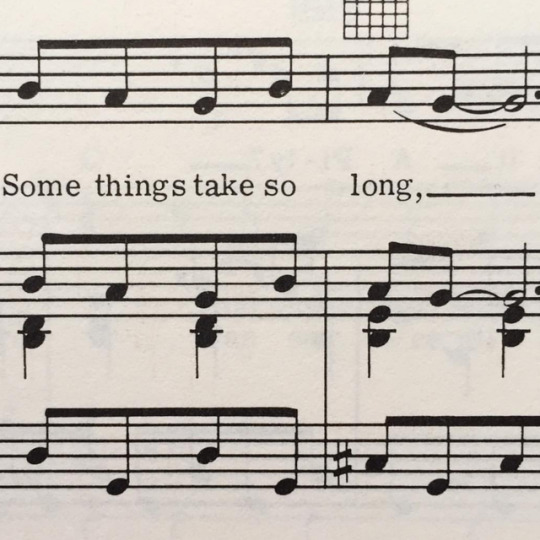
1 note
·
View note
Text
Cinta Kucing

We are never as vulnerable as when we love
- Freud
Kamu tahu bagaimana cara kucing mengatakan cinta?
Pelan-pelan ia akan berbaring di hadapanmu. Perut menghadap ke atas- bagian tubuh terlemahnya yang secara naluriah tidak akan dipertontonkan di depan predator maupun kompetitor. Ini ialah isyarat kepercayaan. Tapi jangan sampai terlena dan tergoda untuk mengelus titik Achilles tersebut. Salah-salah , cakaran akan mendarat tiba-tiba. Pertunjukan kelemahan memang isyarat kepercayaan yang mendekati rasa Cinta. Namun pun di dalam semua ekspresi, bahkan Kepercayaan, ada beberapa batasan yang tidak dapat ditembus.
Namun kita kan bukan Kucing, katamu membantah. Bukan, tentu saja, bukan.
Tapi untuk mencinta ialah untuk mengalihkan kuasa akan suatu perihal untuk memberikan efek yang entah seberapa besar kepada diri pribadi- alih alih suat kelemahan, aku malah memandangnya sebagai suatu keberanian. Untuk tercebur hingga basah, untuk melayang setingginya tanpa memandang ke bawah.
Namun kita bukan kucing, katamu nyaris memaksa.
4 notes
·
View notes
Text
Hello, hello dearest lover! Would you mind telling me if it's about the time you're going to break my heart? Because I will crush it with my own hands in advance..
at least, I think I can handle my own tragedy
1 note
·
View note