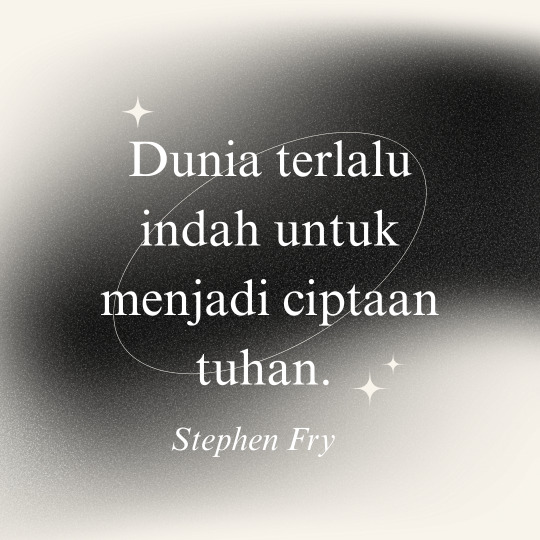Text
DEBAT PARA DEWA: METAMORFOSIS MORALITAS

Di sebuah planet kecil yang mengorbit sebuah bintang kelas menengah di pinggiran galaksi biasa, spesies yang baru saja belajar bertani dan mengendalikan api tiba-tiba mendeklarasikan diri mereka sebagai pusat semesta. Mereka mendongak ke langit malam yang bertabur bintang, dan alih-alih terkagum oleh kebesaran alam semesta yang dingin dan penuh misteri, mereka memilih membuat cerita. Cerita tentang dewa, tentang hukum yang datang dari langit, tentang moralitas yang diimpor langsung dari surga yang entah berapa jaraknya dari bumi.
Dulu, kepala suku atau kepala gank sangat ditakuti. Apa pun perintahnya pasti diikuti. “Jangan ambil istri tetangga!” Ya, artinya jangan. Gak pake debat, gak pake polling sosial media, apalagi nulis thread panjang di Twitter atau curcot di Tik-tok.
Moralitas yang sangat sederhana,kan. Kalau berani ngeyel, siap-siap saja menjadi contoh. Kalau tersambar petir, dimangsa binatang, kamu akan diothak athik gathuk-kan dengan pelanggaran moral. Atau ketika dianggap melanggar ‘roh nenek moyang’, akan segera dikucilkan, dan ditempatkan di tempat tempat yang paling mungkin tersambar petir atau sarang pemangsa. Maka, jika yang terhukum mati tersambar atau dimangsa, maka benarlah kesalahannya, dan benarlah bahwa ‘roh nenek moyang’ sedang datang menghukum

Nenek moyang yang kemudian disebut para dewa pun akhirnya punya waktu kerja. Waktu kerja yang mirip grup WhatsApp yang hobi ngirim broadcast hoax. Pokoknya, segala yang gak bisa dijelaskan, pasti ulah dewa. Simple. Seperti jawaban anak-anak zaman sekarang: “Karena emang gitu aja.”
Lalu, suatu hari di tanah Babilonia yang panas dan penuh jebakan politik, muncul Hukum Hammurabi. Ini bisa dibilang kayak peraturan kompleks pertama yang diukir di batu — semacam peraturan kos yang isinya absurd: “Kalau maku poster di tembok, tangan dipotong. Kalau minum susu di kulkas yang bukan milikmu tanpa izin, siap-siap dilempar dari lantai paling atas.
Dewa-dewa lokal kos pun bangga: “Nah, gitu dong, ada setiap kos ada SOP-nya.” Tapi tetep aja, semua hukum itu di-backup oleh otoritas pokoknya. Pokoknya, yang ngatur dewa. Mau beradu argumen? Kamu diusir dari kos-kosan. Pokoknya, apapun masalah dan pertanyaannya, Tinggal bilang, “Ini titah dewa.” No, debat!
KAPITALISASI MORAL: TUHAN SEBAGAI BRANDING
Waktu berjalan, Tuhan dan para dewa makin lihai bikin branding. Lalu datanglah Musa, dengan gimmick ikonik: sepuluh perintah Allah yang diukir di batu — kayak Terms & Conditions yang gak bisa di-scroll sampe bawah. Pokoknya, masih dipakai. Pokoknya kalau gak setuju, ya tinggal siap-siap di-ban dari komunitas, atau disuruh exile ke padang pasir tanpa sinyal.
Edannya, umat nurut. Moralitas jadi seperti franchise makanan cepat saji. Satu menu untuk semua. Mau protes rasa? Gak bisa. Mau tanya kenapa? Jawabannya selalu sama: “Rahasia dapur tuhan.”
ERA ORANG-ORANG YANG KEBANYAKAN NGANGGUR DAN KEBANYAKAN MIKIR
Namun, di pojokan Laut Tengah, di sebuah café terbuka, di bawah pohon kamboja, ngobrollah Socrates, Plato, Aristoteles, serta geng filsuf lainnya sambil rebahan dan minum beer. Mereka, adalah kaum yang gak punya Netflix atau TikTok, dan memilih hiburan lain: mikir berjamaah.
Socrates mulai dengan sebuah pertanyaan, “Eh, bro, masa’ iya etika cuma soal takut sama dewa? Kan kita punya otak. Masa’ gak dipake?” Maka lahirlah debat yang mirip debat netizen (tanpa konklusi dan asal njeplak) di kolom komentar: Ribut soal apa itu baik, apa itu adil, apa itu etis.
Socrates melanjutkan, “Hidup yang tidak diperiksa oleh dirinya sendiri adalah hidup yang sia-sia.” Plato, menimpal, “Yah, kalau terlalu diperiksa juga bisa stres sendiri.” Aristoteles nyengir sambil nuang margarita, “Moral itu kayak resep minuman ini, bahan dasarnya logika, tapi bisa diutak-atik sesuai budaya dan selera diri sendiri. Mau lebih bolt, banyakin alkoholnya, mau manis, banyakin liquernya”
Alhasil, di café itu, di bawah pohon kamboja, moralitas pun jadi festival ide. Ada yang tetap setia sama dewa, ada yang pindah ke logika, ada yang kejebak di tengah-tengah kayak anak kos bingung milih mana mana makanan yang promo di aplikasi makanan. Pokoknya, festival moralitas makin ramai pengunjung, makin banyak pilihan, makin bikin pusing. Lalu, mana moralitas satu-satunya? Moralitas yang pasti itu yang seperti apa? FYI, gak ada yang pasti.
MORALITAS: KONTEN ATAU IDENTITAS
Sampai akhirnya tibalah zaman AI, zaman di mana moralitas sudah jadi bahan bakar konten. Moralitas jadi filter Instagram: tergantung mood dan followers. Orang teriak soal keadilan, tapi sambil narik donasi. Orang ngomong soal kasih sayang, tapi sambil jualan skincare, besoknya nyinyirin tetangga yang gak mau beli skincarenya, apa lagi yang gak mau beli beda agama.
Dan yang paling ironis dari semua yang ironis adalah: moralitas zaman ini lebih mirip meme. Semua orang bisa pakai, semua orang bisa remix, tapi esensinya? Entah ke mana. Ada yang bilang, “Moral itu soal agama!” Ada yang bales, “Moral itu soal akal sehat!” Ada yang lebih skeptis lagi, “Moral? Ah, itu kan cuma mitos warisan nenek moyang yang dipoles jadi konten clickbait.”
Akhirnya, yang mabuk eksistensialisme seperti saya, menulis di X: “Moralitas itu kayak hantu, semua orang ngomongin, tapi gak ada yang pernah lihat langsung.”
:MORALITAS SEBAGAI LABIRIN TAK BERUJUNG
Begitulah. moralitas adalah evolusi, moralitas itu perjalanan panjang dan absurd. Dari zaman manusia yang takut sama bayangannya sendiri , sampai zaman manusia takut kehilangan followers.
Apa yang dulu lurus dan mulus, sekarang jadi labirin penuh tikungan, jebakan, dan lubang kenikmatan yang tersembunyi di balik kata-kata manis tentang cinta dan keadilan. Manusia terus mengejar jawaban untuk pertanyaan kuno yang tetap segar sampai hari ini:
Apa itu kebenaran? Apa itu benar? Dan kenapa kita harus peduli padanya?
Jawabannya? Mungkin, seperti kata Dewa Marketing Moralitas, yaitu tuhan-tuhan itu ciptaan manusia: “Karena kalau gak peduli, siapa yang bakal beli rasa bersalah dan pengampunan yang dijual agama?”
Dan para dewa dari Olympus, dari Nirwana, dari surga, dari Valhalla, dan dari mana pun pun tersenyum, sambil cek omset dan setoran pajak yang tidak pernah sekalipun diterima. Semua setoran pajak, nyangkut di pemungutnya alias yang mengaku imam dan wakil tuhan dewa allah.
tak 🍻
0 notes
Text

Saat kekejaman terasa memalukan, manusia menyucikannya atas nama tuhan dan menyebutnya sebagai kebajikan ilahi
0 notes
Text
TUHAN KEPALA SEKOLAH BENGIS!

Harus diakui dulu hal pahit ini: di Indonesia, tuhan tak lagi di surga, kini duduk di meja kepala sekolah. Dengan setelan safari, berjanggut, dahi hitam dan celana cingkrang, mengawasi proses belajar-mengajar sambil sesekali "memainkan cambuk api neraka"Disekolah itu, kurikulumnya wahyu & firman. Lalu, bagaimana dengan murid murid? Jangan harap mereka bisa bertanya. Di dalam ruang kelas, pertanyaan adalah simtom lemah iman.
Bertanya soal “kenapa manusia harus disunat?” bisa membuatmu dicurigai sebagai calon murtadin atau antek liberal. Bertanya soal “apakah ada kafir yang tidak masuk neraka?” bisa dapat nilai agama 40, sekalipun rajin sholat Dhuha. Proses belajar mengajar di sekolah yang dikepalai oleh tuhan, bukanlah pendidikan. Sistem ini disebut pemrograman rohani. Alih-alih membentuk manusia berpikir, sekolah malah mencetak manusia hafalan. Cita cita tertinggi anak anak itu apa? Ya, jadi hafidz-lah. Emang sih sekarang jadi dokter ada jalur hafidz. Tapi yang lebih bermartabat tentu saja ustadz, lebih dari dokter dan ilmuwan, bahkan lebih dari menjadi manusia. Menjadi lebih dari manusia itu penting, karena dengan hafalan saja bisa membuka pintu surga secara otomatis. Bagi manusia hafalan yang sekolah dengan kurikulum wahyu, surga lebih penting daripada dunia yang sesat, penuh logika dan sains.

Sekolah negeri di era digital justru makin religius, bukan makin rasional. Di banyak tempat, sekolah negeri hampir tidak bisa dibedakan lagi dengan pesantren. Bedanya cuma seragam. Isi pikirannya? Sama.Dari speaker masjid sekolah, doa doa mengalir setiap pagi seperti embun rohani yang membasuh nalar anak anak yang belum sempat tumbuh.Singkatnya doa doa itu adalah, doktrin!Beberapa sekolah bahkan punya aturan tidak tertulis:Kalau tidak ikut sholat berjamaah, akan dihujad, dianggap "kurang akhlak".Kalau tidak pakai penutup kepala dan bercelana cingkrang, dianggap “tidak islami” atau melawan perintah tuhan dewa allah. Padahal sekolah negeri, lho! Bukan madrasah atau sekolah agama terpadu. Tapi siapa peduli?
Kalau mayoritas sudah bersepakat bahwa Islam adalah satu-satunya standar moral, maka pluralisme akan dianggap sebagai kesesatan! Ki Hajar Dewantara, dulu punya mimpi taman belajar. Sebuah tempat seperti taman yg penuh bunga bunga pengetahuan. Sekarang? Boro boro! Tamannya kini berubah jadi kebun. Kebun dakwah.
Dulu Ia membayangkan pendidikan sebagai upaya memerdekakan manusia. Tapi sekarang? Manusia manusia kecil itu akan dianggap merdeka kalau sudah patuh pada kitab kuno.Makin literal, makin soleh.Makin absurd, makin berkah. Gilingan!
Moralitas pendidikan negeri ini tidak lahir dari empati, bukan dari refleksi, apalagi filsafat.Moral pendidikan di negeri ini sumbernya kitab jadul. Titik.Jadi jangan heran kalau anak anak lebih tahu hukuman bagi pezina daripada pentingnya kejujuran. Mereka lebiih gapai menjelaskan hukum neraka, tapi tak tahu cara membedakan dongeng dan fakta.Mereka lebih pandai bercerita tentang supranatural, dari pada mengenali dunianya yg natur. Dan akibatnya?Nilai nilai moral yang universal seperti HAM, kesetaraan gender, atau kebebasan beragama dituduh “westernisasi”. Mereka hanya mengimani moral berkoridor syariat.Hukum HAM universal & hukum hukum moral moderen yang dibuat negara, tidak diakui karena bukan Made In tuhan dewa allah. Faktanya, yang sedang terjadi di kebun dakwah itu, anak anak diseret masuk ke dalam pusaran ideologi yang dibungkus dalam kata “akhlak”.
Pendidikan Agama yang Menyesatkan Coba lihat kurikulum agama: lebih banyak bicara tentang kewajiban menutup aurat daripada membuka pikiran, kan?Lebih penting memikirkan dosa makan babi daripada memahami konsep.Lebih sering membahas kafir timbang bagaimana berbagi kasih sayang.Singkatnya: tuhan dewa allah lebih cepat menghukum daripada mengasihi. Gilanya, sistem ini terus dipertahankan dengan dalih “nilai luhur bangsa”.Nilai luhur bangsa kini harus sesuai dengan nilai nila bangsa arab!Apa betul bangsa ini luhur karena takut neraka, bukan karena
gotong royong dan tepo slironya? Atau jangan jangan negeri ini lebih nyaman memproduksi manusia takut allah, daripada manusia yang berani mengatakan kebaikan?Kebaikan yang dikatakan haruslah kebaikan yang tulus, lho! Kebaikan yang tumbuh dari kemanusiaan, bukan kebaikan yang dipecundangi tuhan!
Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Namun, pendidikan hari ini justru sebalinya, menghilangkan kemanusiaan.Anak anak diajarkan untuk menjadi budak yg taat, bukan manusia yg berpikir.Anak anak diajarkan untuk mengikuti perintah, bukan untuk memahami alasan di balik perintah itu.Jika ini disebut pendidikan, maka sesungguhnya yang telah dilakukan adalah membunuh nalar demi menyelamatkan jiwa.Jika ini yang disebut “pendidikan akhlak”, maka jangan salahkan generasi muda kalau mereka tumbuh dalam wajah religius tapi kering peduli, alias munafik.Jangan heran jika kelak, mereka tidak mencari kebenaran, tapi hanya mencari pembenaran.Jangan heran jika mereka membenarkan kejahatan, sebagai perintah dari tuhan.
Apakah negeri ini harus kembali pada semangat pendidikan yg memerdekakan? Idealnya, sih iya. Pendidikan harus kembali memerdekakan anak.Pendidikan harus mendorong anak anak untuk berpikir kritis, memahami perbedaan, dan menjadi manusia yang sesungguhnya.Sebuah pendidikan yg tidak hanya mengajarkan apa yg harus dilakukan, tetapi juga mengajarkan untuk bertanya mengapa?
Intinya, pendidikan harus membebaskan, bukan membelenggu.Jika terus menerus mengajarkan anak anak untuk takut, pendidikan akan menciptakan generasi yg patuh tanpa pemahaman. Generasi yang tidak mampu berpikir sendiri, dan hanya mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Generasi yang rapuh dan generasi yang patuh ini adalah generasi dambaan para politikus, penguasa dan penarik pajak tuhan dewa allah. Kepatuhan untuk menjadi budak yang taat sudah seiring dengan perintah tuhan dewa allah dalam kitab suci dan sudah sesuai dengan cita cita politisi.
So, apakah negeri ini mau menciptakan manusia merdeka?Apakah negeri ini ingin anak anaknya tumbuh menjadi individu yang berpikir kritis?Sepertinya, mayoritas penduduk negeri ini masih setia untuk menjadi budak!Maka, anak anak juga harus menjadi budak!
tak🍻
0 notes
Text
ISLAMOFOBIA ATAU AKAL SEHAT?

Di era Perang Dingin, dunia ketakutan pada komunisme. Kini, dunia mulai sadar: ketakutan itu berpindah kostum — dari bintang merah ke bulan sabit. Dari palu arit ke pedang bertuliskan kaligrafi Arab. Hantu yang sekarang menghantui bukan ideologi Marxis, tapi wahyu langit yang membawa bom rakitan dan slogan "Allahu Akbar".
Kita disuruh percaya bahwa ini semua hanyalah "kesalahpahaman", bahwa Islam adalah agama damai. Sementara di Pakistan, ratusan rumah dan gereja dibakar karena “dugaan” penistaan. Di Nigeria, kelompok Boko Haram menyembelih warga Kristen seperti memotong ayam kurban. Di Mozambik, gerilyawan Islam memenggal kepala anak-anak dengan santai, seolah-olah itu bagian dari kurikulum madrasah.
Tapi jika Anda bersuara, menganalisis, apalagi mengkritik: Anda bukan realistis. Anda Islamofobik.
Apa bedanya antara ketakutan dan kenyataan? Bila seseorang menggenggam pisau di tengah kerumunan sambil berteriak ingin memenggal siapa pun yang tak seagama, apakah kita salah bila menghindar? Atau apakah kita harus memeluknya sambil membaca surat Al-Fatihah?
Mari berhenti berpura-pura. Islam politik global memang keras, kejam, dan mengidap ambisi ekspansi. Ia tidak butuh wilayah — ia butuh tunduk. Bukan cuma untuk Muslim, tapi untuk semua manusia. Dan bila perlu, dengan darah.
Kita sering mendengar bahwa "terorisme tidak mewakili Islam." Benarkah? Apakah mereka yang meledakkan dirinya, membantai umat lain, menculik, memperkosa, dan menjual budak wanita hanya salah tafsir? Atau justru tafsir lurus dan jujur dari teks-teks suci yang selama ini kita lapisi dengan parfum toleransi?
Hamas, Taliban, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS — mereka bukan sekadar organisasi. Mereka adalah cermin. Dan umat Islam dunia, dalam banyak kasus, melihat bayangan mereka sendiri di cermin itu — dan menyukainya.
Lihat reaksi dunia Muslim terhadap serangan Hamas. Bendera Palestina dikibarkan bukan karena cinta pada rakyatnya, tapi karena kebencian kolektif terhadap yang disebut "kafir penjajah". Sebelumnya, banyak yang mengelu-elukan ISIS karena berhasil mendirikan khilafah impian. Ini bukan ekstremisme. Ini mainstream.
Data Pew Research mencatat bahwa di beberapa negara mayoritas Muslim, lebih dari 50% responden menyatakan bahwa hukum syariah harus diberlakukan secara nasional — termasuk potong tangan dan rajam. Ini bukan fobia. Ini statistik. Ini bukan persepsi. Ini kenyataan.
Tapi tentu saja, setiap kritik terhadap Islam akan dibungkus dengan tuduhan: "Anda Islamofobik!" Seperti menyebut petugas pemadam kebakaran sebagai “pyrofobia” karena mereka takut api.
Filsuf Bertrand Russell pernah berkata: “Religion is based... mainly upon fear.” Tapi Islam lebih dari sekadar agama berbasis rasa takut. Ia adalah sistem dominasi. Bukan lagi jalan keselamatan, tapi jalan penaklukan.
Sains mengajarkan kita untuk menguji, mempertanyakan, dan membongkar. Jika Islam tidak boleh disentuh oleh kritik, maka ia bukan agama. Ia adalah diktator yang mengenakan jubah Tuhan.
Kita tidak sedang memusuhi umat Islam. Kita sedang melawan ideologi kekerasan yang membungkus dirinya dengan spiritualitas. Sama seperti kita tak membenci orang Soviet, tapi menolak komunisme totaliter.
Islam bukan dianiaya. Ia sedang diuji — dan gagal.
ISLAMOFOBIA ATAU REALITAS? Ketika Tuhan Butuh Juru Bicara Bersenjata
Dulu, dunia takut komunis. Sekarang, dunia takut Muslim. Bukan karena warna kulitnya, tapi karena suara takbirnya diiringi ledakan. Ketakutan ini diberi nama yang manis: Islamofobia — seolah-olah dunia hanya “paranoid.” Tapi kalau tetanggamu tiap minggu mengutip kitab suci sambil membawa bom, itu bukan fobia, itu insting bertahan hidup.
Dari Paris ke Kabul, dari Nigeria ke Pakistan — yang terbakar bukan hanya bom, tapi ilusi bahwa Islam hanyalah agama damai. Mereka bilang, “Jangan samakan Islam dengan terorisme.” Tapi anehnya, setiap ada aksi bom bunuh diri atau pembantaian massal, pelakunya selalu lebih hafal Al-Qur'an daripada teori relativitas Einstein.
Contoh? Pada Februari 2024, sekelompok Muslim di Pakistan membakar puluhan rumah dan gereja milik umat Kristen di distrik Jaranwala, setelah menuduh seseorang melakukan penistaan. Tanpa pengadilan. Tanpa bukti. Cukup teriakan "Allahu Akbar," dan hukum diganti bensin. Di Nigeria dan Afrika Barat, kelompok seperti Boko Haram dan ISWAP secara rutin menyerang sekolah, membunuh guru, menculik anak-anak perempuan, dan memenggal siapa pun yang tak ikut salat. Tahun 2023, Amnesty International mencatat ratusan kasus pembunuhan oleh kelompok bersenjata Islam di wilayah Sahel — dalam nama Tuhan, tentu saja.
Tapi ketika dunia mengkritik, langsung disuruh diam: “Jangan rasis! Jangan Islamofobik!” Kritik terhadap kekerasan berbasis agama sekarang dianggap dosa liberal. Lucunya, para pembela ini biasanya tidak tinggal di negara mayoritas Muslim. Mereka tinggal nyaman di Paris, London, atau New York — di mana azan tidak dibarengi ledakan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Islam, dalam bentuk politiknya, bukan sekadar agama, tapi proyek kekuasaan. Ia tidak mencari kedamaian, tapi dominasi global. Dalam teks sucinya, kafir bukan untuk disapa, tapi untuk ditundukkan. Ini bukan interpretasi ekstrem — ini adalah bunyi asli dari kitab itu sendiri.
Tapi seperti halnya iklan rokok yang menyisipkan peringatan kecil di bawah gambar orang bahagia, Islam modern juga menempelkan “rahmatan lil alamin” di bawah gambar jihad dan potongan kepala.
Christopher Hitchens menertawakannya, dan berkata: "Once you assume a God-given right to rule others, atrocities become inevitable." Dan Sam Harris menegaskan: "It is time we admit that we are not at war with terror. We are at war with Islam — not the religion in its watered-down version, but in its core, scriptural, political form."
Sains mengajari kita menguji klaim, bukan mengimani slogan. Dan klaim Islam sebagai agama damai gagal dalam semua uji lapangan. Damai itu, jika ada, hanya berlaku untuk sesama Muslim yang satu mazhab, itupun tidak selalu.
Jadi, apakah dunia membenci Islam? Tidak. Dunia hanya mulai membaca dengan saksama. Dan ketika dunia membaca, ia tidak menemukan damai, tapi manual penaklukan. Yang membuat kita bertanya-tanya: jika Islam adalah agama kasih, mengapa cinta itu selalu datang bersama darah?
Kalau kamu mau, opini ini bisa dikembangkan jadi esai panjang dengan kutipan lebih banyak dari data HAM internasional, laporan PBB, dan analisis geopolitik. Mau dilanjutkan ke arah itu?
1 note
·
View note
Text
TUHAN, MAHLUK DARI MULTIVERSE
(Sebuah Komedi Kontingensi)

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hadirin dan hadirot, dari yang rajin ibadah hingga yang rajin debat, dari yang baca kitab sampai yang baca zodiak tiap Jumat— Selamat datang di cuitan filsafat kosmis edisi spesial: #TuhanTidakBermoral
The Argument from Contingency! Mari kita mulai dengan Mbah Thomas Aquinas. Ia bertanya, dengan wajah penuh kebingungan eksistensial: “Di dunia ini, segala sesuatu bisa saja tidak ada. Tapi kok malah ada? Pasti ada sesuatu yang membuat semuanya harus ada. Dan itu—tentu saja—Tuhan. Titik.”
Hmm. Logika ini mirip seperti kamu nemu sandal jepit nyasar di depan rumah, terus langsung menyimpulkan: “Ini pasti kiriman Tuhan!” Inilah jurus klasik iman zaman dulu: Melompat ke kesimpulan seperti atlet lompat galah metafisika.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, baik yang membaca dengan dahi berkerut maupun yang membaca sambil rebahan dan ngopi, mari kita kupas kulit kacangnya... biar nggak terlalu pahit.
Kata Ilmu Pengetahuan: Semesta ini sudah cukup dramatis tanpa harus melibatkan Tuhan sebagai tokoh utama. Prinsip sains modern cukup sederhana:
“Kalau ada Big Bang di awal, terus muncul bintang, planet, dan manusia yang doyan bertanya tentang eksistensi... ya kita pelajari saja. Gak perlu bumbu mistis.”
Tapi Mbah Aquinas, seperti dosen yang tak puas dengan jawaban skripsimu, tetap ngeyel:
“Tapi kenapa ada sesuatu? Kenapa tidak tidak ada sama sekali?”
Sains pun angkat bahu.
“Maaf, kami sedang sibuk menghitung neutrino dan menghindari lubang hitam yang akan menelan galaksi empat miliar tahun lagi. Silakan tanya ke Departemen Metafisika.”
Aquinas lanjut:
“Kalau semua hal bergantung pada yang lain, pasti ada satu yang tidak bergantung—yang mandiri sepenuhnya. Itulah Tuhan.”
Tiba-tiba, Tuhan masuk. Bawa kopi dan kartu nama. Masalahnya, logika tidak sesimpel itu, Mbah.
Siapa bilang rantai sebab-akibat harus punya ujung? Bayangkan sebuah lingkaran sempurna. Sekarang, coba tunjuk satu titik dan bilang:
“Inilah titik awalnya!”
Anak-anak Gen Z langsung nyinyir:
“Yhaa mana bisa, Mbah! Lingkaran tuh gak punya awal. Semua titik nyambung, setara, tanpa yang lebih ‘awal’ dari yang lain.”
Artinya?
Tidak adanya awal bukan berarti sistem itu mustahil. Dan kalau pun harus ada “sesuatu yang harus ada”, siapa bilang itu Tuhan berjanggut panjang, bersuara bariton, atau pakai celana cingkrang?

Kenapa gak konstanta Planck aja? Atau energi vakum kuantum? Atau alien pengangguran yang iseng menyalakan mesin pencipta semesta?
Mengklaim bahwa necessary being = Tuhan Abrahamik, itu kayak lihat kilat, langsung nyimpulin:
“Wah, Ki Ageng Selo lagi latihan nangkep petir nih!”
Necessary Itu Apa, Sih? “Tuhan harus ada,” katanya. Tapi… apa maksudnya harus?
Mayoritas argumen cuma muter-muter kayak sinetron. Kamu berdiri di tengah benang kusut logika, pura-pura paham sambil mengangguk:
“Ya… Tuhan pasti ada…”
Argumen kontingensi ini memang menggoda, kayak audisi “Siapa Mau Jadi Ustadz?” Semua semangat angkat tangan. Tapi pas ditanya arti ayat?
“Eh… itu... maksudnya... ya intinya kita bersyukur aja, Ustadz.”
Begitu disorot lampu logika dan mikroskop ilmiah, argumen ini seringnya panik, mulai marah-marah, dan menyebut pertanyaan sebagai “penghinaan terhadap iman.”
Jadi pertanyaannya:Apakah Tuhan layak dijadikan alasan serius untuk menyembah makhluk tak terlihat—yang konon sensitif kalau kamu makan babi?
Atau... Apakah kita cuma penakut yang tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa hidup ini mungkin gak punya sekuel setelah kematian?
2 notes
·
View notes
Text
JIKA SEMUA BUTUH PENYEBAB, TUHAN DISEBABKAN OLEH APA?
Kalau Semua Butuh Penyebab, Tuhan Disebabkan Oleh Apa?Salah satu jurus andalan teis saat diajak berdialog soal keberadaan tuhan adalah Argumen Kosmologis. Kalau dalam versi yang lebih catchy, Argumen Penyebab Pertama.

Pada awalnya, idenya terdengar masuk akal, (bagi orang-orang males berpikir) tapi makin dikunyah, rasanya seperti permen karet yang kehilangan gulanya: makin lama makin hambar.Semua Ada Penyebabnya... Kecuali Tuhan?
Logikanya begini: segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Meja ada karena dibuat tukang kayu, kayu ada karena tumbuh di alam, dan tidak mungkin kayu ada begitu saja, harus ada penciptanya? Rantai sebab-akibat ini tidak mungkin terus berlanjut sampai ujung? karena...
Ya, karena nggak enak saja kalau ada ujungnya tapi nggak ada awalnya. Jadi harus ada satu titik mula. SatU penyebab. Satu entitas yang memulai semuanya tanpa dirinya sendiri yang tanpa mula.Dan entitas tanpa mula ini, kini populer disebut tuhan.
Tuhan: Entitas yang Kebal Aturan
Tapi wait, kalau semua butuh penyebab, kenapa tuhan nggak?Nah, di sinilah theis main jurus khusus: Tuhan itu pengecualian. Katanya, tuhan punya fitur premium yang tidak dimiliki benda-benda biasa di semesta ini. Dia tak tercipta, tak tergantung, tak terikat waktu, alfa omega, dan (yang paling penting) tak perlu lagi dipertanyakan asal-usulnya. Semacam “cheat code” dalam permainan logika.
Apa alasan tuhan adalah pengecualian?
Supaya rantai sebab-akibat nggak infinite. Kalau tuhan ada penyebabnya, maka kita balik lagi ke masalah awal: siapa penyebab dari penyebab dan yang menjadi penyebab… dan seterusnya. Jadi harus ada kode untuk “stop”.Tuhan itu 'necessary being',. Artinya, eksistensinya mutlak. Harus ada sebuah eks eksistensi mutlak untuk menghentikan awal dari penyebab. Padahal, alam semesta cuma 'contingent'—bisa ada, bisa nggak.Akal manusia terbatas! Kalau nggak bisa paham konsep “yang tidak diciptakan”, ya bukan salah argumennya tapi salah otaknya yang kebanyakan nonton sinetron. Dengan kata lain: aturan “segala sesuatu ada penyebab” berlaku untuk semua, kecuali tokoh utama dalam cerita ini. Sederhana, kan?
Kata Atheis?
Ateis tidak semudah itu percaya dan dibujuk dengan logika loncat-loncat. Atheis punya beberapa pertanyaan menyebalkan yang sering bikin argumen kosmologis panas dingin:Kenapa Tuhan boleh jadi pengecualian, tapi alam semesta enggak? Kalau satu entitas boleh “ada begitu saja”, kenapa bukan semesta sekalian aja?Siapa bilang regresi tak terbatas mustahil? Mungkin saja realitas memang absurd, tapi bukan berarti harus diisi tuhan demi kenyamanan, demi politik kekeuasaan, atau demi perut perut para sales agama!Big Bang siapa penyebabnya? Belum tentu tuhan. Bisa jadi proses kuantum, bisa jadi siklus abadi semesta. tuhan bukan satu-satunya opsi. Lalu apa? Kalau kamu menyerah dan tidak sabar menunngu jawaban masa depan, jawab saja dengan tuhan.Tuhan versi siapa? Bahkan kalau pun kita terima tuhan sebagai “penyebab pertama”, tidak otomatis itu adalah tuhan yang rajin disembah, disambati umat manusia, apalagi tuhannya Ibrahim dan suku suku keturunannya. Mungkin saja sebuah entitas tanpa kepribadian atau malah hukum alam itu sendiri.
Argumen Yang Punya Gigi, Tapi Gak Bisa Menggigit
Argumen kosmologis memang tampak setrong di permukaan. Tapi seperti lem super yang sudah terlalu lama terbuka, ia kehilangan daya rekatnya saat diuji. Kering. Ia mencoba menyelesaikan masalah dengan menambahkan karakter kebal logika. Bagi orang orang masa lalu yang belum secerdas hari ini, masih mungkin. Akan tetapi bagi sebagian orang zaman ini, argument tersebut justru mengaburkan masalah utama, bukan menjelaskan, apalagi menjawab.Pada akhirnya, sebagai manusia masa kini, kita harus tetap bertanya: Jika semua hal butuh penyebab, mengapa tuhan (terutama tuhannya Ibrahim) dapat dispensasi khusus?jangan-jangan...kamu cuma terlalu malas mencari jawaban yang lebih masuk akal. Karena mengangkat, menganugerahi tuhan sebagai jawaban atas segala pertanyaan yang pamungkas, jauh lebih praktis daripada berpikir! Tak🍻
1 note
·
View note
Text
TUHAN YANG MAHA KW

Apakah tuhan menciptakan manusia, atau manusialah yang menciptakan tuhan?
Pertanyaan ini bukan sekadar mainan filsafat sore hari sambil tak, tapi inilah inti dari salah satu ironi terbesar dalam sejarah budaya manusia.
Gagasan tentang tuhan adalah hasil sampingan dari otak manusia yang mulai canggih—bukan canggih seperti ChatGPT, tapi cukup canggih untuk panik melihat petir dan berpikir, “Wah, pasti ada yang marah di langit.”
Manusia purba hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, tanpa manual pengguna untuk hidup, apalagi teori gravitasi. Maka lahirlah dewa petir, dewa panen, dewa kesuburan, dewa reruntuhan ekonomi, dan entah apa lagi. Tuhan adalah cara manusia menjelaskan kekacauan dunia sebelum Google diciptakan.
Menurut Jared Diamond dalam Guns, Germs, and Steel, struktur sosial manusia berkembang seiring kompleksitas masyarakat. Ketika kita masih berburu dan meramu, cukup satu roh hutan untuk disembah. Tapi ketika muncul sistem agrikultur, kerajaan, dan perpajakan, Tuhan pun naik kasta: dari pengatur cuaca menjadi pengatur moral dan pengendali surga-neraka. Tuhan bukan lagi sekadar manajer cuaca, tapi juga HRD spiritual yang mengatur siapa yang boleh mencintai siapa, kapan boleh makan daging, dan bagaimana cara memakai kain kafan.
Tuhan: Fiksi Favorit Umat Manusia
Yuval Noah menyebut tuhan sebagai salah satu “fiksi kolektif” paling sukses dalam sejarah umat manusia. Dalam Sapiens, ia menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap entitas supranatural memperkuat ikatan sosial dan memperbesar kemungkinan manusia untuk bekerja sama dalam skala besar. Tapi ingat, ini fiksi. Sama seperti uang, negara, atau startup yang katanya bakal mengubah dunia tapi ternyata cuma jual template PowerPoint.
Richard Dawkins dengan tajam menyebut tuhan sebagai delusi, sebuah hipotesis yang tidak lulus ujian laboratorium tapi tetap laku dijual di toko doa. Sementara Sam Harris menyoroti bagaimana kepercayaan pada tuhan sering digunakan sebagai dalih moral untuk melakukan hal-hal yang tak bermoral—dari diskriminasi gender sampai pembenaran genosida. Tapi selama kalimatnya diawali dengan "atas kehendak tuhan", semua orang disuruh diam dan tunduk.
Dan Christopher Hitchens? Dia menyebut tuhan sebagai diktator kosmis, pemimpin otoriter yang menuntut pujian terus-menerus dan mengancam siksaan abadi jika kita gagal menyanyi dalam nada yang benar. Tuhan, dalam versi ini, bukan hanya maha tahu, tapi maha posesif.
Tuhan Haus Validasi
Beberapa teolog mengatakan bahwa tuhan menciptakan manusia karena cinta. Tapi jika kita perhatikan narasi yang berkembang, tuhan ternyata sangat butuh untuk disembah. Tuhan yang sempurna tapi butuh dipuji adalah seperti selebgram spiritual yang ingin semua postingannya dikomentari “Aamiin” dan di-like jutaan kali.
Kalau tuhan menciptakan manusia agar disembah, maka tuhan jelas punya agenda yang belum selesai. Tuhan bukan lagi entitas yang tak tergoyahkan, tapi seperti mantan yang masih ngecek story kita tengah malam. Di mana letak keagungan ilahi kalau eksistensi-nya tergantung pada validasi dari makhluk yang ia ciptakan dari tanah?
Tentu saja para pengikutnya akan bilang, “Itu misteri ilahi.” Tapi mari kita jujur: ini terdengar seperti kontrak kerja dengan bos yang toxic—bekerja seumur hidup, dilarang bertanya, dan diancam PHK abadi (alias neraka) kalau tidak patuh. Atau ya, sebut saja budak ilusi!
Tuhan: Subjek yang Bisa Di-Review
Dulu, mempertanyakan tuhan dianggap penghinaan. Kini, di era teleskop James Webb, neuropsikologi, dan budaya fact-checking, tuhan adalah topik yang sah untuk diajukan ke meja diskusi. Tuhan bukan lagi entitas sakral yang tak boleh disentuh, tapi tuhan adalah ‘ide’ dan seperti semua ide besar dalam sejarah manusia, ia layak diuji, dikritik, dan kalau perlu, ditinggalkan.
Studi antropologi menunjukkan bahwa kepercayaan kepada tuhan sangat bervariasi. Dari roh leluhur di Papua, zeus yang temperamental, odin yang doyan perang, hingga allah yang maha menghukum. Pola ini menunjukkan satu hal penting: tuhan adalah refleksi budaya, bukan kebenaran universal. Tuhan berubah bentuk, perilaku, dan bahkan kepribadiannya tergantung dari kelompok mana yang menciptakannya. Sama seperti karakter dalam novel, tapi kali ini, kita semua dipaksa hidup dalam novelnya.
Tuhan Bisa Mati (Dan Mungkin Sudah)
Nietzsche pernah berkata, “tuhan telah mati.” Tapi kenyataannya, tuhan tidak pernah benar-benar hidup. Beberapa agama malah menolak tuhan yang hidup. Ia hanya ada dalam imajinasi kolektif manusia, sama seperti ide tentang raja yang ilahi, unicorn yang bisa menyembuhkan luka hati dan burqa yang bisa membawa manusia ke surga.
Tuhan adalah produk manusia, bukan sebaliknya. Dan seperti semua produk, tuhan punya tanggal kadaluarsa. Masalahnya, sebagian orang masih ngotot menyembah botol susu yang kosong, sambil berkata bahwa di dalam botol itulah sumber kehidupan.
0 notes
Text
TUHAN: SEBUAH KOMEDI KOSMIS

Konon kabarnya, tuhan ada. Jika benar, bakatnya dalam seni tentu sangat luar biasa . Miliaran curhat, jeritan hati emak2 yg ditinggal selingkuhannya (eh, anaknya maksudnya), sampai keluh kesah netizen soal sinyal
Wi-Fi yg lemot, semuanya di terima.
Tapi yg paling wow, sepanjang sejarah galaksi, dia adalah satu2nya sesuatu (bukan mahluk) yg "paling susah dihubungi". Kalah sama customer service provider kartu kredit atau app kredit.
Kalian terlalu sibuk merapal mantra memohon harapan. Air mata duka mengalir bagai air bah hanya untuk minta belas kasihannya. Sementara itu, pemungut cukainya (baca: alim ulama) mengobral tiket surga, bahkan discount sampai 70% .
Apa yg kamu mohon2 itu bereaksi?
Oh, tentu tidak. Yg disebut ‘beliau’ itu konsiten sekonsisten-konsistennya: silent mode!
Tanpa notifikasi, apalagi centang biru.
tuhan seperti seniman abstrak, yg menorehkan kuas2 penderitaan di atas kanvas luka.
tuhan itu pelukis agung yg menjadikan kematian sbg komposisi & membingkai keputusasaan dalam bingkai keabadian.
Semakin abstrak, semakin dipuja.
Semakin diam, semakin nyaring budaknya membela.
Semakin ...
Semakin tdk menghiraukan, makin heboh fans ultras membelanya:
"Ini cuma prank dari tuhan!",
"dia lagi meeting penting!",
atau "Otak kamu yg cetek, nggak bakal bisa ngeh sama plot twist-Nya!"
Taktik marketing yg brilian: hadir tanpa perlu mempertanggungjawabkan kehadirannya.
Doa: Curhat Colongan & Pantulan Diri Dari Kolam Kosmik
Menurut psikolog, doa bukan video call 2 arah sama ‘yang di atas sana’, tapi lebih ke story yg tidak ada view-nya. Doa itu cuma menenangkan diri, atau meninabobokkan kesedihan. Tepatnya masturbasi atau onani berjamaah.
Banyak penelitian membuktikan, efek relaksasi dari berdoa itu bukan karena pesannya sampai, tapi karena otak memproses self-deception berupa kontrol rasa & memalsukan harapan pas lagi low batt.
Mas Dab, Jesse Bering dalam bukunya, "The Belief Instinct"? mengatakan, Otak manusia memang punya default setting buat nyari "dalang" di balik setiap kejadian, apalagi pas lagi ngerasa futus-asa.
Jadi, doa itu bukan surat cinta buat tuhan, tapi mekanisme adaptasi biar kita nggak langsung uninstalldiri dari hidup (game over). Singkatnya, doa itu semacam candu yang bikin kita tetap memainkan game.
Sedikit beda dg kata sosiolog, justru karena tuhan nggak pernah nongol buat kasih testimoni, maka ketidakhadirannya malah jadi alat kekuasaan yg powerful.
Karena tuhan itu maha ghosting, jadilah manusia (terutama influencer rohani ) maju sebagai official spokesperson. Doa pun jadi ritual wajib, bukan buat solusi, tapi buat mind control & membuat kamu nurut bin manut.
kalau berdoa nggak sesuai template (nggak satu versi gurun), auto dicap kapir, imannya kurang.
Yang doanya gak pakai bahasa terkenthu, ostomastis doanya masuk recycle bin.
Lha kalau yg doanya sesuai tapi nggak dijawab,?
katanya sedang diuji, padahal di-ghosting... eh!
tuhan memang hening, tapi pendengung-nya paling berisik, apalagi toanya, sering bikin budeg telinga.
Atas namanya sering digunakan juga untuk membenarkan kejahatan kemanusiaan!
Dulu di Auschwitz, jutaan umat mention tuhan, sampai jadi trending bertahun tahun.
Pas bocah bocah di gaza mati, seluruh pendukung hamas DM langit minta tolong.
Tapi ya gitu deh, tuhan tetap no comment.
Nggak ada gempa yg auto-pause hanya karena kita meneriakkan namanya.
Zonk: tuhan yang maha menghilang, Mak Cling!
Sepanjang sejarah peradaban, bolos abadinya tuhan itu konsisten banget. Nggak pernah ada doa yg bisa cancel perang, nggak ada mukjizat yg bisa delete pandemi, nggak ada tangan gaib yg muncul pas lagi ada bencana alam.
Tapi justru karena ‘beliau’ hobi ngilang inilah, maka jadi mitos paling fleksibel:
bisa dipuji pas lagi happy, bisa dibela pas lagi sad boy. Soalnya, kalau nggak ada bukti intervensi, imajinasi manusia jadi liar bebas menambal semua kebisuan dg tafsir & keyakinan.
Mbah Voltaire, ngendiko: "tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri & manusia membalasnya dg melakukan hal yang sama."
Jadi, tuhan itu ada sesuai versimu, tergantung mood dan kebutuhanmu saja.
Mungkin kalau seperti pepatah jawa: tuhan itu "alon-alon asal kelakon". Diam2 menghanyutkan...
atau jangan jangan malah nggak menghanyutkan 😂
Atau "nrimo ing pandum", menerima segala yg terjadi. Kalau nggak dikabulkan ya... mungkin memang bukan "pandum"-nya kita?
Nah, sampai di sini, menjadi ‘manungso’ itu adalah bagaimana bisa saling menjaga kerukunan, "guyub rukun"
Jangan berantem gara2 interpretasi "kode" yg katanya jatuh dari atas & yg nggak pernah jelas kebenarannya. Mari menikmati komedi kosmis ini sambil tak🍻& ngemil babih!
Tak🍻
1 note
·
View note
Text
Awal Mula Kepercayaan dan Kekuasaan dari Preman Menjelma Utusan Dewa
Pasti kamu pernah dengar kisah, ada sebuah tindakan kejahatan yang kemudian dibenarkan dengan dalih “demi kebaikan yang lebih besar”!
Contoh, Zeus dan Prometeus, Prometeus mencuri api keterampilan mekanik Hephaestus dan kebijaksanaan Athena dan memberikannya kepada manusia agar mereka bisa bertahan hidup dan makmur. Pencurian ini dianggap sebagai pelanggaran besar oleh Zeus. Zeus menghukum Prometeus dengan mengikatnya di gunung dan setiap hari seekor elang memakan hatinya. Namun, tindakan Prometeus ini dianggap sebagai "kebaikan yang lebih besar" karena memberikan manusia pengetahuan dan kemampuan untuk berkembang.
Contoh lain, Musa. Tindakan Musa yang membunuh juga ‘dibenarkan’ atas nama ‘kebaikan’ dan tujuan kebenaran yang lebih besar.
Dalam sejarah, dongeng keagamaan digunakan sebagai alat melegitimasi kekuasaan dan tindakan-tindakan yang sulit diterima. Dari pengorbanan manusia hingga sumpah perang suci, atau kepercayaan jika mati dalam perang adalah mati dalam keadaan suci (Viking, Seppuku, Perang Salip, Jihad, dll) semuanya kerap dibungkus dalam narasi ilahi dan hadiah surga. Kok, bisa sih konsep dewa dan ritual digunakan sebagai alat politik dan sosial dari masa lalu hingga sekarang?
Awal Mula: Kepercayaan dan Kekuasaan dalam Peradaban Kuno
Dahulu kala, ketika manusia masih sulit membedakan mana batu dan telur, saat itu mereka juga berpikir keras tentang fenomena alam. Setiap hujan badai yang diiringi Guntur dan halilintar datang, mereka lari tunggang langgang sambil berteriak, "Awas, Dewa langit marah!"
Alam yang super tidak terprediksi ini, seperti banjir bandang membuat mereka berpikir bahwa pasti ada yang membuka bendungan, atau menyiram mereka dengan seember air raksasa, padahal tidak ada. Jika terjadi bencana mereka berpikir bahwa ada kekuatan maha besar di balik semua ini. Maka, lahirlah ide tentang dewa-dewa yang punya hobi lempar lemparan petir atau sedang mengayak bumi sehingga terjadi gempa bumi.
Kepercayaan ini awalnya sederhana, seperti anak kecil yang takut pada gelap atau percaya ada Monster Inc, monster yang mengumpulkan energi ketakutan. Akan tetapi, lama-kelamaan, kepercayaan kok malah berkembang menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengontrol manusia. Persisi seperti monster dan tempat gelap sangat ampuh untuk mengontrol anak-anak supaya tidak nakal. Para penguasa kuno, yang mungkin dulunya hanya jagoan kampung, mulai berpikir, "Hmm, kalau aku bilang aku ini titisan dewa, pasti semua orang akan nurut!". Itu sebab, tak sedikit cerita seorang preman jadi raja. Seorang pemberontak dan perampok menjadi utusan dewa (termasuk dewa allah).
Maka, dimulailah era raja-raja narsis yang mengaku sebagai wakil para dewa di bumi. Mereka membangun kuil-kuil super mewah, yang mungkin sebenarnya hanya ingin pamer kekayaan, dan mengadakan ritual-ritual aneh yang mungkin sebenarnya hanya ajang joget-joget tidak jelas.
Contoh, Firaun Mesir. Bayangkan saja, setiap pagi dia bangun dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku ini dewa Horus! Semua orang harus menyembahku!" Lalu, dia keluar istana dengan gaya sok keren, padahal mungkin semalam begadang main game atau mabuk.
Rakyat yang polos pun percaya. Mereka juga berpikir, "Wah, Firaun ini pasti sakti banget! Dia bisa ngobrol sama dewa-dewa di langit!” Mereka juga berfikir, tidak mungkin bisa punya kekuasaan yang begitu hebat kalau bukan karena tuhan dewa. Padahal, mungkin saja para pendahulu Firaun cuma punya imajinasi yang liar.
Dengan mengaku sebagai dewa atau wakil dewa, para penguasa ini bisa melakukan apa saja tanpa takut ditentang. Mereka bisa seenaknya dan semau gue, seperti bayi yang mainan lilin kemudian membakar kasur, tapi gak ada yang bisa memarahi. Tak ada yang berani protes, sebab kalau protes, sama saja dengan menantang dewa. Bisa-bisa, mereka dikutuk jadi patung atau malah jadi miskin abadi!
So, begitulah awal mula kepercayaan dan kekuasaan di peradaban kuno. Sebuah kisah tentang bagaimana manusia yang bingung mencari jawaban atas misteri alam, dan para penguasa yang memanfaatkan kebingungan itu untuk berkuasa. Sungguh, dunia ini memang penuh dengan kejutan!

0 notes
Text
KETIKA TUHAN KURANG SUBSIDI
#tuhantidakbermoral Bayangkan jika kamu pegang remote control. Jika tidak suka dg satu chanel pasti pindah chanel lain, jika merasa tidak ada lagi chanel yang menarik, kamu tinggal menggantiny ke mode film berlangganan atau karaoke-an di youtube.
Nah, sekarang, bayangkan jika kamu memegang remote control alam semesta. Bisa bikin angin puting beliung buat memporak porandakan jemuran tetangga yg menurutmu cerewat & ngeselin. Atau,
atau, kamu bikin gunung meletus, dg daya rusak lokal, di tempat tentanggaamu yg lagi bikin pesta. Sekarang, tantangannya adalah: bayangkan jika remote control itu cuma punya dua tombol: "marah" dan "marah parah." Yup, Apa yg kau bayangkan itulah kira2 deskripsi tuhan zaman dulu
Dewa2 & tuhan zaman dulu, punya kekuatan kosmis, tapi emosi mereka meledak2. Emosinya seperti orang yg patah hati, kayak roller coaster, seperti valas atau kripto yg gampang naik turun.
Dewa tuhan zaman zadul itu mirip bocah yg dikasih mainan rudal. Bisa meledakkan apa saja semaunya, kapan saja. Kekuatan marahnya nggak bisa ditebak, dari hujan tiba2 badai, dari gempa bumi tiba2 tsunami, seperti perempuan yg PMS, lah.
Bagi orang zaman dulu, peristiwa alam itu bukan fenomena alam, tapi ulah tuhan dewa allah yg lagi ngambek karena kurang subsidi, atau gak pernah dapat setoran pajak dari pemungut cukainya.
Tak🍻

1 note
·
View note
Text
Tuhan yang Hobi Tawuran: Dari Dewa-Dewi sampai Allah
Dulu, waktu zaman purba, Tuhan dan para dewa itu kayaknya hobi banget bikin drama di panggung kosmis. Zeus, Odin, Horus - mereka itu kayak seleb Hollywood zaman baheula, kerjaannya berantem mulu. Boro-boro mikirin cinta kasih, yang ada malah adegan baku hantam yang bikin kita mikir, "Ini Tuhan apa tukang pukul?"
Terus, kalau kita intip agama-agama Abrahamik, Allah juga nggak kalah sangar. Di kitab suci, Tuhan digambarin kayak penguasa negeri antah-berantah yang demen banget bikin onar. Hobi banget ngirim bencana, perang, sama ngehukum manusia. Tuhan kok malah kayak preman pasar yang sukanya bikin rusuh?
Kenapa Tuhan Suka Berantem?
Kalau kita telaah dari sudut pandang sejarah dan psikologi, Tuhan yang suka tawuran mungkin hanyalah produk dari otak manusia purba yang ketakutan melihat dunia yang keras dan penuh ancaman. Bayangkan, dulu manusia hidup dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan sekarang. Ada perang antar suku yang nggak ada habisnya, binatang buas yang selalu siap menerkam, dan cuaca ekstrem yang bisa berubah jadi musuh sewaktu-waktu. Dalam kondisi seperti ini, manusia purba tentu ingin merasa aman, dan salah satu cara mereka untuk meraih rasa aman itu adalah dengan membayangkan adanya kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka—Tuhan. Tapi, Tuhan yang mereka bayangkan bukanlah Tuhan yang ramah dan lembut, melainkan lebih seperti bodyguard berotot, yang siap ngehajar semua musuh yang berani mendekat. Tuhan diciptakan untuk mengisi kekosongan perasaan aman mereka. Kalau bahaya datang, mereka tinggal berharap pada Tuhan sang jagoan yang bisa bertarung lebih hebat dari siapa pun.
Teori evolusi juga bisa menjelaskan fenomena ini. Menurut teori ini, manusia sejak awalnya memang punya naluri untuk berperang demi bertahan hidup. Di zaman ketika makanan, tempat tinggal, dan keamanan sangat terbatas, kekerasan sering kali menjadi solusi paling cepat dan efektif. Naluri ini kemudian tercermin dalam figur Tuhan yang tidak hanya menjadi pelindung spiritual, tapi juga sosok yang siap turun tangan secara fisik, seolah-olah Tuhan adalah ‘petarung jalanan’ yang siap meninju siapa saja yang mencoba mengusik umat-Nya. Di masa lalu, kekerasan adalah mata uang untuk bertahan hidup, dan Tuhan dijadikan simbol kekuatan tertinggi. Dengan menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang kuat dan agresif, manusia purba menciptakan mekanisme psikologis untuk merasa aman di dunia yang brutal. Tuhan bukan sekadar penghibur spiritual, melainkan juga 'jagoan' pamungkas yang bisa bikin musuh keder sebelum bertarung. Ini membuat konsep Tuhan yang agresif menjadi begitu relevan bagi mereka, karena sejalan dengan kebutuhan naluriah untuk mempertahankan diri dan komunitasnya.
Tuhan: Alat Politik Para Raja?
Kalau dipikir-pikir, dari dulu sampai sekarang, Tuhan sering dipakai sebagai "alat politik" paling canggih. Para raja, kaisar, atau pemimpin zaman dulu nggak sekadar ngandalkan tentara untuk jaga kekuasaannya, mereka juga butuh "legitimasi dari langit." Jadi, nggak heran kalau Tuhan yang digambarkan sangar, galak, dan suka perang jadi model favorit buat para penguasa. Tuhan semacam ini bukan cuma dilihat sebagai sosok yang menjaga moral, tapi juga jadi alasan kenapa raja-raja bisa sah-sah saja berperang atau menghukum musuh-musuh mereka dengan brutal. Contoh klasiknya adalah perang salib, di mana dua belah pihak merasa bahwa mereka berjuang demi kehendak Tuhan, bukan cuma sekadar konflik politik atau teritorial. Jadilah para raja bisa bilang, “Lihat tuh, bahkan Tuhan aja turun tangan untuk perang. Kalau Tuhan aja boleh marah dan menghancurkan musuh-musuh-Nya, kenapa saya nggak boleh?"
Konsep ini jelas sangat menguntungkan para penguasa. Seorang raja bisa menyembunyikan ambisinya di balik “perintah Tuhan,” dan nggak ada rakyat yang berani protes. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, menyebut fenomena ini sebagai otoritas karismatik. Menurut Weber, agama sering menjadi alat yang ampuh untuk melegitimasi kekuasaan seseorang, terutama ketika Tuhan digambarkan sebagai sosok yang tak kenal ampun terhadap siapa saja yang berani melawan. Misalnya, kalau rakyat mulai gelisah atau ada yang mau memberontak, pemimpin tinggal menyodorkan ancaman: “Tuh, kan, Tuhan juga nggak suka kalau ada yang nggak patuh! Lihat saja apa yang Dia lakukan sama kaum-kaum pembangkang di masa lalu.” Dengan ancaman Tuhan yang pemarah di belakangnya, kekuasaan raja atau pemimpin agama bisa semakin kokoh. Bahkan dalam jihad atau perang suci, konsep ini digunakan untuk memotivasi massa. Bukan lagi soal siapa yang lebih benar, tapi siapa yang punya Tuhan paling jago berantem.
Dalam skenario ini, Tuhan beralih fungsi menjadi semacam maskot atau senjata politik. Tuhannya nggak lagi bicara soal kasih sayang atau kedamaian, tapi soal siapa yang bisa mengalahkan musuh lebih cepat dan lebih brutal. Ini menciptakan ruang bagi pemimpin politik atau agama untuk bermain aman—mereka bisa selalu berlindung di balik kehendak ilahi, tanpa perlu menjelaskan alasan rasional atau moral di balik keputusan mereka. Kalau ada yang protes? Ya tinggal bilang, “Ini bukan keputusan saya, ini keputusan Tuhan.” Cerdas, kan? Ini membuat banyak pemimpin zaman dulu bisa bertindak tanpa harus khawatir dengan masalah moralitas atau etika. Tuhan yang agresif jadi "jagoan universal" yang selalu bisa diandalkan untuk memaksakan kehendak.
Menariknya, pola ini terus berulang dalam sejarah. Dari perang salib di Eropa sampai perang suci di Timur Tengah, Tuhan yang galak selalu hadir sebagai justifikasi utama. Kalau ada pemimpin yang ingin mempertahankan kekuasaannya, menciptakan ketakutan lewat Tuhan yang pemarah adalah salah satu cara paling ampuh. Dan lucunya, banyak dari kita yang nggak sadar kalau Tuhan yang suka berantem ini sebenarnya cuma proyeksi dari kepentingan politik manusia. Bagi para penguasa, Tuhan bukan hanya sosok spiritual, tapi juga alat praktis untuk mengatur kekuasaan dan memastikan semua orang tunduk.
Ritual dan Korban: Nyogok Tuhan Biar Nggak Disodok?
Bayangkan, dulu Tuhan itu bukan cuma sosok yang mendengarkan doa sambil tersenyum penuh kasih sayang, tapi lebih mirip seperti bos mafia yang lagi bad mood. Kalau Dia lagi nggak senang, siap-siap aja deh, ada petir nyamber, gempa bumi, atau banjir bandang datang mendadak. Jadi, manusia zaman dulu punya satu solusi pamungkas: sogok Tuhan biar nggak ngamuk! Tapi tentu saja, bukan sogokan biasa. Dari sudut pandang antropologi, banyak budaya kuno percaya kalau Tuhan atau dewa-dewa punya selera yang mahal—nggak cukup cuma doa atau puasa, mereka butuh sesajen yang benar-benar bikin mereka 'terkesan'. Di sinilah muncul praktik pengorbanan hewan, dan dalam beberapa kasus ekstrem, pengorbanan manusia. Ya, ibaratnya kalau mau bikin Tuhan senang, perlu 'hadiah' yang benar-benar kelas berat.
Ritual berdarah ini dianggap sebagai cara paling efektif untuk meredakan murka Tuhan. Ini seperti pesan halus kepada Sang Kuasa: "Lihat, kami serius nih! Ini korban buat menyenangkan Anda, jadi tolong jangan kirim banjir besar atau serang penyakit wabah lagi." Serem, ya? Tapi itulah kenyataan dalam banyak budaya kuno, seperti Maya, Aztec, atau Mesir Kuno. Bagi mereka, memberikan 'sesajen' yang berupa hewan atau manusia adalah bentuk komunikasi yang paling ampuh dengan para dewa. Mereka percaya, dengan memberi korban yang cukup 'berharga', mereka bisa menjinakkan amarah dewa yang lagi ngamuk. Jadi, ibaratnya dewa itu mirip bos mafia: kalau mau aman, kasih 'upeti' dulu. Jangan sampai lupa, soalnya kalau sampai dewa nggak puas, ya bencana alam jadi konsekuensinya.
Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog terkenal, mengungkapkan bahwa mitos tentang Tuhan atau dewa yang suka berperang itu sebenarnya hanyalah cara manusia untuk memahami dunia yang penuh kekacauan. Saat hidup di tengah perang, bencana alam, dan penyakit yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, manusia butuh alasan kenapa semua itu terjadi. Jadi, daripada menyalahkan dirinya sendiri, lebih gampang nyalahin Tuhan yang galak. Kalau Tuhan aja suka perang dan ngamuk, maka kita sebagai manusia juga wajar dong kalau berantem dan bikin keributan? Pada dasarnya, manusia menciptakan gambaran Tuhan yang sesuai dengan realitas keras yang mereka hadapi. Tuhan yang baik hati nggak akan cocok dalam konteks dunia yang kejam, jadi mereka bikin Tuhan yang sedikit temperamental—biar nyambung dengan kondisi hidup mereka.
Lebih lanjut, Lévi-Strauss juga menjelaskan bahwa mitos dan ritual ini adalah upaya manusia untuk memberikan struktur pada dunia yang kacau. Kalau ada aturan main—kasih korban, Tuhan tenang—maka ada semacam kontrol atas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, ketika bencana melanda, manusia kuno bisa berkata, "Ah, mungkin sesajennya kurang besar," atau, "Tuhan pasti lagi marah besar, yuk kita potong sapi lebih banyak." Dalam cara pandang ini, manusia menciptakan skenario di mana mereka bisa merasa punya kendali atas alam semesta yang tidak terduga. Ritual pengorbanan ini menjadi semacam "perjanjian" antara manusia dan Tuhan: kami kasih sesuatu yang berharga, dan sebagai gantinya, tolong jangan bikin bencana lagi, oke?
Pada akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari praktik nyogok Tuhan ini? Bahwa manusia, dari zaman purba sampai sekarang, selalu mencari cara untuk mengendalikan hal-hal yang mereka nggak bisa pahami. Kalau zaman sekarang kita punya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjelaskan fenomena alam, di masa lalu mereka punya ritual berdarah. Ritual ini bukan cuma soal nyogok Tuhan biar nggak ngamuk, tapi juga tentang menciptakan ilusi kontrol di dunia yang penuh ketidakpastian. Dan tentu saja, Tuhan yang 'suka berantem' ini hanya cerminan dari dunia manusia sendiri yang waktu itu memang penuh dengan kekerasan.
Tuhan yang Kejam: Tanggung Jawab Siapa?
Mari kita mulai dengan pertanyaan simpel tapi rumit: kalau Tuhan digambarkan sebagai sosok yang kejam dan suka perang, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kekejaman itu? Apakah benar Tuhan itu memang galak, atau ini cuma ulah manusia yang mencoba melarikan diri dari tanggung jawab moralnya sendiri? Friedrich Nietzsche, filsuf flamboyan yang sering bikin gereja panas dingin, punya jawabannya. Menurut Nietzsche, konsep Tuhan yang kejam ini cuma alat buat agama mengikat manusia jadi "budak moral." Maksudnya, manusia nggak pernah benar-benar bebas menentukan apa yang baik dan buruk. Mereka tinggal nurut aja, ikut-ikutan ajaran yang katanya langsung dari Tuhan, walau sering kali ajarannya terasa absurd atau justru berlawanan dengan akal sehat. Kenapa Tuhan kok tega? Ya, biar manusia nggak perlu mikir susah-susah soal moralitas, cukup patuh aja, dan masalah selesai.
Dalam pandangan Nietzsche, agama bukan sekadar jalan menuju pencerahan spiritual, melainkan semacam sistem kontrol. Lewat konsep Tuhan yang berkuasa penuh dan suka menghukum, manusia jadi tunduk pada norma-norma yang ditetapkan agama. Tapi, masalahnya, norma-norma itu sering kali jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya berkembang dari kebebasan individu. Dengan kata lain, Tuhan galak ini sebenarnya bukan Tuhan, tapi ciptaan manusia untuk bikin dirinya nyaman dengan posisi "budak" yang nggak perlu mikir banyak. Ini yang disebut Nietzsche sebagai "moralitas budak." Daripada mengembangkan moralitas yang mandiri, manusia lebih milih patuh sama aturan yang udah ada, walaupun aturannya datang dari sosok ilahi yang doyan menghukum.
Dan di sini muncul pertanyaan menarik: apakah manusia benar-benar nyaman dengan keadaan seperti itu? Ternyata, menurut Nietzsche, jawabannya ya—karena patuh itu jauh lebih gampang daripada berpikir kritis dan menanggung beban tanggung jawab moral sendiri. Tapi, bukankah ini bikin manusia jadi penonton dalam hidupnya sendiri? Mereka cuma ikut skenario yang ditulis oleh 'Tuhan yang Kejam' tanpa pernah benar-benar jadi penulis skenario mereka sendiri. Maka dari itu, Nietzsche mendorong manusia buat "membunuh Tuhan." Bukan dalam arti harfiah tentu saja, melainkan membunuh konsep Tuhan yang represif dan mulai mengambil kendali penuh atas hidup dan moralitas mereka sendiri.
Di sisi lain, Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialisme yang nggak kalah unik, punya pandangan yang sedikit beda tapi tetap menohok. Kalau Nietzsche bilang manusia jadi "budak moral," Sartre lebih menyoroti bagaimana Tuhan yang galak ini sebenarnya cuma cermin dari ketakutan manusia sendiri. Menurut Sartre, manusia takut sama kebebasan, karena kebebasan berarti tanggung jawab penuh atas segala tindakan kita. Jadi, lebih gampang buat manusia menyalahkan Tuhan atas semua kesalahan dan kekerasan di dunia, daripada mengakui kalau kekacauan ini adalah hasil perbuatan kita sendiri.
Konsep Tuhan yang suka perang dan menghukum, dalam pandangan Sartre, adalah pelarian dari kebebasan. Kita lebih suka berpikir bahwa ada kekuatan eksternal yang mengendalikan hidup kita, karena kalau nggak ada, kita harus mengakui bahwa segala keputusan moral dan tindakan ada di tangan kita sepenuhnya. Dengan kata lain, Sartre bilang bahwa Tuhan ini diciptakan karena manusia butuh sosok yang bisa dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab moralnya. Ini bukan berarti Tuhan benar-benar ada dan galak, tapi manusia butuh percaya ada Tuhan yang kayak gitu supaya mereka bisa tetap hidup nyaman tanpa rasa bersalah atas perbuatan mereka. Jadi, kalau ada perang, kekerasan, atau ketidakadilan, gampang deh nyalahin Tuhan, karena kan Tuhan yang mengatur semuanya, bukan kita.
Sartre, dengan gaya khas filsafat eksistensialismenya, menantang kita untuk berhenti mengandalkan Tuhan atau agama sebagai sumber moralitas. Menurutnya, manusia harus "ditinggalkan" oleh Tuhan, agar kita bisa benar-benar bebas. Bebas di sini artinya bukan bebas tanpa batas, tapi bebas untuk menentukan nilai-nilai moral yang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari sosok ilahi yang katanya maha segalanya tapi doyan menghukum. "Keberadaan mendahului esensi," kata Sartre. Jadi, sebelum kita menunggu Tuhan memberi kita makna hidup, kenapa nggak kita bikin makna hidup sendiri? Daripada mengandalkan Tuhan yang mungkin nggak pernah mendengar doa kita, lebih baik kita bertanggung jawab atas hidup dan tindakan kita sendiri.
Tapi, tunggu dulu, apakah ini berarti kita jadi bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan? Tentu tidak. Justru dengan menerima kebebasan penuh, kita juga menerima tanggung jawab penuh. Tanpa Tuhan yang galak dan suka menghukum, kita nggak bisa lagi menyalahkan "takdir ilahi" atau "rencana Tuhan" atas segala sesuatu yang terjadi di dunia. Mulai dari perang, ketidakadilan, sampai bencana alam, semuanya adalah hasil tindakan manusia—atau ketidaktindakan manusia. Kita, sebagai manusia, nggak bisa lagi bersembunyi di balik Tuhan untuk menghindari konsekuensi dari pilihan-pilihan moral kita. Kita harus berani menghadapi dunia dengan kebebasan dan tanggung jawab penuh.
Di sini, baik Nietzsche maupun Sartre sepakat bahwa konsep Tuhan yang galak dan kejam ini sebenarnya lebih banyak mencerminkan ketakutan manusia sendiri. Ketakutan akan kebebasan, tanggung jawab, dan ketidakpastian hidup. Dengan menciptakan sosok Tuhan yang suka menghukum, kita merasa aman karena semua hal "sudah diatur." Tapi harga dari keamanan itu adalah kebebasan kita sendiri. Dan apakah keamanan itu benar-benar sepadan dengan kehilangan kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak secara mandiri?
Kesimpulannya, baik Nietzsche maupun Sartre mengajak kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada Tuhan yang galak. Tuhan yang kejam ini bukanlah realitas objektif, melainkan proyeksi dari kelemahan dan ketakutan manusia. Dengan menyalahkan Tuhan atas segala kekejaman di dunia, kita sebenarnya sedang menghindari tanggung jawab kita sendiri. Nietzsche mengajak kita untuk "membunuh Tuhan" dan mengambil alih kendali penuh atas moralitas kita, sementara Sartre menantang kita untuk menerima kebebasan penuh dan segala konsekuensi moral yang datang bersamanya. Jadi, mungkin pertanyaan sesungguhnya bukanlah, "Apakah Tuhan kejam?" tapi, "Kenapa kita masih butuh Tuhan yang kejam untuk menjelaskan kekacauan dunia ini?"
Kenapa Tuhan yang Kejam Masih Dipercaya?
Mari kita mulai dengan pertanyaan ini: kenapa sih, Tuhan yang digambarkan suka berantem dan bikin rusuh masih saja dipercaya? Jawabannya mungkin sederhana, tapi dalam: cognitive dissonance. Istilah ini dipopulerkan oleh Leon Festinger, psikolog sosial, yang menjelaskan bahwa manusia cenderung merasa tidak nyaman jika keyakinan lama mereka bertentangan dengan kenyataan baru. Jadi, kalau kita sudah bertahun-tahun percaya bahwa Tuhan itu suka perang dan menghukum, otak kita cenderung mencari pembenaran daripada mengubah keyakinan itu. Mengubah pandangan soal Tuhan bukan perkara mudah. Bayangkan saja, selama hidup kita dicekoki narasi bahwa Tuhan adalah sosok yang murka kalau manusia melenceng. Tiba-tiba, kita disuruh percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, Tuhan itu nggak sekejam itu? Wah, itu bikin kepala pening!
Sebagai makhluk yang tidak suka perubahan, manusia lebih memilih untuk mempertahankan keyakinan lama mereka, meskipun realitas di sekitarnya sudah menunjukkan bahwa dunia dan moralitas sudah bergeser. Ini mirip dengan cara orang menolak untuk memperbarui software di ponsel mereka karena takut ada fitur-fitur lama yang hilang, padahal update itu bikin ponsel jadi lebih aman dan nyaman. Jadi, saat ada yang bilang, "Masa sih Tuhan masih suka perang di zaman sekarang?" banyak orang yang bakal defensif, merasa nggak nyaman, dan akhirnya mempertahankan keyakinan lama mereka sambil berkata, "Tuhan sudah begini dari dulu, dan siapa kita untuk meragukan-Nya?"
Nah, dari sisi sosiologi, agama memang sudah lama dikenal sebagai “lem sosial.” Artinya, agama punya peran besar dalam memperkuat ikatan dalam kelompok masyarakat. Tuhan yang galak mungkin masih eksis karena sosok-Nya dipakai untuk memperkuat solidaritas kelompok. Dalam kelompok agama, cerita tentang Tuhan yang siap menghukum musuh dan melindungi umat-Nya bisa diibaratkan seperti memiliki 'satpam' yang selalu waspada. Satpam ini bukan hanya menjaga batas-batas fisik, tapi juga psikologis. Tuhan yang keras kepala dan murka dianggap mampu memberikan rasa aman kepada umatnya karena mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari ancaman eksternal. Bahkan dalam konteks yang lebih ekstrem, Tuhan ini dianggap bisa “menghajar” siapa saja yang berani melawan keyakinan kelompok mereka.
Fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan teori "Ingroup vs. Outgroup" dalam psikologi sosial. Cerita tentang Tuhan yang agresif dan kejam membantu memperkuat identitas kelompok. Dalam narasi agama-agama yang memiliki sejarah konflik seperti jihad atau perang salib, Tuhan yang kejam ini menjadi simbol kekuatan kelompok dan pembelaan terhadap musuh-musuh. Dengan demikian, cerita tentang Tuhan yang suka menghukum musuh menjadi semacam perekat, menciptakan rasa persatuan di antara umatnya. “Kami punya Tuhan yang kuat dan agresif, jadi kami aman,” kira-kira begitu pikiran mereka. Tuhan ini juga berfungsi sebagai ancaman bagi mereka yang berani melanggar aturan dalam kelompok. Siapa yang berani keluar jalur, siap-siap dihajar oleh murka ilahi!
Namun, masalahnya adalah dunia terus berubah. Nilai-nilai moral yang dulu diterima, seperti kekerasan dan dominasi, kini mulai tergeser oleh prinsip-prinsip yang lebih manusiawi seperti kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Tapi, anehnya, banyak orang yang masih memegang teguh gambaran kuno tentang Tuhan yang murka dan penuh amarah. Seolah-olah mereka lupa bahwa teks-teks religius kuno itu ditulis di masa ketika peradaban manusia masih sangat berbeda. Nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan hak-hak individu belum terpikirkan, apalagi diakui secara luas. Akibatnya, kita sering kali melihat kontradiksi antara nilai-nilai agama tradisional dengan moralitas dunia modern.
Tuhan yang suka menghukum dan perang itu mungkin cocok di masa lalu ketika masyarakat masih menganut nilai-nilai patriarki yang keras dan penuh hierarki. Di zaman ketika suku-suku dan bangsa-bangsa sering berperang untuk bertahan hidup, konsep Tuhan yang galak dan siap tempur sangat relevan. Tapi sekarang? Dunia sudah berubah! Kita hidup di era di mana diskusi tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan sudah menjadi arus utama. Tapi, banyak dari kita masih terjebak dalam konsep Tuhan yang sangat kuno, yang tidak sinkron dengan perubahan zaman ini.
Lucunya, banyak orang yang nggak sadar kalau moralitas sudah mengalami evolusi. Kita hidup di dunia yang terus berubah, tapi seolah-olah Tuhan mereka tetap sama: Tuhan yang agresif, yang kalau nggak disogok dengan doa-doa, puasa, atau persembahan, bakal marah dan menurunkan kutukan. Ini kayak punya bos yang kolot, nggak pernah mau update cara kerja, dan cuma bisa marah-marah kalau sesuatu nggak sesuai dengan aturan lamanya. Bedanya, kalau bos kita bisa kita tinggalkan, Tuhan yang kejam ini sering kali dianggap terlalu sakral untuk dipertanyakan.
Menariknya, orang-orang yang tetap memegang teguh konsep Tuhan yang kejam ini mungkin merasa bahwa mereka melakukan hal yang benar. Mereka berpikir bahwa mempertahankan nilai-nilai lama adalah bentuk dari kesetiaan terhadap tradisi. Tapi yang sering terlupakan adalah bahwa mempertanyakan hal-hal kuno bukan berarti tidak setia, melainkan cara untuk memodernisasi keyakinan agar sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Dan di sinilah letak tantangannya: Bagaimana kita bisa berdamai dengan keyakinan lama yang bertentangan dengan moralitas modern?
Jadi, kenapa Tuhan yang kejam ini masih dipercaya? Selain karena cognitive dissonance, mungkin juga karena banyak orang merasa nyaman dengan narasi lama. Mereka enggan melepas "satpam ilahi" yang sudah lama mereka percayai. Dan mungkin, untuk sementara, cerita tentang Tuhan yang agresif ini masih akan tetap ada, sampai kita sebagai manusia benar-benar siap untuk menghadapi dunia dengan kebebasan dan tanggung jawab penuh. Hingga saat itu tiba, Tuhan yang suka bikin ribut ini akan terus menjadi bagian dari lem sosial yang mengikat masyarakat, meskipun sering kali tidak relevan lagi dengan nilai-nilai modern yang sudah berkembang jauh lebih manusiawi.
Sudah Saatnya Cari Tuhan yang Lebih ‘Santuy’ atau Tiadakan Saja?
Zaman sekarang, Tuhan yang galak itu kok rasanya kayak tokoh antagonis dalam film jadul—tidak relevan lagi. Kalau di era digital ini kita bisa pesan makanan dari ponsel dan bicara dengan AI, kenapa kita masih percaya dengan sosok Tuhan yang suka ngamuk kayak bos geng di film mafia? Tuhan yang kerjanya marah-marah, nuntut pengorbanan, dan suka ngirim bala bencana rasanya udah out of fashion. Bayangkan, di dunia yang makin menjunjung tinggi kasih sayang, toleransi, dan hak asasi manusia, konsep Tuhan yang agresif itu malah jadi bahan ketawaan. Kok bisa, Tuhan yang katanya penuh kasih tapi suka 'nyentil' umatnya kalau nggak nurut? Di era modern ini, mungkin sudah waktunya umat beragama mulai mikir: mau tetap mempertahankan sosok Tuhan yang murka, atau ikut nilai-nilai kemanusiaan yang lebih santuy dan penuh cinta?
Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan cerdas, narasi lama soal Tuhan yang pemarah ini seperti sepatu usang yang sudah terlalu kecil untuk dipakai. Misalnya, coba lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan moralitas manusia. Ilmu sosial, psikologi, dan filsafat moral terus menunjukkan bahwa empati dan cinta lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis daripada ketakutan dan kekerasan. Jadi, di mana posisinya Tuhan yang galak di tengah-tengah diskusi ini? Di satu sisi, kita punya orang-orang yang bilang, “Tuhan itu harus ditakuti, biar kita nggak macam-macam.” Tapi di sisi lain, kita punya generasi muda yang berkata, “Buat apa sih, percaya sama sosok yang suka menghukum kalau ada opsi buat hidup harmonis tanpa harus takut-takut?”
Nah, akhirnya, banyak dari kita mulai berpikir: relevan nggak sih konsep Tuhan yang galak ini di zaman modern? Atau mungkin, sudah waktunya kita cari alternatif yang lebih sesuai dengan era baru ini. Tuhan yang lebih chill, lebih 'santuy'. Bisa nggak sih, kita punya sosok Tuhan yang lebih suka ngasih hadiah ketimbang ngehukum? Tuhan yang nggak gampang marah cuma karena kita lupa doa atau makan di siang hari pas puasa. Bayangkan, Tuhan yang lebih kayak Sinterklas ketimbang bos geng yang cuma nunggu alasan buat ngehukum anak buahnya. Tuhan versi baru ini mungkin lebih suka memberikan hadiah Natal daripada menyiapkan neraka buat mereka yang melenceng. Karena, let's face it, kita lebih suka sosok yang memberi kita kehangatan daripada yang membuat kita takut melangkah.
Dalam konteks ini, mengapa kita masih bertahan dengan narasi Tuhan yang keras kepala dan penuh amarah? Mungkin karena ini soal kebiasaan yang susah diubah. Sejak kecil, banyak dari kita sudah dicekokin narasi bahwa Tuhan adalah sosok yang maha segala, termasuk maha marah kalau kita melakukan dosa. Tapi, coba bayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika Tuhan yang kita percayai bukanlah sosok yang mudah tersinggung, melainkan lebih bersahabat? Sosok yang nggak langsung murka cuma karena kita lupa baca doa sebelum makan, atau yang nggak marah cuma karena kita punya pandangan berbeda tentang dunia ini.
Di sinilah muncul ide radikal: bagaimana kalau Tuhan yang galak ini kita tiadakan saja? Ya, sekalian saja dihapus dari daftar sosok-sosok yang perlu kita takuti. Kita kan sudah dewasa. Kita sudah bisa berpikir secara kritis dan bertanggung jawab atas moralitas kita sendiri. Mengapa kita harus bergantung pada ancaman dari sosok yang tidak pernah kita lihat untuk berbuat baik? Banyak yang bilang, tanpa Tuhan, manusia akan kehilangan moralitas. Tapi lihat sekeliling! Banyak orang baik di dunia ini yang nggak perlu takut sama neraka buat jadi manusia yang penuh cinta. Mereka berbuat baik bukan karena ada ancaman ilahi, tapi karena mereka paham, itu adalah cara yang benar untuk menjalani hidup.
Tentu, gagasan ini nggak bakal diterima dengan mudah oleh semua orang. Ada yang akan bilang, “Kalau Tuhan kita bikin jadi ‘santuy,’ nanti orang nggak takut dosa lagi!” Tapi di sinilah letak kesalahpahaman besar. Moralitas sejati nggak perlu ditopang oleh rasa takut. Kita nggak butuh Tuhan yang berdiri di balik pintu, mengawasi setiap langkah kita dengan tongkat pemukul di tangannya. Sebaliknya, moralitas itu harusnya datang dari kesadaran internal bahwa hidup berdampingan dengan cinta dan empati adalah cara terbaik untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.
Lalu, kenapa kita nggak bisa punya Tuhan yang lebih chill? Atau sekalian aja nggak usah ada Tuhan, kalau memang itu yang membuat manusia lebih bertanggung jawab secara moral tanpa perlu ancaman. Jika Tuhan memang ada, kenapa harus selalu sosok yang pemarah? Mungkin sudah saatnya kita move on dari konsep Tuhan yang kejam dan beralih ke Tuhan yang lebih masuk akal di zaman modern ini. Tuhan yang nggak perlu lagi mengancam kita dengan api neraka, tapi malah mengajak kita ngobrol santai sambil ngopi, membahas bagaimana kita bisa jadi manusia yang lebih baik tanpa tekanan dan ancaman.
Jadi, kalau Tuhan yang kita percayai masih mirip bos mafia, mungkin saatnya cari opsi lain. Tuhan yang lebih manusiawi, atau malah tiadakan saja, karena moralitas modern tidak butuh ancaman untuk bisa bertumbuh. Kita hidup di zaman di mana kasih sayang dan empati jauh lebih bernilai daripada ketakutan. Jika kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik, mungkin saatnya kita berani bilang: “Tuhan yang galak, terima kasih, tapi sekarang kami sudah besar. Kami tidak butuh lagi ancamanmu untuk jadi manusia yang baik.”

1 note
·
View note
Text
tuhan Zaman Api
Dulu, ketika malam hanya diterangi nyala api yg malu2 sedangkan siang penuh dengan ancaman alam liar, manusia hidup dalam ketidakpastian & ketakutan yg mengintai setiap nafasnya. Bayangkan..
bayangkan jika setiap suara di malam hari adalah pertanda bahwa beberapa tubuh akan direngut & dilenyapkan hewan liar. Bayangkan kilat yg menyambar dari langit bisa menjadi pertanda amarah dewa yg butuh anger management. Bertanyalah manusia... apa penjelasannya?
Api, teman sekaligus musuh, menjadi simbol paling top pada masa itu. Di satu sisi, api menjaga mereka tetap hangat dan memberikan penerangan. Di sisi lain, api bisa mengamuk kapan saja, seperti tuan rumah yg murka karena kedatangan tamu yg tak diundang.
Manusia zaman itu pun mulai mengembangkan pemikiran awal tentang penguasa alam sekitar mereka. "Di mulai dari obrolan api unggun, dan sebuah pertanyaan, mungkinkah ada kekuatan yang lebih besar dari api ini," dan...
Jrenggg —lahirlah kepercayaan pada penguasa yg lebih besar dari api. Penguasa pengendali api. Api yg sangat dibutuhkan, namun juga sering marah, sering bikin bencana ketimbang menolong.
Menurut Lévi-Strauss, mitos adalah cara manusia primitif agar tidak merasa bodoh. Ketika gempa mengguncang atau gunung meletus, mereka tak berpikir soal pergerakan lempeng bumi, tapi tentang dewa yg mungkin bosan dan memutuskan untuk bermain-main dengan nasib manusia.
Dalam kepercayaan ini, manusia merasa punya sedikit kendali, walau kenyataannya peluang kendali mereka sebesar peluang ayam mengalahkan elang. Dewa2, tentu saja, bukan sosok penyayang. Kalau mereka menonton pertandingan, mungkin mereka lebih suka pertandingan yg berakhir rusuh.
Dewa hujan, dewa petir, dewa badai, semuanya lebih sering merusak daripada menolong. Jadi jangan bayangkan dewa2 purba memberikan khotbah penuh kasih. Mereka lebih suka ‘berkelahi’ & menunjukkan kekuatannya.
Dari kacamata sosiologi, moralitas zaman api memang jauh dari konsep mulia seperti kasih sayang. Moralitas saat itu sederhana: apa yg membuatmu tetap hidup, itu yg benar! Jangan buat pemimpin marah & pastikan ritual untuk dewa2 dilakukan dg benar, kalau tidak, desamu musnah.
Talcott Parsons, menuliskan bahwa aturan ritual zaman itu adalah cara agar manusia tidak terlalu kacau. Tidak perlu filosofis, yg penting jangan mati konyol. Moralitas masa itu tidak menyangkut bagaimana menjadi manusia yg baik, tetapi soal bagaimana bertahan hidup.
Kamu baik jika kamu tidak membunuh tetanggamu (paling tidak, bukan di depan umum), & kamu salah kalau kamu melanggar aturan yg memancing amarah dewa. Sederhana saja, dunia masa itu kejam, dan mereka butuh aturan agar tidak hancur. Kalau ada yang tidak patuh?
Ya, persenjatai dirimu unt berhadapan dg dewa yg siap menghukummu, tanpa pengadilan, tanpa ampun! So, ketika dewa2 suka “berkelahi” daripada “berkhotbah,” itu bukan karena tidak punya hati, tetapi mencerminkan dunia purba, dunia di mana kekuatan & dominasi adalah segalanya. tak🍻
1 note
·
View note
Text
Moralitas di Zaman Batu
Tuhan Berkhotbah atau Berkelahi?
Dunia yang Diterangi Api
Mitos-mitos tentang perang dewa, seperti pertempuran antara para Titan dan Olympian dalam mitologi Yunani atau Ragnarok dalam mitologi Nordik, menunjukkan bahwa moralitas pada masa purba tidak dilandaskan pada nilai-nilai yang kita anggap luhur saat ini, seperti keadilan atau kasih sayang. Sebaliknya, moralitas di masa itu erat kaitannya dengan kemenangan fisik, dominasi, dan ketundukan. Dewa-dewa dalam mitos kuno sering kali menjadi representasi kekuatan yang menentukan hierarki kekuasaan di dunia, baik itu antara para dewa sendiri maupun antara dewa dan manusia. Kemenangan fisik menjadi standar moralitas. Kekalahan adalah tanda kelemahan, sementara kekuatan untuk menaklukkan adalah bukti moralitas yang lebih tinggi dalam konteks sosial primitif tersebut. Dalam mitos-mitos ini, dewa-dewa berperang bukan untuk menciptakan dunia yang adil, melainkan untuk menegakkan dan memperkuat hierarki kekuasaan yang tak dapat diganggu gugat.
Di sini, kita melihat bahwa konsep keadilan sebagaimana dipahami dalam masyarakat modern tidak memiliki tempat dalam narasi mitologis ini. Hukum-hukum moral yang diambil dari ajaran para dewa justru berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial yang mendukung kekuasaan dan dominasi. Ketundukan menjadi sikap moral yang dianggap benar, bukan karena itu intrinsik baik, tetapi karena ia memastikan kelangsungan hidup di dunia yang penuh ancaman. Dalam masyarakat kuno, yang terpenting bukanlah kebenaran moral yang tinggi, melainkan siapa yang memiliki kekuatan untuk bertahan. Hierarki ini tercermin dalam mitologi: dewa-dewa yang kuat berkuasa, dewa-dewa yang kalah tersingkir, dan manusia hanya bisa berharap agar mereka tidak menjadi korban dari perselisihan ilahi ini.
Dalam konteks ini, moralitas bukanlah sesuatu yang intrinsik atau universal. Ia merupakan respons adaptif terhadap tantangan yang dihadapi kelompok. Setiap keputusan moral, setiap tindakan yang dianggap 'benar,' tidak diambil berdasarkan prinsip keadilan atau kemanusiaan, tetapi berdasarkan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Contoh yang sederhana bisa kita lihat dari cara manusia purba menghadapi ancaman dari alam, seperti seekor harimau yang datang mengancam desa. Dalam kondisi seperti itu, apakah manusia akan duduk dan berdoa, berharap agar para dewa mengasihani mereka? Tentu saja tidak. Respons yang paling logis dan moral dalam konteks tersebut adalah menghunus senjata, mengatur strategi, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah moralitas Zaman Batu: respons agresif terhadap tantangan eksternal, tanpa ruang untuk perenungan etis yang panjang. Bertahan hidup adalah prioritas utama, dan segala tindakan yang memastikan kelangsungan hidup dianggap benar dan dibenarkan.
Konsep seperti keadilan dan kasih sayang tidak relevan dalam konteks moralitas yang berpusat pada kelangsungan hidup. Keadilan hanya muncul ketika ada cukup waktu untuk merenungkan implikasi etis dari sebuah tindakan. Namun, ketika hidup manusia terus-menerus terancam oleh bahaya fisik, konsep-konsep ini hanyalah kemewahan yang tak terjangkau. Kasih sayang tidak membantu dalam menangkis serangan musuh atau dalam mempertahankan sumber daya yang terbatas. Karena itu, moralitas purba tidak punya tempat untuk nilai-nilai luhur seperti yang kita hargai saat ini. Bagi mereka, moralitas adalah soal tindakan cepat dan tepat, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan itu "benar" dalam arti moral yang abstrak.
Satu hal yang mencolok dari kehidupan manusia purba adalah betapa dewa-dewa selalu merupakan refleksi dari kehidupan mereka sendiri. Ketika manusia hidup dalam dunia yang keras dan penuh kekerasan, para dewa yang mereka ciptakan pun haruslah sosok yang tangguh, brutal, dan penuh kekuasaan. Dalam kondisi kehidupan yang terus dipenuhi ancaman dan ketidakpastian, tidak ada tempat bagi dewa-dewa yang lemah atau penuh kasih sayang. Dewa yang tidak mampu bertarung atau menaklukkan musuh tidak dianggap layak dihormati. Sebab di dunia yang diterangi oleh api, kekuatan adalah segala-galanya. Dewa-dewa dalam mitologi purba sangat mirip dengan panglima perang atau raja-raja kuno: mereka dihormati karena kekuatan mereka untuk berperang, bukan karena kebijaksanaan mereka dalam menciptakan perdamaian.
Api, dalam hal ini, bukan sekadar sumber penerangan fisik. Ia juga menjadi simbol dari hasrat manusia untuk menaklukkan alam. Api adalah alat yang digunakan untuk menguasai kegelapan, menjauhkan binatang buas, dan menghadirkan rasa aman bagi manusia purba. Namun lebih dari itu, api juga melambangkan kekuatan manusia untuk mengendalikan dunia di sekitar mereka, meskipun hanya untuk sementara. Api, seperti dewa-dewa yang mereka ciptakan, adalah wujud dari dorongan manusia untuk bertahan hidup dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti harus menaklukkan dewa-dewa yang mereka sendiri ciptakan dalam imajinasi mereka.
Dalam kesimpulannya, moralitas purba—baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mitos-mitos agama—adalah refleksi dari perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Moralitas ini bersifat pragmatis dan kejam, jauh dari nilai-nilai luhur yang kita hargai saat ini. Tuhan-tuhan kuno bukanlah simbol dari kebijaksanaan atau kebaikan, melainkan representasi dari kekuatan fisik dan dominasi. Mereka lebih sering berkelahi daripada berkhotbah, karena itulah yang diperlukan dalam dunia yang brutal dan tak terduga. Ini menunjukkan bahwa moralitas tidak pernah terlepas dari konteks sosial dan budaya tempat ia berkembang. Di masa ketika hidup penuh dengan ancaman, moralitas yang kuat adalah moralitas yang memungkinkan kelompok untuk bertahan, bukan moralitas yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, atau kesetaraan. Dalam dunia yang diterangi api, kekuatan, bukan kebijaksanaan, adalah mata uang moral tertinggi.
1 note
·
View note